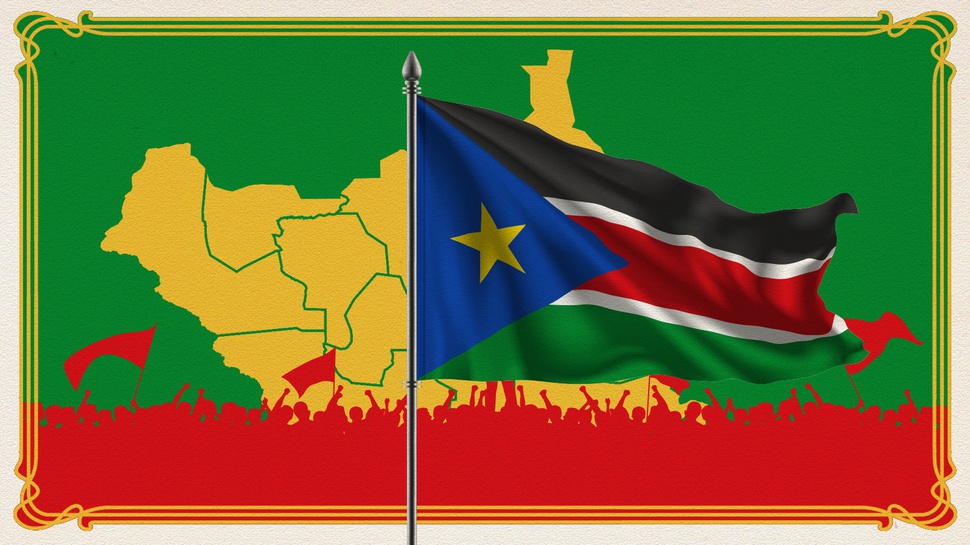tirto.id - Republik Sudan Selatan merdeka pada 9 Juli 2011, tepat hari ini 10 tahun lalu. Negara ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) paling muda. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan bagian dari proses politik yang panjang, yang terjadi di negara berpenduduk sekitar 12 juta jiwa.
Kemerdekaan ini bermula dari Perjanjian Naivasha atau Perjanjian Perdamaian Komprehensif antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dengan Pemerintah Sudan pada 2005. Perjanjian ini berhasil mengakhiri perang sipil. Pada 9 Juli 2005, mereka memperoleh hak otonomi. Melalui proses otonomi inilah Sudan Selatan yang mengembangkan pemerintahan demokratis, menjadwalkan untuk menggelar referendum kemerdekaan penuh.
Kesepakatan Naivasha mendapat dukungan dari Intergovernmental Authority on Development (IGAD), dan konsorsium negara-negara pendonor, meski prosesnya berlangsung cukup panjang. Dimulai dengan The Machakos Protocol pada 2002 yang merundingkan bentuk pemerintahan, kesepakatan pembagian kekuasaan dan sektor-sektor riil, hingga usaha mencari resolusi masalah konflik dan keamanan pada 2004.
Kelompok Pembebasan Selatan
Sebelum membentuk pemerintahan sendiri, Sudan adalah bagian dari wilayah kekuasaan Raja Farouk, raja dinasti Muhammad Ali ke-10 yang menguasai Mesir dan Sudan sejak 1936. Namun kegagalannya membangun pemerintahan yang solid membuatnya dipaksa turun takhta saat Revolusi Mesir 1952.
Kekacauan politik kala itu membuka jalan bagi Sudan menjadi negara merdeka. Setelah membersihkan pengaruh Inggris dan Mesir, Sudan dideklarasikan sebagai negara independen pada 1 Januari 1956.
Setelah merdeka, konflik internal langsung terjadi antara kekuatan Utara dan Selatan. Sudan Selatan yang mayoritas Kristen dan animisme, awalnya bagian dari negara Sudan yang mayoritas Arab Muslim dengan pusat pemerintahan di Utara. Namun sejak merdeka, Sudah Selatan dipimpin oleh penganut Katolik Roma, Salva Kiir Mayardit.
Sebelum menjadi Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Sudan sejak 2005. Catatan kariernya dalam dunia politik dan militer Sudan bahkan dimulai jauh sebelum itu. Dalam perang sipil Sudan pertama yang berlangsung hingga 1972, ia bergabung dengan Batalion Anyanya--gerakan separatis Sudan Selatan.
Batalion Anyanya adalah kekuatan militer pemberontak dalam konflik tersebut, dan Salva Kiir hanya mencapai pangkat perwira rendahan hingga akhir perang. Batu loncatan dalam karier militernya terjadi pada Juli 1983. Saat itu, pemimpin revolusioner John Garang membawa 3000 pasukan revolusioner dan mengambil alih kepemimpinan pasukan dengan membentuk Sudan People's Liberation Army (SPLA). Sementara Kiir bergabung dengan Sudan People's Liberation Movement (SPLM), kekuatan sayap politik dan militer khusus dalam SPLA dan menjadi deputi untuk Garang.
“SPLM/SPLA adalah kelompok pembebasan terbaik yang pernah dibentuk di Sudan. Mereka juga merupakan kelompok ideologis paling terorganisasi,” kata Bona Malwal dalam Sudan and South Sudan: From One to Two (2015:152).
Formasi kekuatan baru itu menimbulkan rangkaian konflik baru yang dikenal dengan perang sipil Sudan ke-2. Sebagai pemimpin militer dengan pengetahuan dan pengalaman ekstensif, John Garang mengajukan visi perjuangan yang jelas; representasi golongan minoritas harus terbentuk dan harus ikut memimpin. John Garang yakin bisa menurunkan presiden Omar al-Bashir dengan formasi pemerintahan yang terdiri dari semua golongan, suku, dan agama di Sudan.
Sudan Selatan Merdeka
Perjuangan John Garang dan SPLA mendapat dukungan dari negara-negara tetangga seperti Libya, Uganda, dan Ethiopia. Pelbagai dukungan itu membuat Garang sanggup menghimpun kekuatan di sebagian besar wilayah Selatan yang disebut New Sudan. Akan tetapi, banyak pihak menuduhnya menjalankan perjuangan untuk merebut keuntungan finansial yang didapat dari persediaan minyak bumi di wilayah tersebut.
Minyak bumi pertama kali ditemukan di wilayah Sudan Selatan pada pertengahan 1970-an. Sumber keuntungan finansial ini segera membuat suasana politik semakin tegang. Pemerintahan Sudan di Utara berkali-kali dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada pembagian kekuasaan. Maka itu, tidak akan ada juga pembagian keuntungan finansial dari sumber daya alam.
Di sisi lain, dukungan negara-negara tetangga memungkinkan John Garang memimpin pasukan militernya secara diktatorial. Perbedaan pendapat bisa berujung pada hukuman mati. Salah satu bentuk dukungan paling utama datang dari rezim Marxis Haile Mariam Mengistu di Ethiopia. Selain menyediakan persenjataan, Mengistu juga memberikan tanah untuk dijadikan pusat pengungsian bagi warga Sudan Selatan yang melarikan diri dari perang. Setelah 400.000 orang ditampung, Garang juga membangun pusat pelatihan militer.
“Secara khusus, tempat ini juga menjadi tempat pengungsian bagi 17.000 anak-anak Sudan Selatan. Banyak di antara mereka yang disebut Lost Boys of Sudan ini diberikan pelatihan militer. Tentara anak-anak ini bergabung dengan SPLA dan ada yang usianya bahkan baru 12 tahun,” tulis Richard Cockett dalam Sudan: Darfur and the Failure of an African State (2010:198).
Namun, dukungan di perbatasan Ethiopia itu tidak berlangsung lama. Pada musim Semi 1991, pemberontakan oleh Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front menumbangkan rezim Mengistu. Mereka menutup suplai senjata dan mengusir orang-orang Sudan Selatan dari wilayahnya. Belum selesai merapatkan barisan setelah diusir pulang, sebuah usaha kudeta terjadi dalam tubuh SPLA yang dilakukan Riek Machar dan Kam Akol.
Dengan identitas kelompok SPLA-Nasir, dua tokoh komandan senior itu memimpin pasukannya dan menuduh Garang memerintah dengan teror diktatorial. Meski prematur, di luar dugaan usaha kudeta mereka justru mengangkat isu perpecahan etnis dalam tubuh SPLA ke permukaan. Perpecahan ini akhirnya berkembang ke konflik etnis antara Nuer dan Dinka. Pertempuran kemudian terjadi selama berbulan-bulan dan menewaskan ribuan pada awal 1992. Dalam konflik ini, untuk pertama kalinya muncul gagasan kemerdekaan Sudan Selatan.

Gagasan itu bertolak belakang dengan visi John Garang yang ingin mempersatukan seluruh Sudan. Pada 14 september 1992, Salva Kiir Mayardit yang menjabat kepala staf dipromosikan menjadi panglima dan wakil ketua SPLA. Lima tahun kemudian, Kiir memimpin pasukan SPLA dalam Operation Thunderbolt. Operasi militer untuk menduduki kota-kota penting Sudan ini sukses besar dengan dukungan pasukan Ethiopia, Uganda, dan Eritrea. Selain memperkuat posisi politik SPLA, kesuksesan itu juga secara signifikan melemahkan kontrol pemerintah Sudan atas wilayah Sudan Selatan.
Seiring waktu, Kiir meraih posisi tertinggi sebagai pimpinan utama SPLA. Di waktu yang sama, John Garang tetap konsisten berjuang mewujudkan ideologi yang ia sebut sebagai Sudanisme. Sebagai ideologi, Sudanisme bermaksud mewujudkan suatu pemerintahan negara Sudan modern yang sekuler. Ia yakin orang-orang Sudan bisa hidup dengan sinergi baru dan komunikasi yang akrab antaretnis. Dalam berbagai kesempatan, ia juga mempromosikan gagasan pemerintahan multi-etnis yang merangkul semua pihak tanpa satupun golongan atau kelompok agama yang menjadi karakter utama Sudan modern.
Gagasannya yang konsisten mengantarkannya pada posisi Wakil Presiden Sudan pada awal Januari 2005. SPLA dan pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai di Nairobi, Kenya. Bulan Juli tahun itu, Omar al-Bashir menandatangani kesepakatan untuk menjadikan Sudan Selatan sebagai wilayah otonom. Kesepakatan ini mengakhiri perang sipil Sudan ke-2 sekaligus mengatur upaya pembagian wilayah kekuasaan.
Beberapa poin penting lain disepakati seperti pembagian keuntungan dari ekspor minyak. Selain itu, mereka juga sepakat mengangkat John Garang sebagai presiden wilayah otonomi Sudan Selatan dan menjadwalkan referendum di Sudan pada 9 Januari 2011. Setelah kesepakatan itu, Sudan bagian Utara yang mayoritas Muslim tetap menjalankan hukum Islam (Sharia), sementara model hukum itu ditolak dengan tegas di Sudan Selatan.
Namun, nasib John Garang kurang mujur. Belum genap satu bulan menduduki jabatan sebagai presiden wilayah otonom, ia terbang ke Uganda untuk menemui Presiden Yoweri Museveni di rumahnya di Rwakitura. Ia tidak berangkat dengan pesawat kepresidenan resmi Sudan karena pertemuan itu tidak ia laporkan kepada pemerintah Sudan. Ia menumpang helikopter Mi-172 milik pemerintah Uganda. Dalam perjalanan pulang ke Sudan, helikopter itu mengalami kecelakaan dan menewaskan Garang, enam rekan kerjanya, serta tujuh orang kru dari Uganda.
Upacara penguburan resmi diselenggarakan bulan Agustus. Kiir naik menggantikan posisi Garang sebagai Wakil Presiden Sudan dan presiden wilayah otonom Sudan Selatan. Mereka tetap menjalankan agenda referendum pada 9-15 Januari 2011. Hasilnya sesuai dugaan: 99 persen warga Sudan Selatan memilih untuk melepaskan diri, sementara hanya 1 persen yang menginginkan penyatuan dengan Sudan.
Pada 9 Juli 2011, negara baru Republik Sudan Selatan resmi berdiri dengan Salva Kiir Mayardit sebagai presiden. Empat hari kemudian mereka resmi terdaftar sebagai negara anggota PBB.
Editor: Irfan Teguh