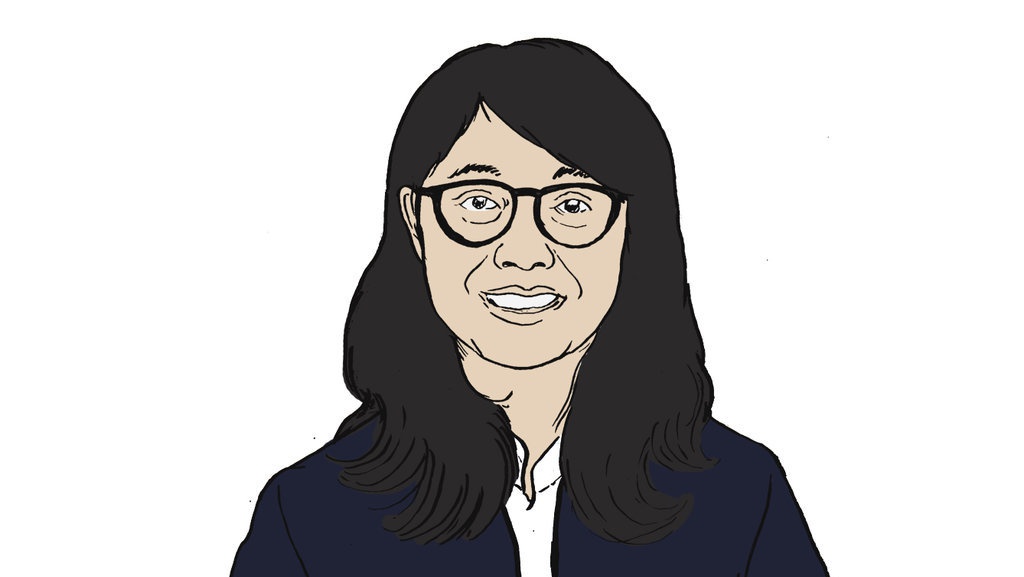tirto.id - Sebagian akademisi, feminis, dan aktivis percaya bahwa mengatasi minimnya representasi perempuan baik di parlemen ataupun di partai politik adalah kunci untuk memajukan kepentingan perempuan di Indonesia. Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah menerapkan aturan kuota gender yang mengharuskan partai-partai politik mengajukan minimal 30% kandidat perempuan dalam pencalonan legislatif. Sejumlah kelompok masyarakat sipil bekerja keras untuk mendorong partai-partai politik memenuhi kuota tersebut. Pada 2004, jumlah kandidat perempuan hanya 11%, yang sempat naik signifikan menjadi 17,86% pada 2009, dan turun sedikit ke 17,32% pada 2014.
Namun, kebangkitan politik identitas dan Islam politik, terutama sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, menghadirkan permasalahan baru bagi kaum feminis dan siapapun yang mendukung kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia. Kini kaum feminis mendapat tantangan baru dari gerakan perempuan konservatif religius yang secara aktif dan intensif menyerang feminisme dari dalam sistem.
Pada Pemilu 2019, terlihat mulai munculnya pengaruh kandidat perempuan yang anti-feminis. Mereka memiliki kecakapan kepemimpinan yang sangat baik, pandai dan artikulatif dalam menyampaikan argumen, dan gencar berkampanye di tingkat akar rumput. Kaum feminis harus siap menandingi narasi mereka karena para kandidat ini dan para aktivis yang berafiliasi dengan para kandidat perempuan anti-feminis ini akan punya pengaruh besar dalam wacana kebijakan bila berhasil lolos ke parlemen.
Saya berbicara dengan beberapa kandidat perempuan konservatif untuk memahami bentuk partisipasi politik perempuan yang baru muncul ini. Kaum feminis perlu mengakui dampak dari keragaman ideologi di antara kandidat perempuan yang akan memberikan perlawanan atas gerakan mereka di parlemen.
Kandidat Perempuan Konservatif
Tak banyak penelitian mengenai peran perempuan dalam pemilihan umum Indonesia. Namun, sejalan dengan tulisan saya terdahulu, kelompok partisan dan relawan perempuan, yang dikenal sebagai “emak-emak”, berperan penting dalam kampanye pemilihan tahun ini. Sementara emak-emak kadang-kadang digunakan hanya secara simbolis oleh politisi laki-laki yang lebih senior supaya mereka tampak peduli dengan pemilih perempuan, banyak perempuan Islam konservatif berkampanye dengan cara-cara baru dan unik.
Sri Vira Chandra, calon legislatif DPRD PKS dapil Jakarta Timur, lebih dikenal sebagai Umi Vira. Sri adalah seorang ustazah dan aktif dalam organisasi seperti Wanita Indonesia dan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA). Sambil berkampanye, ia terus melanjutkan pekerjaannya sebagai pendakwah, mendatangi satu per satu majelis taklim, memberikan siraman rohani, mengajarkan keterampilan hidup, dan memberdayakan perempuan sesuai dengan norma-norma Islam. Dalam sebuah wawancara bulan lalu, dia mengatakan:
“Saya enggak mau dianggap feminis. Saya adalah muslimah yang tahu bahwa di dalam Islam perempuan memiliki tempat mulia. Perempuan diberikan wewenang yang sangat besar oleh agamanya untuk memberikan kebaikan untuk bangsa dan negara, dan itu dimulai dari keluarga. Karena jangan lupa ada nilai spiritual yang diperjuangkan supaya keluarga bisa bertemu di akhirat. Saya enggak tahu, kalau feminis kenal akhirat, enggak? Di titik itu kita tidak ketemu.”
Fitriah Abdul Aziz adalah caleg DPR dari Partai Bulan Bintang. Wakil ketua Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini telah berpengalaman dalam keterlibatannya di banyak organisasi. Daerah pemilihan Fitriah meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Ia menargetkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, untuk memenangkan pemilihan. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan kepada saya:
“Di mata saya, tidak baik bagi perempuan yang bekerja jauh dan tanpa muhrim, apalagi mereka punya suami dan anak di negaranya. Maka, jauh lebih baik jika negara hanya mendukung tenaga kerja laki-laki yang diberi izin kerja di luar negeri. Apalagi saat ini tidak ada langkah kongkrit untuk membuat aturan yang bisa melindungi pekerja migran perempuan dari pemerkosaan, perbudakan, atau penempatan di bidang pekerjaan yang tak sesuai keahlian mereka. Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Tenaga Kerja dan agen pengiriman TKI/TKW harus bekerja sama di bawah satu payung.”
Dua saluran utama yang digunakan perempuan konservatif dalam kampanye adalah majelis taklim dan media sosial. Majelis taklim tidak selalu bersifat politis, namun perkembangan politik Islam baru-baru ini telah mengubahnya menjadi arena penting untuk kampanye.
Azizah Nur Tamhid adalah seorang caleg DPR dari PKS dapil Jabar VI yang mencakup Kota Bekasi dan Kota Depok. Suaminya, Nur Mahmudi Ismail, adalah mantan walikota Depok, Jawa Barat. Untuk kontestasi legislatif kali ini, Azizah sangat bergantung pada sang suami dalam hal pendaan kampanye. Sebagai ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK dan pimpinan himpunan Majelis Taklim Al-Mubarokah dengan ratusan anggota, ia menggantungkan kemenangannya pada jaringan yang cukup luas ini di dapilnya.
Azizah, Fitriah, dan Umi Vira sering mendekati calon pemilih perempuan melalui ceramah di majelis taklim. Sambil berdakwah, mereka tak henti menekankan betapa penting dan mendesaknya partisipasi perempuan dalam politik dan mendorong perempuan untuk memilih mereka. Umi Vira mengatakan:
“Umi bilang: Ibu-ibu kita di majelis taklim, kita tidak bisa buat peraturan. Kalau kita mau buat peraturan, kita harus masuk ke politik. Kita harus perjuangkan kebijakan yang menurut kita penting dan itu harus masuk politik dan ada wakil dari ibu-ibu.“
Di luar majelis taklim, para kandidat pun lihai menggunakan media sosial untuk memperluas pengaruh. Kampanye media sosial penting karena ruang gerak pemilih perempuan lebih sempit dibandingkan pemilih laki-laki. Norma sosial yang mengondisikan perempuan sebagai penanggungjawab pekerjaan rumah tangga mengakibatkan akses informasi yang terbatas, hanya di lingkaran pertemanan mereka atau media sosial. Walhasil, media sosial menjadi saluran utama untuk pesan-pesan anti-feminis yang disebarkan oleh perempuan juga. Baru-baru ini, akun Indonesia Tanpa Feminis menjadi viral, mempromosikan pesan "tubuhku bukan milikku, tetapi Allah" untuk menyangkal gagasan feminis tentang otonomi tubuh. Pesan ini merupakan bagian dari serangkaian kampanye online oleh kaum konservatif, seperti Pemuda Hijrah, Indonesia Tanpa Pacaran, dan Ayo Poligami, yang menyasar anak muda.
Menyusun Kebijakan Sensitif Gender
Medan pertempuran bagi kandidat perempuan konservatif terletak pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Para kandidat ini memandang RUU P-KS berpotensi mengancam moralitas bangsa. Fitriah Abdul Aziz dari PBB mengatakan:
“Tentu menolak. Justru RUU P-KS itu memudahkan orang berperilaku seks bebas. RUU P-KS ini judulnya bagus, tapi isinya banyak kemuslihatan atau pengelabuan. Program saya tidak cocok dengan RUU ini karena motivasinya berbeda. Kalau RUU P-KS motivasinya memudahkan atau membuka jalan buat seks bebas, program saya justru menghambat langkah-langkah menuju seks bebas.
Umi Vira dari PKS meragukan akar RUU itu sendiri. Ia mengatakan:
“RUU P-KS terlalu sarat dengan istilah-istilah feminis radikal. Kalau mau, buang istilah itu. Jangan pakai istilah kekerasan berbasis gender. Persoalan yang mereka angkat bukan kasus kekerasan tapi kejahatan. Seolah-olah dengan banyaknya kejahatan seksual kepada anak, kita butuh RUU P-KS. Padahal sudah ada UU perlindungan anak dan UU PKDRT. Kita tidak perlu lagi sebenarnya. Maka dari itu kita mengatakan RUU ini hanya untuk golongan tertentu.”
Garda depan kampanye penentang RUU ini adalah AILA, di mana Umi Vira adalah anggotanya. AILA didirikan pada 2013 oleh sejumlah organisasi Islam termasuk MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), KMKI (Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam), dan INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations).
AILA melancarkan advokasi pada level kebijakan terkait masalah perempuan, anak-anak, dan keluarga. Semua anggota dewannya adalah perempuan kecuali seorang penasihat, Bachtiar Nasir, tokoh Salafi yang juga memainkan peran penting dalam Gerakan 212. Selain Umi Vira, beberapa anggota AILA lainnya juga mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif 2019, termasuk Sekretaris Jenderal Nurul Hidayati yang bertarung untuk kursi DPR mewakili PKS di dapil Tangerang.
AILA pertama kali mendapat sorotan publik pada 2017, ketika mereka mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau tiga pasal dalam KUHP yang dianggap mengizinkan perzinaan, pencabulan, dan homoseksualitas. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mereka. AILA sekarang memusatkan perhatiannya ke RUU P-KS. Sudut pandang AILA sejalan dengan kandidat yang saya ajak bicara. AILA percaya undang-undang ini akan menghancurkan fondasi keluarga Indonesia.
Kebijakan penting lain yang perlu disoroti selama periode legislatif mendatang adalah revisi UU Perkawinan. Merespons isu pernikahan anak, para aktivis feminis berjuang untuk meningkatkan batas usia hukum minimum seorang pengantin wanita dari saat ini, 16 tahun. Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang perkawinan 1974 tidak konstitusional, dan mengamanatkan revisi undang-undang dalam waktu tiga tahun selama periode legislatif berikutnya. Seperti disebutkan dalam artikel yang diterbitkan oleh Center for Gender Studies (CGS):
"Masing-masing individu tidak bisa dipukul rata tingkat kematangan fisik maupun kedewasaannya. Ada diantara mereka yang belum mecapai usia 18 tahun tetapi sudah memiliki kematangan fisik sekaligus memiliki kedewasaan. Namun ada juga orang belum memiliki kedewasaan. Jadi mempersamakan batas minimal usia pernikahan dengan dalih “kesetaraan gender” merupakan argumen yang absurd dan hanya mengekor pada konvensi-konvensi internasional tanpa mampu bersikap kritis. Meng-universalkan usia 18 sebagai usia minimal pernikahan, justru berpotensi merampas hak dan tidak menghargai pilihan kaum perempuan yang tentunya berbeda-beda karena pengaruh faktor lingkungan sosial dan budaya serta nilai-nilai agama."

Dibandingkan organisasi konservatif lain, AILA unggul dalam menghimpun dukungan kelompok intelektual untuk mengkritik kebijakan gender dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan semacam ini belum pernah digunakan oleh pendukung agenda anti-feminis Indonesia. Kelompok intelektual di belakang AILA bertugas menajamkan argumen-argumen konservatif mereka dalam advokasi kebijakan serta mempengaruhi wacana publik dengan studi dan analisis via perspektif Islam. Bersama PKS, AILA pun tak luput dari perdebatan kebijakan RUU P-KS yang sedang berlangsung di parlemen. Pengaruh mereka yang kian besar mungkin memengaruhi pandangan partai-partai konservatif lainnya untuk berbalik melawan kebijakan yang sensitif gender.
Mempersiapkan Pertarungan
Sebagian besar perhatian masyarakat Indonesia telah terserap habis untuk pemilihan presiden, dan tidak banyak tersisa untuk pemilihan legislatif. DPRD di tingkat kabupaten dan kota, misalnya, diizinkan untuk membuat peraturan daerah yang kerap berakar pada budaya patriarki lokal atau nilai-nilai agama yang menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan. Pada 2017, Komnas Perempuan mencatat 421 peraturan daerah yang diskriminatif memposisikan tubuh perempuan sebagai objek moral, contohnya memberlakukan jam malam atau mewajibkan perempuan untuk mengenakan jilbab. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat—bukan hanya di tingkat nasional, strategis untuk menggerakkan agenda perempuan, dan perempuan yang terpilih di lembaga ini akan menentukan dimensi hukum pada persoalan dan relasi gender di masa pemerintahan berikutnya.
Meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen adalah tugas penting. Namun, tak semestinya hal itu menjadi fokus tunggal ketika menganalisis peran perempuan dalam politik di Indonesia. Kita perlu secara kritis mempelajari implikasi kebijakan yang diperjuangkan perempuan sendiri, dan menempatkan praktik politik mereka dalam iklim politik hari ini. Desakan untuk memenuhi kuota gender tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki agenda kesetaraan gender, tetapi juga mereka yang berdiri bersama gerakan anti-feminis yang mewakili suara kelompok konservatif. Seiring menguatnya gerakan mereka dan pengaruhnya pada wacana kebijakan publik, tujuan akhir dari kebijakan afirmatif, yakni mengaktualisasikan hak-hak dan perlindungan perempuan di Indonesia, tampaknya lebih sulit untuk dicapai.
---------
Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "An anti-feminist wave in Indonesia’s election?". Penulisnya, Dyah Ayu Kartika (Kathy), adalah peneliti pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina), Jakarta. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu gender.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id