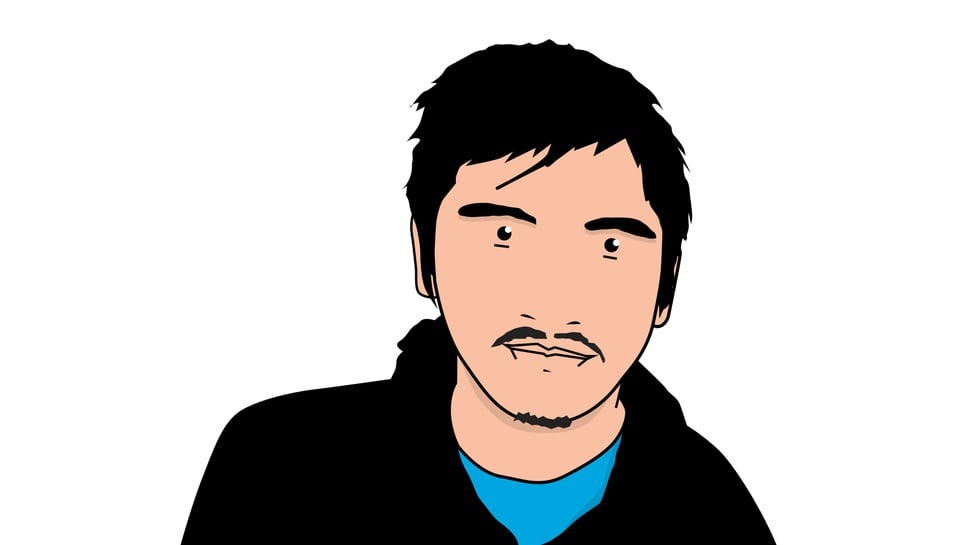tirto.id - Yang jauh lebih kusut dari jas milik Dirjen HAM adalah penegakan HAM itu sendiri.
Mualimin Abdi, Direktur Jenderal (Dirjen) HAM di Kementerian Hukum dan HAM, menuntut sebuah usaha laundry kiloan. Tak tanggung-tanggung, Sang Dirjen menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar 210 juta. Ia kesal karena jas miliknya kembali dalam keadaan kusut.
Tak ada keraguan bahwa setiap warga negara berhak menuntut keadilan. Jangankan jas yang kusut, sehelai sempak yang hangus disetrika atau hilang saat dijemur pun bisa dianggap merugikan. Apalagi jika sempak itu mengandung nilai immateriil tak ternilai. Sempak yang dikenakan pemuda bernama (katakanlah) Dani Armhan saat menjuarai turnamen bina raga Jember Cup atau sempak yang dikenakan pemuda bernama (katakanlah) Buana Arlan saat menjuarai lomba menyeberangi Sungai Amazon di tengah kepungan piranha, misalnya, boleh jadi punya nilai immateriil yang besar bagi pemiliknya.
Kita tak tahu nilai imateriil jas Sang Dirjen itu disebabkan apa. Yang pasti, upaya Sang Dirjen untuk menuntut ganti rugi kadung menjadi berita. Kendati gugatan sudah dicabut, namun publik telanjur mempersoalkan sikap Sang Dirjen. Namun tiap seorang pejabat tinggi menuntut rakyat kecil, apalagi setingkat Dirjen di kementerian yang mengurusi hukum, publik boleh bertanya: apakah jabatan telah digunakan sebagaimana wajarnya atau malah dipakai memastikan urusannya menjadi cepat dan lancar -- pendeknya: abuse of power?
Pertanyaan itu relevan bukan karena banyaknya pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang. Pertanyaan itu penting terutama karena sangat banyak cerita susahnya rakyat kecil mendapatkan keadilan. Ada banyak kasus di mana rakyat kecil menjadi korban proses pemeriksaan atau penyidikan yang intimidatif tanpa didampingi pengacara hingga menjadi korban peradilan yang tidak adil.
Setiap orang bisa bertanya: apa jadinya jika Jessica Kumala Wongso bukan berasal dari keluarga mampu? Jika kasus yang menimpa Jessica dialami buruh bangunan atau tukang setrika di sebuah usaha laundri, sangat mungkin mereka tak bisa membela diri secanggih dan sehebat Jessica, yang dibela pengacara kenamaan, yang punya kemampuan mendatangkan saksi ahli dari perguruan tinggi dan luar negeri.
Publik juga berhak bertanya: sudah seberapa tegak, sih, HAM di Indonesia sampai-sampai Dirjen HAM harus menuntut usaha laundry kiloan? Apakah kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah demikian minim sehingga Sang Dirjen punya cukup waktu berperkara urusan jas yang kusut?
Setiap orang, sekali lagi, berhak menuntut keadilan, termasuk Dirjen HAM. Tapi kita berhak bertanya: ke mana Sang Dirjen saat rakyat di Bukit Duri digusur padahal upaya hukum yang mereka ambil masih berjalan? Ke mana Sang Dirjen saat sebuah gereja di Pasar Minggu dipersoalkan atau saat jemaat GKI Yasmin rutin beribadah di depan istana karena gerejanya disegel? Atau saat warga di Papua tak habis-habisnya mengalami kekerasan?
Betapa tidak menariknya pemerintahan saat pejabat tingginya mempersoalkan jas yang kusut namun pada saat yang sama seorang ibu dua anak berjuang habis-habisan menuntut nasib suaminya yang tewas diracun. Ya, Suciwati sedang menuntut pemerintah, melalui Komisi Informasi Publik, agar membuka dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus terbunuhnya Munir. Saat berita tentang Dirjen HAM mencuat ke publik, Suciwati merilis surat terbuka yang meminta negara bertanggungjawab terhadap raibnya dokumen hasil kerja TPF Munir.
Tentu saja tidak ada korelasi langsung antara jas kusut milik Dirjen HAM dengan raibnya dokumen kasus Munir. Akan tetapi, sekali lagi, publik bisa dan sangat boleh bertanya: seberapa serius, sih, negara melindungi warganya? Apakah (dokumen kasus) Munir tidak lebih penting daripada urusan-urusan pribadi para pejabat negara? Atau bagaimana?
Nyawa Munir tentu saja hanya selembar. Tapi selembar nyawa tetaplah kehidupan. Negara wajib melindungi setiap kehidupan warganya, tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Dan untuk setiap lembar nyawa yang hilang, negara harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Untuk diketahui, pemerintahan SBY membentuk Tim Pencari Fakta guna mengusut terbunuhnya Munir melalui sebuah Keputusan Presiden (Kepres) pada 2004. Kepres itu dikeluarkan tak lama setelah SBY menjadi presiden. SBY sendiri menganggap pengungkapan kasus Munir sebagai sebuah hal yang sangat penting. Dalam retorika keminggris khas SBY, ia berkata kalau kasus Munir adalah "a test of our history".
Tapi apa lacur! Temuan-temuan TPF, yang dokumennya diserahkan kepada SBY pada 2005, tak kunjung dibuka. Jangankan menindaklanjuti, mengumumkan saja tidak. Dan yang lebih membuat prihatin, kosa kata khas SBY yang lain, dokumen itu sekarang entah ada di mana. Boro-boro menindaklanjuti, menjaga dan menyimpan dokumennya saja embuh.
Tidak ada satu pun lembaga negara yang mau bertanggungjawab. Sekretaris Kabinet, yang saat itu dipimpin Sudi Silalahi, mengaku tidak menerima dan menyimpan. Begitu juga dengan Sekretariat Negara, yang kala itu dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Lembaga lain? Kementerian lain? Sami mawon.
Padahal, tak lama setelah TPF menyerahkan dokumen, pemerintah mengaku telah mendistribusikannya kepada lembaga-lembaga terkait. Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet, pada 27 Juni 2005, mengatakan: "Hari ini (Senin, 27/6/2005) laporan TPF sudah didistribusikan ke menteri-menteri terkait untuk dianalisa. Nanti kalau sudah selesai mereka mempelajari baru dibahas bersama-sama dengan presiden."
Entah di mana dan bagaimana dokumen itu dipelajari oleh para pejabat terkait bersama presiden. Bisa dikatakan, merujuk pernyataan SBY, ia telah gagal melewati ujian sejarah yang dibuatnya sendiri.
Jika pemerintahan SBY saja mengaku tidak tahu di mana dokumen tersebut, mudah saja bagi pemerintahan Jokowi untuk mengabaikannya. Lha wong pemerintahan sebelumnya saja, yang menerima dokumen tersebut, seperti lepas tangan, apalagi rezim penggantinya. Pemerintahan sekarang punya alasan untuk ikut-ikutan angkat tangan.
Walau pun opsi lain masih tersedia: memanggil kembali TPF Munir. Opsi yang membutuhkan syarat: pemerintah memang mau serius menuntaskan kasus ini. Opsi yang jika diambil berarti mengakui kegagalan negara dalam urusan remeh temeh administratif.
Jika dokumen negara yang sangat penting, yang dihasilkan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh sebuah Kepres, pun tidak jelas di mana rimbanya, mestikah diherankan jika status kewarganegaraan seorang menteri pun lolos dari pemeriksaan administratif? Ataukah justru ini memang bukan kelalaian melainkan kesengajaan? Sengaja diraibkan, sebagaimana Munir juga sengaja dimatikan?
Munir akhirnya dibunuh dua kali. Ia pertama kali dibunuh dengan arsenik pada 2004. Ia dibunuh lagi untuk kedua kalinya dengan cara mengaburkan (jika kata "menghilangkan" di rasa tendensius) keberadaan dokumen yang berusaha mengungkap kematiannya. Yang pertama Munir dibunuh dalam statusnya sebagai manusia, yang kedua Munir dibunuh dalam statusnya sebagai simbol keadilan dan HAM.
Tiba-tiba saya ingat pernyataan diplomat Indonesia, Nara Masista Rakhmatia, yang beberapa waktu lalu menjawab tuduhan negara-negara Pasifik terkait pelanggaran HAM di Papua. Ia, mewakili negara, berkata dengan lantang sekali: "Komitmen Indonesia terhadap jas pejabat tak perlu dipertanyakan lagi."
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.