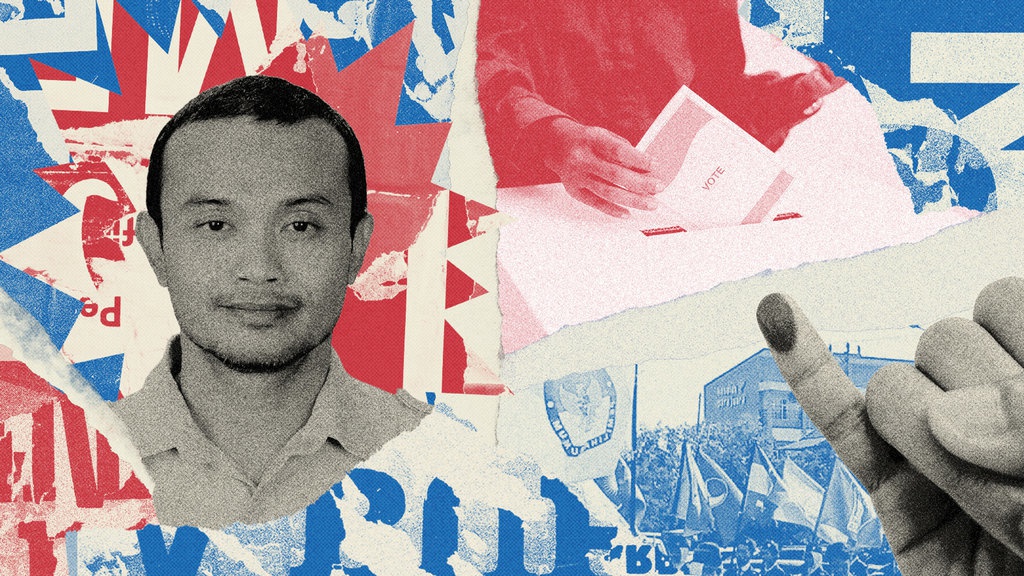tirto.id - Dalam pidatonya di Kongres Partai Golkar (12/12/2024), Presiden Prabowo menyampaikan pendapat untuk memperbaiki sistem pemilu (pemilukada) dengan mengembalikannya kepada mekanisme pemilihan melalui DPRD. Pernyataan itu menuai pro dan kontra, serta membuka kembali perdebatan yang memuncak pada 2014 silam.
Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Tingginya penolakan publik terhadap UU yang mengatur pemilihan tidak langsung kepala daerah itu menjadi pertimbangan lahirnya Perppu tersebut. Meski begitu, SBY juga menyampaikan bahwa keputusannya menerbitkan Perppu adalah ikhtiar untuk menegakkan demokrasi.
Mengikhtiarkan demokrasi menjadi proyek besar masyarakat politik, sejak ribuan tahun lalu hingga saat ini. Meski para filsuf Yunani kuno menempatkan demokrasi sedikit lebih baik dibandingkan tirani, agaknya demokrasi memang menjadi sistem yang paling mungkin dijalankan. Demokrasi bukan yang ideal, tetapi merupakan tatanan yang dapat mempertemukan dan mengakomodasi berbagai kepentingan, kelas sosial, kelompok dan golongan yang beraneka ragam, dalam satu konsep yang disebut people power atau daulah rakyat.
Dengan keunggulan tersebut, demokrasi menjadi satu-satunya sistem yang mampu memberikan harapan bagi semua pihak untuk “berkuasa”, tanpa kecuali. Tantangannya adalah bagaimana menata dan mengelola beragam kepentingan untuk duduk bersepakat merumuskan skema yang adil, jelas, akuntabel, dan berkelanjutan.
Secara substantif, demokrasi yang baik diukur dari kemampuan menjalankan secara langsung kuasa rakyat (direct democracy). Namun, seiring dengan perkembangan komunitas politik secara populasi maupun kewilayahan, kondisi tersebut tidak lagi dimungkinkan. Proyek demokrasi kemudian bergeser menjadi upaya mendesain prosedur perwakilan dengan tetap tidak kehilangan substansi kuasa rakyat. Diskursus demokrasi substansial berkembang menjadi demokrasi prosedural, dengan fokus pada perumusan mekanisme kelembagaan untuk memutuskan siapa pemegang sah kuasa rakyat. Pada momen ini, demokrasi modern melahirkan prosedur yang dikenal sebagai Pemilihan Umum. Sebuah agenda besar yang rutin dijalankan komunitas politik sebagai manifestasi daulah rakyat.
Dengan logika tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah anak kandung demokrasi. Karenanya, kita harus bersepakat bahwa narasi soal perbaikan/perubahan sistem pemilu ada dalam koridor penguatan demokrasi, bukan untuk memperlemah apalagi membunuh demokrasi. Tulisan ini berusaha menelisik wacana pemilukada tidak langsung (melalui DPRD) dari sudut pandang studi “political engineering”.
Rekayasa Sistem Pemilu dan Demokrasi
Soal peran sistem pemilu dalam proyek demokrasi, masyarakat politik telah diingatkan oleh Giovanni Sartori (1968) bahwa “Electoral system is the most manipulative instrument in politics”.
Sartori, salah seorang pelopor studi rekayasa politik, menilai bahwa sistem pemilihan memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan perilaku aktor untuk menghasilkan tujuan tertentu yang diinginkan. Sistem pemilihan dikatakan manipulatif karena desainnya dapat diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan (mungkin) merugikan yang lainnya. Dengan begitu, poin krusialnya adalah untuk apa dan demi siapa perubahan sistem pemilu tersebut dilakukan?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ulasan Ricardo Blaug (2002) dalam artikelnya “Engineering Democracy” dapat membantu kita mengurai kompleksitas diskursus tersebut. Dari sekian banyak model dan praktik demokrasi yang berjalan di berbagai penjuru dunia, Blaug berpendapat bahwa rekayasa demokrasi dapat disederhanakan menjadi dua poros: merepresentasikan kepentingan negara/state disebut dengan Incumbent Democracy (ID) dan kepentingan rakyat/society dengan konsep Critical Democracy (CD).
Dua kutub rekayasa tersebut dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu motivasi/tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Dari sisi motivasi, ID bertujuan menjaga dan memperkuat institusi politik yang ada (state, government, status quo, dsb), sedangkan CD bertujuan memperkuat demokrasi dari sisi “society/people” (partisipasi, pemberdayaan, inklusif, dsb).
Dari sisi metode, ID fokus pada penguatan pemilu, representasi politik, reformasi kebijakan secara top-down di ranah negara, sedangkan CD mendorong adanya deliberasi, komunalisme, dan bottom up di level society. Dari dua aspek tersebut, ID menghasilkan prosedur demokrasi yang stabil tetapi beresiko menjadi elitis dan birokratis, sedangkan CD memperkuat demokrasi secara substansial tetapi berpotensi menimbulkan disorganisasi dan ketidakstabilan politik.
Konsepsi Blaug kemudian menjadi dasar bagi para engineer politik dalam merancang demokrasi melalui tiga pendekatan. Pendekatan Governance-Driven Democracy/GDD mewakili poros ID (Warren, 2009), Democracy-Driven Governance/IDD mengarah pada kutub CD (Bua & Bussu, 2020), dan pendekatan Innovation-Driven Democracy/IDD (Affandi, 2024) bertujuan mencari titik temu/keseimbangan antara ID dan CD melalui inovasi demokrasi.
Ketiga pendekatan tersebut menjadi pilihan dalam mendesain sistem pemilu dan demokrasi yang kontekstual sekaligus fungsional sesuai dengan kebutuhan. Jika menghendaki penguatan kelembagaan demokrasi yang stabil, praktis, dan dilakukan dalam jangka pendek–namun berisiko memperkuat posisi elit dan status quo–GDD menjadi pilihan terbaik. Sebaliknya, jika ingin merancang demokrasi yang lebih substantif, dengan daulah rakyat sebagai hulu dan hilirnya, maka proyek jangka panjang tapi “bergelombang” dalam skema DDG dapat menjadi opsi.
Sementara itu, jika tidak ingin terlalu ekstrem pada dua kutub Incumbent Democracy maupun Critical Democracy, pendekatan IDD perlu dipertimbangkan lebih serius. Fokus IDD adalah bagaimana mendesain inovasi kelembagaan (state) tanpa kehilangan substansi demokrasi yang tecermin pada kuasa rakyat/society dengan lebih praktikal dan fleksibel.
Pemilukada melalui DPRD: “Memperkuat atau Memperlemah” Demokrasi?
Apakah pemilukada melalui DPRD dapat menjadi “obat”, atau malah menjadi “euthanasia” bagi demokrasi di masa depan? Tergantung dari sisi mana kita melihatnya.
Manakala narasi perubahan sistem pemilu dengan mengembalikan pemilukada melalui pemilihan DPRD hanya dilatari oleh tingginya ongkos politik yang dikeluarkan para kandidat, tentu mudah bagi publik menyimpulkan bahwa tawaran itu dibuat demi kepentingan elit. Apalagi, narasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para ketua dan petinggi partai yang hadir di acara Partai Golkar. Selain itu, sejumlah elit politik juga terkesan menyalahkan rakyat/publik, karena tingginya pragmatisme pemilih memunculkan biaya tambahan dalam bentuk “money politics”. Jika betul hanya ini dasar pemikiran yang digunakan, menghukum rakyat dengan mencabut hak pilihnya dalam pemilukada adalah gagasan naif, dangkal, dan mencerminkan kemunduran demokrasi.
Mengeliminasi pemilihan langsung yang menjadi puncak manifestasi kedaulatan rakyat dan menyerahkannya kepada lembaga perwakilan rakyat hanya akan mengarahkan kita pada kutub Incumbent Democracy. Dalih bahwa dipilih melalui DPRD sama halnya dengan dipilih secara demokratis memang tidak memberi efek fatality pada demokrasi, tetapi memberi sinyal kuat bahwa demokrasi semakin pro-elit. Hal itu ditandai dengan pembatasan dan kontrol terhadap partisipasi, penyederhanaan, rasionalisasi prosedur demokrasi hingga menarik hak pilih rakyat. Semuanya juga menjadi ciri kuat bangkitnya otoritarianisme baru yang harus diantisipasi.
Di sisi lain, kebutuhan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan memperkuat masyarakat agar moral hazard politik transaksional tidak dominan, juga tidak kalah penting untuk segera dilakukan. Di sinilah dibutuhkan peran teoritisi dan perekayasa demokrasi, untuk merancang-bangun tatanan demokrasi yang cocok dan khas Indonesia. Tentu tidak dalam waktu singkat, tetapi adanya kesadaran untuk membangun Critical Democracy melalui skema deliberasi, inklusi dan pemberdayaan rakyat, harus menjadi misi kebangsaan kita di masa depan.
Mencari titik temu dan keseimbangan
Kita berharap pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih sebatas wacana, sehingga pernyataan Presiden Prabowo Subianto dapat dimaknai sebagai trigger atau semacam early warning bagi publik dan komunitas politik untuk mengkaji secara serius tata kelola demokrasi di masa depan. Ada cukup waktu bagi kita untuk melakukan refleksi dan evaluasi menuju pemilu serentak 2029.
Namun, jika dibutuhkan keputusan lebih cepat dengan mengupayakan keseimbangan antara state vs society, elit vs rakyat, atau incumbent vs critical, pendekatan IDD dapat menjadi alternatifnya. IDD mengasumsikan adanya integrasi antara state dan society dalam membangun proyek demokrasi dengan merumuskan atau menemukan kesamaan kepentingan (common interest). Ketika common interest terbangun, upaya-upaya perbaikan dapat dilakukan secara lebih fleksibel, inovatif, tanpa “merombak” bangunan kelembagaan yang sudah ada (Affandi, 2024).
Terkait mahalnya biaya politik, misalnya, pendekatan IDD tidak sesederhana dengan melimpahkan kesalahan hanya kepada society/people yang dianggap pragmatis. Tentu ada kontribusi dari kubu state/elit politik dalam meningkatkan fenomena money politics, yang sengaja melakukan vote buying dengan harapan bisa memenangi kontestasi. Oleh karena itu, penting bagi para teoritisi, praktisi, dan para pengambil kebijakan untuk memutuskan terlebih dahulu apa yang menjadi common interest dalam rekayasa demokrasi ke depan. Isu mahalnya ongkos pemilukada harus dipersempit pada efisiensi penyelenggaraan pemilu, bukan pada biaya kandidasi yang sangat personal dan terkadang susah diukur.
Jika hal ini telah disepakati, tentu kita tidak akan gegabah mencabut hak pilih rakyat pada pemilukada yang akan datang. Ada beberapa opsi dan prosedur yang dapat dilakukan dengan mengedepankan inovasi dan memperhatikan keseimbangan antara state vs society. Merekayasa sistem pemilu, sangat mungkin dilakukan tanpa harus membunuh demokrasi dengan mengeliminasi pemilu sebagai agenda akbar politik. Salah satunya dengan merumuskan desain kelembagaan inovatif melalui pemanfaatan teknologi yang efisien, efektif dan akuntabel dalam bentuk e-election, e-voting hingga i-voting, dll.
Wacana tersebut juga sudah lama didiskusikan dan telah banyak contohnya di negara lain, tetapi belum bisa segera diwujudkan karena kita belum serius menjalankannya. Opsi lain, misalnya, mengkaji penyelarasan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan, yakni mengembalikan posisi pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat/administrator. Dengan kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah pusat di daerah, gubernur dapat ditunjuk langsung oleh presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Mekanisme tersebut mampu memangkas kebutuhan anggaran pemilukada yang dilakukan hanya pada tingkatan kabupaten/kota.
Jika sistem pemilu adalah instrumen politik paling manipulatif, maka harus dipastikan bahwa upaya apa pun untuk menata ulang pemilu wajib melibatkan semua pihak (state dan society). Dengan demikian, desain pemilukada ke depan tidak terlalu ekstrem mengarah ke Incumbent Democracy yang dapat terpeleset menjadi new-authorianism, tetapi juga tidak fanatik ke society/critical democracy yang dapat overlapping menjadi populism hingga anarcho-communalism.
*Penulis adalah dosen Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id