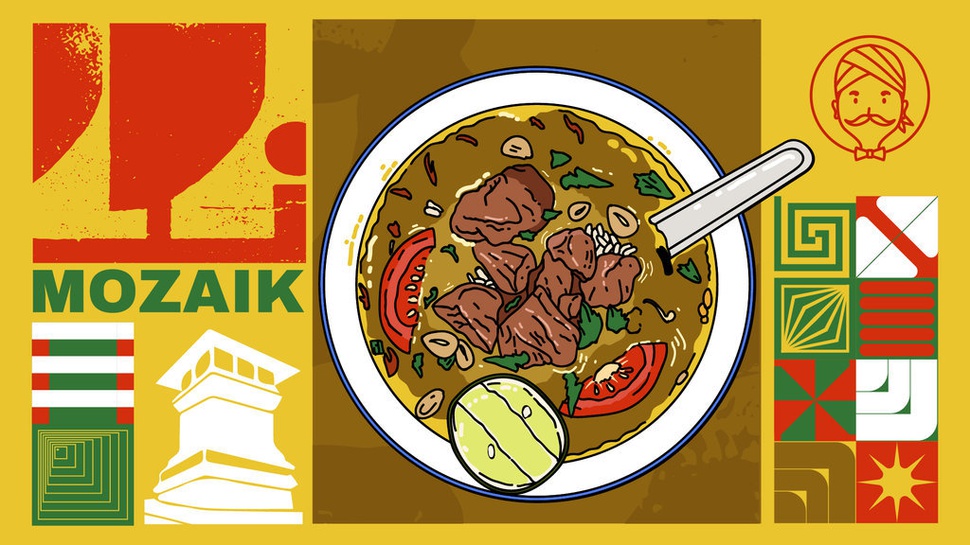tirto.id - Sunan Kudus bukan orang Jawa totok. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab, Uzbekistan, dan Champa. Belajarnya pun ke Palestina. Namun dalam urusan syiar agama, ia paham betul relung budaya masyarakat Jawa.
Hingga kini, petilasan Sunan Kudus yang merekam kearifan dakwahnya masih bisa disaksikan, baik dalam bentuk benda seperti Masjid al-Aqsha dan menaranya, maupun tak benda seperti seruannya untuk tidak menyembelih sapi.
Dari al-Quds hingga Kudus
Kabupaten Kudus terletak di Jawa Tengah, berbatasan dengan Demak di barat daya, Jepara di barat laut, Pati di sebelah timur, dan Grobogan di sebelah selatan. Semula masyarakat menyebutnya Tajug. Nama Kudus digunakan seiring berjalannya Islamisasi di wilayah itu.
Perubahan tersebut tidak lepas dari sosok Sunan Kudus, salah satu figur penting di Kesultanan Demak. Saat muda Sunan Kudus yang bernama asli Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan sempat melanjutkan pendidikan di Palestina. Masa belajarnya di negeri itu bersamaan dengan pagebluk yang memakan banyak korban.
Atas usaha Ja’far Shadiq, wabah tersebut musnah. Amir Palestina yang kagum dengan kemampuannya lantas memberi Ijazah Wilayah padanya, suatu kewenangan untuk mendiami daerah tertentu di wilayah kekuasaannya.
Dalam perkembangannya, Ja’far Shadiq memohon kepada Amir Palestina agar diizinkan memindahkan kewenangan tersebut ke Pulau Jawa. Setelah diizinkan, ia pulang ke Jawa dan membangun sebuah masjid di Kudus yang diberi nama Masjid al-Aqsha, meniru nama masjid legendaris di al-Quds atau Yerusalem, Palestina.
Seturut Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid II (2005:54), dari kata al-Quds yang secara bahasa bermakna “suci”, nama Kudus dipakai untuk menyebut daerah yang menjadi “kota keagamaan, kota suci, dan mempunyai masjid yang besar lagi indah” itu. Ja’far Shadiq sendiri kemudian populer dengan panggilan Sunan Kudus.
Hingga kini silsilah Sunan Kudus masih menjadi polemik. Satu versi menyebutnya sebagai putra Sunan Undung, yang konon memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Mesir. Setelah menemui sepupunya di Cirebon yakni Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, Sunan Undung pergi ke Ampeldenta, Surabaya, dan menjadi murid Sunan Ampel.
Hubungan Sunan Ampel dan Sunan Undung sangat dekat, lebih dari guru-murid. Itu sebabnya, Sunan Ampel menikahkan muridnya itu dengan salah satu cucunya yang bernama Nyi Ageng Manila, adik Raden Maqdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Keduanya lantas dikaruniai seorang anak bernama Ja’far Shadiq alias Sunan Kudus.
Versi lain menyatakan Sunan Kudus putra Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung bin Ali Murtadha bin Ibrahim al-Samarqandi. Ia menikah dengan Dewi Rukhil, putri Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel bin Ibrahim al-Samarkandi. Jadi, Sunan Kudus dan istrinya adalah cicit Ibrahim al-Samarqandi.
Dalam Hikayat Hasanuddin disebutkan, karena hubungan kekerabatan dengan Sunan Ampel, Sunan Ngudung dipercaya menjadi imam keempat Masjid Demak dengan gelar Penghulu Rahmatullah di Undung. Mengikuti karier ayahnya, pada 1527 Sunan Kudus juga diangkat menjadi imam kelima di masjid yang sama.
Akulturasi adalah Kunci
Sunan Kudus seorang polymath. Kepakarannya dalam rumpun ilmu agama terentang mulai ilmu al-Qur’an, Kalam, Hadis, Tafsir, Sastra, Mantiq, hingga Fikih. Di Kesultanan Demak, ia menduduki jabatan qadhi atau hakim sekaligus faqih alias yuris. Sementara di lingkaran Walisongo, ia dikenal sebagai Waliyyul ‘Ilmi, pemegang otoritas keilmuan saat itu.
Sebagai bagian dari strategi dakwahnya, Sunan Kudus menggubah Gending Maskumambang dan Mijil yang menceritakan proses penciptaan manusia. Ia juga mengajarkan Gusjigang, akronim bagus, ngaji, dagang; sebuah prinsip hidup di mana setiap pemuda harus berakhlak bagus, pandai mengaji, dan ulet dalam berdagang.
Di tengah masyarakat yang ratusan tahun menganut ajaran Hindu-Budha, Sunan Kudus menjalankan dakwahnya dengan kearifan dan semangat toleransi. Demi menjaga perasaan mereka sekaligus agar Islam mudah diterima, ia melarang penyembelihan sapi dan menggantinya dengan kerbau sebagai alternatif konsumsi.
Penganut Hindu-Budha menjalankan Ahimsa, yaitu seruan untuk tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Menyembelih sapi jelas melanggar aturan ini. Selain itu, dalam ajaran Hindu sapi merupakan hewan yang disakralkan. Mamalia ini bahkan digambarkan sebagai ibu pertiwi yang memberikan kesejahteraan di muka bumi.
Selain warisan tak benda berupa Gending Maskumambang dan Mijil, etos kerja Gusjigang, dan seruannya untuk tidak menyembelih sapi sebagai wujud toleransi terhadap penganut Hindu-Budha, strategi akulturasi Sunan Kudus dalam dakwah juga terlihat pada bangunan masjid yang didirikannya, yaitu Masjid al-Aqsha.

Masjid al-Aqsha dan Soto Kudus
Seturut Syaiful Arif dalam “Strategi Dakwah Sunan Kudus” (2014:249), meskipun syiar Islam yang dilakukan Sunan Kudus membawa serta budaya baru, tapi hal tersebut tidak bersifat ikonoklastik alias menghancurkan ikon-ikon yang sudah lebih dahulu ada. Ikon-ikon tersebut justru dipertahankan untuk kemudian diisi dengan “ruh” baru, yaitu nilai-nilai Islam.
Masjid al-Aqsha, disebut juga Masjid al-Manar atau Masjid Menara Kudus berada di daerah Kauman, pusat kota Kudus. Peletakan batu pertama bangunan yang secara arsitektur menunjukkan akulturasi budaya Islam, Hindu, dan Budha itu dilakukan pada 19 Rajab 956 H. atau bertepatan 23 Agustus 1549 M.
Keterangan tersebut didasarkan pada sebuah inskripsi Arab dengan khat Tsuluts Qadim yang terpahat pada lempengan batu dan diletakkan di atas dinding mihrab Masjid al-Aqsha. Prasasti yang berisi sengkalan lamba (informasi pendirian bangunan dengan rangkaian kata) itu memiliki panjang 46 sentimeter dan lebar 30 sentimeter.
Masjid al-Aqsha memiliki sepuluh pintu dan empat jendela. Di dalam ruangan terdapat delapan soko guru atau tiang utama berbahan kayu jati. Tidak seperti kebanyakan masjid, masjid ini memiliki dua gapura, pertama di luar masjid yang disebut Lawang Kembar atau Pintu Kembar, dan kedua di dalam ruang utama masjid.
Gapura atau paduraksa yang berada di dalam masjid semula berada di luar. Ketika masjid diperluas dan demi mempertahankan bangunan bersejarah, gapura tersebut tidak dihancurkan. Jika diamati, kedua gapura memiliki bentuk yang sangat mirip dengan kori agung, yakni gapura yang banyak ditemukan di Bali.
Lokasi Masjid al-Aqsha dekat dengan kediaman Sunan Kudus dan merupakan episentrum gerakan dakwah saat itu. Masjid ini terbilang unik karena menunjukkan akulturasi berbagai budaya sekaligus toleransi masyarakat dalam arsitektur bangunannya, yang dimaksudkan Sunan Kudus untuk mempermudah transmisi nilai-nilai Islam.
Selain gapura, jejak akulturasi itu juga bisa disaksikan pada bentuk menara yang menyerupai Pure Agung, yaitu pure besar tempat menyimpan abu jenazah para menak Majapahit. Menara yang terbuat dari bata merah setinggi 18 meter dan luas 100 meter persegi itu dihiasi 32 piring keramik dan ukiran khas bermotif Hindu-Jawa.
Di tempat wudhu Masjid al-Aqsha, jejak akulturasi sekaligus toleransi juga bisa kita saksikan. Pada dinding pancuran atau saluran air terlihat relief yang konon bersumber dari ajaran Budha. Relief yang menyerupai sulur-sulur tersebut bermakna Delapan Jalan Kebenaran atau Asta Sanghika Marga.
Seruan Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi demi menjaga perasaan para penganut Hindu-Budha, selain merupakan wujud toleransi beragama juga turut memengaruhi citarasa kuliner masyarakat Kudus. Jika di kota lain soto daging berbahan daging sapi, di Kudus hidangan tersebut disajikan dengan daging kerbau.
Selain untuk soto, daging kerbau juga diolah masyarakat Kudus menjadi sate dan pindang. Sate Kudus terbuat dari daging kerbau yang dicincang, diberi bumbu, dililit, lalu dibakar. Sedang Pindang Kudus terbuat dari daging kerbau yang dipotong-potong lalu dimasak dengan santan, kepayang, dan daun melinjo.
Soto, sate, dan pindang ala Kudus yang menggunakan daging kerbau sebagai bahan dasar tidak lain karena kuatnya pengaruh ajaran Sunan Kudus tentang toleransi. Meski kini mayoritas warga di kabupaten tersebut memeluk Islam dan Sunan Kudus telah wafat ratusan tahun lalu, ajarannya tak lekang oleh zaman.
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Nuran Wibisono