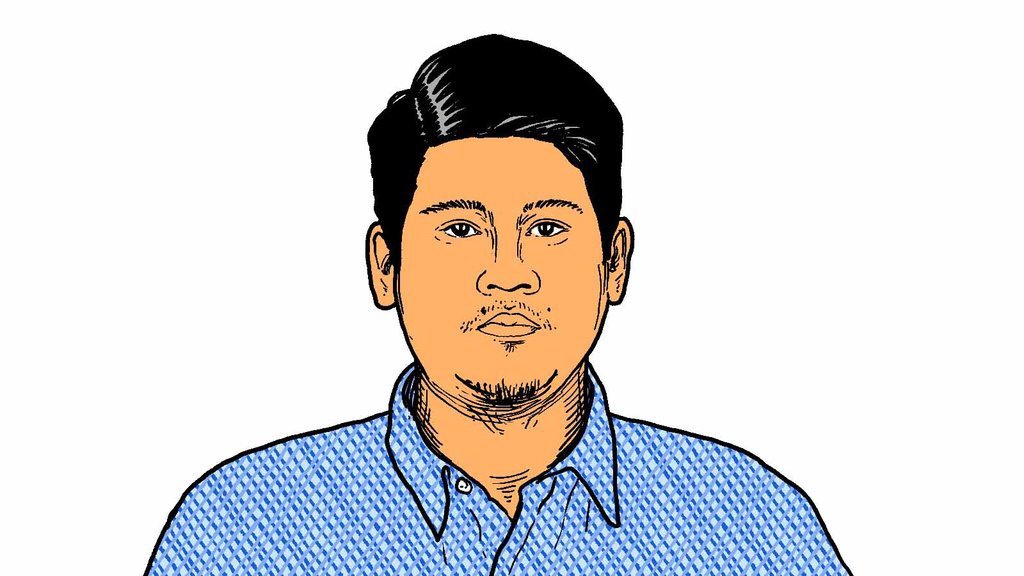tirto.id - Hijrah merupakan konsep sentral dalam tradisi Islam. Sentralitas hijrah dapat dilihat pada digunakannya peristiwa hijrah sebagai penanda tahun oleh masyarakat Islam yang pergantiannya ke 1442 baru saja kita rayakan. Hijrah juga menandai “karir” kenabian rasul Muhammad dalam babak Makiyah dan Madaniah, pembabakan yang kemudian membagi ayat-ayat dalam Al-Qur’an berdasarkan ruang-waktu pewahyuannya. Sebagai peristiwa menyejarah, jarang sekali ada yang bisa menandingi hijrah sebagai titik-balik dramatis, terlebih jika kita menghubungkannya dengan besar populasi muslim hari ini dan segala dinamika global yang timbul karenanya.
Sentralitas hijrah membuatnya menjadi konsep yang padat dan kaya makna. Dalam “Hijra As History and Metaphor: A Survey Of Qur'anic and Hadith Sources” yang terbit di jurnal The Muslim World (April 1998) Daod Casewit membagi pemaknaan hijrah dalam dua jenis berdasarkan rujukan Al-Qur’an dan Hadits: yaitu hijrah sebagai peristiwa historis itu sendiri dan hijrah sebagai metafora. Jika pemaknaan hijrah sebagai peristiwa historis telah berakhir dengan Fathul Makkah, pemaknaan hijrah sebagai metafora belum final, belum berakhir, masih terbuka sebagai arena kontestasi pemaknaan.
Keterbukaan “hijrah” sebagai arena kontestasi pemaknaan dalam rujukan metafora dapat dilihat pada bagaimana beberapa kelompok Islam menggunakan istilah hijrah secara sepihak. Daulah Islamiyah yang dipimpin Baghdadi misalnya, menggunakan istilah hijrah untuk mengajak kaum muslim seluas dunia bergabung dalam apa yang ia klaim sebagai kekhalifahan di Irak dan Suriah alias ISIS.
Dalam lingkup nasional di Indonesia, “hijrah” sebagai metafora pertaubatan individual mengemuka di kalangan kaum muda muslim sejak beberapa tahun terakhir. Pemuda Hijrah, lembaga dakwah asal Bandung, merupakan salah satu yang paling awal memulai tren ini. Metafora hijrah sebagai pertaubatan atau perbaikan diri individual ini sebenarnya memiliki pijakan kuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai pendekatan dakwah, metafora hijrah juga telah menerbitkan kegairahan Islami yang mewarnai komunitas-komunitas muda muslim. Melalui jejaring internet, tren yang bermula dari komunitas-komunitas muda di Bandung ini kemudian dapat meluas hingga cakupan nasional, khususnya di kota-kota besar dengan penduduk mayoritas muslim.
Hijrah yang Mana?
Gerakan Hijrah yang belakangan menjadi tren ini merupakan salah satu tarikan dari proses Islamisasi di Indonesia yang arenanya adalah masyarakat luas dan dipengaruhi oleh berbagai konteks. Seperti halnya proses islamisasi di tantangan kolektif kemudian diubah menjadi tantangan individual saja—yang tidak dapat disebut sebagai proses tunggal alih-alih proyek yang heterogen baik dalam nilai maupun organisasi kepelakuannya—Gerakan Hijrah tidak bisa dibilang sepenuhnya padu dan koheren. Di tataran metode dan penekanan, kelompok-kelompok Hijrah juga beragam. Ada kelompok yang menekankan Hijrah meninggalkan hubungan lawan jenis sebelum menikah seperti yang dilakukan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) yang dibesut La Ode Munafar; ada kelompok Hijrah yang fokusnya pada meninggalkan bermusik seperti The Strangers Al-Ghuroba yang diinisiasi para mantan musisi. Ada pula kelompok Hijrah yang berfokus pada busana menutup aurat seperti Hijab Squad yang dipelopori para pesohor muslimah seperti, Shireen Sungkar, Alyssa Soebandono, Dewi Sandra, dan lain-lain.
Keberagaman komunitas yang bergerak mengatasnamakan Hijrah ini menjadikan Gerakan Hijrah payung yang mewadahi bermacam-macam figur, nilai, prioritas, dan metode pendekatan yang diusung. Tidak satu pun agen Gerakan Hijrah yang cukup memiliki legitimasi untuk menafsir dan menentukan sendiri arah Gerakan Hijrah.
Meskipun kecenderungannya berbeda-beda, berbagai komunitas Hijrah memiliki beberapa kesamaan karakter yang membuat komunitas-komunitas ini berada dalam satu payung. Pertama, gerakan ini dilihat oleh berbagai media massa sebagai tren para pesohor level nasional yang mengubah gaya hidupnya menjadi, apa yang menurut mereka, lebih Islami. Nama-nama seperti Arie Untung yang pernah menjadi VJ MTV; sederetan artis yang dulu dikenal lewat sinetron seperti Dude Herlino, Teuku Wisnu, Shireen Sungkar, Alyssa Subandono, dan Dewi Sandra; mantan musisi seperti Sakti eks Sheila on Seven yang mengubah namanya menjadi Salman Al-Jugjawy, Yuki eks Pas Band, Ucay eks Rocket Rockers, dan lain-lain; presenter televisi Fitri Tropica; hingga skateboarder Fani Krismandar merupakan deretan pesohor yang disebut Majalah Tempo “Ramai-ramai Berhijrah” (Tempo, 2019).
Kedua, komunitas-komunitas Gerakan Hijrah aktif berdakwah melalui media sosial internet. Menurut Quinton Temby, peneliti ISEAS Yusof Ishak Singapura, gerakan Hijrah dilirik kaum muda karena keluwesan di dunia jejaring. Keluwesan online ini tidak ditemukan pada organisasi-organisasi besar Islam yang mapan seperti NU dan Muhammadiyah (South China Morning Post, 2019). Para pesohor yang ramai-ramai berhijrah juga kemudian menyiarkan kesalehannya lewat media sosial sambil mendorong para penggemar untuk mengikuti langkah mereka. Akun-akun media sosial komunitas-komunitas Hijrah juga menghimpun banyak pengikut. Akun Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, misalnya, diikuti lebih dari satu juta pengikut, sedang akun Pemuda Hijrah (shiftmedia.id) diikuti hampir dua juta pengikut.
Ketiga, lantaran pendekatan dakwahnya lewat media sosial inilah Gerakan Hijrah lekat dengan kaum muda, khususnya yang termasuk dalam kurun generasi milenial. Laporan The Generation Z: Global Citizenship Survey yang dikerjakan Varkey Foundation menunjukkan 93 persen kaum muda Indonesia percaya iman agama penting bagi kebahagiaan. Angka ini jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 45,3 persen. Melalui hasil survey yang melibatkan 20.000 kaum muda di 20 negara ini kita dapat melihat kaum muda Indonesia sebagai lahan dakwah yang subur, terlebih dengan kemudahan akses melalui media sosial internet.
Keempat dan barangkali yang paling penting, komunitas-komunitas Gerakan Hijrah mampu membingkai makna “Hijrah” menjadi laku berbenah diri menjadi lebih Islami. Menurut Wakyudi Akmaliah, peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, fenomena serupa Gerakan Hijrah pernah terjadi pada 1970-an. Hanya saja pada waktu itu istilah yang digunakan adalah “Taubat” ketimbang “Hijrah”. (Tempo, 2019) Sedang menurut Muhammad As’ad, pengajar Universitas Hasyim Asy’ari Jawa Timur, makna “Hijrah” digeser oleh Gerakan Hijrah dari makna teologis ke makna kultural. Dalam penelitian ini, pembingkaian makna ini akan dilihat sebagai pengunaan istilah “Hijrah” sebagai metafor ketimbang pergeseran makna.
Ada beragam sambutan baik dan kewaspadaan terkait tren Gerakan Hijrah ini. Salah satu artikel Republika merayakan Gerakan hijrah sebagai exceptionalism di tengah derasnya arus kaum muda milenial yang menurutnya semakin sekuler dan menjauh dari agama. Fenomena Gerakan Hijrah, tulisnya, “membuktikan kaum milenial bukan golongan yang monolitik yang dapat disimpulkan secara satu dimensional”. Lebih jauh, artikel tersebut menuliskan fenomena Hijrah ini memiliki karakter yang khas di masing-masing kota. “Di Bandung, misalnya, gerakannya lebih trendi melalui komunitas hobi. Sementara di Jakarta, ada egalitarianisme yang coba diangkat, di Yogyakarta lebih membumi dengan masyarakat, serta di Jawa Timur tradisionalisme masih mengakar” (Republika, 2018).
Pihak-pihak yang menyambut baik Gerakan Hijrah cenderung seragam dalam melihat fenomena ini, yaitu sebagai bangkitnya ghirah Islam kaum muda. Di sisi lain, pihak yang lebih waspada dalam melihat Gerakan Hijrah, berwaspada atau bahkan bercuriga lantaran alasan yang berbeda-beda. Pertama, ada kewaspadaan yang muncul lantaran Gerakan Hijrah akan, atau bahkan sudah, menggeser otoritas keislaman dari institusi-institusi Islam yang telah mapan. Para pendakwah baru dari Gerakan Hijrah, yang banyak di antaranya tidak berakar dari institusi Islam mapan seperti NU atau Muhammadiyah, dipandang tidak berlegitimasi untuk berdakwah di hadapan umat banyak. Quinton Temby melihat NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, sebagai salah satu yang paling sinis terhadap Gerakan Hijrah, dan melihat Gerakan Hijrah tak lebih dari para pesohor yang mencoba menggairahkan lagi karirnya setelah masa keemasan sudah lewat (South China Morning Post, 2019).
Kewaspadaan kedua muncul lantaran Gerakan Hijrah menjadi tren bersamaan dengan menguatnya gelombang populisme Islam di Indonesia. Ketika tren Hijrah semakin menjamur di kota-kota besar, kelompok-kelompok Islamis sedang rajin turun ke jalan. Ditambah lagi dengan konsolidasi kekuatan Islamis dengan kandidat dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto. Beberapa figur Gerakan Hijrah seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Arie Untung juga turut serta baik dalam demonstrasi 212 maupun pernyataan dukungan untuk Prabowo. Kewaspadaan terhadap Gerakan Hijrah pun muncul dari kelompok-kelompok sekuler dan pendukung kandidat presiden petahana Joko Widodo.
Kewaspadaan ketiga barangkali adalah kewaspadaan yang berkaitan dengan konteks global. Penggunaan istilah “Hijrah” sebagai metafora dari pertaubatan diri menuju gaya hidup Islami barangkali sedang tren di lingkup nasional Indonesia, namun di lingkup global Islamic State (IS) melalui media propagandanya juga menyerukan Hijrah. Namun Hijrah yang diseru IS bukan sekedar mengubah gaya hidup menjadi Islami dengan meninggalkan musik, menghapus tattoo, dan rajin ke masjid. IS melalui majalan onlineDabiq menyeru, atau lebih tepatnya menyelewengkan seruan Hijrah, demi menarik orang-orang dari berbagai negara untuk datang dan bergabung bersama IS yang dipimpin Al-Baghdadi dalam agenda politik dan militernya di Iraq dan Suriah. IS memanfaatkan konsep Hijrah geografis tradisional , menyebut semua wilayah yang belum dikuasai sebagai Darul Harb dan hanya daerah di bawah kekuasaan IS yang dapat disebut Darul Islam, sehingga kaum Muslim seluas dunia harus meninggalkan negerinya, lalu bergabung bersama dan membantu agenda IS di wilayah yang dikuasainya.
Berbagai kewaspadaan ini diwarnai biasnya masing-masing sehingga mengajukan kritik tehadap Gerakan Hijrah secara mendalam saja tidak cukup. Kewaspadaan terkait legitimasi pendakwah Hijrah misalnya, dipengaruhi bias organisasi-organisasi Islam mapan yang melihat Gerakan Hijrah sebagai pesaing yang berpotensi merebut jamaah. Apalagi status pendakwah belakangan bisa didapatkan melalui pengakuan dan popularitas melalui media daring, tidak lagi harus melalui sistem hirarkis oleh tantangan kolektif kemudian diubah menjadi tantangan individual saja. Kewaspadaan yang menyamakan Gerakan Hijrah sebagai cabang dari populisme Islam juga terlalu menyederhakan Gerakan Hijrah yang majemuk. Kenyataannya, beragam kelompok Hijrah sangat menjaga jarak dari politik lantaran menganggap politik itu tidak keren, bahkan yang berhaluan Salafi mengharamkan politik elektoral. Sedang kewaspadaan yang menyamakan Gerakan Hijrah dengan kampanye IS abai pada bagaimana Gerakan Hijrah di Indonesia memaknai “Hijrah” secara metafor dengan makna yang berbeda, namun juga berkecenderungan alarmist dan Islamofobik.
Kritik yang mendalam terhadap Gerakan Hijrah dengan pemaknaan hijrahnya sebagai pertaubatan individual dan berbenah diri dengan gaya hidup islami justru dapat berlandasakan pada teks Al-Qur’an, Hadits, dan sirah yang kemudian ditempatkan pada konteks kekinian.
Sebagai peristiwa historis, Hijrah terbagi menjadi Hijratul-ula dan Hijra al-nabawiyya. Hijratul-ula ke Habasyah dihitung sebagai pelarian sementara di bawah perlindungan Raja Najasyi yang beragama Kristen, nabi Muhammad sendiri tidak ikut dalam Hijrah ini. Baru kemudian Hijra al-nabawiyya ke Madinah dihitung sebagai Hijrah permanen yang hukumnya wajib bagi seluruh umat Muslim yang berada di Makkah dalam keadaan dipersekusi. Penekanan wajibnya Hijra al-nabawiyya bersama Nabi Muhammad sebagaimana tertera dalam Qur’an surat An-Nisa ayat 100, “Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Hijrah dijadikan laku yang wajib dan utama, sehingga mereka yang meninggal dalam keadaan berhijrah diganjar kebaikan. Sebaliknya pada An-Nisa ayat 97 tertulis malaikat menolak alasan seorang Muslim yang meninggal di Makkah dalam keadaan belum berhijrah. “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’. Mereka menjawab: ‘Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)’. Para malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?’. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat Kembali,”.
Jadi dapat kita lihat baik bahwa Hijrah sebagai peristiwa historis yang dijelaskan dalam Al-Qur’an lekat dengan kolektivitas umat. Hijrah historis ini diserukan bukan pada kaum muslim sebagai individu yang terpisah-pisah, melainkan sebagai kolektif umat yang solid. Karena diserukan pada umat sebagai kolektif inilah Hijrah dapat menjadi siasat geopolitik yang diorkestrasi secara kolosal oleh Nabi Muhammad. Hijrah ke Madinah ini yang kemudian menjadi titik balik sejarah awal umat Islam akhirnya mampu menaklukkan penindasnya dalam peristiwa Fathul Makkah.
Dengan penaklukkan Makkah maka berakhir pula Hijrah sebagai peristiwa historis. Dalam pengertian ini tidak diserukan lagi kepada umat muslim untuk berhijrah sebagaimana para sahabat nabi di era awal Islam. Meskipun begitu, selain melihat keagungan Hijrah dan mengambil pelajaran berharga dari peristiwa kolosal tersebut, terdapat pula laku yang disebut pengganti terdekat Hijrah, yaitu jihad. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ”Tidak ada Hijrah setelah Fathul Makkah, tetapi (yang ada adalah) jihad dan niat. Maka apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkatlah”. Seperti tertera pada Hadits yang menyatakan berakhirnya Hijrah setelah fathul Makkah, dinyatakan bahwa meskupun Hijrah tekah berakhir, “tapi masih ada jihad”.
Dalam Hadits lain yang dibukukan Ahmad bin Hanbal, diceritakan Nabi Muhammad ketika ditanya “Laku iman apa yang paling baik?”, Nabi menjawab, “Hijrah”. Lalu ketika ditanya “Hijrah macam apa yang paling baik?”, nabi menjawab, “Jihad” (Casewit, 1998). Ada pun jihad di sini maknanya lebih luas dari sekedar jihad perang yang berdimensi kekerasan. Seperti tertera dalam Hadits yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sahih Ibn Hibban, “Jihad yang paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah”. Sedang Hadits berstatus hasan yang diriwayatkan Trimidzi menyebutkan, “Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang zalim.”
Kampanye Hijrah yang kini diusung oleh Gerakan Hijrah di Indonesia lebih dekat pada metafor niat dan amal baik, “perjalanan” dengan orientasi moral dan spiritual. Dalam salah satu Hadits Nabi Muhammad bersabda, “Hijrah belum berakhir sehingga berakhirnya taubat, dan taubat tidak akan berakhir sehingga matahari terbit dari sebelah barat.” Inilah yang menjadi landasan dari metafora hijrah sebagai pertaubatan individual. Taubat menjadi analogi yang dekat dengan Hijrah historis lantaran sama-sama bergerak meninggalkan satu hal untuk mendekatkan diri pada satu hal lain. Jika dalam Hijrah historis orang meninggalkan Makkah demi mendatangi Madinah bersama Nabi Muhammad, maka dalam taubat seseorang meninggalkan larangan Allah demi mendekatkan diri pada apa yang diperintahkan Allah. Namun jika Hijrah historis diserukan kepada umat Islam sebagai kolektif, hijrah metafor pertaubatan lebih diserukan kepada muslim sebagai individu.
Dalam dakwah dan unggahannya di media sosial, berbagai kelompok Gerakan Hijrah melulu menggunakan istilah Hijrah sebagai metafor perbaikan diri secara islami dan pertaubatan individual. Dalam berbagai kesempatan, Hijrah juga digunakan sebagai kiasan dari hal-hal yang akrab dengan kehidupan generasi muda perkotaan yang sebetulnya tak bersangkutan khusus dengan keislaman. Hijrah ditempelkan pada proses mencari kerja, memulai bisnis, hingga move on dan mencari jodoh. Attaki dalam salah satu ceramahnya menjelaskan istilah Hijrah yang digunakannya memang bermakna kiasan yang kekinian. Dalam salah satu ceramahnya, istilah Hijrah digunakan sebagai metafora perubahan dari status belum menikah (jomblo) menjadi menikah (Mutiara Islam, 2019). Dalam ceramah ini Attaki mengutip Annisa ayat 97, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”, seolah pertanyaan dalam ayat ini ditujukan pada orang-orang yang belum berani menikah karena alasan materiil. Padahal ayat ini adalah peringatan yang cukup keras bagi para muslim yang memisahkan diri dari kolektif dengan tidak berhijrah ke Madinah pada peristiwa Hijra al-nabawiyya.
Akibat penggunaan Hijrah metafor makna Hijrah menjauh dari asal-muasal historisnya yang penuh keagungan. Istilah “Hijrah” kini memang menjadi populer dalam perbincangan kaum muda muslim perkotaan, khususnya mereka yang berlatar kelas menengah. Namun dalam prosesnya, Hijrah kemudian dilekatkan sebagai kiasan hal-hal yang terlalu sehari-hari. Keutuhan makna Hijrah yang lekat dengan jihad dan kolektivitas umat tergerus oleh penggunaan metafora Hijrah yang menitik-beratkan pada kesalehan individual beserta kiasan-kiasan turunannya.
Tren Hijrah metafor sebagai pertaubatan individual ini juga membawa gelombang depolitisasi yang memang semakin meluas di bawah hegemoni neoliberalisme. Depoliticization dalam kamus Merriam-Webster tergolong sebagai kata kerja yang berarti “to remove the political character of: take out of the realm politics”. Dalam KBBI, padanannya, yaitu “depolitisasi” digolongkan sebagai kata benda yang berarti “penghilangan (penghapusan) kegiatan politik”. Salah satu bentuk depolitisasi di level masyarakat dapat dilihat pada bagaimana isu-isu yang merupakan tantangan kolektif kemudian diubah menjadi tantangan individual saja.
Pendakwah-pendakwah Gerakan Hijrah melulu menekankan dilema menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sebagai perjuangan individual. Perkara-perkara sosial yang turut meningkahi dilema tersebut seperti kesenjangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi politik tidak masuk dalam agenda Hijrah. Dalam hal ini, depolitisasi terjadi ketika Gerakan Hijrah menggunakan strategi retorika yang menutup kemungkinan istilah “Hijrah” untuk menjadi lebih politis.
Padahal hari-hari ini adalah saat yang krusial bagi umat Islam sedunia untuk menggali kembali pelajaran dari Hijrah histroris, yang bukan hanya sebuah perjalanan spiritual tetapi juga tindakan kolektif dan siasat geografis yang kolosal. Tentu mengambil pelajaran Hijrah untuk memperbaiki diri menuju hidup yang lebih islami juga suatu keutamaan—walaupun kita dapat perdebatkan kembali apa dan bagaimana yang dimaksud dengan “islami” itu. Tapi lebih terutama dan mendesak lagi bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran Hijrah untuk meninggalkan situasi cupet dalam sekat-sekat dan menganiaya diri sendiri, menuju situasi di mana kita tolong menolong dalam kebaikan tanpa terpisah oleh sekat-sekat apa pun.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id