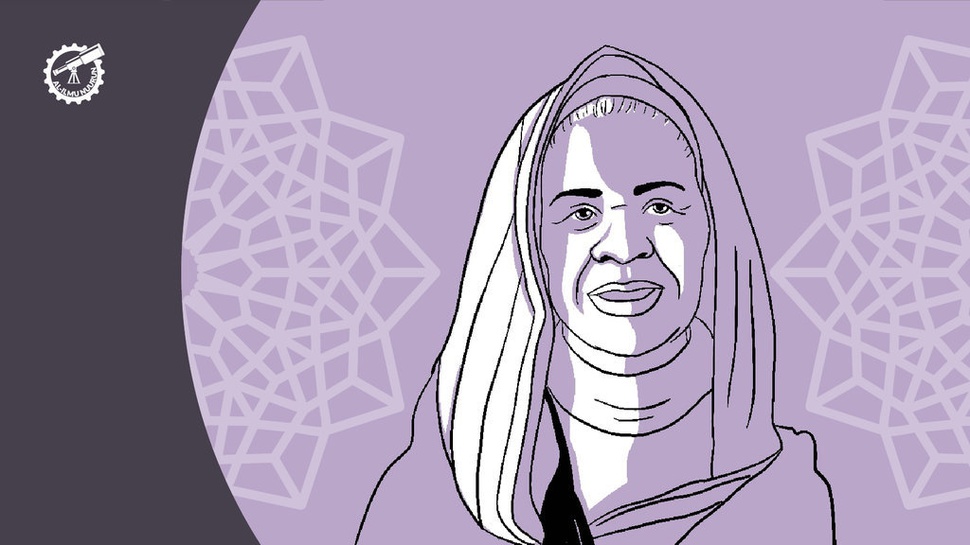tirto.id - Membongkar prasangka itu sulit, terlebih jika sudah terlembaga dan diterima sebagai norma. Untuk mendobraknya, orang membutuhkan keberanian ganda. Misalnya, anggapan klasik yang menuding perempuan tak bisa dipercaya untuk menafsirkan Al-Qur’an karena mereka emosional dan irasional sehingga tak cocok untuk bekerja serius menafsirkan teks. Dalam pandangan, atau tepatnya prasangka, ini perempuan dianggap lemah.
Padahal tak ada larangan tekstual bagi perempuan untuk menafsirkan wahyu. Jika kita merentang sejarah panjang kebudayaan Islam, akan ditemui banyak penafsir dan sosok perempuan yang berkontribusi dalam kehidupan intelektual Islam. Efek kolonialisme dan keterpurukan internal masyarakat muslim ikut berkontribusi dalam hal ini dan mempersulit perempuan mendapatkan legitimasi dan kuasa di tengah masyarakat. Menggugat hubungan gender macam itu tentu tabu di masa tersebut, karena ia masih dianggap isu sensitif.
Tapi mengapa kita tak menoleh kepada teladan dari zaman yang lebih dekat?
Aisha Abd al-Rahman Bint al-Shati di Mesir menjadi contoh paripurna yang berusaha untuk mencari panduan moral dan spiritual kitab suci. Penafsir lain dari Libanon, Nazirah Zayn al-Din (m. 1976), pada umur 20 sudah menulis buku yang mengkritik status inferior perempuan melalui penafsiran teks. Selain Bint al-Shati, di Mesir ada Zainab al-Ghazali (m. 2005) yang menulis komentar Al-Qur’an dari perspektif perempuan. Zainab adalah pendiri Asosiasi Muslimat di Mesir (Jama’at al-Sayyidat al-Muslimat) yang diminta Hassan al-Banna untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Al-Ghazali menolak, tapi ia patuh pada al-Banna.
Penafsir feminis yang nisbi baru muncul di akhir abad ke-20 dan masih aktif hingga kini setidaknya ada dua. Dari Mesir, ada nama Heba Raouf Ezzat yang bersemangat dalam menggali penafsiran Al-Qur’an sekaligus menjadi aktivis hak asasi manusia. Dari Amerika, Amina Wadud menjadi banyak sorotan dengan karyanya, Qur’an and Woman (diterbitkan di Malaysia, 1992). Kemunculan tafsir feminis ini, terlebih dipublikasikan dalam bahasa Inggris, bersamaan waktunya dengan karya berpengaruh dari dua feminis lain yakni Leila Ahmed dan Fatema Mernissi.
Qur’an and Woman segera mendapat tanggapan luas. Penerjemahan ke bahasa Indonesia, Turki, dan Arab muncul dalam rentang waktu lima tahun dan bahasa-bahasa lain pada masa berikutnya. Amina Wadud menjadi figur yang suaranya menggema dalam semangat kesetaraan gender masyarakat muslim, terutama di Asia Tenggara.
Bermula dari Rasisme Amerika
Bernama asli Mary Teasley, Wadud lahir dari keluarga campuran Afrika-Amerika. Ayahnya seorang pendeta Metodis, bagian dari denominasi Kristen Protestan di Amerika. Saat Wadud kuliah di Universitas Pennsylvania, ia memeluk Islam. Tak lama setelah konversi ini, ia tinggal di Libia selama dua tahun. Lalu ia melanjutkan jenjang pascasarjana dalam bidang kajian Islam dan Timur Tengah di Universitas Michigan. Selama masa studi doktoral ini ia menyempatkan diri untuk belajar bahasa Arab, tafsir Al-Qur’an, dan filsafat di tiga kampus ternama Mesir: Universitas Amerika di Kairo, Universitas Al-Azhar, dan Universitas Kairo.
Seperti diakui dalam karya semi-autobiografinya, Inside the Gender Jihad (2006), ia hijrah menjadi seorang muslim lantaran fenomena yang mencekam dirinya dalam menghadapi penindasan ganda sebagai seorang perempuan Afrika-Amerika. Ia terjebak dalam sekam diskriminasi ras dan seksual di Amerika dengan kondisi yang miskin dan tanpa hak istimewa. Ditambah lagi dengan masalah sosial yang diliputi logika kapitalis dan lelaki kulit putih, Amina menemukan Islam sebagai sandaran baru yang “menawarkan perhatian, perlindungan, dukungan finansial, dan pemujaan pada perempuan.” Ini menjadikannya keluar dari sangkar penindasan dan memperjuangkan keadilan bagi banyak orang.
Posisi Wadud sebagai perempuan dan orang dengan ras "berbeda" di Amerika itu membuat tampilan Islam yang lain. Ini termasuk juga identitas muslim Afrika-Amerika sejak masa Malcolm X hingga Sherman Jackson, seorang sarjana muslim terpandang. Melalui Islam, Wadud menemukan wahana untuk memperjuangkan apa yang ia tekankan sebagai ‘keadilan gender’ baik di Barat maupun dunia muslim.
Ia mengakui proses menegakkan keadilan itu tak mudah dan tidak sederhana. Tak ada satu strategi, metode, dan proses serupa obat generik. Di sini, ia juga mengakui relativitas budaya dan konteks dari masyarakat yang berbeda. Kendati ia menekankan secara umum keadilan gender didasarkan pada teori fundamental bahwa Islam itu adil untuk perempuan dan Allah berkehendak menyematkan perempuan dengan marwah kemanusiaan yang paripurna.
Sebagai bagian dari "jihad gender"-nya, Wadud mencari sesuatu yang ia namakan 'hermeneutics of care' untuk memasukkan analisis perempuan dalam menafsirkan ulang ajaran kitab suci. Ia ikut membuka ruang untuk mengawinkan hermeneutika Al-Qur’an dari perspektif gender, yang saat pertama kali dipikirkannya di akhir 1980-an adalah sesuatu yang baru dan segar.
Wadud mengambil metode penafsiran yang diajukan Fazlur Rahman yang berusaha menggali spirit etis dari ajaran Islam. Hermeneutika double movement Rahman—melihat masa kini lalu meneropong ke ruang dan waktu ketika kitab suci diturunkan, kemudian dikembalikan lagi ke masa kini—menjadi model bagi Wadud untuk membangun paradigma hermeneutika feminis-nya. Sebagaimana feminis muslim lain, ia berupaya membongkar wacana fundamental yang menjadi basis paradigmatik pengertian Islam dan muslim. Lalu ia menempatkan perempuan secara sentral dalam politik wacana dan aktivisme sosial-politik.
Metode yang ia bangun dinamakan ‘hermeneutika tauhid’. Metode ini menekankan bagaimana konsep keesaan Allah, yang menjadi basis pewahyuan Al-Qur’an, hadir secara merata. “Kesatuan Al-Qur'an merembes ke berbagai bagian,” tulisnya.
Seperti Rahman, ia berargumen bahwa kitab suci ini membangun paradigma kesetaraan untuk semua umat manusia dalam hal gender, kelas, ras, atau lainnya. Paradigma tauhid ini menekankan baik perempuan maupun lelaki akan dimintai pertanggungjawaban hanya berdasarkan perbuatan masing-masing, bukan dilihat dari jenis kelamin. Dalam bahasa Quranik, pembedanya ialah takwa, yakni yang ditulis Wadud sebagai ‘kesadaran Tuhan’.
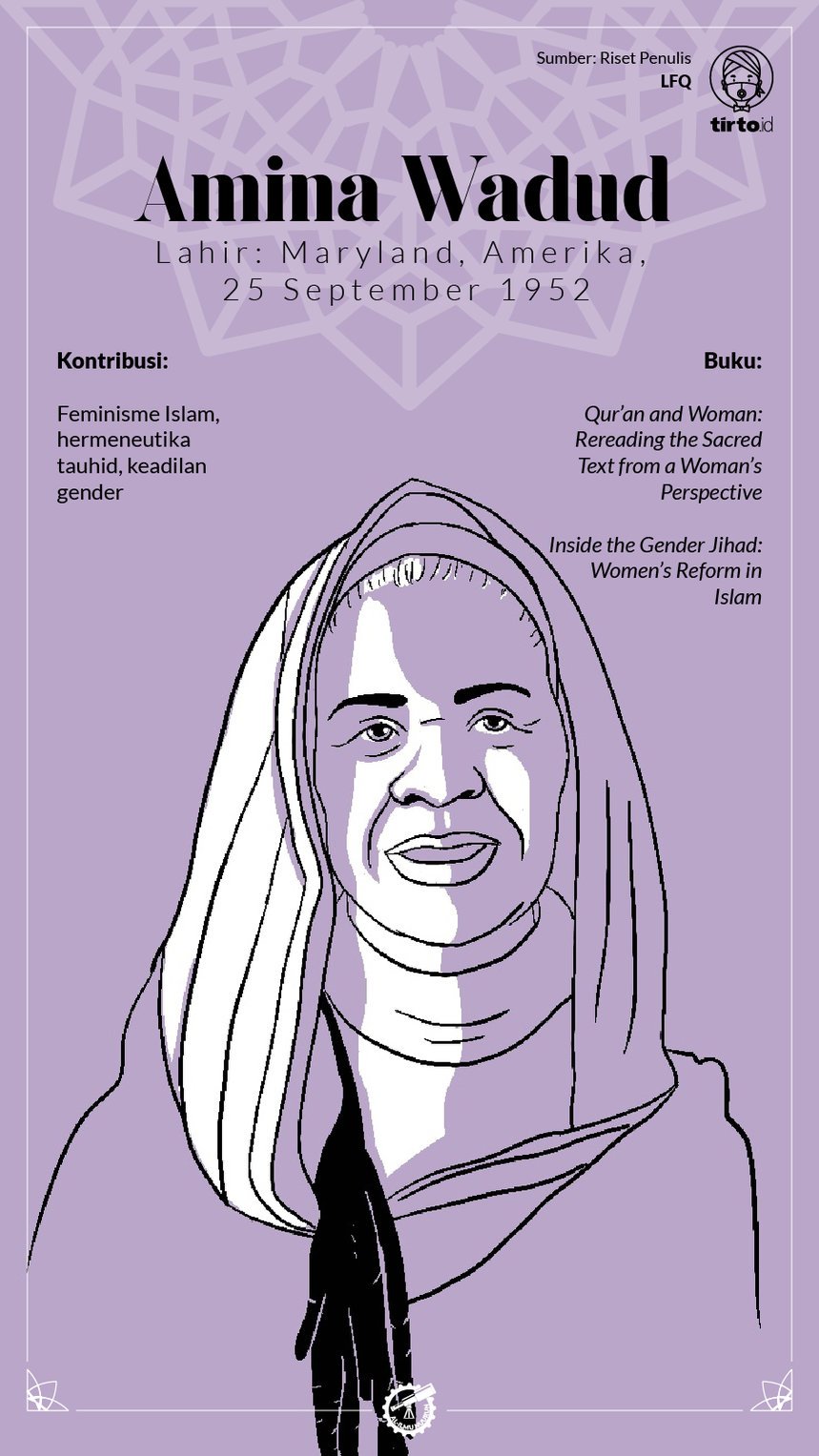
Tafsir yang Tidak Misoginis
Ketika membaca potongan ayat "wa li-l-rijal `alayhinna darajah" (lelaki memiliki satu derajat di atas perempuan) dalam surah Al-Baqarah ayat 228, ia mengartikan darajah terkait dengan takwa, bukan tingkatan seperti dalam terjemahan Al-Qur’an berbahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali. Pada 1990-an terjemahan itu banyak dibaca orang-orang berbahasa Inggris. Lagipula, menurut Wadud, potongan ayat ini bukan prinsip Al-Qur’an secara universal, sehingga ia perlu dibaca sebagai alternatif, bukan diterima secara literal. Hanya dengan menggali ayat-ayat lain secara keseluruhan, prinsip universal bisa ditemukan.
Dalam hal itu, Wadud membaca Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, seperti dalam metode tafsir tradisional, justru untuk menemukan mana yang universal dan mana yang partikular. Memang, ia sejak awal tertarik untuk mendalami semantik kitab suci. “Ketertarikan filologis saya dalam mengetahui kehalusan Al-Qur’an dan kedalaman analisis tafsirnya membuat saya menekankan pembacaan demi konstruksi ambiguitas Quranik,” tulisnya.
Melalui penggalian inilah ia berupaya mendestabilisasi pembacaan atas ayat suci yang berpotensi misoginis. Ia seperti membangun teori abrogasi baru, yakni menegasikan makna ayat yang melecehkan paradigma tauhid dengan prinsip universal Al-Quran: egalitarianisme. Melalui pembacaan ayat-ayat lain, ia memahami bagaimana Al-Qur’an sesungguhnya membangun rujukan yang inklusif-gender. Dengan begitu ia mengesampingkan bahasa yang lebih condong pada pemihakan lelaki—beserta nalar patriarki—dari lingkungan budaya ketika kitab suci ini diturunkan.
Wadud menyumbang pada iklim Islam progresif; bukan hanya pada cara pandang Quranik yang lebih adil dan setara, tetapi juga dalam rangka memperjuangkan keadilan sosial yang ia hadapi di negerinya dan kemudian berjuang membangun jaringan internasional. Di kalangan muslim progresif lain, bukan berarti pendekatannya bebas dari kritik; misalnya datang dari sarjana-pemikir Afrika Selatan Ebrahim Moosa.
Wadud pun mengakui pembacaan perempuan ini tak berarti sempurna dan menyeluruh, kendati ia bersikukuh analisis tekstual ini perlu diupayakan kaum perempuan dan terus disempurnakan, ketimbang menunggu dorongan dari orang lain. Wadud lalu menjadi model sebagai a jihad for justice bagi banyak feminis muslim. Bersama intelektual dan aktivis seperti Asma Barlas, Nimat Hafez Barazangi, dan lainnya, Wadud menjadi teladan bagi generasi feminis muslim selanjutnya.
Peran Wadud semakin mendapat sorotan internasional saat ia memimpin salat bagi jamaah campuran perempuan dan lelaki pada Maret 2005. Meski banyak dikecam, ia lebih memilih diam, kecuali saat diminta stasiun televisi Al Jazeera. Barangkali karena keberanian inilah muncul fenomena imam perempuan dengan berbagai variasinya di Barat. Di Kopenhagen ada Sherin Khankan. Di Berlin ada Seyran Ateş, perempuan keturunan Kurdi-Turki, yang menjadi imam di Masjid Ibn Rushd-Goethe yang lokasinya tak jauh dari Restoran Nusantara.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan