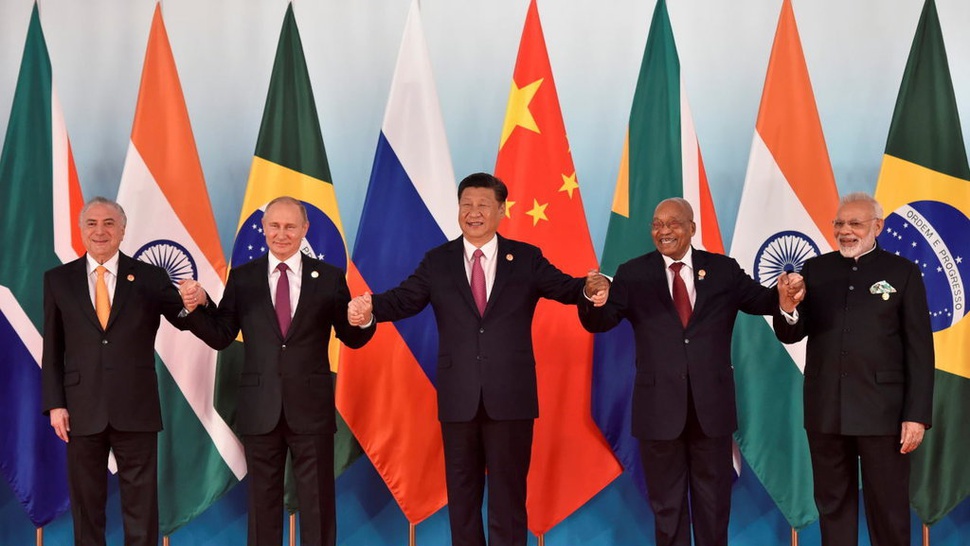tirto.id - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) yang digelar pekan lalu membuahkan 23 kesepakatan kerja sama business to business (skema b to b) antara pengusaha Indonesia dan Cina. Penandatanganan kesepakatan yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini bakal difokuskan pada empat koridor, yakni: Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, serta Bali.
Sejauh ini, sejumlah perusahaan sudah menyetujui skema b to b dengan perusahaan asal Cina. Beberapa di antaranya merupakan proyek sektor energi, seperti elektrifikasi Sulbagut 1 dan Sulawesi Utara 3 yang dikembangkan PT Toba Bara Sejahtera--perusahaan yang sebagian sahamnya dipegang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, ada pula kerja sama untuk dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dikembangkan PT Indonesia Dafeng Heshun dan PT Lentera Damar Amerta. Masing-masing perusahaan akan menggarap proyek PLTA Kayan dan PLTA Salo Pebatua.
Luhut mengatakan, proyek OBOR yang disepakati Cina dan Indonesia itu memang lebih aman karena berbasis pada kesepakatan b to b. Pemerintah tak banyak terlibat, kecuali pada tahap feasibility studies yang berkaitan dengan lingkungan hidup, nilai tambah, skema bisnis, dan pemanfaatan pekerja lokal.
Meski demikian, Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyayangkan minimnya proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) non-PLTA. Bisa jadi, kata dia, itu lantaran tidak adanya perusahaan Indonesia lain yang mengembangkan proyek EBT dengan investor atau lembaga dana dari Cina, selain Indonesia Dafeng Heshun dan Lentera Damar Amerta.
Menurut dia, hal itu menunjukkan pemerintah belum serius mengembangkan kriteria proyek OBOR dan mekanisme koordinasi di dalam negeri. Misalnya, kata dia, dalam mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
"Sejauh ini di sisi pemerintah, saya amati belum ada upaya untuk mengembangkan kriteria untuk proyek-proyek Belt and Road Initiative. Sementara di pihak Cina juga sangat fleksibel dengan ketentuan hal yang bersifat due diligence dan safeguard," kata Fabby.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Riki Ibrahim punya penilaian sendiri mengapa perusahaan enggan mengembangkan pembangkit listrik EBT lewat skema b to b dengan Cina. Alasannya, kata dia, lantaran teknologi asal Cina, belum terbukti bagus dari sisi kualitas.
Oleh karena itu pula, kata Riki, sebagai BUMN yang bergerak dalam pengembangan energi panas bumi, Geo Dipa masih mengandalkan pinjaman sindikasi bank dengan bunga murah ketimbang skema b to b dengan Cina.
"Nanti repot malah jadi ketergantungan, kecuali dia mau buat pabrik teknologinya juga di sini. Supaya ekspor dan produk dalam negeri kita juga meningkat. Jangan kita membeli terus," kata Riki saat dihubungi reporter Tirto, Senin (29/4/2019).
Hal tersebut tak hanya terjadi pada pembangkit listrik EBT, melainkan juga tenaga fisik seperti batu bara. PLTU Cilacap, yang menggunakan pembangkit asal Cina misalnya, sangat tidak efisien dan tak ramah lingkungan.
"PLTU juga turbinnya belum proven. Artinya belum ketahuan bagaimana performanya dalam 10 tahun. Yang sudah bisa dilihat itu PLTU Cilacap, dari Cina udah 4 tahun, tapi itu, kan, boros banget, PLN saja sampai menjerit," tutur Riki.
Tak Sejalan dengan UU
Sementara itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono mengkritik kerja sama one belt on road lantaran proyek yang dibiayai tidak ada kaitannya dengan pengurangan emisi, padahal, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement lewat UU Nomor 16 tahun 2016.
Regulasi itu juga merupakan komitmen untuk membatasi kenaikan temperatur global agar di bawah 2°C. Sebelumnya, pada 2009, Indonesia juga ambil bagian dalam COP 15 di Copenhagen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yang dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Isinya mencakup upaya Indonesia mencapai penurunan emisi tanpa syarat sebesar 29 persen dan bersyarat sebesar 41 persen pada 2030. Namun, kesepakatan yang ditandatangani dalam KTT OBOR pekan lalu justru bertentangan dengan komitmen tersebut.
"Sebelum OBOR itu, pemerintah Cina membuat laporan pelaksanaan. Di dokumen itu disebutkan sektor listrik masih memiliki porsi terbesar dan proyek listrik PLTU batu bara pada 2018 hampir 42 persen," kata Yuyun dalam konferensi pers di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta Selatan, Senin kemarin.
Apalagi proyek yang ditawarkan untuk memperoleh pembiayaan pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi tersebut adalah 4 PLTU, yakni PLTU Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara, dua PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan dan Tenggara, dan PLTU Ekspansi Celukan Bawang Bali.
"Proyek ini tidak ada korelasinya dengan pengurangan emisi, jadi tidak ramah lingkungan. Dan ada celah saat proyek ditinggalkan. Misalnya sampah batu bara," kata Yuyun.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz