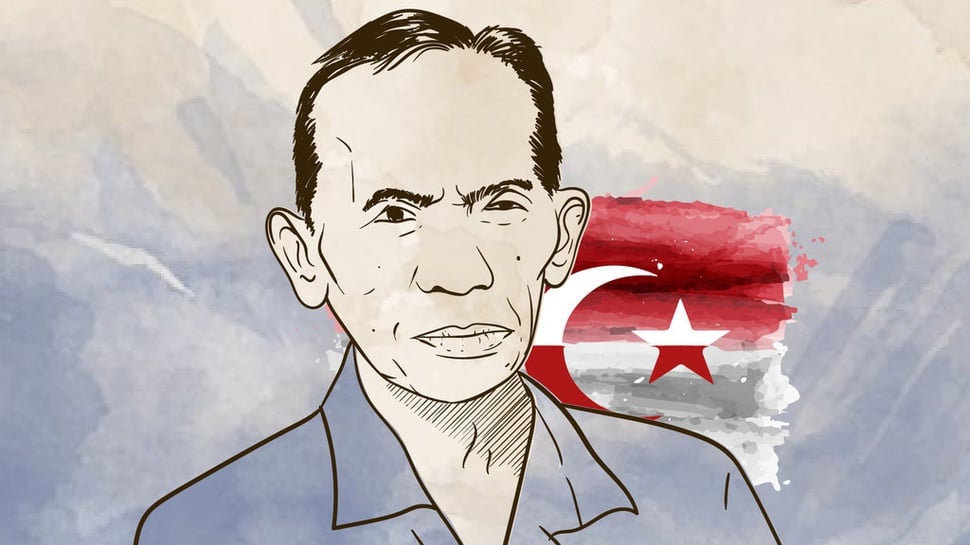tirto.id - Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada tahun 1905. Lima puluh tujuh tahun kemudian pendiri Negara Islam Indonesia ini meninggal dunia di hadapan regu tembak di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu.
Narasi yang membalur hampir sekujur hayatnya adalah seorang pemberontak. Kekecewaannya terhadap pemerintah Republik di pengujung era revolusi membuat ia memilih bergerilya selama belasan tahun di hutan-hutan di Jawa Barat.
Jika melihat ulang masa lalunya sebelum perang berkecamuk di Pasifik, Kartosoewirjo muda sejatinya adalah karib Sukarno, Presiden Indonesia pertama yang menandatangai surat hukuman mati bagi dirinya. Mereka juga lahir dari rahim tokoh pergerakan yang sama, yakni Tjokroaminoto.
Tahun 1920-an, Kartosoewirjo dan Sukarno sempat bersama-sama menjadi penulis di surat kabar Fadjar Asia. Dalam harian yang didirikan Agus Salim dan Tjokroaminoto ini, terserak jejak pandangan politik Kartosoewirjo sebelum mereka berpisah jalan.
Lahir di Tengah Kemunduran Sarekat Islam
Fadjar Asia pertama kali terbit pada November 1927. Surat kabar yang dibidani orang-orang Sarekat Islam ini lahir setelah organisasi pergerakan tersebut mengalami kemunduran setelah pecah karena masuknya pengaruh komunis.
Surat kabar pertama dan utama di kalangan Sarekat Islam adalah Oetoesan Hindia yang mula-mula terbit pada Desember 1912. Pembacanya sangat banyak dan setia.
Memasuki 1924, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar baru bernama Bendera Islam sebagai respons terhadap isu khilafah yang menghangat di kalangan negara-negara Islam seiring runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani.
Namun, Bendera Islam ternyata hanya bertahan selama tiga tahun. Sarekat Islam pun kembali fokus kepada nasionalisme Indonesia. Saat itulah Fadjar Asia lahir dan dianggap sebagai penerus Bendera Islam.
Dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984), surat kabar yang terbit dengan jumlah halaman 10 sampai 12 ini awalnya mendapat suntikan dana dari Raja Arab Saudi yang terkesan dengan cita-cita Agus Salim untuk menyadarkan rakyat Indonesia, agar mampu membebaskan diri dan tanah airnya dari penjajahan bangsa asing.
Pertemuannya dengan raja tersebut terjadi saat Agus Salim pulang dari Mekah pada tahun 1927 ketika menghadiri Muktamar Alam Islami.
“Raja tersebut lalu berkenan menyumbangkan sejumlah uang, sesuatu pemberian yang oleh Agus Salim langsung dimanfaatkan untuk menerbitkan surat kabar. Usaha ini dilakukan bersama dengan Tjokroaminoto dan seorang teman lagi yang memiliki modal kuat,” tulis penyusun buku tersebut.
Fadjar Asia yang mempunyai tujuan sebagai “penerangan Islam tentang agama, adab, dan politik” kemudian dipimpin oleh Agus Salim dan Tjokroaminoto. Sementara Kartosoewirjo sebagai redaktur.
Surat kabar ini berkantor di Pasar Senen, Batavia. Tjokroaminoto sesekali mengisi halaman pertama, misalnya seperti pada 21 Juli 1929 saat ia menulis soal budi pekerti Islam buat kaum miskin.
Takashi Shiraishi penulis buku Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (2005) mengatakan dalam Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa (2016) bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Oetoesan Hindia dan Fadjar Asia.
Jika Oetoesan Hindia adalah koran Sarekat Islam yang sangat berpengaruh karena dibaca banyak orang, maka Fadjar Asia hanyalah jurnal internal Sarekat Islam, koran yang terbit pada masa-masa kemunduran organisasi tersebut.
“Fadjar Asia muncul saat Sarekat Islam tengah merosot dan berada di bawah bayang-bayang surat kabar sebelumnya,” ujar Shiraishi.
Meski demikian, Fadjar Asia tetap memperlihatkan kesungguhannya dalam membela rakyat yang tertindas. Agus Salim sebagai pimpinan sampai harus turun ke lapangan, masuk ke daerah-daerah perkebunan di pedalaman Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
“Ia (Agus Salim) melaporkan keadaan buruh-buruh yang diperas tenaganya dengan upah yang sangat minim,” tulis penyusun Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984).
Membela Rakyat dan Anjuran Kembali kepada Islam
Sebagai redaktur, Kartosoewirjo pun banyak menulis di surat kabar itu. Beberapa tulisannya di Fadjar Asia belakangan dikumpulkan dan diterbitkan bertajuk Nasib Rakyat di Tanah Jajahan (2018).
Seperti tulisan-tulisan Agus Salim yang banyak melaporkan kondisi rakyat yang menderita, Kartosoewirjo pun menulis dengan langgam serupa. Namun, dalam beberapa artikel ia berkali-kali menekankan tentang pentingnya berserah kepada Allah Swt dan kembali kepada jalan Islam. Hal ini sebetulnya tak mengherankan karena seperti ditulis sebelumnya, surat kabar ini memosisikan dirinya sebagai “penerangan Islam tentang agama, adab, dan politik”.
Dalam Fadjar Asia edisi 12 Februari 1929, Kartosoerwirjo menulis artikel bertajuk “Rakyat dan Nasibnya”. Ia menyinggung soal nasib kuli-kuli kontrak perkebunan yang bernasib buruk, kaum pergerakan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendekam di terungku, juga nasib kaum pergerakan lain yang diasingkan.
“Kita tahu atau sekurang-kurangnya kita mengerti, bagaimana besar untung-malang yang menimpa kaum buruh bangsa kita di pantai Sumatra Timur itu, yang terikat oleh suatu perjanjian yang sangat merendahkan derajat kaum buruh,” tulisnya.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut merupakan perpanjangan nasib buruk rakyat Indonesia yang dari dulu belum pernah merdeka secara luas dan benar. Sejak zaman kerajaan hingga kedatangan bangsa Eropa, rakyat selalu menjadi golongan yang tertindas.
“[…] maka yang boleh dianggap merdeka cuma rajanya saja, tetapi rakyatnya sejak zaman itu sampai kini tinggal dalam gelombang penghambaan dan penghinaan yang serendah-rendahnya dan sedalam-dalamnya,” imbuhnya.
Menghadapi persoalan seperti itu, Kartosoewirjo menawarkan solusi yang tak lebih dari sekadar pariwara: bergabung dengan Sarekat Islam.
Mula-mula ia mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, tak ada suatu apa pun yang dapat dijadikan sebagai sandaran dan perlindungan, melainkan hanya kepada Allah Swt.
Sebelum mengimbau untuk bergabung dengan Sarekat Islam, ia terlebih dulu menyalahkan rakyat (umat Islam) yang dianggap kondisi keislamannya saat itu sangat “ganjil”—tanpa menerangkan maksud dari kata tersebut—sehingga nasibnya begitu buruk. Setelah itu ia pun melanjutkan:
“Sekalipun begitu kita bergirang hati dan tidak akan berkecil hati sedikit pun, karena di tanah air kita ini ada suatu pergerakan yang semata-mata bersandarkan kepada Islam dan keislaman, yang hanya bercita-cita akan memuliakan Islam di atas segala-galanya.”
Tulisan Kartosoewirjo dengan langgam seperti itu bertebaran di Fadjar Asia, di antaranya: “Rakyat Mulai Sadar Akan Hak-haknya” (16/2/1929), “Mudahnya Hak Rakyat Jajahan Dilanggar” (23/2/1929), “Beban Penderitaan Rakyat” (27/4/1929), “Mana Hak Rakyat?” (8/6/1929), dan lain-lain.

Pada edisi 3 Juni 1929, Kartosoewirjo menulis artikel berjudul “Soal Kaum Buruh dan Majikan”. Ia mengabarkan dua orang buruh yang kena pecat perusahaannya.
Menurut Kartosoewirjo, kedua buruh ini tak mempunyai kekuatan karena mereka tidak berserikat. Padahal mereka berhak dan bahkan wajib menuntut haknya. Dan sekali lagi, Kartosoewirjo kembali mengajak pembacanya untuk bergabung dengan organisasi yang ia termasuk di dalamnya.
“Oleh karena itu, maka saya mengharap saudara-saudara sekalian kaum buruh […] hendaklah suka menyertakan diri dalam kalangan pergerakan kita, agar supaya segala apa yang kita harapkan dapat dibuktikan dengan kekuatan tenaga dan pikiran kita sendiri,” tulisnya.
Selain menekankan tentang pentingnya kembali kepada jalan Islam dan berorganisasi demi mengumpulkan kekuatan, Kartosoewirjo juga sempat menyinggung soal perilaku bangsa Belanda terhadap kaum perempuan terutama yang berada di perkebunan.
Dalam Fadjar Asia edisi 3 Juni 1929, ia menulis artikel yang penuh kegeraman bertajuk “Belanda Kebun yang Suka Mempermainkan Anak Istri Orang”.
Ia dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang kulit putih yang bekerja di perkebunan-perkebunan adalah kaum yang terasing dari kesopanan dan kemajuan. Mereka amat doyan mempermainkan perempuan, baik yang dijadikan nyai atau pun sekadar menggodanya.
“Perempuan bangsa kita yang selalu terganggu keamanan dirinya oleh orang-orang yang bertabiat hewan, yang seolah-olah tidak kenal atau memang tidak kenal akan budi bahasa,” tulisnya.
Pada artikelnya, Kartosoewirjo mengutip tulisan pengalaman seseorang yang bernama Siti Masiah di Sumatra. Perempuan itu mengisahkan sebuah perjalanan dari Siantar ke Prapat dengan memakai mobil. Pada mobil tersebut, selain dirinya dan perempuan-perempuan lain yang berasal dari Toba dan Jawa, terdapat pula dua orang Belanda. Ia duduk di antara dua orang Belanda itu.
Mula-mula, bule-bule itu mengajaknya ngobrol dan ia anggap wajar saja sebab kalau sekadar ngomong dalam perjalanan baginya sudah biasa. Kemudian seorang di antara mereka bertanya soal isi bungkusan barang bawaannya: sebuah mesin tulis. Sementara Belanda itu menyangka isinya sebuah gramofon.
“Aeee, ini dia gramofon, en boleh bikin senang-senang, en minta dia punya mangkok kita boleh putar en saya dansa,” ucap si bule kegirangan.
Saudara Siti Masih yang juga turut dalam mobil berkata, “Bukan gramofon Tuan, itu hanya mesin tulis kepunyaan adik saya.”
“Mesin tulis?” tanya si Belanda kaget.
“Ya, tuan,” jawabnya lagi.
“Kowe punya adik mana?” tanya si Belanda.
Saudaranya kemudian menunjuk kepada Siti Masiah. Dan sebelum Belanda itu berkata lagi, Siti Masiah telah menghajarnya dengan cepat memakai bahasa Belanda.
“Apa Tuan kira kaum ibu bangsa Indonesia tidak dapat menduduki bangku sekolah?” ucap Siti Masiah.
“Dari Java sampai ke Deli saya berjalan dan saya tulis apa pandangan saya dengan pertolongan mesin tulis ini, tulisan itu kelak ada yang saya siarkan dalam surat kabar dan ada yang saya akan jadikan buku,” lanjutnya.
Mendengar perkataan seperti itu, si Belanda langsung merah mukanya karena malu. Sikapnya berubah menjadi sopan. Sementara Belanda satunya lagi kemudian mencoba menawarkan makanan, tapi ia tolak.
Menurut Siti Masiah, orang-orang Belanda itu terlalu lama tinggal di perkebunan dan mereka terbiasa berlaku kurang ajar kepada para perempuan pribumi. Lebih dari itu mereka juga kerap berlaku kasar dan mengejek kuli-kuli kontrak. Hal ini membuat mereka tidak tahu dunia luar, terutama perkotaan, di mana golongan terpelajar mampu melawannya.
“Sekali ia (orang Belanda) keluar kota atau sedang di perjalanan, hendak dicobakan [menggoda] kaum ibu yang terpelajar, sudah tentu tidak dapat,” ucapnya.
Dengan menyertakan kisah ini, Kartosoewirjo hendak mengkritisi orang-orang Belanda yang kurang ajar, juga membangunkan kesadaran kaum perempuan pribumi atas perlakuan bule-bule itu terutama di perkebunan.
“[…] bangsa kita sudah terkenal akan kemurahan harganya. Malah seringkali tidak ada harganya sama sekali, atau lebih tegas lagi tidak dihargai sedikit pun juga!” imbuhnya geram.
Sampai akhirnya Fadjar Asia berhenti terbit, pandangan-pandangan politik Kartosoewirjo senantiasa hadir dalam surat kabar itu. Secara garis besar—karena surat kabar ini dinakhodai oleh orang-orang Sarekat Islam—persoalan-persoalan penderitaan rakyat yang dihamparkannya pun kerap diakhiri dengan solusi atau ajakan untuk bergabung dengan organisasi itu.
Ketika zaman berubah, dan ia bertualang dengan menjadi musuh Republik, akar pikirannya bisa kita telusuri dari cuplikan-cuplikan pemikirannya saat ia menjadi penulis di Fadjar Asia. Islam senantiasa menjadi pokok pikirannya.
Dan setelah itu, ia pun tandas di hadapan sejarah. Dalam sebuah pidato yang terkumpul dalam Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno: 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara, Sukarno berucap:
“Lantas bersama-sama dengan Kartosoewirjo almarhum saya mengemudikan surat kabar Fadjar Asia. Ini pikiran, Saudara-saudara, yang keluar dalam Fadjar Asia itu saya pupuk terus, saya pupuk terus, saya pupuk terus. Oleh karena ini akan menjadi salah satu pilar daripada revolusi […] yang Bung Karno selamat sampai sekarang sebagai pemimpin gerakan dan revolusi, yang Kartosoewirjo digiling oleh revolusi, sehingga dia tidak lagi masuk sejarah sekarang ini.”
Editor: Nuran Wibisono