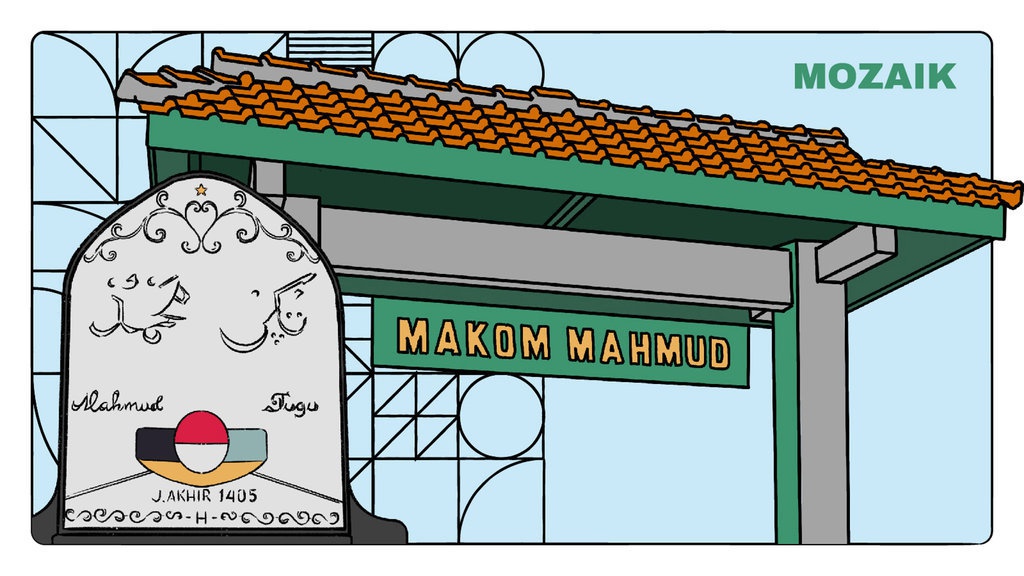tirto.id - Rabu, 3 April 2024, sekitar pukul 13.30, sebuah papan digital menyala dan menampilkan tulisan "Makom Mahmud", yang tergantung di gapura Kampung Mahmud. Di sebelah kiri gapura, berdiri sebuah plang besi berkarat bertuliskan "Situs Mahmud".
Hari itu, cuaca cukup cerah dan udara terasa sejuk. Beragam buah tangan mulai dari kopiah, baju muslim, hingga buku-buku keagamaan, dijajakan masyarakat tepat di depan rumah biliknya. Namun, situasi kampung sangat lenggang. Sepi dari para peziarah.
"Memang, jika sudah masuk bulan Ramadhan [Kampung] Mahmud suka sepi dari pengunjung, yang biasanya datang untuk berziarah ke makam Eyang Dalem Abdul Manaf," terang Ence Shahibul Mahmud, keponakan dari sesepuh Kampung Mahmud, Haji Nuron, saat ditemui di rumahnya.
Makam Eyang Dalem Abdul Manaf adalah makam keramat utama yang berada di lingkungan Kampung Mahmud. Di luar bulan Ramadhan, khususnya di malam Jum’at, hari Maulid Nabi, dan hari peringatan acara Rajaban (Isra Mikraj), kampung sesak oleh para pengunjung yang melakukan ziarah ke makam keramat tersebut.
Tanah Sekepal dari Makkah
Mengutip Dewi Astuti & Risma Rismawati dalam Adat Istiadat Masyarakat Jawa Barat (2018), secara administratif Kampung Mahmud terletak di RW. 04, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
Kampung ini dikelilingi Sungai Citarum. Sebelah barat, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Sungai Citarum lama. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ciratum baru.
Ence Shohibul (64), selaku ketua RW. 04, menyebut bahwa kini Kampung Mahmud menjadi tempat tinggal sekitar 320-an keluarga. Semuanya memeluk agama Islam dan 99 persen merupakan penduduk asli.
Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang, Kampung Mahmud didirikan oleh Eyang Dalem Abdul Manaf. Cerita berawal saat ia meninggalkan Cirebon menuju tanah suci, Makkah. Setelah tinggal beberapa waktu, ia memilih untuk pulang ke negeri asalnya.
Sebelum pulang, ia memanjatkan doa di tempat yang disebut Gubah Mahmud, dekat Masjidil Haram. Dalam doanya, ia memohon untuk tinggal di suatu tempat demi menyebarkan agama Islam tanpa tersentuh oleh Belanda.
Singkatnya ia mendapat ilham yang mengisyaratkan bahwa tempat yang diharapkannya berada di atas tanah berawa. Setelah itu, ia melakukan perjalanan pulang dengan membawa segenggam tanah karamah dari Makkah.
Setibanya di Pulau Jawa, ia segera melakukan pencarian tanah berawa yang sesuai dengan isyarat dalam Ilham yang didapatnya. Pencarian itu membawa dirinya ke sebuah rawa yang berada di pinggiran Sungai Citarum. Setelah itu, rawa diurug dan tanah karomah ia bawa dari Makkah dikubur di rawa tersebut.
"Kemudian lahan yang semula rawa itu berubah menjadi lahan yang layak untuk sebuah perkampungan. Satu per satu rumah bermunculan sehingga membentuk sebuah kampung," tulis Rosyadi dalam "Komunitas Adat Kampung Mahmud di Tengah Arus Perubahan" (Jurnal Patanjala Vol. 3, No. 2, Juni 2011, hlm. 331-347).
Menurut Haryani Saptaningtyas dalam This Is Our Belief Around Here: Purification in Islamic Thought and Pollution in Islamic Thought and Polluiton of Citarum River (2021), nama Mahmud berasal dari bahasa Arab ahlakul mahmudah, yang berarti akhlak yang terpuji. Hal ini menjadi sebuah pesan bahwa penduduk Mahmud harus memiliki sikap dan perilaku yang terpuji.
Dalam perkembangannya, kampung ini dikenal sebagai tanah haram, yang berarti terlarang dimasuki oleh orang-orang non muslim. Alasannya tidak lepas dari tanah karamah yang dibawa dari tanah suci.
Penduduk kampung sangat meyakini apa yang dilakukan oleh karuhun mereka memberi keselamatan untuk kampungnya. Lokasi kampung yang berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan sungai Citarum tak pernah sekalipun dilanda banjir.
Bahkan rasa aman tersebut menjadikan kampung ini sebagai tempat pelarian orang-orang yang menjadi target penangkapan pemerintah kolonial Belanda.
Penyebaran Islam di Bandung Selatan
Sulit secara pasti mengetahui kedatangan Eyang Dalem Abdul Manaf ke Mahmud. Sebagian meyakini ia pertama kali tiba pada abad ke-15 Masehi. Namun, ada pula yang menyebut kedatangannya pada "kisaran tahun 1670-an," tutur Ence.
Mengutip Afghoni dan Ade Slamet dalam "Pendekatan Antropologis dalam Pemahaman Hadis (Studi Atas Peziarah di Makam Eyang Mahmud)" (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 1, 1 (September 2016: 17-26), ia merupakan keturunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Selain itu, terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan Raja Mataram.
Perbedaan versi tersebut timbul karena ketiadaan sumber tertulis yang otentik. Bahkan, toko buku dan kitab yang ada di Kampung Mahmud tidak memiliki koleksi buku yang berkaitan dengan Eyang Dalem Abdul Manaf dan sejarah berdirinya kampung tersebut.
Kisah tentang Eyang Dalem Abdul Manaf dan Kampung Mahmud hanya dituturkan secara turun temurun melalui tradisi lisan, yang dimulai dari rumah hingga pengajian-pengajian di masjid dan madrasah yang dipimpin oleh para sesepuh.
Ketiadaan sumber tertulis disebabkan rasa khawatir para sesepuh akan penyalahgunaan silsilah dan kebesaran nama Eyang Dalem Abdul Manaf. Namun, tak dipungkiri, hal ini justru berdampak kepada pengetahuan sejarah generasi berikutnya yang kian terkikis.
"Tahsedengkeun sekarang, sampe [nama] kakek juga kadang-kadang ada yang engga tau,” ungkap Ence.
Terlepas dari ketiadaaan sumber tertulis, Eyang Dalem Abdul Manaf tetap diyakini penduduk Kampung Mahmud sebagai waliyullah yang menyebarkan agama Islam paling awal di wilayah Bandung selatan.
Mengutip Febri Nugraha dalam "Aktivitas Mubalig Syeikh Abdul Manaf dalam Penyebaran Agama Islam di Kawasan Bandung Raya Pada Abad 17-18 M" (Jurnal Priangan Vol. 1 (2) 2022, hlm. 1-5), tablig dan pendidikan pesantren menjadi metode utamanya dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, ia juga mengenalkan ajaran tasawuf untuk hidup dalam kesederhanaan dan menghindarkan diri dari segala hal yang bersifat duniawi.
Selama berdakwah, ia dibantu oleh Eyang Abdullah Gedug dan Eyang Agung Zaenal Arif, yang merupakan keturunan keempat dari Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Ketiganya merupakan karuhun yang sangat dihormati masyarakat Kampung Mahmud.
Setelah Eyang Dalem Abdul Manaf wafat, dakwah di Bandung selatan diteruskan oleh keturunan dan murid-muridnya. Selain meninggalkan Kampung Mahmud, ia mewariskan Masjid Agung Mahmud yang didirikannya.
Ia dimakamkan di dalam lingkungan Kampung Mahmud dan menjadi makam keramat yang menjadi tujuan utama para peziarah. Di sebelah makamnya terdapat makam Eyang Dalem Zainal Arifin.
Sepeninggalnya, sistem kepemimpinan di kampung ini diturunkan kepada keturunannya berdasarkan penguasaan terhadap ilmu agama. Pemimpin adat atau sesepuh mengemban tugas dalam mengatur kehidupan penduduk, khususnya di bidang keagamaan dan aturan-aturan adat yang berlaku.
Sesepuh berhak menunjuk seseorang untuk menjadi ketua RW yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan administratif. Namun, dalam beberapa kesempatan, ketua RW pernah dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk Kampung Mahmud. Di samping itu, ketua RW berhak menunjuk seseorang untuk menjadi ketua RT.
Tradisi di Kampung Mahmud
Kampung Mahmud memiliki aturan dan ciri khas tersendiri. Dulu, semua penduduk sepenuhnya tinggal di rumah panggung yang terbuat dari bilik bambu dengan membentuk huruf L. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari ajaran hidup sederhana yang diajarkan Eyang Dalem Abdul Manaf.
Awalnya, air sungai Citarum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Penduduk dilarang untuk menggali sumur di dalam rumah. Ini adalah pesan dari Eyang Dalem Abdul Manaf kepada penduduk kampung agar senantiasa menjaga dan melestarikan sungai Citarum.
Air sungai Citarum dimanfaatkan warga untuk bertani, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya sebagian kecil hasil pertanian yang dijual ke luar kampung, salah satunya ke Pasar Caringin, Bandung. Di samping itu, sebagian penduduk kampung bekerja sebagai pedagang dan pengrajin kayu (mebel).
Pendidikan agama menjadi yang paling utama, yang dimulai di rumah melalui bimbingan orang tuanya, hingga pengajian rutin di masjid dan madrasah yang dipimpin oleh para sesepuh. Salah satu materinya adalah manakib tentang sejarah Eyang Dalem Abdul Manaf.
Meski begitu, jika merasa membutuhkan, penduduk diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA. Bahkan, "kalau sekarang mah yang kuliah juga udah banyak,” ucap Ence.
Mengutip kembali Rosyadi (2011), tradisi yang rutin dilakukan penduduk kampung meliputi upacara 7 bulanan kehamilan (tingkeban), upacara membangun rumah, ziarah kubur makam karuhun (leluhur), Rajaban (Isra Mikraj), dan Muludan (Maulid Nabi).
Ada upacara memandikan keris dan benda-benda pusaka. Upacara ini rutin dilakukan setiap tanggal 27 Mulud (Rabi’ul Awal) yang dipimpin langsung oleh sesepuh kampung.
Terakhir, Ence Shohibul menjelaskan tentang tradisi nyadran dan tabligh akbar di Kampung Mahmud yang rutin dilaksanakan setiap kali menyambut datangnya bulan Ramadhan. Sedangkan saat Idulfitri, selepas melaksanakan salat id, warga kampung ziarah massal ke makam keramat.
Pekan pertama setelah Idulfitri, diadakan tradisi rutin yang dikenal dengan istilah Lebaran Syawal--semacam Lebaran Ketupat di Jawa. Acara diawali dengan salat sunah di Masjid Agung Mahmud dan diakhiri dengan acara makan ketupat di rumah sesepuh.
Terdapat istilah pamali atau larangan di Kampung Mahmud. Di antaranya dilarang mendirikan rumah dengan tembok yang berkaca, menabuh gong, memelihara angsa, dan menggali sumur di dalam rumah.

Dalam pandangan nenek moyang Kampung Mahmud, tembok dan kaca merupakan simbol dari nafsu duniawi. Selain itu, dianggap sebagai atribut dari rumah-rumah orang Belanda. Sehingga hal itu harus ditinggalkan.
Suara gong yang menggetarkan, dianggap sebagai simbol kesombongan. Sedangkan angsa dilarang untuk dipelihara karena dianggap berisik. Pada masa kolonial, suara angsa itu dikhawatirkan mengundang perhatian pasukan Belanda. Selain itu, suaranya berpotensi merusak konsentrasi ibadah.
Larangan-larangan adat tersebut terbilang longgar. Tak ada hukum adat dan sosial yang dijatuhkan secara langsung kepada para pelanggar. Namun, para sesepuh dan penduduk meyakini bahwa akan datangnya kesulitan dalam kehidupan orang-orang yang melanggar adat.
Maka tak mengherankan jika kini sudah banyak rumah yang memadukan bilik bambu dengan tembok. Tanah-tanah penduduk secara bebas dapat diperjualbelikan kepada orang di luar kampung, yang setelahnya membangun rumah tembok.
Kiwari,jumlah bangunan dan rumah-rumah panggung yang sepenuhnya dari bilik bambu semakin sedikit. Salah satu bangunan yang masih menjaga ciri khasnya adalah Masjid Agung Mahmud.
Kampung Mahmud sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi. Tidak ada larangan mengenai penggunaan listrik, televisi, dan kendaraan bermotor. Bahkan, penduduk kampung sudah banyak yang menggunakan smartphone.
Dalam laporan jurnalistik Kompas berjudul Ekspedisi Citarum: Sejuta Pesona dan Persoalan (2018), limbah industri yang mencemari aliran sungai Citarum menimbulkan permasalahan terhadap kehidupan penduduk Kampung Mahmud. Jangankan dikonsumsi, air sungai jika terkena kulit saja mengakibatkan rasa gatal.
Kondisi itu pada akhirnya mendorong warga menggali sendiri sumur di rumahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id