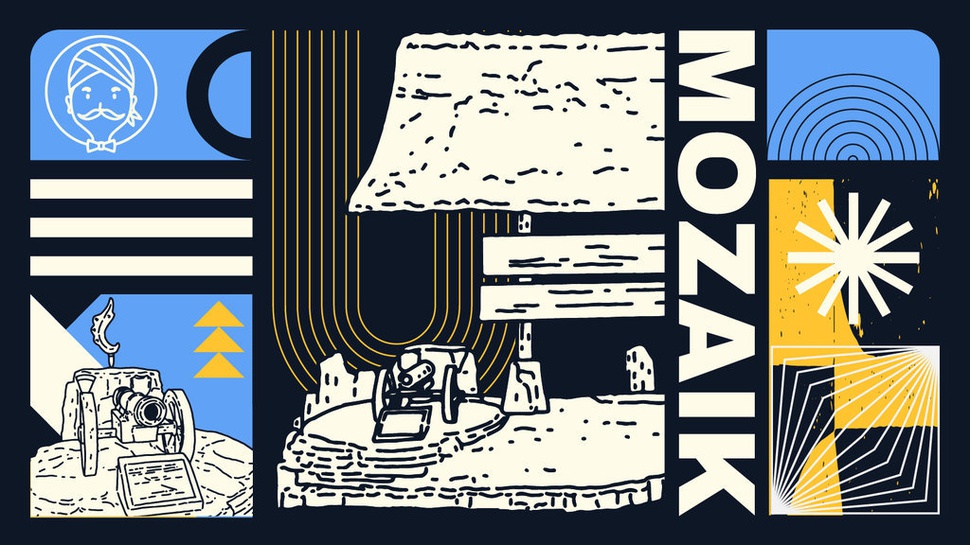tirto.id - Di tengah modernisasi kawasan Bandung Raya, Kampung Adat Cireundeu terus berusaha mempertahankan tradisi. Secara administratif, kampung ini terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat.
Cireundeu berasal dari nama tanaman yaitu reundeu (Staurogyne longata O.K) yang dulu banyak tumbuh di daerah ini. Tanaman reundeu merupakan jenis tanaman herbal lokal yang banyak manfaatnya.
Salah satu tradisi yang masih dijalankan warga kampung adalah mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Ini menjadi pembeda di tengah pola konsumsi masyarakat Sunda yang didominasi nasi. Singkong juga diolah menjadi berbagai macam makanan yang dikemas dan memiliki nilai ekonomis.
Pada awal abad ke-20, masyarakat Cireunde masih mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Perlakukan pihak kolonial terhadap keberadaan makanan pokok masyarakat saat itu membuat masyarakat Cireundeu mulai menggantinya dengan singkong. Turunnya harga disertai perampasan beras membuat masyarakat kelaparan.
Menurut Muhammad Arif dan Sujiyo Miranto dalam buku Daya Dukung Kearifan Lokal Terhadap Kelestarian Lingkungan Kampung Cireundeu (2022), gerakan mengganti beras dengan singkong diinisiasi oleh Haji Ali dan diikuti oleh warga sekitar pada tahun 1918.
Gerakan ini melahirkan konsep yang dipegang teguh oleh masyarakat Cireundeu sampai sekarang, yakni: “keun baé teu bisa nyawah asal boga paré, teu boga paré asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal bisa dahar, najan teu dahar asal kuat” (tidak apa tidak bisa mengolah sawah asalkan punya padi, tidak punya padi asalkan bisa menanak nasi, tidak bisa menanak nasi asalkan bisa makan, walaupun tidak makan, asalkan kuat).
Dalam hal kepercayaan, sebagian masyarakat Cireundeu memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan.
Selain di Cireundeu, penganut ajaran ini tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat. Menurut Ira Indrawardana dalam "Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman" (2011)--disampaikan dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda II--mereka tersebar di Kasepuhan Cigugur Kuningan, Ciamis, Masyarakat Kanekes, dan Kasepuhan Adat Banten Kidul yang terdapat di Kampung Ciptagelar Sukabumi.
Kampung Adat Cireundeu memiliki keterkaitan dengan Kasepuhan Cigugur Kuningan yang menjadi cikal bakal munculnya gerakan spiritual atau yang lebih akrab dikenal dengan Agama Djawa Sunda (ADS) yang dipelopori oleh Madrais, yang memiliki nama asli Pangeran Sadewa Alibassa Widjaja Ningrat.
Pengaruh kepercayaan Sunda Wiwitan dari Kasepuhan Cigugur dengan mudah memengaruhi masyarakat Cireundeu karena banyak kesamaan antara kedua daerah.
Kesamaan geografis dan pola mata pencaharian antara keduanya membuat Madrais dan para pendakwahnya yang dikenal dengan istilah "badal" berhasil memikat hati orang-orang Cireundeu.
Kedua tempat berada di lereng gunung. Cigugur berada di lereng Gunung Ciremai, sedangkan Cireundeu berada di lereng bukit Puncak Salam. Sementara mata pencahariannya bercocok tanam. Kesamaan ini menurut Tendi dkk. dalam buku Bertahan Melawan Terpaan: Agama Jawa Sunda Pada Masa Kepemimpinan Tejabuana (2021) mempermudah badal menyampaikan ajarannya.
Mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat petani Sunda terhadap mitologi mengenai dewa-dewi yang sangat dekat dengan tanaman padi, seperti Dewa Ismaya, Dewi Uma, dan yang paling utama adalah Dewi Sri yang juga sering disebut sebagai Nyi Pohaci.
Dalam menyebarkan ajarannya, Madrais sempat mendapat pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ini berkenaan dengan tuduhan atas penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh Madrais dan badal-badalnya terhadap masyarakat.
Pada tahun 1903, koran Preanger Bode edisi 17 April melaporkan penipuan yang dilakukan Madrais di Tasikmalaya yang membuatnya diseret ke penjara. Beberapa literatur menuliskan, pemimpin ajaran Sunda Wiwitan ini sempat dibuang ke luar Pulau Jawa.
Setelah mengalami masa-masa sulit, masyarakat menganut kepercayaan Sunda Wiwitan mendapat angin segar setelah komunitasnya dilembagakan secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk komunitas adat. Setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi munculnya statuta pembentukan lembaga bernama Agama Djawa Sunda (ADS) itu.
Pertama adalah kedekatan antara Madrais dengan orang-orang Belanda. Koran-koran berbahasa Belanda menyebut, Madrais memiliki seorang penasihat Eropa yang merupakan pensiunan pegawai Landraad di Cirebon dengan gaji seratus gulden per bulan.
Selain itu, eksistensi gerakan pengikut Madrais diakui lewat surat rekomendasi dari R. A. Kern kepada Gubernur Jenderal D. Fock. Tendi dkk. menyebut Pejabat Penasihat Urusan Bumi Putra di Hindia Belanda melihat gerakan ini sebagai komunitas yang tidak pernah membahayakan kelangsungan Pemerintahan Kolonial selama 40 tahun.
Koran Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie edisi 30 Oktober 1931 menyebut gerakan yang digagas Madrais bukanlah gerakan politik yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Kolonial. Apalagi, para pengikutnya sangat taat kepada pemerintah. Mereka membayar pajak tepat waktu dan melakukan kegiatan sosial di daerahnya seperti memelihara jalan desa.
Alasan kedua pelembagaan Agama Djawa Sunda yang dilakukan pemerintah adalah menghadapi perkembangan Islam untuk kepentingan kolonialisme.
Menurut Chaider S. Bamualim dalam kumpulan tulisan berjudul "Negotiating Islamisation and resistance: a study of religions, politics and social change in West Java from the early 20th Century to the present melihat", pelembagaan Agama Djawa Sunda sebagai wujud nyata politik pecah Belanda di Pulau Jawa.
Selain itu, Pemerintah Kolonial juga memberi gelar kebangsawanan bagi Madrais. Gelar ini penting bagi Madrais untuk memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi.
Setelah pengukuhan Agama Djawa Sunda sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah, kehidupan para pengikutnya berjalan mulus. Perlindungan pemerintah membuat komunitas spiritual ini dapat berkembang dengan lebih leluasa.
Kondisi ini berbalik 180 derajat setelah Madrais meninggal dan Belanda hengkang dari negeri koloninya. Pada masa pendudukan Jepang, struktur sosial masyarakat Hindia Belanda berubah. Saat itu, Agama Djawa Sunda mendapat tekanan dari pihak imperialis Jepang sehingga harus membubarkan diri.

Kemerdekaan Indonesia membuat kegiatan Agama Djawa Sunda kembali menggeliat. Namun, perjuangan Tejabuana untuk membangun kembali Agama Djawa Sunda tidak membuahkan hasil. Di masa Orde Lama, organisasi ini kembali bubar karena terdesak oleh keputusan-keputusan pemerintah saat itu.
Mngutip Tendi dkk. sejumlah kebijakan pemeritah membuat Agama Djawa Sunda teralienasikan, terasing dari kehidupan masyarakat di sekitarnya karena pelbagai macam adat dan tradisi yang dimiliki oleh Agama Djawa Sunda dianggap tidak sesuai ketentuan pemerintah.
Bubarnya Agama Djawa Sunda tahun 1960-an tidak menyurutkan langkah masyarakat Cireundeu untuk tetap memeluk kepercayaan yang sudah mereka anut sejak lama. Mereka tetap menjaga afiliasi dengan Kasepuhan Cigugur dalam satu ikatan.
Untuk menjaga eksistensi para penganut Agama Djawa Sunda, dibentuklah organisasi bernama Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) tahun 1981. Organisasi ini bubar setahun setelah berdiri dan berganti nama menjadi Adat Karuhun Urang (AKUR).
Bersama Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan Adat Banten Kidul yang terdapat di Kampung Ciptagelar Sukabumi, AKUR tetap mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan sampai sekarang.
Penulis: Hevi Riyanto
Editor: Irfan Teguh Pribadi