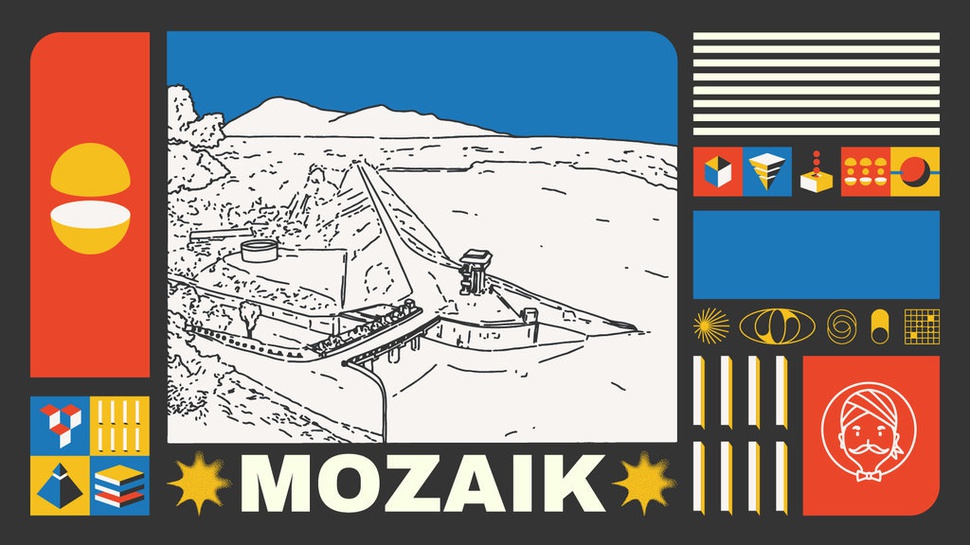tirto.id - Kemarau panjang membuat volume air Waduk Gajah Mungkur menyusut. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar waduk memanfaatkan kondisi ini untuk bercocok tanam dan mencari ikan di sisi area genangan.
Selain itu, sekitar 200 meter dari jalan perkampungan tampak sebuah kompleks permakaman dengan nisan yang berserakan di tengah area waduk yang mengering.
Permakaman yang terletak di Kecamatan Wuryantoro itu, seturut camat setempat, memang biasa terlihat jika wilayah tersebut dilanda kekeringan.
Sebagian besar batu kijing di atas makam sudah rusak akibat terkikis air. Namun, beberapa di antaranya masih utuh dan terbaca.
Waduk Gajah Mungkur yang terletak di Kabupaten Wonogiri dan mulai dibangun pada 1976 itu memang dibayar mahal dengan menenggelamkan puluhan desa beserta seluruh sejarah dan kenangannya, termasuk makam-makam yang kiwari kembali muncul ke permukaan.
Kerja sama dengan Jepang
Pembangunan Waduk Gajah Mungkur merupakan bagian dari rencana induk pengembangan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo untuk kepentingan irigasi, PLTA, air minum, perikanan darat, dan pariwisata.
Selain iitu, juga untuk konservasi sumber daya air dan pengendali banjir ketika musim penghujan tiba yang kerap menimbulkan kerusakan terhadap lahan-lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar aliran sungai.
Menurut Ir. Abdullah Angoedi dalam Sejarah Irigasi di Indonesia 1 (1984), ide proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur pertama kali dicetuskan oleh Hoofd Mangkunegorosche Waterstaat, Ir. R. M. Sarsito Mangunkusumo di Surakarta pada tahun 1941.
Namun, saat itu karena situasinya tidak memungkinkan, maka ide tersebut tidak dapat langsung direalisasikan.
Merujuk pada laporan utama Japan International Coopertion Agency (JICA) yang berjudul Feasibilty Report On The Wonogiri Multipurpose DAM Project (1975), baru pada tahun 1963-1965 dilakukan investigasi dan studi teknik untuk proyek pembangunan waduk.
Namun, rencana pembangunan lagi-lagi tertunda karena situasi politik dalam negeri kembali terguncang akibat G30S. Maka pada 1966 dan 1968 banjir besar tak terhindarkan dan kembali melanda daerah-daerah di sekitar DAS Bengawan Solo, termasuk Wonogiri yang merupakan hulu dari aliran sungai tersebut.
Setelah rezim berganti, Pemerintah Orde Baru berupaya merekonstruksi perekonomian dan infrastruktur negara, khususnya di bidang pertanian. Maka itu, pengendalian sumber daya air menjadi salah satu prioritas utama.
Dengan bantuan teknis dari Pemerintah Jepang, pada 1972-1974, dilakukan pengkajian ulang daerah DAS Bengawan Solo, termasuk proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur.
Selanjutnya, dari bulan November 1974 hingga April 1975, atas permintaan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang mengirimkan tim survei dipimpin oleh N. Aihara beserta 20 orang ahli dari Pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Japan International Cooperation Agency (JICA).
Selain itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan Nippon Koei Consulting Engineers, Co. Ltd untuk penyelidikan rinci dan desain rekayasa pembangunan waduk.
Setelah tahap penyelidikan selesai, dengan mengandalkan dana APBN, bantuan Pemerintah Jepang, dan dana pinjaman dari Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), pembangunan waduk yang dirancang untuk masa operasi 100 tahun itu dimulai pada 1976 dan diresmikan Soeharto lima tahun kemudian.
Penenggelaman Lahan dan Permasalahan Transmigrasi
Mengutip Candra Dedy Saputra dalam "Migrasi (Bedol Desa) Masyarakat Wonogiri: Dampak Pembangunan Waduk Gajah Mungkur tahun 1976-1990”, untuk kelangsungan proyek pembangunan, pemerintah menenggelamkan 51 desa di Kabupaten Wonogiri.
Saat itu, alokasi dana ganti rugi yang disiapkan pemerintah sekitar Rp100 sampai Rp1.000 untuk setiap tanah warga yang terdampak proyek pembangunan.
Pemerintah memindahkan sekitar 67.515 jiwa melalui program transmigrasi atau bedol desa ke daerah-daerah di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemindahan dilakukan dalam 20 tahap pemberangkatan dengan menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah.
Namun, bagi masyarakat yang “memilih untuk pindah di dalam Pulau Jawa harus membayar biaya sendiri,” tulis Graita Sutadi dalam thesisnya yang berjudul Operations Plan Of The Wonogiri Reservoir, Central Java, Indonesia (1982).
Seturut Sri Utami dan Agus Trilaksana dalam "Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Tahun 1976-1986", sebagian besar masyarakat tak punya pilihan selain tunduk pada pemerintah. Jika menolak, mereka tahu konsekuensinya.
Meski begitu, sebagian kecil penduduk yang tinggal di area proyek pembangunan menolak untuk ikut dalam program transmigrasi.
Sutrisno, Kepala Desa Nguntoronadi, contohnya. Bersama dengan sepuluh orang lainnya, ia secara terang-terangan menentang program transmigrasi. Mereka menganggap biaya ganti rugi yang dialokasikan pemerintah tidak seimbang dengan aset yang dimilikinya di lahan yang akan dijadikan sebagai area genangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa kepala desa yang ikut dalam program transmigrasi memilih kembali ke Wonogiri. Hal tersebut terjadi karena gaji yang mereka dapatkan jauh lebih kecil dari sebelumnya.
Selain itu, beberapa kepala desa merasa dibohongi terkait iming-iming jabatan struktural di wilayah barunya yang dijanjikan pemerintah kepada mereka jika bersedia ikut dalam program transmigrasi.
Proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur juga berdampak pada masyarakat di Desa Banyuripan, Desa Tunggulsari, Desa Pagotan, dan Desa Karangjati yang berdekatan dengan Kabupaten Wonogiri.
Secara terang-terangan mereka menetang program transmigrasi dari pemerintah karena "menganggap kalau ke luar Jawa pasti hidup akan sengsara,” pungkas Ir. Ridha Sinaro, dkk (2007).
Anggapan tersebut terbukti seperti yang terjadi di awal-awal kedatangan para transmigran ke Sumatra Barat. Saat itu, mereka dihadapkan dengan kondisi tanah gambut yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat produksi pertanian.
Sedangkan di Sumatra Selatan, khususnya di Desa Karang Menjangan, mereka dihadapkan pada permasalahan sengketa tanah dengan penduduk setempat hingga berujung pada aksi penolakan terhadap kehadiran para transmigran dari Wonogiri.
Bahkan, permasalahan yang sama terjadi pula di antara “sesama transmigran mengenai pergeseran patok-patok. Sehingga, beberapa transmigran tidak mendapat jatah tanah pekarangan, ladang, dan sawah,” pungkas Candra Dedy Saputra (2016).
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi