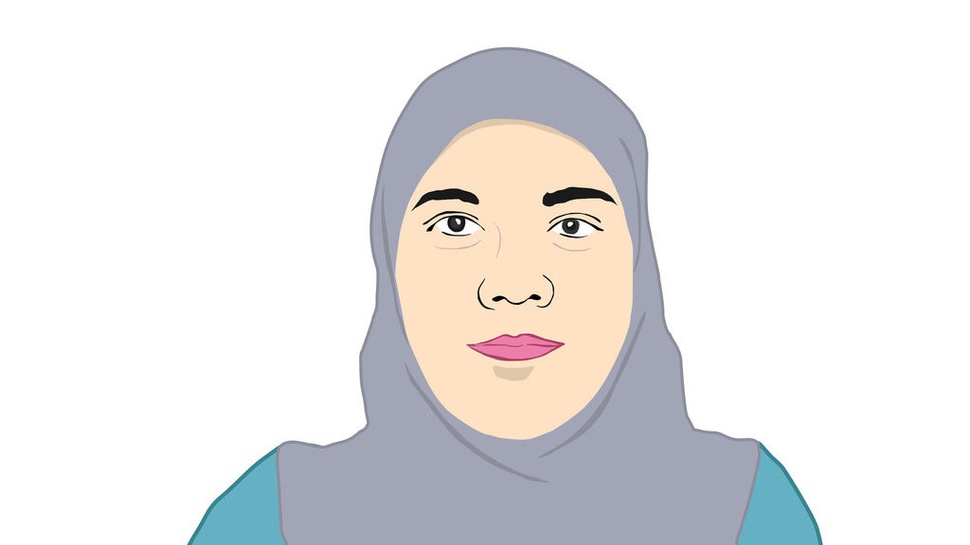tirto.id - Di Amerika Serikat, kasus-kasus kejahatan seksual di kampus mendapat sorotan tajam dan menjadi isu nasional.
Pada 2016, Universitas Yale diguncang kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen. Thomas Pogge, profesor etika sekaligus seleb TED Talks—yang sering menyerukan tanggung jawab negara-negara kaya untuk memperbaiki tatanan ekonomi dunia yang menyebabkan kemiskinan global—diduga keras menyalahgunakan otoritas akademik dengan memaksa sejumlah mahasiswanya untuk berhubungan seks.
Salah seorang korban bahkan mengatakan bahwa Pogge mengancam akan menjatuhkan sanksi profesional jika keinginannya tidak dituruti. Kasus Pogge membuka kebobrokan Universitas Yale yang cenderung diam ketika merespons aduan pelecehan seksual yang melibatkan para profesor. Salah satu korban Pogge menyatakan pihak kampus berusaha menyuapnya agar tutup mulut.
Belum usai kasus Pogge, April tahun ini profesor filsafat Universitas California, Berkeley, John Searle diterpa kasus serupa. Mantan mahasiswanya Joanna Ong melaporkan sederet perilaku tidak senonoh Searle, misalnya nonton film porno di depan dirinya dan membuat komentar seksis. Aduan Ong bukan yang pertama.
Sebelumnya, adalah rahasia umum jika Searle selalu dikelilingi asisten gadis-gadis muda berjulukan “Searle Girls” di lingkungan fakultas. Pada 2014, seorang mahasiswi menyatakan bahwa Searle tidak mau menerimanya sebagai asisten. Alasan Searle: sang mahasiswi sudah menikah sehingga tidak bisa mendedikasikan diri untuk pekerjaan asisten. Mahasiswi yang lain melaporkan bahwa Searle berusaha menciumnya. Tiga belas tahun silam, Searle diadukan karena mengelus-elus kaki seorang mahasiswi di bawah meja.
Kejahatan seksual di perguruan tinggi sebenarnya bukan hal baru, termasuk di Indonesia. Kasus terakhir yang cukup mencuri perhatian adalah pelecehan seksual oleh EH, seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.
Pada Juni 2016, The Jakarta Postmenurunkan kisah korban EH yang bernama Maria. Menurut Maria, EH mengundangnya untuk konsultasi makalah di sebuah pusat studi dalam kampus pada pukul 8 malam. Dalam sesi konsultasi tersebut, Maria dikejutkan oleh EH yang tiba-tiba menggerayangi payudaranya dan menempelkan penis ke tubuhnya. Maria, lagi-lagi, bukan satu-satunya korban EH.
Margaretta Sagala, alumnus kampus tempat EH mengajar, mengirim surat pembaca ke The Jakarta Post. Ia menyatakan EH bukan anak di bawah umur yang tidak memahami apabila tiap hubungan seksual membutuhkan consent (kesepakatan).
"Ironisnya, EH adalah orang yang mengajari saya teori-teori feminis. EH tahu bahwa kebanyakan korban pelecehan seksual tidak akan melapor," tulis Margaretta.
Sebagaimana Searle dan Pogge, EH dikenal sebagai sosok intelektual publik dan bintang di jurusannya. Lebih ironis lagi, sebagaimana dibilang mantan muridnya, EH bahkan mengajar kuliah bertema gender dan feminisme.
Eric Schwitzgebel, profesor filsafat Amerika menyebut fenomena ini sebagai “moral licensing”. Ia menjelaskan bagaimana orang-orang yang menggeluti kajian etika justru melakukan banyak perbuatan tidak etis.
Schwitzgebel menunjukkan, misalnya, mengapa buku-buku yang paling sering dicuri dari perpustakaan kampus adalah buku-buku etika, atau mengapa pakar filsafat etika yang berkoar-koar bahwa makan daging adalah tindakan amoral justru menolak jadi seorang vegetarian.
Prinsip moral licensing kira-kira berlaku seperti ini: Karena saya telah melakukan hal-hal yang baik untuk sesama, maka tak masalah jika sekali-dua kali saya melanggar pantangan.
Moral licensing ini bisa menjelaskan mengapa seorang dosen yang cemerlang nan populer dapat melakukan pelecehan seksual. Namun, terlepas dari wilayah kajian si pengajar, ada kepercayaan umum yang sejak awal memungkinkan kejahatan seksual langgeng di kampus-kampus: mengajar adalah sebuah profesi yang sangat mulia dan bermanfaat bagi orang banyak—"pahlawan tanpa tanda jasa", dalam istilah populer di Indonesia.
Memanfaatkan Relasi Kuasa
Hingga saat ini di Indonesia belum ada data komprehensif tentang kejahatan seksual di kampus. Sangat sulit untuk mengetahui seberapa sering prevalensi kejahatan seksual di lingkungan kampus, siapa pelaku dan siapa korbannya.
Namun, dari email aduan yang pernah dibuka oleh Rifka Annisa, sebuah pusat krisis dan lembaga nirlaba yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis di Yogyakarta, dalam satu bulan saja terdapat 11 email yang melaporkan kejadian pelecehan seksual di kampus; tujuh di antaranya dilakukan dosen terhadap mahasiswanya.
Saat Rifka Annisa bertanya kepada korban apakah mereka ingin melanjutkan laporan, kesebelas pelapor menyatakan tidak ingin memproses lebih lanjut dan hanya ingin bercerita tentang kejadian yang pernah menimpa mereka. Mengapa mereka menolak untuk memproses kasusnya lebih lanjut?
Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan dengan kultur yang unik. Dalam institusi ini proses pengembangan pengetahuan di kelas, lab, atau proyek-proyek penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen bisa berlangsung cukup cair dan egaliter. Batas-batas antara guru dan murid yang berlangsung di SD hingga SMU seakan kabur.
Namun, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa tak terelakkan. Bagaimanapun, dosen memiliki otoritas untuk mengajar, memberikan penilaian, serta membimbing tugas akhir. Di hadapan mahasiswa, dosen memiliki otoritas yang lebih tinggi dan mewakili wajah universitas. Dalam pelbagai kasus kejahatan seksual di kampus, ada kalanya dosen mengancam mahasiswa agar tidak melapor pada pihak yang berwajib. Sementara mahasiswa segan melapor karena takut berdampak pada kelangsungan studi mereka.
Pogge, Searle dan EH adalah idola mahasiswa karena dianggap cerdas, simpatik, dan menyenangkan. Dengan reputasi akademiknya, mereka memiliki modal sosial dan kultural yang cukup untuk membangun pengaruh dan kepercayaan yang besar di mata publik—termasuk merajut opini publik yang bisa menyudutkan korban saat melapor. Dalam banyak kasus pelecehan seksual di kampus, tidak jarang korbanlah yang justru diolok-olok sebagai barisan sakit hati yang cari perhatian, bahkan dituduh mencemarkan nama baik dosen dan institusi.
Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa merupakan populasi yang paling rentan terhadap pelbagai bentuk eksploitasi struktural di kampus. Pemerintah memiliki undang-undang perlindungan anak yang terbatas untuk "seseorang yang belum berusia 18 tahun" dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi pasangan suami-istri heteroseksual. Namun, tidak ada peraturan yang melindungi mahasiswa—yang rata-rata berusia 19-27 tahun—dari kekerasan fisik maupun psikologis di kampus.
Di samping itu, ketiadaan peraturan standar tentang pencegahan dan penanganan kasus kejahatan seksual di kampus mendorong penyelesaian melalui jalur “kekeluargaan”, yang sebenarnya lebih banyak merugikan korban daripada menjatuhkan hukuman yang pantas bagi pelaku.
Hal-hal seperti di atas belum mempertimbangkan jika pelakunya berstatus PNS. Umumnya mereka diperlakukan sebagai "aset kampus" yang tak tergantikan dan keberlangsungan karier mereka dijamin oleh pelbagai prosedur pemecatan yang sangat rumit dan berliku. Seorang PNS hanya dapat dipecat secara tidak hormat jika yang bersangkutan telah sah terbukti melakukan pelanggaran pidana oleh pengadilan.
Apa yang Bisa Dilakukan Kampus?
Alih-alih melindungi pelaku yang bisa memperburuk reputasi institusi pendidikan, pihak universitas perlu menegaskan bahwa kejahatan seksual merupakan hambatan bagi produksi pengetahuan yang menjadi aktivitas inti pendidikan tinggi. Kejahatan seksual juga bisa merusak kepercayaan peserta didik yang berhak mendapatkan suasana yang aman untuk belajar.
Ada banyak kampus dunia yang menerbitkan panduan ketat dan mendetail tentang pencegahan kejahatan seksual di kampus, layanan konseling yang berhak diakses korban, serta mekanisme pengaduan. Panduan tersebut juga merinci jenis-jenis perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual. Universitas Harvard dan berbagai kampus di Korea Selatan, misalnya, bahkan telah melakukan sosialisi pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sejak periode orientasi mahasiswa baru.
Kampus perlu membangun infrastruktur yang memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika, seperti memasang kamera CCTV di area-area tertutup, memberikan penerangan yang cukup di setiap sudut gedung, menyediakan ruang terbuka umum yang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas.
Langkah pertama yang bisa diambil universitas untuk menangani kejahatan seksual adalah membangun sistem layanan bagi korban/penyintas dengan tiga prinsip dasar pelayanan korban kejahatan seksual: jaminan perlindungan, jaminan kerahasiaan, dan jaminan kesetaraan. Harus dipastikan agar korban dapat melapor tanpa merasa dihakimi petugas layanan. Sistem layanan ini juga harus mengakomodasi mahasiswa perantau—ada banyak sekali korban berlatar belakang anak rantau yang akhirnya menyerah karena ingin lekas-lekas lulus dari kampus dan melanjutkan hidup.
Jika kampus tak mampu memberikan asistensi atau pendampingan intensif, kampus wajib menyediakan jasa psikolog/psikiater, penanganan kesehatan fisik, dan keamanan jika korban mendapatkan ancaman. Sistem ini memerlukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar kampus seperti rumah sakit, LSM, dan kepolisian.
Adapun tim investigasi yang independen dan imparsial dapat dibentuk dengan melibatkan perwakilan semua pihak di kampus. Sistem ini bisa dimulai dengan membentuk tim penyidik dari pihak rektorat, fakultas, mahasiswa, dan staf kampus, yang (jika perlu) bekerja sama dengan kepolisian yang memiliki kapasitas penyidikan. Kampus juga perlu mengatur mekanisme sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku.
Pada akhirnya Kementerian Ristek dan Dikti bisa mengambil langkah penting dengan menerapkan regulasi menyeluruh di tingkat nasional yang mewajibkan seluruh universitas negeri dan swasta memiliki sistem dan mekanisme jelas untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual.
Tanpa itu semua, para pelaku hanya akan menganggap kejahatan seksual sebagai perkara sepele dan terus mengulangi perbuatannya, seraya mengamini bahwa perilaku mereka otomatis terampuni berkat status "pahlawan tanpa tanda jasa."
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.