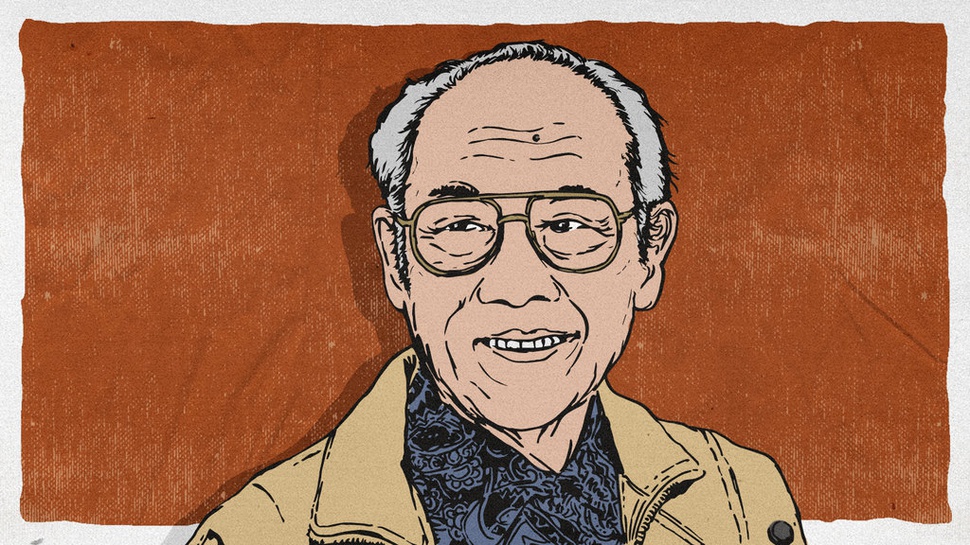tirto.id - Kesehatan Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya ditulis Pram) kian memburuk. Ia dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta, dan sempat dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU). Tak lama berselang, Pram meminta pulang ke rumahnya di Utan Kayu. Hari ketiga di rumah, setelah menyisihkan tabung-tabung dan peralatan yang merintanginya, Pram meminta rokok kretek kesayangannya. Ia lalu mengembuskan napas penghabisan pada pukul 09.15, tanggal 30 April 2006, tepat hari ini 15 tahun lalu.
Dalam Pram Melawan! Dari Perkara Sex, Lekra, Sampai Proses Kreatif (2011: 143, 374) yang disusun oleh P. Hasudungan Sirait, Rin Hindryati P, dan Rheinhardt disebutkan, di masa mudanya Pram ternyata pernah belajar mistik. Ketika penyakitnya kian parah, Pram gemar berbicara tentang kematian. Ia acap mengatakan sudah siap dan tak takut mati karena merasa sudah menunaikan segala yang perlu ia kerjakan.
Untuk kematiannya, Pram berpesan: “…Kalau aku mati jangan bikin apa-apa, jangan didoain segala, langsung saja bawa ke krematorium. Bakar di sana. Abunya bawa pulang. Mau dibuang juga terserah. Tapi, kalau bisa, wadahi dan taruh di perpustakaanku.”
Pesan hanya tinggal pesan. Jenazahnya tidak dikremasi, melainkan dikuburkan di TPU Karet Bivak setelah sebelumnya disalatkan.
Keluarga, kerabat, sejumlah aktivis dan penulis muda, hadir dalam pemakamannya. Mereka sedih dan kehilangan, tapi juga menggalang semangat sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebagai ucapan selamat jalan. Mereka menyanyikan "Internationale" dan lagu yang populer dalam masa-masa perjuangan melawan kediktatoran Soeharto: "Darah Juang".
Hikayat Keluarga dan Pendidikan
Pram lahir di Blora, 6 Februari 1925. Ia anak sulung dari sembilan bersaudara. Saat dilahirkan, usia kandungan ibunya baru delapan tahun. Ayahnya bernama M. Toer, sedangkan ibunya Saidah.
M. Toer berasal dari keluarga Bupati Kediri. Ia tumbuh dalam kebudayaan Jawa, dan terdidik dalam sekolah Barat. M. Toer pernah menjadi guru di Holand Indische School (HIS) Rembang, dan selepas menikah menjadi kepala sekolah di Perguruan Budi Utomo di Blora. Ia merupakan tokoh sosial-politik setempat dan pernah memegang jabatan yang pernah dipegang Dr. Sutomo yang pindah ke Surabaya. Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Blora.
Menurut Pram, ayahnya juga pengarang prosa dalam dalam bahasa daerah dan telah menghasilkan beberapa lagu dalam bahasa Jawa. Di antara karyanya, ada yang menjadi lagu-lagu rakyat. Selain itu, ayahnya pernah mengarang buku teks sekolah dasar yang tidak mengikuti kurikulum pendidikan kolonial. Pada 1930-an, M. Toer menulis dalam majalah dan surat kabar yang diterbitkan di Semarang dan Surabaya. Ia seorang penganut nasionalis kiri yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.
Sedangkan ibunya, Saidah, anak penghulu Kabupaten Rembang dan terdidik dalam Islam pesisir yang menurut Pram: lebih murni ketimbang Islam pedalaman. Saidah pernah belajar di sekolah dasar Belanda, juga di rumah melalui guru-guru Belanda yang didatangkan oleh kakeknya. Ketika berumur 18 tahun, Saidah menikah dengan gurunya: M. Toer--yang ketika itu berumur 32 tahun.
Karena penghasilan suaminya sebagai guru tidak mencukupi, Saidah pun mencari nafkah tambahan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang kerap menjadi bahan percekcokan dalam keluarga. Pram begitu prihatin atas kondisi ibunya. Itulah sebabnya, pengaruh ibu sangat besar pada dirinya.
Selain itu, seperti ditulis Koh Young Hun dalam Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia (2011: 1-22), Pram juga merasa telah terjadi konflik antara dua kebudayaan: Islam pesisir yang dianut ibu, dan Islam pedalaman yang dianut ayah. Di luar itu, terdapat sikap yang sama dalam diri ayah dan ibunya, yakni jiwa patriotik nasionalis kiri. Inilah faktor yang mengikat keduanya. Pram dididik agar menjadi manusia bebas dan tak malu bekerja.
Warsa 1929, Pram masuk sekolah dasar perguruan Budi Utomo, tempat ayahnya menjadi kepala sekolah. Ia tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam pelajaran sehingga tiga kali sempat tak naik kelas. Ayahnya masygul. Pram dikeluarkan dari sekolah dan selama setahun ayahnya sendiri yang mengajarnya secara teliti dan keras.
Setahun kemudian Pram masuk sekolah lagi. Sejak itu, prestasinya mulai normal sampai akhirnya lulus pada tahun 1939. Artinya, ia memerlukan waktu sepuluh tahun untuk lulus dari sekolah itu yang umumnya diselesaikan paling lama tujuh tahun.
Selepas itu, Pram tidak sekolah selama satu tahun karena ayahnya menolak keinginannya untuk meneruskan pelajaran ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah menengah pertama pada zaman kolonial Belanda.
Tahun 1940, Pram mulai belajar di Radio Vakschool Surabaya dengan biaya dari hasil usaha ibunya berjualan padi. Sekolah itu dipilihnya karena sejak di sekolah dasar ia banyak mempelajari bidang kelistrikan dari buku-buku pamannya, seorang mekanik yang bekerja di Kaledonia Baru. Pada akhir 1941, ia lulus dari sekolah radio tetapi tidak menerima ijazah. Surat tanda tamat belajar itu mesti dikirim dulu ke Bandung untuk disahkan, tetapi ternyata tidak dikembalikan.
Pram pulang ke Blora sebelum bala tentara Jepang masuk. Pada Mei 1942, ibunya wafat dalam usia 34 tahun. Tak lama setelah itu, ia meninggalkan Blora untuk merantau ke Jakarta dan masuk Taman Siswa. Di sekolah ini ia belajar bahasa Indonesia selama satu tahun. Lewat pelajaran ini, gurunya yang bernama Mara Sutan, menumbuhkan semangat nasionalisme kepada para muridnya. Sore dan malam hari, Pram bekerja sebagai juru tik di Kantor Berita Jepang, Domei.
Februari 1944, Domei menyeleksi para pegawainya yang lulusan sekolah menengah untuk belajar di “Stenografi Tjuo Sangiin”. Pram terpilih untuk belajar selama setahun, dan ia mulai berkenalan dengan berbagai tokoh politik. Setelah itu, ia menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam di Gondangdia (kini menjadi kantor imigrasi)--belajar filsafat, sosiologi, dan psikologi. Di samping itu, ia juga kembali bekerja di Domei, di bagian khusus perkembangan peperangan Cina-Jepang. Lalu pada Juni 1945, Pram meninggalkan Jakarta hendak menjelajahi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Percikan Revolusi
Agustus 1945, ketika bermukim sejenak di Kewedanaan Ngadiluwih, Kediri, ia mendengar dari bekas anggota Pembela Tanah Air mengenai kemerdekaan Indonesia. Pram segera menuju ke Surabaya dan kembali ke Jakarta setelah sebelumnya singgah ke Blora--menyaksikan kota yang dulunya mati karena pendudukan Jepang, kini tiba-tiba hidup kembali.
Oktober 1945, Pram menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat dan ditempatkan di Cikampek dalam kesatuan Banteng Taruna (Resimen 6) sebagai prajurit II. Dalam waktu singkat ia naik pangkat menjadi "sersan mayor".
Menurut A. Teeuw dalam Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer (1997: 19-25), pada pertengahan 1946 Pram menjadi perwira persuratkabaran dengan pangkat letnan dua, dan memimpin pasukan yang terdiri dari 60 orang prajurit. Garis depan mereka berpusat di Cibarusa, Klender, Bekasi, Cakung, Kranji, Lemah Abang, Krawang, dan Cileungsi, sementara markas besarnya di Cikampek.
Selama bertugas di Cikampek, ia menulis novel perdananya, Sepuluh Kepala Nica. Sayang, naskah itu hilang. Saat itu, Pram juga bertugas sebagai pembantu militer untuk surat kabar Merdeka di Jakarta. Suatu ketika, Pram nyaris mati saat kereta api yang ditumpanginya terbalik dan tenggelam dalam lumpur di Purwokerto.
Pram tidak lama menjadi prajurit. Tanggal 1 Januari 1947 ia meninggalkan kesatuannya tanpa menerima gaji yang belum dibayar selama tujuh bulan. Pram muak dengan praktik suap, permusuhan, dan konflik kepentingan di tubuh tentara. Ia lalu kembali ke Jakarta dan bekerja sebagai redaktur majalah Sadar, yang merupakan edisi Indonesia dari majalah The Voice of Free Indonesia bersama Naipospos.
Pada waktu itulah ia mengarang naskah Di Tepi Kali Bekasi berdasarkan pengalamannya di garis depan. Sebuah fragmen dari cerita itu, yakni Kranji Bekasi Jatuh, telah diterbitkan oleh The Voice of Free Indonesia. Saat itu pula Pram mulai berkenalan dengan H.B. Jassin yang bekerja di Balai Pustaka. Bulan April 1947, Pram menjadi ketua bagian penerbitan Indonesia. Jabatan itu dipegangnya karena ketua bagian sebelumnya ditangkap Nica dengan tuduhan terlibat dalam gerakan bawah tanah.
21 Juli 1947, aksi militer Belanda yang pertama pecah. Semua milik Republik Indonesia di Jakarta dikuasai oleh tentara Belanda. Pram mendapat tugas dari atasannya untuk mencetak dan menyebarkan risalah-risalah dan majalah perlawanan. Ia ditangkap oleh tentara Belanda dengan bukti surat-surat di kantongnya. Pram kemudian disiksa oleh Angkatan Laut Belanda yang terdiri dari orang-orang Belanda totok, Belanda peranakan, dan orang Ambon. Ia dimasukkan ke dalam tahanan tangsi Angkatan Laut di Gunung Sahari, lalu dipindahkan ke tangsi Polisi Militer. Selanjutnya ia dipindahkan ke Pulau Edam.
Selama dalam penjara, Pram menulis sejumlah novel dan cerpen, seperti Perburuan dan Keluarga Gerilya. Karya-karya itu, berkat bantuan Prof. Resink, dapat diseludupkan dan disiarkan di pelbagai majalah, di antaranya Mimbar Indonesia dan Siasat. Pram dibebaskan pada 18 Desember 1949.
Dalam Gelombang Politik
Tak lama setelah dibebaskan, Pram menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka untuk karyanya Perburuan. Tanggal 15 Januari 1950 ia menikah dengan Arafah Iljas, anggota Palang Merah. Mei 1950, ia bekerja di Balai Pustaka sebagai penyunting di bagian sastra Indonesia modern, dan pernah pula menjadi redaktur majalah anak-anak, Kunang-Kunang.
Dua hari setelah menjadi redaktur Balai Pustaka, Pram terpaksa pulang ke Blora karena ayahnya sakit keras dan kemudian wafat. Peristiwa ini ia tuangkan dalam roman Bukan Pasarmalam. Januari 1952, Pram mendirikan agensi kesusastraan bernama L & F Acy Duta, tapi tidak bernapas panjang. Lalu pada September 1952, Pram bersama Basuki Resobowo mendirikan Gelanggang Kesenian, sebuah badan kesusastraan.
Mei 1953, Pram melawat ke Belanda untuk belajar atas biaya Sticusa (Stichtung voor Culturele Samenwerking, Yayasan Kerja Sama Kebudayaan Belanda-Indonesia). Selama di Belanda, ia menulis novel Midah Si Manis Bergigi Emas. Kumpulan cerpennya yang berjudul Cerita dari Blora, menerima hadiah sastra dari Badan Musyawarah Kesenian Nasional (BMKN). Januari 1954, ia kembali ke Indonesia.
L & F Acy Duta yang telah mati tidak dapat dihidupkan lagi. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi keluarganya terpuruk. Pram terpaksa meninggalkan istrinya setelah empat kali diusir. Awal 1955, ia menikah lagi dengan Maimunah Thamrin, keponakan Mohammad Husni Thamrin.
Menurut Hong Liu dalam artikel "Pramoedya Ananta Toer and China: The transformation of a cultural intellectual", Indonesia, No. 61 (1996: 119-43), pada Oktober 1956 Pram melawat ke Beijing atas undangan Lembaga Sastrawan Cina Pusat untuk menghadiri peringatan ke-20 meninggalnya pujangga Lu Xun. Di Cina, Pram memperoleh pengertian yang agak luas tentang pentingnya faktor rakyat jelata dalam pembinaan bangsa yang kuat-padu bersama dengan pembangunan yang menyeluruh. Ia mulai curiga terhadap kemajuan sosio-ekonomi Barat.
Februari 1957, Pram menulis esai "Jambatan Gantung dan Konsepsi Presiden" di Harian Rakjat untuk mendukung gagasan Presiden Sukarno perihal Demokrasi Terpimpin. Lalu bersama Henk Ngantung dan Kotot Sukardi, Pram membentuk delegasi seniman agar menyatakan sikap mendukung cita-cita Demokrasi Terpimpin. Delegasi seniman yang terdiri dari 67 orang itu menghadap presiden pada Maret 1957. Kemudian pada 28 Desember 1957, Pram dilantik sebagai anggota penasihat Kementerian Petera (Pengerahan Tenaga Rakyat).
Juli 1958, Pram mendirikan kelompok diskusi Simpat Sembilan yang beranggotakan para seniman, wartawan, dan mahasiswa. Lalu pada 7 September 1958, ia memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Pengarang Asia-Afrika di Tasykent. Dalam delegasi ini, Utuy T. Sontani dan Dodong Djiwapradja turut serta. Dari sana, Pram terus melawat ke Turkmenia dan Moskow. Setelah singgah di Siberia, Beijing, dan Rangoon, Pram kembali ke Indonesia pada 21 Oktober 1958.
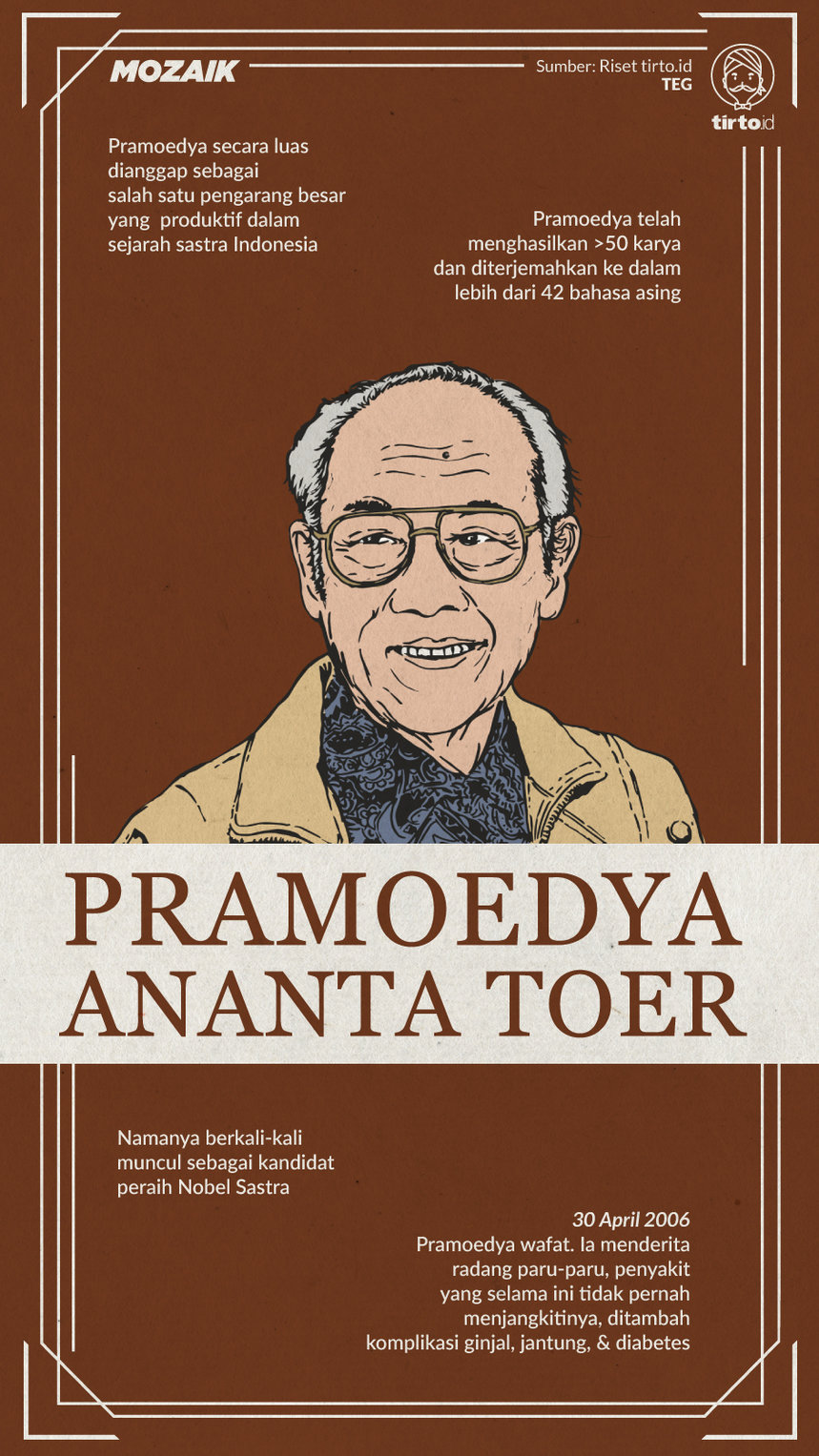
Tanggal 23 Januari 1959, ia ikut dalam Kongres Nasional I Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra) di Solo. Pram bukan anggota organisasi, ia diundang karena dianggap sebagai sastrawan yang masyhur. Ia kemudian diangkat menjadi anggota pleno Lekra berdasarkan keputusan kongres.
Maret 1960, Pram menerbitkan Hoa Kiau di Indonesia. Buku ini dituduh berisi pembelaan terhadap pedagang-pedagang keturunan Cina yang diusir dari daerah tingkat kecamatan. Akibatnya, ia diseret ke penjara Cipinang selama sembilan bulan tanpa proses pengadilan.
Menurut Hilmar Farid dalam “Pramoedya dan Historiografi Indonesia”, sejak 1960 hingga 1965, Pram menjadi anggota Komite Peace Organization. Mulai 1958 sampai 1965, ia juga bekerja sebagai anggota panitia yang menangani program Asia African Writers Conference. Di antara kesibukannya, Pram juga bekerja sebagai redaktur rubrik “Lentera”, lampiran kebudayaan harian Bintang Timur antara 1961 sampai 1964. Selama periode itu, ia memberikan kuliah sejarah dan sastra modern di Fakultas Sastra Universitas Res Publika, dan memberikan kuliah sejarah bahasa Indonesia di Akademi Wartawan Dr. Abdul Rivai. Pramoedya juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Akademi Sastra Multatuli.
Sejak 13 Oktober 1965, semua kegiatan intelektualnya seketika terhenti. Ia dituduh terlibat dalam kegiatan-kegiatan Lekra yang dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai badan yang disusupi komunisme. Tanpa proses pengadilan, Pram ditahan di Rumah Tahanan Militer Tangerang sampai bulan Juli 1969. Selanjutnya ia dipindahkan ke penjara Karang Tengah, Nusakambangan. Pada 16 Agustus 1969, Pram bersama 850 tahanan politik lainnya dikirim ke Pulau Buru.
Anak-Anak Rohani
Menurut Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony (2002: 222-3), pada mulanya Pram tidak boleh menulis. Namun setelah Jenderal Soemitro datang ke Pulau Buru pada 1973, barulah ia diizinkan menulis. Sejak itu ia menulis tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ia juga menulis Arok Dedes, Arus Balik, Mangir, dan Nyany Sunyi Seorang Bisu.
Pram baru dibebaskan pada 21 Desember 1979 setelah melewati penjara Magelang, Semarang, dan Salemba. Meski demikian, ia dikenakan wajib lapor dan tidak mempunyai hak memilih atau dipilih dalam pemilu.
Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa terbit pada Agustus dan Desember 1980. Namun, keduanya segera dilarang beredar di seluruh Indonesia oleh pemerintahan Soeharto sejak 29 Mei 1981. Alasan yang ditimpakan: mengandung ajaran terlarang, yakni "pertentangan kelas". Tahun 1985, Jejak Langkah dan Sang Pemula diterbitkan. Keduanya juga dilarang sejak 1 Mei 1986. Selanjutnya diterbitkan Gadis Pantai tahun 1987, Rumah Kaca, dan Hikayat Siti Mariah pada April 1988, yang kelak semuaya dilarang.
"Sudah saya menulis apa yang ingin saya tulis. Sudah saya punya apa yang ingin saya punya,” ujar Pram dua bulan sebelum meninggal.
Editor: Irfan Teguh Pribadi