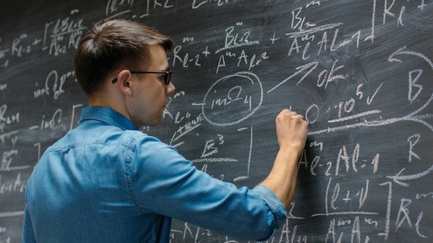tirto.id - Tak hanya Indonesia yang kerap berkutat dengan masalah manajemen, baik itu berkaitan dengan pengorganisasian manusia maupun perencanaan keuangan.
AS pernah terkungkung dalam masalah mandeknya proyek kereta cepat California yang menghubungkan San Francisco dan Los Angeles. Dimulai sejak 2008, proyek ini kerap mengalami penundaan dan menerima banyak kritik dari masyarakat maupun politisi.
Biaya pengerjaannya terus melonjak, dari perkiraan awal 33 miliar dolar AS menjadi 100 miliar dolar AS. Meski banyak pihak yang menyarankan untuk menghentikan proyek ini, karena biaya tak terkendali dan manfaat yang diragukan, pemerintah tetap keukeuh menjalankannya, dengan pembangunan yang lambat.
Di Finlandia, megaproyek pembangkit listrik tenaga nuklir Olkiluoto 3 juga tak lepas dari masalah. Sejak pertama kali dicanangkan pada 2003, proyek pembangunan reaktor nuklir terbesar di Eropa ini berkali-kali mangkrak.
Proyek ini baru selesai pada 2022, terlambat 13 tahun dari waktu yang telah direncanakan. Biaya pengerjaannya pun membengkak, dari mulanya 3 miliar euro menjadi 11 miliar euro, lebih dari tiga kali lipat!
Kasus yang terjadi di dua negara tersebut menggambarkan contoh manajemen yang buruk. Proyek atau gagasan yang ambisius tetap dilaksanakan meskipun sudah jelas tidak efektif karena birokrasi, tekanan politik, atau ketidakmampuan untuk mengakui kegagalan sejak dini.
Kekeraskepalaan negara, organisasi, atau perusahaan, dalam menjalankan sesuatu, tergambarkan melalui metafora yang disebut Teori Kuda Mati (Dead Horse Theory). Teori ini menggambarkan situasi seseorang atau kelompok yang terus berupaya melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak efektif atau tidak mungkin berhasil.
Analogi ini diambil dari seseorang yang berusaha menunggangi kuda yang sudah mati—tindakan yang sia-sia dan tidak akan membawa hasil.
Asumsi Dasar Teori Kuda Mati
Teori Kuda Mati, meskipun mungkin terdengar seperti konsep yang aneh atau bahkan terkesan lucu, sebenarnya menawarkan perspektif menarik tentang cara manusia menghadapi kegagalan dan upaya yang tidak membuahkan hasil.
Asumsi mendasar dari teori ini adalah bahwa kuda, dalam konteks metaforis, telah mati ketika ditunggangi. Ini berarti, kuda tersebut tidak lagi dapat berfungsi atau memberikan manfaat apa pun.
Mengakui kuda tersebut telah mati seharusnya menjadi latihan yang objektif dan mudah. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa turun dari kuda dan meninggalkan upaya yang gagal bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat disarankan.
Teori Kuda Mati berakar pada pemahaman bahwa manusia sering kali terjebak dalam upaya yang tidak produktif atau bahkan merugikan. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis, kehidupan bernegara, hubungan interpersonal, hingga proyek-proyek skala besar.
Tidak ada pencetus tunggal maupun sosok yang pertama kali melontarkan teori ini. Meski ada dugaan berasal dari warisan lokal suku Indian Dakota, teori ini lebih merupakan sebuah metafora atau anekdot yang digunakan dalam konteks manajemen untuk menggambarkan situasi ketika seseorang terus melanjutkan suatu proyek atau gagasan yang sudah jelas tidak mungkin berhasil atau sudah “mati”.
Konsep Kuda Mati menekankan pentingnya mengetahui titik ketika seseorang harus berhenti mengalokasikan sumber daya ke sesuatu yang tidak memberikan hasil. Teori ini menawarkan perspektif yang berbeda: lebih baik mengakui kegagalan dan mencari solusi baru daripada terus membuang-buang sumber daya yang berharga.
Selain itu, teori ini menyoroti bahwa upaya yang gagal kerap dianggap sebagai rahasia umum. Meskipun menyadari upayanya tidak berhasil, seseorang sering kali enggan mengakuinya secara terbuka. Ini bisa disebabkan oleh rasa malu, takut akan kegagalan, atau tekanan sosial. Manusia memang sering kali terjebak dalam masalah yang tidak perlu, terutama ketika mereka enggan untuk menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.
Teori Kuda Mati mengingatkan kita bahwa terkadang solusi yang paling sederhana, misalnya mengakui kegagalan dan mencari jalan baru, adalah yang paling efektif.
Kekurangan Rencana dan Masalah yang Tidak Dapat Dipecahkan
Vijay Govindarajan dalam bukunya, Three Box Solution: A Strategy for Leading Innovation, menyarankan perusahaan memahami solusi tiga kotak, yakni mengelola masa kini, secara selektif meninggalkan masa lalu, dan menciptakan masa depan.
Vijay melihat, perusahaan sering kali berkutat di kotak kedua. Mereka kesulitan melupakan keberhasilan dan pola pikir lama. Ia menekankan adanya seleksi. Artinya adalah melupakan pola pikir usang dan mempertahankan yang relevan.
Bahkan, ada pula perusahaan yang berusaha "menghidupkan kembali kuda mati". Misalnya dengan membentuk komite baru, memberikan pelatihan tambahan, mengubah citra, atau bahkan mempromosikannya lagi dengan lebih gencar, tetapi idenya tetap usang.
“Itu cara yang buruk untuk menjalankan negara, itu cara yang buruk untuk menjalankan perusahaan, cara yang buruk untuk menjalankan kehidupan pribadi seseorang,” katanya, dalam wawancara dengan Forbes.
Meskipun menawarkan perspektif yang berharga tentang cara menghadapi kegagalan, Teori Kuda Mati mengakui bahwa tidak ada kekurangan rencana mengenai pemecahan masalah yang tidak dapat dipecahkan.
Dalam banyak kasus, manusia terus mencari solusi yang tidak ada, bahkan meskipun sudah terbukti bahwa upayanya sia-sia. Ini bisa disebabkan oleh optimisme yang berlebihan, ketidakmampuan untuk menerima kenyataan, atau ketakutan akan konsekuensi dari kegagalan.
Teori Kuda Mati menegaskan bahwa terkadang masalah tersebut memang tidak dapat dipecahkan, dan upaya untuk terus mencoba hanya akan memperburuk situasi.
Mengapa Organisasi Terjebak dalam Sunk Cost Fallacy?
Implikasi utama dari Teori Kuda Mati adalah bahwa meninggalkan upaya yang gagal bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Dalam banyak kasus, manusia cenderung terjebak dalam sunk cost fallacy, yakni kecenderungan untuk terus berinvestasi dalam upaya yang gagal karena mereka telah menginvestasikan banyak waktu, uang, atau usaha ke dalamnya.
Sunk cost fallacy merupakan fenomena psikologis yang sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keputusan bisnis, investasi, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, istilah ini merujuk pada biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan.

Dalam konteks psikologi, sunk cost fallacy muncul ketika seseorang membuat keputusan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan (sunk cost), alih-alih mempertimbangkan manfaat atau kerugian di masa depan. Misalnya, seseorang terus menonton film yang tidak menarik hanya karena telah membeli tiketnya, atau perusahaan terus menggelontorkan dana ke proyek yang gagal karena telah menginvestasikan banyak sumber daya di awal.
Fenomena ini pertama kali dijelaskan secara formal oleh ekonom Richard Thaler dan dihubungkan dengan teori perilaku ekonomi, melalui bukunya, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. Sunk cost fallacy bukan hanya masalah logika atau ekonomi, tetapi juga melibatkan emosi dan psikologi manusia.
Rasa kehilangan (loss aversion), penyesalan, dan keengganan mengakui kegagalan, sering kali menjadi faktor pendorong di balik keputusan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak efektif.
Terkadang, individu atau kelompok berharap bahwa dengan terus berinvestasi, situasi akan membaik, meskipun tidak ada indikasi proyeknya akan mengalami keberhasilan.
Misalnya, dalam investasi pribadi, seseorang mungkin terus memegang saham yang merugi karena mereka telah membelinya dengan harga tinggi. Alih-alih menjual saham tersebut dan menginvestasikan uangnya ke tempat lain, ia berharap harga saham akan naik kembali, padahal indikasinya saham tersebut terus menurun.
Ketika Teori Kuda Mati Diterapkan dengan Bijak
Pada awal 2000-an, Netflix melihat potensi besar dalam teknologi streaming. Meskipun bisnis DVD-nya masih menguntungkan, mereka memutuskan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi streaming. Keputusan tersebut membawa Netflix menjadi pemimpin global dalam industri hiburan digital.
Bayangkan, jika tetap bertahan pada model DVD dan terlambat menyadari potensi, Netflix mungkin sudah kalah saing.
Perusahaan lain yang sukses keluar dari kubangan Teori Kuda Mati adalah Microsoft. Setelah melihat potensi besar dalam komputasi awan (cloud computing), mereka memutuskan untuk mengembangkan Azure, platform cloud mereka.
Meskipun itu berarti mengalihkan sebagian besar sumber daya ke bisnis baru, keputusan tersebut membuat Microsoft tetap relevan dan kompetitif di era digital.
Perusahaan yang berhasil adalah mereka yang berani mengambil risiko, berinovasi, dan mengalihkan sumber daya ke peluang baru, meskipun itu berarti meninggalkan model bisnis atau produk yang sudah mapan di masa itu.
Menurut Marcin Majka dalam artikel jurnal “Dead Horse Theory: How to Rebuild and Revitalize Your Product”, kurangnya budaya inovatif memicu perlawanan terhadap perubahan di dalam organisasi, yang berdampak pada adaptabilitas. Hierarki yang kaku dan penghindaran risiko dapat menghambat kreativitas dan menghalangi respons yang efektif terhadap dinamika pasar.
Mempertahankan strategi yang sudah terbukti gagal dapat berdampak negatif, misalnya pemborosan sumber daya, penurunan moral tim, kehilangan peluang dan reputasi publik. Waktu, uang, dan tenaga, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk strategi yang lebih efektif, justru terbuang percuma. Ketika menyadari upayanya tidak membuahkan hasil, motivasi dan produktivitas tim akan menurun.
Jika terus fokus pada strategi yang gagal, sebuah organisasi bakal kehilangan peluang untuk mengembangkan inovasi berikutnya, bahkan merusak reputasi organisasi di mata pemangku kebijakan, pelanggan, investor, mitra bisnis, dan pangsa pasar.
Agar tak terjebak dalam Teori Kuda Mati, pemimpin perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Misalnya, melakukan evaluasi secara teratur terhadap strategi yang sedang dijalankan dengan berlandaskan pada data dan metrik yang jelas untuk mengukur efektivitasnya.
Sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa jalannya organisasi ditentukan oleh keputusan pemimpin. Pemimpin sejati memahami momentum ketika organisasinya perlu berubah arah, menyetop berbagai kerugian, dan menghentikan proyek yang tidak produktif.
Pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengakui ketika strateginya sudah jelas tidak akan berhasil. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan dan kecerdasan. Kegagalan merupakan bagian dari proses belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua upaya akan berhasil.
Dengan mengakui kegagalan dan menghentikannya, organisasi akan terdorong untuk berinovasi dan bereksperimen tanpa rasa takut. Jadi, jika hari ini Anda menemukan diri Anda atau organisasi Anda sedang “menunggangi kuda mati”, ingatlah bahwa terkadang langkah terbaik adalah turun dari kuda tersebut dan mencari kendaraan baru yang lebih menjanjikan.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id