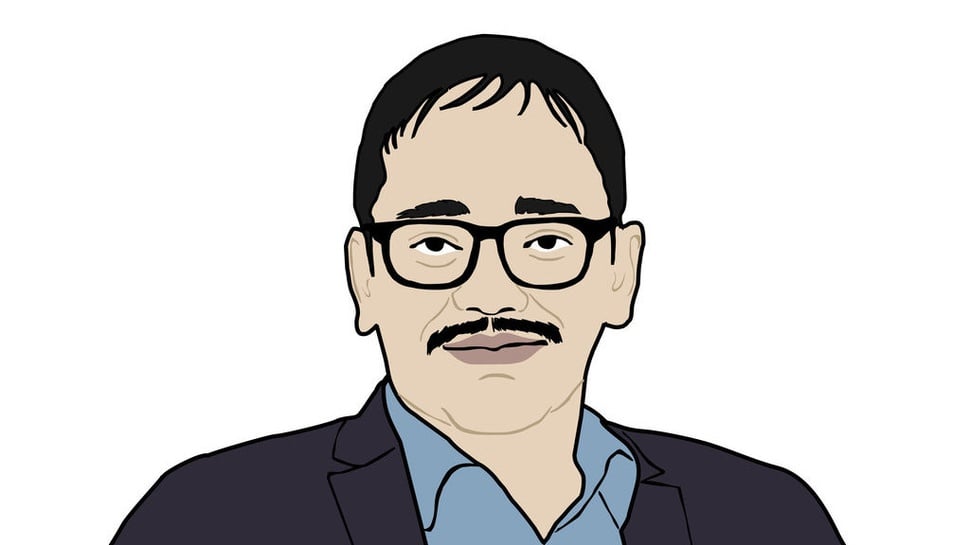tirto.id - Wacana pemindahan ibukota bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Menjelang Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah membuat rencana memindahkan ibukota ke Jawa Barat dengan pertimbangan lebih terlindungi secara militer. Pada dekade 1950-an, presiden Sukarno menggulirkan wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada masa yang lebih kontemporer, presiden SBY pun pernah menggulirkan wacana tersebut pada masa pemerintahannya. Namun, semua menjadi wacana di atas kertas yang belum sempat terwujud atas dasar beragam faktor yang melatarbelakangiinya.
Jadi, ketika presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur, gelombang reaksi yang muncul—antara setuju dan tidak setuju—sudah dapat diduga sebelumnya. Bagaimana negara membiayainya? Apakah ini kebijakan yang tepat? Apakah benar pemindahan ibukota akan membawa energi pemerataan pertumbuhan di Indonesia?
Tak bisa dipungkiri, rencana pemindahan ibukota selalu mengundang perdebatan. Perdebatan itu sendiri menunjukkan bahwa ibukota bukan sekedar pusat pemerintahan negara semata, tetapi juga membentuk sentimen emosional atau “struktur perasaan”, meminjam istilah teoritisi kebudayaan Raymond Williams, yang dibentuk oleh faktor-faktor dominan, residual, dan emergent dalam perkembangan sejarahnya. Dengan meminjam pendekatan tersebut, tulisan ini mencoba menelusuri dengan cara apa ibukota dianggap penting dalam kesadaran umum masyarakat Indonesia, dan faktor-faktor dominan, residual, dan emergent seperti apa yang bekerja dibalik pembentukan kesadaran tersebut?
Pola Sejarah
Upaya menggali struktur perasaan yang menaungi perdebatan tentang arti penting ibukota dalam kesadaran masyarakat Indonesia menuntut sebuah penelusuran sejarah panjang yang merentang sampai periode prakolonial.
Studi arkeologi dan sejarah telah menunjukkan bahwa perpindahan ibukota adalah sebuah kelaziman mengikuti kebangkitan dan kemunduran sebuah sistem kekuasaan dalam masyarakat tradisional. Pergeseran pusat kekuasaan—sekaligus ibukota—dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada peralihan abad ke-9 dan ke-10 menjadi bukti menarik tentang kelaziman tersebut.
Begitu juga dengan kemunculan Majapahit ketika Raden Wijaya membangun ibukota baru di Mojokerto. Singasari dan Kediri sebagai ibukota lama pada akhirnya sekedar menjadi kota satelit yang tidak lagi menjadi ancaman politik dan militer baginya. Pola yang sama terjadi dalam kemunculan para penguasa Islam di pesisir. Penguasa Demak hanya membawa regalia dan simbol-simbol kejayaan penguasa lama pasca invansi militer mereka ke Majapahit, dan membiarkan ibukota lama menjadi belukar tak berarti dengan membangun ibukota baru di Demak.
Pola ini menunjukkan bahwa di dalam sistem kekuasaan tradisional prakolonial, landasan konsentris di dalam lingkar dalam yang menjadikan ibukota sebagai pusat ekonomi dan politik yang menyerap semua kekuatan yang ada di sekitarnya. Ia tidak mengizinkan adanya kekuatan lain yang akan dianggap sebagai tandingan dan ancaman politik serta militer bagi sebuah sistem kekuasaan. Perkembangan sebuah ibukota terjadi dalam pola seperti ini.
Kedatangan penguasa kolonial Belanda, khususnya memasuki era liberal pada akhir abad ke-19, membawa pola baru yang menjadi patahan dalam pola itu. Ibukota tak lagi berperan sebagai pusat segalanya, tetapi lebih mewakili sebuah sistem pemerintahan yang berjalan berbeda dengan sistem ekonomi. Kekuasaan kolonial bekerja dengan topangan sistem ekonomi baru yang secara teori membuat perbedaan tegas antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam ideologi liberal yang memisahkan peran negara dan modal, birokrat dan pengusaha. Sejak ditetapkannya Agrarische Wet 1870 yang menjadi tonggak liberalisasi koloni untuk perkembangan modal swasta, Batavia hanya berjalan sebagai fungsi administrasi pemerintahan kolonial di mata warga Eropa di koloni. Kapitalisme kolonial dalam gelombang penuh bergerak mencari wilayah-wilayah strategis bagi perkembangan modal, yang sekaligus memunculkan kota-kota baru di koloni.
Surabaya menjadi salah satu kota baru yang berkembang dalam iklim perkembangan ekonomi liberal di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Modal kolonial yang bergulir sejak era liberal pada paruh terakhir abad ke-19 mengambil tempat perkembangannya di Surabaya sebagai simpul menghubungkan sentra-sentra produksi penghasil gula dan tanaman keras di wilayah pedalaman yang subur seperti Jombang, Madiun, Pasuruan, dengan pasar dunia di Amsterdam, Londong, dan New York. Surabaya menjadi pusat perkembangan industri di Hindia, sekaligus oposisi dari kalangan industriawan dengan pandangan ekonomi liberal yang bertentangan dengan gaya patronase politik para birokrat di Batavia.
Sentimen populernya bisa ditunjukkan melalui ulasan dalam artikel yang ditulis Moses van Geuns, redaktur Soerabajasch Handelsblad, suratkabar terbesar di Hindia-Belanda saat itu. “Apabila bukan karena tempatnya sebagai pusat pemerintahan, sulit bagi Batavia untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai kota utama di Hindia”, tulis Moses van Geuns, redaktur Soerabajasch Handelsblad, suratkabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia saat itu (“Groeit Batavia”, SH, 16 April 1907). Dalam hal ini Van Geuns mewakili sentimen populer di kalangan jurnalis, seniman, dan industriawan Surabaya yang memandang kota mereka jauh lebih penting dibanding Batavia.
Pandangan ini sendiri tidak terlalu berlebihan. Joseph Chailley-Bert, politikus Perancis yang singgah di Surabaya pada awal abad ke-20 menangkap sentimen itu. “Sebenarnya itu rivalitas yang tidak perlu”, tulisnya. “Surabaya jauh lebih mewah dan kaya dibanding Batavia” (Chailley-Bart, 1901). Ringkasnya, di dalam era kapitalisme kolonial, ibukota bukanlah segalanya—paling tidak di mata warga Eropa yang tinggal di koloni saat itu.
Exemplary Center
Namun, arah perkembangan baru terjadi setelah terbentuknya pemerintahan republik yang merdeka. Jakarta berkembang pesat melampaui kota-kota lainnya. Mengapa hal ini terjadi?
Di sini yang terjadi adalah residu-residu lama dalam tatanan tradisional mendapatkan daya hidupnya kembali. Kekuasaan adalah sumber kehidupan, sekaligus sumber kekayaan dan kemajuan. Kaum industriawan Eropa yang berjarak dan bertentangan dengan negara kembali ke negeri asal, digantikan kekuatan dominan baru dari para pengusaha binaan negara melalui berbagai proyek pemerintah yang melahirkan bentuk “kapitalisme semu” dengan para agen yang menjadi kekuatan emergent yang saat itu lazim disebut “kapitalis birokrat”.
Rezim Orde Baru menjadikan kekuatan emergent tersebut menjadi kekuatan dominan yang membentuk arah dan orientasi pembangunan di Indonesia. Dengan residu tradisional yang menjadikan ibukota bukan sekedar pusat pemerintahan, tetapi juga exemplary center yang memancarkan sinar kehidupan politik, ekonomi, dan budaya bagi wilayah-wilayah lainnya, Jakarta berkembang dengan pertumbuhan luar biasa tanpa tandingan dibanding kota-kota lainnya di Indonesia
Kapital finansial di tangan pemburu rente menjadi kekuatan utama pertumbuhan Jakarta. Perkembangan sektor jasa dan properti tumbuh dalam arus modal uang yang membutuhkan patron-patron politik bagi kelangsungan hidupnya, yang berbeda di bawah kolonialisme Belanda ketika modal modal menjadi kekuatan mandiri tanpa patronase kekuasaan yang melindunginya.
Seiring bergulirnya wacana pemindahan ibukota, berkembang pula sebuah analogi yang membayangkan Jakarta seperti kota-kota di Amerika Serikat yang menampilkan perbedaan kemajuan antara Washington DC sebagai pusat pemerintahan dengan New York atau kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Namun, ini adalah analogi terburu-buru yang tidak berpijak pada sejarah.
Fakta adanya gagasan bahwa perpindahan ibukota dapat merangsang pertumbuhan baru yang semakin mengalirkan “pemerataan” menguatkan adanya cermin pemikiran yang berbalut residu kosmologi tradisional. Pusat kekuasaan adalah sekaligus pusat pertumbuhan. Kekuatan utama yang bergerak dalam pemerataan itu adalah perpindahan para pemburu rente yang tidak bisa jauh dari kekuasaan negara.
Jadi, bayangan bahwa Jakarta akan bertahan dalam kemajuannya sebagai pusat modal finansial layak dipertanyakan. Bisa jadi ia berakhir menjadi belukar beton modern yang kehilangan pesonanya seperti dialami kota-kota tradisional lainnya dalam sejarah Indonesia.
Barangkali saja memang Jakarta akan berkembang dalam arah lain meninggalkan belenggu sejarah lama. Kelas menengah kota yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir—meski sama sekali tidak bisa bebas dari patron-patron politiknya—mungkin saja menjadi kekuatan emergent baru yang membentuk arah dan perkembangan Jakarta sebagai ibukota yang ditinggalkan. Namun, persoalan pentingnya adalah sejauh mana mereka dapat menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia masa depan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.