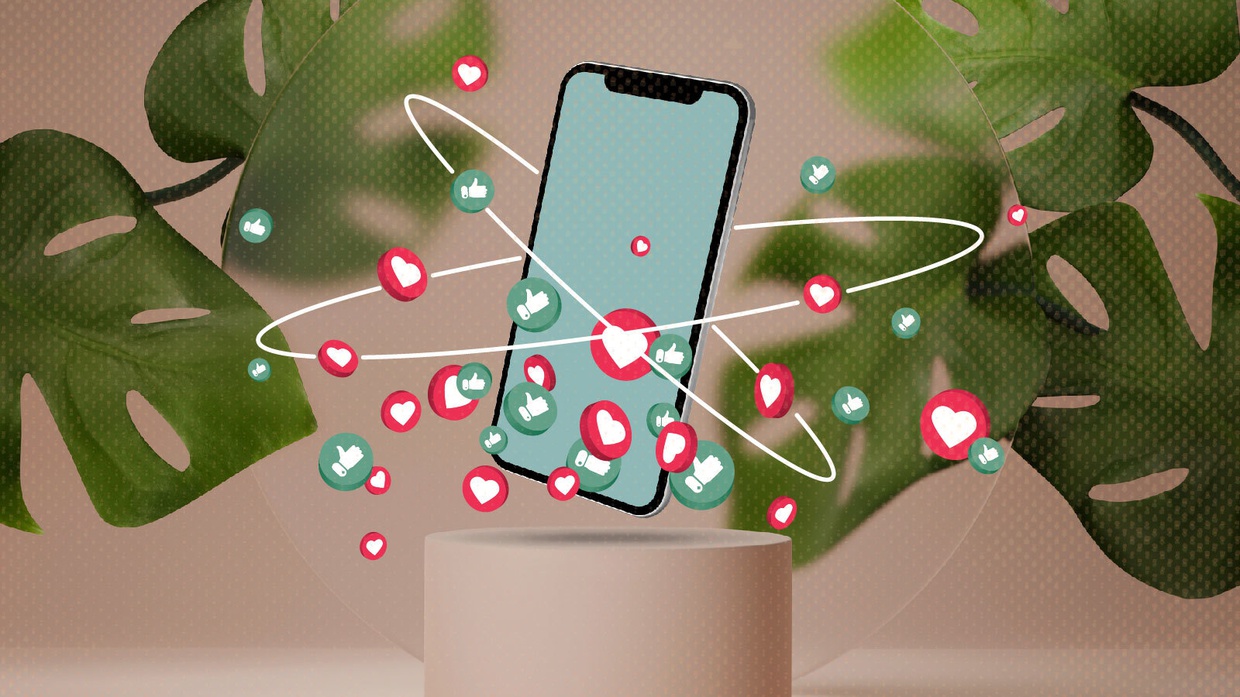tirto.id - Selain kualitas produk dan harga, reputasi jenama menjadi pertimbangan Anges Anya, saat hendak membeli produk kosmetik. “Aku cenderung memilih brand yang iklannya artsy dengan model-model orang biasa dan mengampanyekan self love,” tulisnya via surel, pekan lalu.
Perempuan berusia 28 tahun itu, besar di lingkungan keluarga yang tidak selalu suportif dalam memandang penampilan fisiknya. Sewaktu kecil, ia diejek karena memiliki kulit cokelat dan hal itu bikin dia sempat tidak percaya diri.
“I know, pathetic ya," kata Agnes. "Padahal DNA dan fitur kulit cokelat juga turun dari keluarga".
Ketika mulai mampu menerima diri apa adanya, ia makin tidak tertarik melihat produk kecantikan yang melakukan promosi dengan klaim ‘memutihkan kulit’ atau istilah lainnya sekarang ‘mencerahkan kulit wajah’.
Anya adalah bagian dari milenial yang kini menjadi salah satu kategori konsumen berpengaruh dalam penjualan produk kosmetik. Golongan berpengaruh lainnya adalah Gen Z, individu yang lahir pada rentang tahun 1996 hingga 2012. Pada 2019, lembaga konsultan dan prediksi tren WGSN menganalisis, pada 2020, sebanyak 40 persen konsumen produk kecantikan global akan berasal dari kalangan Gen Z.
Benang merah dari dua golongan konsumen berpengaruh ini adalah motivasi dalam mengonsumsi produk kecantikan. Mereka mempertimbangkan reputasi jenama, gemar mengeksplorasi produk kecantikan, dan tak mudah termakan iklan.
Prinsipnya, peluang transaksi jual beli semakin besar bila ada kesamaan persepsi dan ‘nilai’ antara konsumen dan brand kecantikan. Misal terkait cara pandang terhadap diri sendiri—seperti nilai self love yang disebut di atas—maupun apa yang sedang dianggap penting dalam lingkup sosial.
Apa Keuntungan Bisnis dari Mendorong Pengesahan RUU PKS?
Sepanjang 2021, kampanye soal anti kekerasan seksual—setidaknya turut disemarakkan dua brand kecantikan The Body Shop Indonesia (TBSI) dan L’Oreal Paris (LP)—ramai di media sosial. Kampanye sosial itu beriringan dengan perjuangan berbagai kelompok gerakan perempuan, mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)—yang dirancang sejak 2012—agar segera disahkan melalui DPR RI.
Perbedaan cara pandang yang dimiliki sejumlah anggota badan legislatif di DPR RI, membuat RUU ini tidak dianggap penting. Padahal, isi RUU hendak menjamin perlindungan hak korban kekerasan seksual dan mengaktifkan tanggung jawab negara.
Di tengah dinamika tersebut, TBSI memutuskan turut mendesak pengesahan RUU PKS dan membantu rehabilitasi korban kekerasan seksual. Perusahaan ini berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif mengadvokasi isu tersebut—kini berkolaborasi dengan Yayasan Pulih—, bikin petisi untuk diserahkan ke lembaga legislatif, ikut serta dalam audiensi, melakukan silent demo, dan memberi donasi pada LSM yang bertindak sebagai partner.
“Kami akan terus kawal sampai RUU ini disahkan,” kata Ratu Omayya, Head of Values, Community & Public Relations TBSI.
Setiap tahun, TBSI menggalakkan kampanye sosial yang berkaitan dengan isu lingkungan atau kesejahteraan perempuan. Pada tahun 2004 hingga 2008, TBSI bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2009 hingga 2012, TBSI bekerjasama dengan ECPAT Indonesia melakukan kampanye ‘stop perdagangan anak’ dengan tujuan besar melakukan rehabilitasi korban.
“Kami selalu cari isu yang paling urgent buat di-support,” kata Omayya.

Omayya menuturkan, pada tahun 1976, The Body Shop didirikan aktivis Anita Roddick yang percaya brand kecantikan punya kekuatan membawa perubahan. “Pembeli juga agent of change,” lanjutnya.
Lantas, apakah kampanye ini menguntungkan untuk bisnis TBSI?
“Kampanye dan sales adalah dua hal yang berbeda,” kata Omayya.
Dia menjelaskan, ada jenis konsumen yang membeli karena suka produk, ada pula yang membeli karena tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh brand. Awalnya kategori konsumen itu terbagi hampir sama rata. Namun setelah penggunaan media sosial semakin marak sejak 2015, persentasenya berubah.
“Customer shift drastically,” kata Adina Maria, Brand General Manager of L’Oreal Paris. Menurutnya, lima tahun belakangan konsumen tidak bisa lagi dipersuasi lewat iklan. Mereka—milenial muda dan Gen Z menengah ke atas yang jadi target konsumen LP—sudah teredukasi, kritis, dan tahu apa yang diinginkan.
“Harus ada aksi konkret, interaktif, dan tangible,” ujar Adina menyebut cara mendekati konsumen saat ini. “Enggak bisa menggunakan brand communication tetapi pakai advocacy atau testimony.”
Sejak Maret 2021, LP berkolaborasi dengan Komnas Perempuan dan Hollaback! Jakarta mengadakan kampanye Stand Up Against Street Harassment. Mereka mengkampanyekan, lima langkah cepat mengatasi tindak kekerasan yang terjadi di ruang publik.
Ini adalah kampanye anti kekerasan pertama yang dilakukan LP Indonesia dan sejalan dengan program yang dilakukan LP global. “It’s not CSR but brand purpose,” kata Adina sembari menjelaskan, LP selalu bertujuan untuk, “empowering women”.
Adina merasa masih ada orang yang belum memahami seluruh kategori tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, LP memutuskan membuat kampanye yang fokus mengedukasi publik terkait tindak kekerasan dan memberi pelatihan singkat untuk mengatasinya. Di samping itu LP juga memberi donasi bagi lembaga kolaborator agar aktivitas advokasi mereka tetap berjalan.
Lagi-lagi, apakah kampanye sosial anti kekerasan ini berdampak positif terhadap bisnis?
“Kampanye bertujuan establish brand equity. Gimana bisa diinget dan jadi top of mind konsumen. Dampaknya enggak langsung ke bisnis.”
Merangkul Aktivisme untuk Menangkal Resistensi?
Dalam kolomnya di The Conversation, Joshua T Beck, asistant professor of marketing di University of Oregon menulis, di Amerika Serikat (AS) tren perusahaan mendukung gerakan sosial mulai marak pada 1990-an. Ini terjadi saat para aktivis hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup, mendesak perusahaan-perusahaan besar untuk “bertanggung jawab” kepada publik.
Menurut analisis Beck, hal itu mengakibatkan mayoritas perusahaan besar di AS semisal Amazon dan Walmart, menyatakan dukungan terhadap gerakan sosial sampai saat ini misalnya Black Lives Matter.
“Dampak terhadap harga saham tergantung pada apakah para investor berpikir aktivisme akan menguatkan atau melemahkan relasi jangka panjang dengan konsumen, para pekerja, dan para pembuat kebijakan,” tulis Beck dalam The Conversation.
“Perusahaan bisa menghindari jatuhnya harga saham ketika mereka menjelaskan kepada investor bahwa aktivisme baik untuk bisnis,” lanjutnya.
Di lain sisi, terjadi pula perubahan gaya hidup masyarakat secara global pada pertengahan dekade 2000-an. Muncul pilihan seperti berhenti makan daging merah untuk mengurangi dampak pemanasan global, memutuskan menggunakan kendaraan umum guna mengurangi emisi karbon, berbelanja di toko yang tidak menjual barang dagangannya dalam kemasan plastik, tidak membeli busana dari perusahaan fast fashion yang kurang memperhatikan kondisi buruh, pengelolaan sampah rumah tangga, dan sebagainya.
Dalam papernya, Joost de Moor, akademisi dari Stockholm University, menyebut berbagai pilihan di atas dengan istilah lifestyle politics. Keputusan dari individu yang bisa berdampak pada kehidupan masyarakat dan memantik terjadinya perubahan sosial.
Menurut analisis Moor, lifestyle politics bisa digunakan untuk memobilisasi masyarakat melakukan perubahan gaya hidup. “Upaya mengubah gaya hidup diri sendiri maupun pihak lain ini, pada akhirnya juga ditujukan untuk mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam skala yang lebih besar yakni, dari perusahaan atau pemerintah.”
Dalam konteks perusahaan retail, dampak dari lifestyle politics ini adalah seruan boikot dari konsumen.
Intan Paramaditha, penulis dan dosen Kajian Media dan Film di Macquarie University, Sydney, berpendapat makin intimnya hubungan antara kapitalisme dan gerakan sosial progresif seperti feminisme, LGBTQ, dan anti rasisme adalah hal yang sulit dihindari.
Intan beranggapan, gerakan sosial juga membutuhkan dukungan finansial dan platform yang lebih luas. “Dan sebaliknya, isu-isu sosial memberikan semacam kharisma bagi korporat,” tulisnya via email kepada Tirto.
Perkembangan penggunaan platform media sosial, kata Intan, membuat isu keadilan sosial yang tadinya dianggap politik identitas sebagian kelompok saja—contoh: feminisme—menjadi terdengar luas dan membuat korporat semakin gencar menunjukkan dukungan pada isu-isu yang semakin populer.
L. Ayu Saraswati, associate professor for the Department of Women's Studies at University of Hawai’i, Manoa, dan penulis buku ‘Putih: warna kulit, ras, dan kecantikan di Indonesia’ menganggap, perkembangan teknologi membuat tanggung jawab sosial dari perusahaan berevolusi. Menurutnya, mereka akan terus melakukan berbagai penyesuaian agar citra jenama tetap bagus. Melibatkan diri ke dalam hal yang tengah populer adalah salah satunya.
“Praktik hegemoni begitu. ‘Merangkul’ resistance. Resistensi yang melemah ini kemudian yang bisa jadi masalah,” kata Ayu.
Ayu menaruh perhatian kepada keberlangsungan LSM yang berperan sebagai kolaborator perusahaan dalam berbagai kampanye sosial. Dia merasa yang perlu diperhatikan dan dipertanyakan lebih lanjut adalah sejauh mana sumber pendanaan menjadi tolok ukur kesuksesan gerakan sosial.
Merujuk kejadian di Indonesia, Ayu berkata, pertanyaan yang perlu direfleksikan kembali oleh LSM yaitu, “Bagaimana memposisikan diri ke sesuatu yang secara fundamental berbasis gender, berdasarkan diskriminasi gender? Apa ada jalan, ke depannya, untuk menantang standar kecantikan itu sendiri?”
Jangan Cuma Mendompleng & Jaga Daya Kritis
“Ya saya terima dulu karena idenya bagus dan brand memang punya platform yang jangkauannya luas,” kata Dhyta Caturani, aktivis dan penggagas Purple Code—kolektif yang berfokus isu gender, teknologi, dan hak asasi manusia.
Setelah mengakui kampanye sosial brand memang mampu menjangkau massa yang besar, Dhyta memikirkan hal-hal penting lain. Pertama, apakah korporasi memang konsisten mendukung isu sosial?
“Karena biasanya lebih banyak yang ‘dompleng’ isu yang lagi populer. Misal bikin aktivasi di International Womens Day, The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, atau pas Pride Month sumbang dana,” kata Dhyta.
Kedua, bagaimana sikap perusahaan terhadap isu sosial lain? “Misal pro RUU PKS tetapi enggak pro UU ART [UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga]. Atau enggak dukung aksi massa. Noise itu penting.”
Sebagai orang yang bergelut di ranah aktivisme sosial sejak 1998 dan mengorganisir sejumlah kegiatan sosial, salah satunya One Billion Rising, Dhyta menyadari di Indonesia, masih dibutuhkan peningkatan edukasi dan perubahan mindset dalam memahami isu sosial. “Ini butuh waktu yang sangat panjang,” lanjut Dhyta.
Alasan itu pula yang menyebabkan Dhyta memilih untuk terlebih dulu ‘menerima’ inisiatif-inisiatif untuk ambil bagian dalam advokasi gerakan sosial, semisal pencegahan kasus kekerasan seksual.
Namun bagi Dhyta, kolaborasi bukan kunci untuk bisa bergerak. “Kita menggunakan platform yang kita miliki untuk menyuarakan cause kita juga cukup.”
Di sisi lain, Intan Paramaditha menekankan, publik perlu memiliki kesadaran kritis. Salah satunya dengan mempelajari narasi-narasi yang tidak terlihat di media sosial atau media massa. Contoh kasus: Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras untuk merayakan eksistensi LGBTQ yang didukung sejumlah brand.
“Narasi yang dikedepankan di brand-brand ini adalah keberagaman, tetapi yang tersembunyi adalah bahwa di tahun 1970-an aktivis queer mengalami kekerasan—sebagian dilakukan oleh polisi. Ke mana korporat pada saat itu?”
Berikutnya, melihat isu secara kompleks bahwa aliansi strategis dibuat untuk kepentingan tertentu dan sering berlangsung temporer. Cara pandang yang kritis dan kompleks, kata Intan, akan membantu seseorang dalam melihat narasi yang benar-benar genting dan penting diketahui.
Intan berkata penting bagi publik untuk mengajukan pertanyaan dengan orientasi ke depan, “Ke arah mana advokasi bergerak selanjutnya, setelah aliansi selesai? Bagaimana memberi dukungan agar advokasi tetap berlangsung, meluas, dan independen?”
Penulis: Joan Aurelia
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id