tirto.id - Kalian tiba di Stasiun Jatibarang, Indramayu, menjelang pukul sepuluh pagi. Langit seperti kertas buram. Udara kering dan panas. Debu naik dan turun dan membungkus apa saja yang dapat dijangkaunya: barisan sepeda motor di lapangan parkir, mentimun yang menyembul dari karung-karung di pasar di seberang stasiun, manusia yang berlalu-lalang, daun-daun.
Dua pria dengan muka kepuh menghampiri kalian. Salah seorang dari mereka, yang berbadan kecil, gondrong, dan punya borok di kupingnya, sampai lebih dulu. Ia mengembuskan asap rokok lewat celah lebar di antara dua gigi taringnya. Seorang lagi, yang jangkung dan mengenakan jaket kulit, mendekati kalian sambil merogoh saku belakangnya. Kau melap keringat di kening, lalu menggeser kaki kananmu ke belakang.
“Kalau kemarin kau tidak menawarkan diri buat ikut,” katamu kepada Arlian, “aku mau membawa pisau sebesar lengan anak-anak.”
Pria berjaket kulit itu berhenti, menyisir rambutnya, lalu bertanya kepadamu dengan cara yang sama sekali tidak mengancam (“Ojek, Mas?”). Dan temannya, yang kelak akan diceritakan oleh Arlian, cuma prengas-prenges.
Sampai disadarkan oleh bau asin payau sekitar tiga puluh menit kemudian, rupa-rupa pemandangan berlintasan tetapi kau hanya bisa membayangkan apa-apa yang kau bisa tuliskan tentang Pulau Biawak, tempat tujuanmu.
Setelah makan siang, menumpuk bekal, dan membikin janji dengan dua tukang ojek yang mengantar kalian untuk menggunakan jasa mereka lagi sepulang dari pulau, kalian berangkat dari Pelabuhan Karangsong. Jam menunjukkan pukul dua. Nelayan yang perahunya kalian sewa mengatakan bahwa di depan ada jalan air sejauh 41 kilometer dan pelayaran akan makan waktu selama empat jam.
“Mantap,” kata Arlian sambil merentangkan tangan. Rambutnya berkibar seperti samanera. Kau melindungi matamu dari sinar perak yang dipantulkan ombak Laut Jawa.
Jalan Air
Empat jam di laut, tanpa sinyal ponsel dan ketenangan yang diperlukan buat mengobrol atau membaca buku, jelas tak menyediakan banyak pilihan. Arlian berbaring, terpejam, dan membiarkan kakinya yang melintang di atas dinding kanan perahu basah sebatas paha. Kau menggeser dudukmu ke tengah, berharap di tempat itu guncangan lebih jinak, dan mulai melamun.
Kau pernah membaca tentang seorang Kaisar Jepang yang disingkirkan ke sebuah pulau terpencil pada abad ke-13. Sepanjang pelayarannya, kau kira, ia tak mengenang perebutan kuasa yang menjadi sebab pengusiran itu, melainkan kilasan-kilasan menyenangkan dari seluruh hidupnya: bunga-bunga yang mekar di halaman istana, anak panah pertamanya yang mencapai sasaran, surai kuda kesayangannya yang dikibas angin. Semua ini melintas, saling susul, berjalinan.
Memori, pikirmu, benar-benar menakjubkan. Tanpanya hidup seseorang cuma “sekarang”, dan dengan memori, seseorang dapat memanggil kembali (atau dikunjungi oleh) saat-saat menenteramkan, abai pada pikiran buruk seperti perahu bakal dihantam ombak besar dan terbalik dan kau digerogoti ikan-ikan.
Dan ingatan membawamu ke sebuah ruang yang bersih, terang, penuh buku—jauh dari ombak yang membuat perahumu oleng ke sana-kemari. Kau mendengar dengung halus mesin pendingin udara, bisik-bisik dua perempuan di meja di belakangmu, bunyi kertas yang tergores pena. Kau mencium bau mirip es krim vanila. Kursimu keras, tetapi ia kering dan hangat.
Di antara kedua tanganmu ada buku terbuka, sebuah novel. Di dalamnya, peristiwa bergerak maju-mundur, dari momen ke momen, dan cerita bergerak dengan berayun pada sulur-sulur halus tema dan motif.
Waktu seakan tak berkesinambungan. Ingatan-ingatan penutur novel itu bermunculan secara acak, tiba-tiba, mengejutkan. Suatu kali, ia menguraikan bagaimana ingatannya tentang kampung halaman—bunga-bunga taman, lili air, gereja paroki, orang-orang dusun yang ramah, dan seterusnya—bermekaran dari secangkir teh, setelah ia mencelupkan sepotong kue kering ke dalamnya dan memakan kue itu.
Kau menjentikkan puntung rokokmu ke laut.
Dari jarak 100 meter, Pulau Biawak terlihat seperti hutan yang terapung. Mungkin karena itulah ia pernah dinamai Pulau Bompis (boompjes berarti pepohonan dalam bahasa Belanda). Di bagian mukanya ada sebuah dermaga beton yang dihinggapi puluhan camar putih. Dan agak ke belakang, sebuah mercusuar menjulang sendirian, jauh lebih tinggi ketimbang pohon-pohon, dan tampak menggentarkan dalam lindungan kerangka baja.
Laut dangkal dan jernih. Terumbu karang dan ikan-ikan dengan pelbagai motif dan warna tersebar rapi seakan-akan mengikuti desain tertentu.
Dua dari tiga mesin perahu dimatikan oleh Pak Nelayan. Bunyinya yang menggempur kupingmu selama berjam-jam—ton-ton-ton-ton—jadi lebih jarang, lemah, dan menimbulkan kesan yang menenangkan. Lambat laun ia terdengar olehmu seperti ketukan metronom. Lalu, sayup-sayup, kau mendengar Charles Trenet bernyanyi: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs.
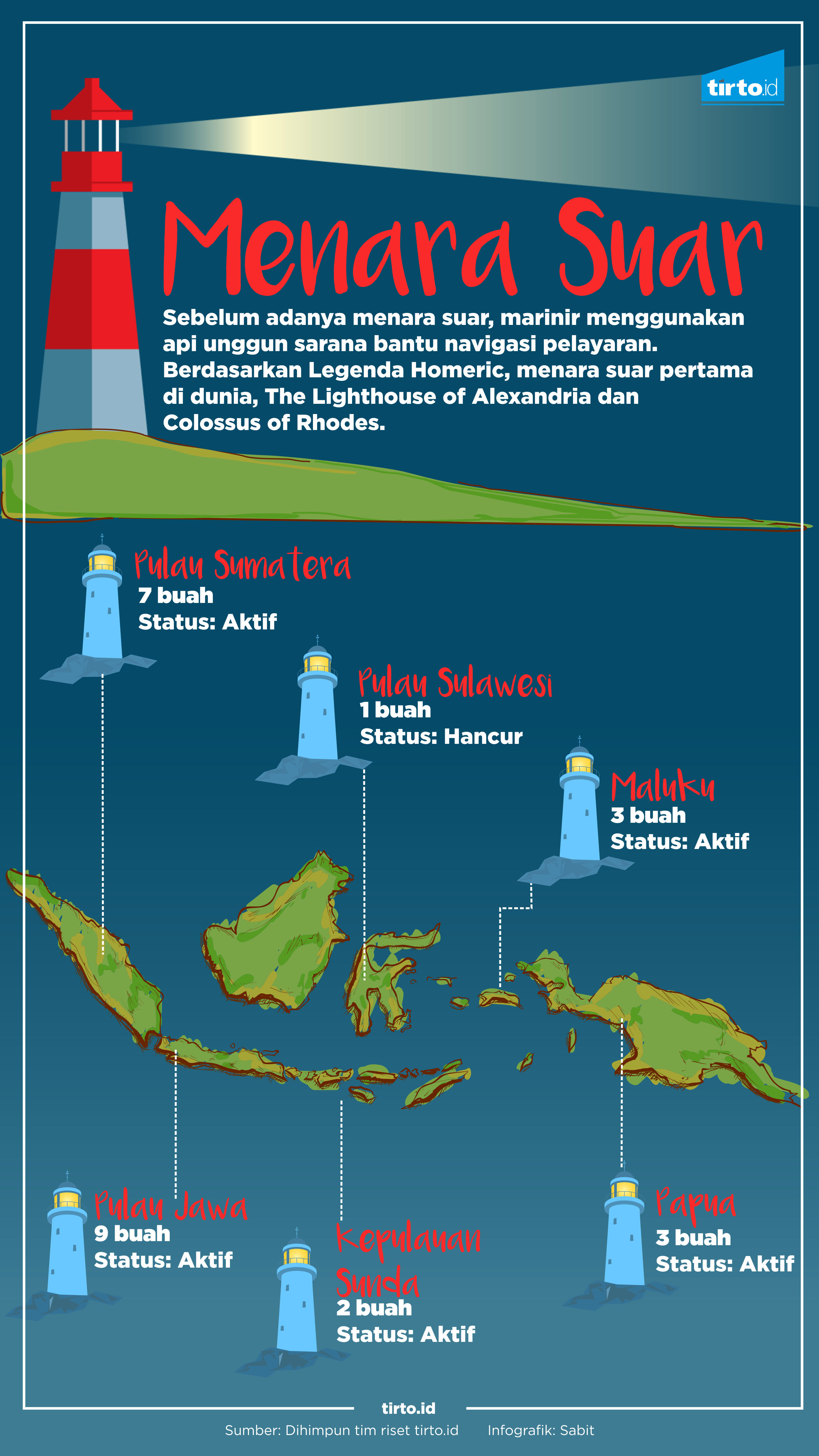
Di Pulau Biawak
Pagi di Pulau Biawak adalah pagi yang membuat Arlian sanggup berkata: “Misalkan Jawa meledak dan tenggelam, dan kita selamat, aku tidak keberatan tinggal di sini.”
“Aku keberatan,” katamu. “Di sini cuma ada laki-laki.”
“Nanti kita bisa menjemput gadis-gadis dari Madura atau Kalimantan atau Sulawesi.”
“Tetap keberatan, aku masih membawa uang kantor.”
Arlian tertawa, mungkin karena kasihan, tetapi kemudian ia bicara lagi: “Bisa, tidak, kau tak berpikir soal pekerjaan sampai jam dua siang saja?”
Dan kalian memutuskan untuk berenang. Di pantai-pantai di tempat asalmu, kau hanya perlu berjalan sepuluh meter dari garis ombak buat menemukan perairan yang cukup dalam buat berenang, sedangkan di Pulau Biawak cara itu berisiko merusak karang dan membuat telapak kakimu lecet-lecet. Namun, untuk berjalan terlalu jauh ke arah laut, kau tak berani. Jangan-jangan, pikirmu, begitu memasuki perairan yang agak dalam, kau bakal langsung tergulung arus bawah.
Pendeknya, pagi itu kalian cuma mengapung-apung sejengkal di atas karang, terpanggang matahari, ketawa (kalian mengira pemilik perahu yang kalian tumpangi sedang merancap di air dan ternyata ia cuma mencuci perahunya), dan kau tetap memikirkan pekerjaan.
Selang beberapa jam, adik sekaligus anak buah si pemilik perahu menjala ikan-ikan kecil dan menjadikan mereka umpan biawak. Tiga ekor biawak terpancing. Arlian, yang baru belajar menggunakan kamera pagi itu, memotret dan merekam footage dari pelbagai sudut, termasuk sudut yang memaksanya merangkak-rangkak, sampai daya baterai kamera itu kering.
Setelah umpan habis dan pengambilan gambar selesai, kadal-kadal bengak itu masih menguntit kalian. Barangkali, bagi mereka, kalian adalah dua ikan asin raksasa.
Itu hari yang menyenangkan. Tetapi bagian terbaiknya, menurutmu, bukan saat kalian berenang atau mengusik biawak, melainkan di puncak mercusuar; 65 meter dari permukaan tanah dan kau memandangi rumpun bakau, sungai yang membelah pulau dari utara ke selatan, rumpun cemara, rumpun pohon bersulur yang ditinggali bangau-bangau, rumpun pohon-pohon mati, pantai, pantai, pantai.
120 hektare pulau itu dan laut yang mengelilinginya terlihat seperti kanvas agung yang disapu dengan satu sekaligus banyak warna: hijau.
Kau tak menyukai ketinggian, sebenarnya. Namun, jarak pandang yang amat luas serta pilihan ekstrem buat tinggal atau melompat, membuatmu merasa sedikit lebih besar ketimbang hidup. Kau bilang kepada Arlian dan Taryono, petugas yang mengantar kalian, bahwa kau kepingin “mengencingi pulau dari atas sini.”
Dua puluh tahun lalu, di balkon sebuah mercusuar lain, kau pernah punya pikiran serupa tetapi tak mengatakannya.
Penulis: Dea Anugrah
Editor: Fahri Salam













