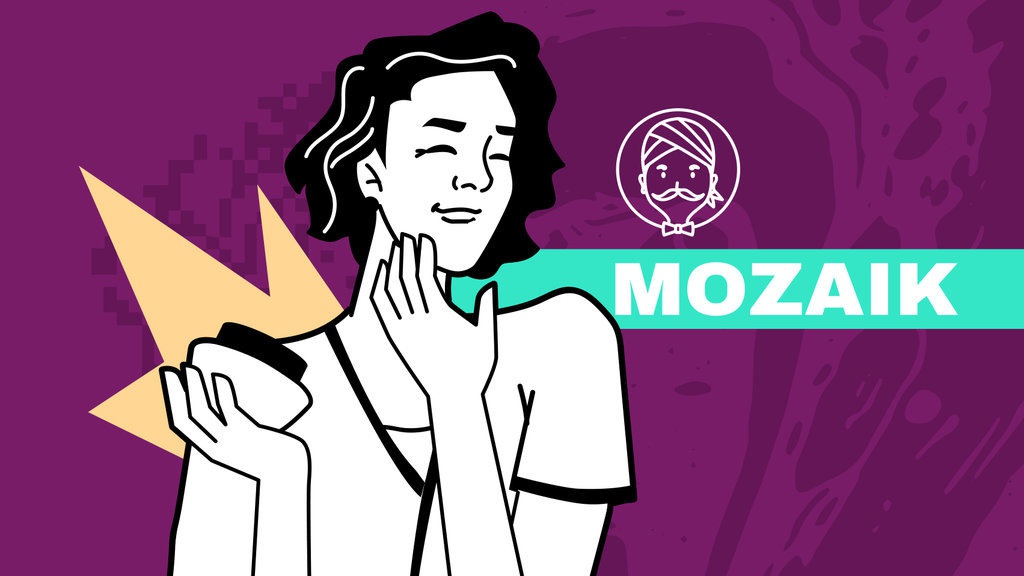tirto.id - Belakangan banyak pemberitaan mengenai produk kecantikan yang ternyata memiliki kandungan zat berbahaya. Dalam enam bulan terakhir, dua di antaranya datang dari pabrikan ternama, yakni Johnson & Johnson dan Unilever.
Pada Agustus 2022, Johnson & Johnson menarik produk bedaknya yang telah beredar selama puluhan tahun karena memiliki kandungan asbes. Ironisnya, keberadaan asbes telah diketahui lama dan disembunyikan selama 70 tahun.
Dua bulan berselang, tepatnya pada penghujung Oktober, Unilever menarik beberapa produknya karena memiliki kandungan benzena, mulai dari Dove sampai TRESemme. Menurut peneliti, kedua kandungan berbahaya itu jika terserap ke dalam tubuh dapat memicu munculnya sel-sel kanker.
Permasalahan ini selalu ada dan berlipat ganda sejak kosmetik pertama kali digunakan manusia.
Zaman Kekaisaran
Berasal dari bahasa Yunani Kosmetikos yang berarti “terampil dalam menyusun atau menata”, manusia sejak lama memang kerap merias diri. Mengacu pada arti tersebut, menelusuri asal-usul penggunaan kosmetik merupakan usaha yang menantang. Ada anggapan bahwa manusia memakai kosmetik sejak masa prasejarah.
Ini didasarkan pada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa masyarakat Neanderthal, hidup sekitar 40 ribu tahun lalu, kerap membuat gambar, baik permanen atau tidak, di tubuhnya. Namun, menurut Fenja Gunn dalam The Artificial Face: A History of Cosmetic (1973), penggunaan saat itu bukan untuk kecantikan, melainkan untuk keperluan sosial, kepercayaan, dan berburu.
Konsep kosmetik dan kecantikan baru terbentuk pada masa modern. Banyak masyarakat yang memanfaatkan bahan alami untuk merias diri dan memperbaiki penampilan, seperti menggunakan racikan bunga dan minyak untuk pewangi tubuh (kini disebut parfum). Terkait ini, kisah paling terkenal berasal dari Mesir Kuno.
Masyarakat Mesir Kuno, baik pria maupun perempuan, kerap merias diri untuk memperindah penampilan, mendapat kesucian dan menegaskan identitas. Mereka pun membubuhkan cairan di mata dan bibir (kini dikenal sebagai eyeliner, eyeshadow, dan lipstik) serta bedak di wajahnya.
Selain untuk norma, mereka juga memercayai nilai fungsional dan praktis dari riasan. Penggunaan bedak, misalnya, dipercaya dapat membuat kulit terlindungi dari paparan sinar matahari, sekaligus menangkal infeksi mata.
Di tingkat elite, Cleopatra, penguasa Mesir Kuno tahun 51-30 SM, menjadi ikon kecantikan yang paling mahsyur. Ciri mencolok dari dirinya adalah kebiasaan menggunakan riasan yang tebal nan indah, mulai dari bedak hingga eyeliner, lengkap dengan model rambutnya yang lurus.
Sementara dari peradaban lain, tata rias juga menjadi bagian melekat dari kehidupan. Di Yunani Kuno sekitar abad ke-8 sampai ke-9 SM, perempuan kerap memakai bedak untuk mendapatkan warna kulit yang lebih baik. Lalu, di Cina pada 3000 SM, masyarakatnya mulai mewarnai kuku masing-masing sebagai penanda kelas sosial.
Namun, akibat minimnya pengetahuan, masyarakat kala itu tidak mengetahui bahwa ada masalah kesehatan yang mengintai di balik hasil riasnya, yakni terserapnya bahan kimia berbahaya.
Para peneliti kotemporer mengungkap, manusia dari berbagai peradaban itu menjadikan timbal sebagai bahan utama kosmetik. Sebagai catatan, timbal adalah salah satu zat kimia yang kini lazim digunakan dalam pembuatan bahan elektronik atau perwarna.
Jika terserap dalam tubuh, baik dalam kadar rendah atau tinggi, timbal akan terurai menjadi senyawa beracun yang dapat memengaruhi sistem syaraf, kardiovaskular, dan ginjal, yang bisa menyebabkan kematian.
Paparan timbal tersebut, kata peneliti University College London Ann Liljas, diduga menjadi salah satu sebab masyarakat Mesir Kuno memiliki angka harapan hidup rendah yang tidak lebih dari 40 tahun.
Disamping timbal, ada pula penggunaan merkuri dan arsenik dengan kadar tinggi yang tanpa disadari masuk ke dalam pori-pori tubuh manusia. Tak heran jika Peter Elsner dan Howard I. Maibach dalam kumpulan tulisan Cosmeceuticals and Active Cosmetics (2005) menyebut, “manusia telah tercemar bahan kosmetik berbahaya lebih dari 10 ribu tahun lalu.”
Era Modern
Seiring meningkatnya kesadaran tentang perawatan tubuh, penggunaan kosmetik pun semakin masif dan menjadi kelaziman, khususnya bagi perempuan.
Sejak pertengahan abad ke-19 di Amerika dan Eropa, manusia mulai berinovasi menciptakan berbagai jenis kosmetik modern, seperti deodoran, sampo, dan krim muka, yang terkemas ke dalam beberapa merek. Temuan itu tentu hasil “racikan” zat kimia di laboratorium.
Sebagaimana dipaparkan Samuel S. Epstein dan Randall Fitzgerald dalam Toxic Beauty (2009), penggunaan riasan semakin besar ketika selebritas dan media mulai mengambil peran pada 1880-an. Lewat fotografi, selebritas berlomba-lomba menggunakan riasan di wajahnya sebelum dilakukan pemotretan untuk keperluan iklan yang disebarluaskan di majalah atau koran.
Layaknya endorsment selebgram pada masa kini, mereka berupaya membuat klaim dan reputasi bahwa hasil riasan itulah yang mempercantik dirinya. Lebih dari itu, perilaku selebritas ini berhasil membentuk persepsi publik tentang paradigma baru “cantik”, yang menjadikan kulit putih berseri sebagai standar.
Seperti yang dilakukan Lillie Langtry (1853-1923), misalnya. Aktris asal Inggris itu sukses menjadi figur pertama di dunia yang melakukan endorsment kosmetik dengan cara yang sudah disebutkan. Selain itu, Ia juga sering melakukan kebiasaan yang kala itu masih belum lazim, yakni menggunakan makeup dalam kegiatan sehari-hari.
Hasil dari tindakan Langtry dan selebritas lain tentu membuat kebutuhan terhadap kosmetik semakin besar. Masyarakat percaya dengan merombak penampilan, standar baru tersebut akan tercapai.
Padahal di balik itu semua ada bahaya yang mengintai. Meskipun pengetahuan tentang zat kimia terhadap kesehatan sudah semakin terang, masyarakat tetap saja tidak lebih mawas dalam memilih kosmetik. Alias setelahnya justru sering bermunculan kasus keracunan kosmetik.
Kasus ini terjadi akibat ketiadaan aturan jelas yang mengatur pembuatan dan penjualan produk rias. Kala itu, baik di AS ataupun negara-negara di Eropa, tidak ada regulasi khusus tentang hal ini. Alhasil, pabrikan pun asal-asalan dalam meracik kandungan kosmetik tanpa menghiraukan bahayanya.

Pada 1930-an, di AS kasus keracunan kosmetik semakin menjadi-jadi. Masih mengutip Samuel S. Epstein dan Randall Fitzgerald dalam Toxic Beauty (2009), rata-rata mereka terpapar penyakit setelah memakai kosmetik yang dilihatnya di media massa.
Ada yang memakai krim muka, dan keesokannya langsung dirujuk ke rumah sakit karena mengalami kerusakan kulit. Ada pula yang menggunakan eyeliner, tetapi 2-3 hari berselang mengalami kebutaan. Kasus-kasus seperti ini menjadi hal biasa kala itu. Tercatat ratusan pengguna terpaksa harus mendapat perawatan medis.
Seperti yang sudah diduga, ditemukan cemaran bahan kimia dalam kosmetik di luar batas normal, mulai dari timbal, arsenik, merkuri, sampai aniline (bahan dasar pewarna tekstil). Khusus timbal, penggunaannya memang tak lekang oleh waktu alias menjadi kegemaran sepanjang masa.
Alison M. David lewat Fashion Victim (2015) memaparkan bahwa timbal berhasil membuat warna kulit menjadi putih secara merata dan terlihat lebih natural.
Setelah kasus ini, pemerintah AS membuat evaluasi menyeluruh dengan lebih memerhatikan kadar zat kimia pada kosmetik. Hasilnya melahirkan aturan produksi kosmetik pertama di dunia, yakni Federal Food, Drug, and Cosmetic Act pada 1938.
Aturan tersebut menjadi inspirasi bagi negara lain untuk membuat regulasi serupa. Namun, bukan berarti zat kimia betul-betul dilarang. Semakin terbukanya pemahaman tentang kimia, membuat manusia menyadari bahwa menghilangkan zat kimia pada kosmetik adalah kemustahilan.
Jadi, penggunaan zat kimia diperbolehkan asalkan masih dalam batas wajar atau tidak lebih dari ketentuan. Misalkan, Food and Drugs Administration (FDA) menyatakan batas jumlah timbal yang diperbolehkan dalam setiap kosmetik kurang dari 10 mg.
Meski demikian, bukan berarti bahaya menghilang begitu saja. Sepanjang zaman, meski aturan dan fungsi pengawasan berjalan baik, tetap ada produsen licik yang memasukkan zat kimia berbahaya secara berlebihan ke dalam kosmetik. Biasanya, langkah ini diambil produsen sebagai jalan pintas untuk mengeruk keuntungan semaksimal mungkin dengan modal minimum.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id