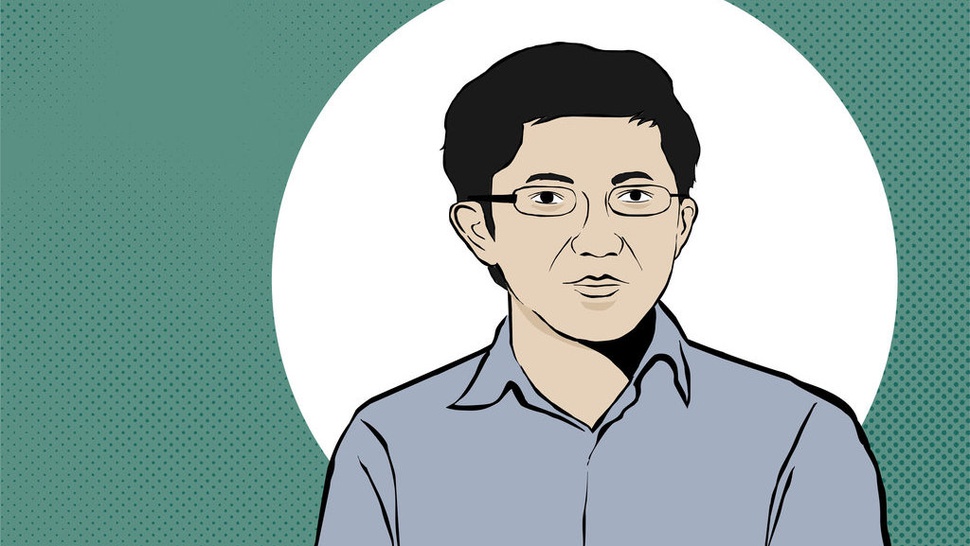tirto.id - Perubahan sosial besar-besaran tengah dihadapi Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, mal, hotel, dan apartemen terus tumbuh, di sebuah provinsi dengan upah minimum provinsi tak lebih antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Perubahan gentrifikasi ini sebagian besar untuk melayani para turis, serta para mahasiswa yang setiap tahun mengalir ke Kota Pelajar. Harga rumah-rumah sewa merentang dan bervariasi, dari termurah hingga termahal, begitupun biaya makan. Ada juga indekos yang menyandang predikat "eksklusif" dengan menawarkan kenyamanan ala hotel atau apartemen, dengan biaya sewa paling kecil Rp2 juta per bulan.
Survei Bank Indonesia wilayah Yogyakarta menunjukkan bahwa biaya hidup dan konsumsi mahasiswa setiap tahun terus meningkat. Ia ekuivalen dengan tingkat inflasi, yang menyebabkan kenaikan bahan makanan, makanan jadi, dan biaya sewa tempat tinggal. Semakin lokasinya dekat kampus, semakin mahal biaya sewanya. Rumah kontrakan, bila terletak di dekat kampus atau perkotaan, bisa di atas Rp15 juta per tahun.
Ada sisi kelam dari perubahan ini. Ketika hotel-hotel baru menjamur, setinggi enam hingga 18 lantai, seketika permukiman warga setempat mengalami penyusutan air tanah di musim kemarau, sesuatu yang baru kali pertama terjadi di Yogyakarta dan jadi keprihatinan meluas, sampai-sampai ada kampanye "Jogja Ora Didol" (Yogya Tidak untuk Dijual). Aksi kekerasan pelajar bergaya preman marak. Rasisme terhadap mahasiswa dari Indonesia wilayah timur menguat. Aksi bergaya eksekusi pernah terjadi di sebuah lembaga pemasyarakatan sipil. Di perdesaan seperti di Kulon Progo maupun Gunungkidul, para petani dan warga tengah menghadapi konflik agraria.
Akhmad Muawal Hasan dari Tirto mewawancarai Ardito Bhinadi dari pusat studi ekonomi, keuangan, dan industri UPN Veteran Yogyakarta, yang melakukan survei bersama Bank Indonesia mengenai biaya hidup mahasiswa di Yogyakarta. Pembahasan utama seputar pola perubahan sosial dan ruang hidup provinsi Yogyakarta.
Apa faktor yang menyebabkan pengeluaran mahasiswa di Yogyakarta naik dari 2008-2012?
Pengeluaran yang terbesar itu tetap makanan dan minuman, lalu kedua untuk pondokan. Yang lainnya relatif terdistribusi.
Faktornya, yang jelas, setiap tahun terjadi inflasi sehingga menyebabkan kenaikan bahan makanan, makanan jadi, pondokan. Tiap tahun, lebih banyak mahasiswa yang masuk ke Yogya daripada yang keluar. Sehingga permintaan naik. Biaya-biaya juga naik setiap tahun.
Gaya hidup juga mempengaruhi terutama yang dibawa dari mahasiswa pendatang. Makin banyak resto, kafe, yang harganya bisa tiga, empat, bahkan lima kali lipat harga makanan di warung makan biasa. Itu juga yang membuat rata-rata biaya pengeluaran makan mahasiswa naik.
Akibatnya, ketimpangan antara mahasiswa dengan pengeluaran tinggi dan rendah semakin lebar.
Kalau melihat angka rata-rata (pengeluaran) mungkin Yogya terlihat makin menakutkan bagi calon mahasiswa dari kalangan bawah. Rata-rata itu, kan, mencakup semuanya, dan terdongkrak dari yang pengeluarannya tinggi. Menakutkan karena sekarang sudah di atas satu juta rupiah per bulan. Padahal mahasiswa itu masih ada yang pengeluarannya 500 ribu rupiah per bulan.
Tapi Yogya memang unik. Pangsa pasar dari kalangan atas sampai bawah. Itu yang membuat Yogya masih bisa disebut kota pendidikan. Beda dari kota lain. Di sini masih bisa kita temukan makanan dengan harga lima ribu rupiah.
Bagaimana dengan nasib warung makan murah?
Ini tugas pemerintah daerah sebenarnya. Beberapa tempat makan murah sudah tergusur. Misalnya, dulu di Jalan Gejayan (dekat Selokan Mataram UGM), banyak warung makan murah. Lalu dipindah di taman kuliner Condongcatur (Concat) sebagai pusat kuliner, dekat terminal, tapi, kan, lama-lama mati.
Sekarang, yang masih terlihat, contohnya di daerah Babarsari. Tapi warung-warung tenda itu kalau tidak dilindungi oleh pemda bisa tergusur oleh keberadaan kafe-kafe dan restoran yang makin menjamur. Dan itu tentu akan merugikan mahasiswa kelas menengah ke bawah.
Cara melindunginya?
Pemerintah bisa menyediakan kawasan seperti pujasera. Ambil contoh di lembah UGM yang cukup berhasil. Dulu banyak warung gerobak dan kaki lima di sepanjang jalan dan bunderan UGM. Lalu disediakan pusatnya di lembah, jadi cukup berhasil. Sayangnya, yang di Concat tak berhasil.
Tren penggusuran warung kaki lima kira-kira sejak kapan?
Sudah lama. Saya lihat dalam kurun waktu 2012 mulai sepi. Dalam sepuluh tahun terakhir, keberadaan mereka makin berkurang sebab “dibersihkan”. Dulu di sekitar stasiun kereta api itu banyak dan sering dipakai mahasiswa untuk jajan. Tanpa perlindungan, mahasiswa kelas bawah akan makin kesusahan cari makan.
Bagaimana sikap pemerintah Yogya?
Saya belum melihat usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Jika tak disediakan lahan, sementara lahan di Yogya semakin sempit, baik untuk perumahan, hotel, maupun mal. Saya pikir pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan kampus untuk hal ini.
Kalo masalah ini tak disikapi serius, lama-kelamaan Yogya tak akan ramah lagi bagi mahasiswa kelas bawah.
Kok biaya hidup tetap naik walaupun Yogya dinamis soal inflasi maupun deflasi?
Itu, kan, data bulan per bulan. Coba tahun per tahun. Bandingkan April 2016 ke April 2017. Naik atau turun, dan cenderung naik.
Kontribusi mahasiswa di Yogya itu cukup besar karena menggerakkan ekonomi mikro dan kecil. Sayangnya juga, di dekat kampus, sekarang banyak mal. Saya terus terang tak setuju di dekat kampus ada banyak mal. Perlu ada pengaturan. Ada Hartono, J-Walk, ada Transmart.
Sekarang Yogya bukan Kota Pelajar, tapi Kota mal dan Hotel. Dulu ke mana-mana di Yogya ketemu kampus. Sekarang sudah dikepung oleh hotel.
Tapi, kan, untuk mendukung visi jadi kota wisata?
Kota wisata apa kota belanja? Harus ada bedanya. Tingkat okupasi hotel enggak sampai dua hari. Kenapa? Karena orang hanya melihat objek wisata satu dua jam, dan pulang. Berbeda dengan di Bali. Kenapa? Sebab akomodasi dibangun di sekitar objek wisata. Yogya malah di tengah kota. Sehingga orang tak ingin berlama-lama di pantai.
Proyeksi ke depan soal kenaikan biaya hidup mahasiswa bagaimana?
Ke depan, biaya hidup naik itu jelas. Saya sudah pernah berbicara soal ketimpangan tertinggi di Yogya. Ketimpangannya itu tak akan mudah selesai di Yogya karena Yogya itu kota pendatang dengan membawa gaya hidup dari kota-kota besar lain.
Ketimpangan itu, kan, diukur dari pengeluaran. Ketimpangan di DIY ini cermin dari ketimpangan mahasiswanya. Karena dengan adanya mahasiswa kaya itulah orangtuanya beli apartemen, beli properti, datang ke Yogya dengan uangnya, harga di Yogya pakai standar Jakarta, biaya hidup di Yogya pakai standar Kalimantan Timur. Ini yang ditangkap oleh industri kuliner sampai hiburan di Yogya.
Jika Yogya tak memberikan perlindungan yang jelas pada industri kecil, lama-kelamaan mereka habis. Yogya tak lagi ramah bagi mahasiswa kelas menengah ke bawah.
Termasuk indekos. Orang, kan, sekarang cenderung membangun indekos yang eksklusif. Ini kan tempat tinggal yang tak ramah bagi mahasiswa yang uang sakunya sedikit. Maka, saya pernah bilang bahwa indekos eksklusif itu perlu diterapkan pajak juga. Mereka sengaja membangun indekos eksklusif di bawah 10 kamar soalnya, menurut peraturan, jika di atas itu akan kena pajak seperti hotel.
Solusinya dua: bikin perda terkait pondokan dan perda untuk perlindungan usaha kecil.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Fahri Salam