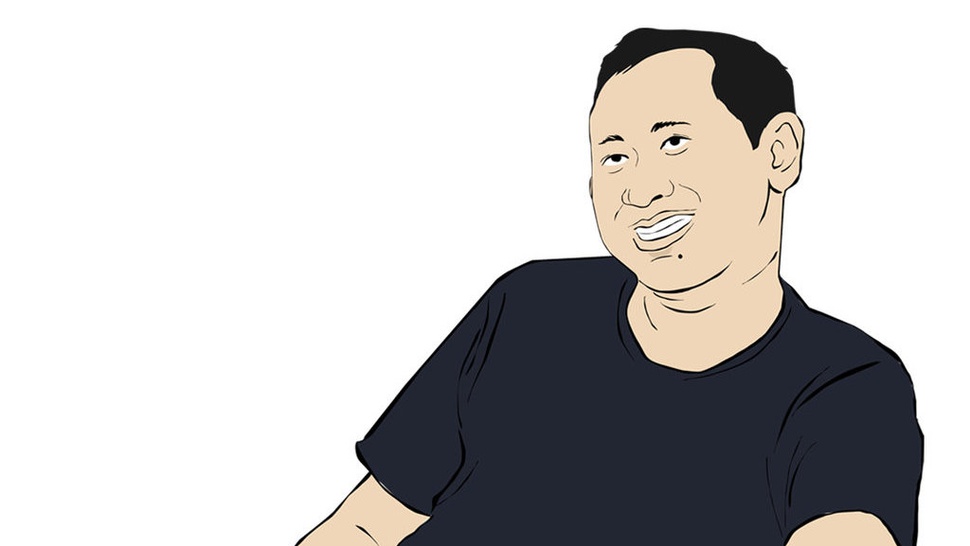tirto.id - Seperti Prince, Madonna, Bono, Adele, atau Santana, sutradara ini juga dikenal hanya dengan satu nama: Edwin. Bila sebagian dari mereka sengaja memakai nama pertamanya, atau menanggalkan nama lahirnya demi nama panggung, beda cerita dengan Edwin. Sejak lahir, namanya memang cuma satu kata.
Bagi sebagian penonton Indonesia, nama itu mungkin asing. Film-film Edwin tak pernah muncul di bioskop arus utama. Namun, buat penikmat film lain, Edwin bukan sembarang sutradara.
Rabu pagi, 1 November 2017. Lima menit sebelum jam 10 pagi, pesan dari Edwin masuk ke gawai. "Saya sudah di Kinosaurus ya, belakangnya Aksara.” Tempat yang ia maksud adalah bioskop alternatif di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Persisnya di belakang toko buku Aksara.
Dalam buku Take 100–The Future of Film: 100 New Directors (Phaidon, 2010), nama Edwin disandingkan dengan Frederich Meire dari Swiss, Sergio Wolf dari Argentina, bahkan Bong Jun-Ho (Okja, 2017) dari Korea Selatan, dan Zach Snyder (Batman Vs Superman, 2016) dari Amerika Serikat. Mereka diusung sebagai 100 sutradara paling menjanjikan saat ini. Menengok riwayat kreatif Edwin, hal itu terasa wajar.
Lewat film pendek ketiganya, Kara, Anak Sebatang Pohon, Edwin adalah sutradara Indonesia pertama yang masuk program Director’s Fornight di Festival Film Cannes pada 2005 silam. Film berdurasi 7 menit ini juga tayang di Festival Film Rotterdam. Di Indonesia sendiri ia menyabet penghargaan Film Pendek Terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2004.
Film pendek kedua Edwin Dajang Soembi, Perempoean jang Dikawini Andjing (2004) juga berjaya di Jiffest Short Film Competition 2005 dan lagi-lagi terbang ke Rotterdam. Sebagai langganan Festival Film Rotternam, Edwin pun diminta panitia festival menggarap film pendek tribute untuk Joel dan Ethan Coen. Ia lantas melahirkan Hullahoops Sounding (2008), film pendek kelimanya yang punya tema erotisme, serupa film pendek pertamanya A Very Slow Breakfast (2002).
Tak cuma piawai meracik film pendek, dua film panjang Edwin pun dirayakan. Babi Buta yang Ingin Terbang(2008) adalah penerima penghargaan FIPRESCI International Critics’ Prize 2009, memenangkan NETPAC Award pada Golden Horse Film Festival, dan tayang di Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente serta Busan International Film Festival. Sedangkan film panjang keduanyaPostcard from the Zoo (2012), berhasil masuk kompetisi utama Berlin International Film Festival (Berlinale)—satu dari tiga festival film terbesar dan tertua di dunia.
The New York Times memuji narasi koheren Edwin dalam Babi Buta. Diskriminasi etnis Tionghoa, represi seksual oleh militer, dan sekelumit tentang gay di Indonesia—yang ditampilkan dalam film ini—diracik Edwin dengan dingin dan berjarak. Ia sutradara yang terkenal dengan film-film penuh bahasa simbolik. Misalnya, petasan di mulut gadis Tionghoa yang diperankan Ladya Cheryl di film Babi Buta, atau ketombe dalam kopi dalam A Very Slow Breakfast, atau patung Ronald McDonald yang tiba-tiba jatuh dari langit menimpa sebuah gubuk di kaki gunung di film Kara, Anak Sebatang Pohon.
Ketika kabar tentang Posesif sampai ke media, tak sedikit yang tertarik melihat ke mana arah Edwin membawa film pertamanya yang menyasar pasar komersial film Indonesia ini.
Edwin menyambut Aulia Adam dari Tirto dengan secangkir espresso. Suasana kedai kopi itu agak riuh. Sambil mendekatkan ponsel ke arahnya, Edwin sedikit membungkukkan badan ke depan, siap menjawab pertanyaan.
Bisa ceritakan tentang apa film Posesif ini?
Karakter utamanya Lala dan Yudhis. Mereka kelas tiga SMA. Yudhis anak baru, pindahan dari sekolah lain. Lala, atlet loncat indah DKI. Lala ini belum pernah pacaran. Yudhis juga belum. Terus mereka ketemu untuk pertama kalinya, enggak sengaja, di sekolah. Ada satu pertemuan lucu yang membuat mereka jadi dekat. Terus, enggak lama kemudian mereka ingin merasa saling memiliki, pacaran. Pertama kalinya merasa jatuh cinta.
Cinta pertama mereka ini, seperti pada umumnya, dibumbui cerita-cerita lucu di awalnya. Tapi, lama-kelamaan kita lihat salah satu dari mereka, si Yudhis, mulai posesif. Rasa takutnya kehilangan Lala juga mulai berlebihan. Wajar orang pacaran takut kehilangan atau cemburu, tapi ini kadarnya berlebihan. Dan mereka kemudian harus berurusan dengan karakter yang posesif ini. Itu premis pendeknya.
Ide karakter Yudhis dan Lala ini muncul dari Anda?
Dari semua yang ada di tim ini. Produser Muhammad Zaidy, Meiske (Taurisia), Gina S. Noer, dan saya duduk intens untuk ngomongin karakter Lala sama Yudhis. Kami ingin punya film yang karakternya itu bisa diingat, yang kuat gitu, yang kalau penonton ngomongin toxic relationship, mereka bakallangsung ingat Yudhis dan Lala. Kami ingin buat film remaja, cinta-cintaan, cinta pertama, terus kami bikin riset: problematika percintaan mereka gimana, itu yang kami eksplorasi.
Kami menemukan banyak cerita di sekeliling kami yang dialami anak-anak SMA, anak SMP bahkan, yang terlibat hubungan yang beracun ini. Bahkan sampai tingkat abusive. Ya kami ingin bikin film yang dekat dengan kami dan memotret apa yang terjadi sekarang. Sebenarnya ini juga terjadi di mana-mana, bukan cuma di kalangan remaja. Di rumah tangga terjadi dan itu dari dulu. Dibicarakan di mana-mana bahkan. Kami ingin fokus ke situ, membahas kalau ini terjadi di lingkungan sekitar kita.
Film diawali dan diakhiri dengan adegan yang sama. Apa tujuannya?
Itu pilihan artistik saja. Kami ingin bikin film yang dari awal ada sentuhan menegangkan. Cuma kemudian, ya namanya film bisa diinterpretasikan macam-macam. Kalau misalnya ada yang mau menginterpretasikan Yudhis memang ada dari awal—stalking misalnya, sebagai penanda bahwa film ini adalah tentang hubungan yang posesif. Kalau ending-nya, kami ingin lihat pilihan Lala dan pilihan ini harus ditempatkan di sebuah momen yang jelas. Dan yang paling jelas adalah, gimana [saat] Lala ketemu lagi sama Yudhis. Bagaimana korban yang akhirnya jadi posesif, kalau ketemu [pelaku]? Kasus-kasus abuse itu sebenarnya [terjadi] karena dimaklumi, sehingga terjadi berulang lagi, berulang lagi. Untuk kasus ini, sebenarnya memang enggak ada cara selain meninggalkannya lagi.
Sebenarnya, kan, Yudhis-nya yang muncul lagi. Dan pas mereka berjalan bersama terakhir kalinya, pilihan Lala apa? Ya, tinggalin aja Yudhis-nya. Tapi ya itu tadi, bentuk kekerasan itu selalu berulang, berulang, berulang.
Ada karakter Ibu yang diperankan Cut Mini. Porsi tampilnya enggak banyak, tapi punya peran penting. Sebagian orang merasa cerita Ibu harusnya lebih dieksplorasi lagi, meski sebagian lain merasa porsi itu sudah cukup. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya, tetap kami ingin punya karakter utama yang fokus di Lala sama Yudhis. Enggak abu-abu juga sebenarnya. Kami juga enggak mau mencari sebab kenapa Yudhis bisa begitu. Tetap apa yang dilakukan Yudhis itu enggak kita terima. Itu kekerasan, kita harus tegas menolaknya. Bukan karena ibunya melakukan itu, terus dia [Yudhis] boleh melakukan [kekerasan] itu.
Nah, kami sangat yakin dan enggak mau penonton kita terjebak ke sana, terus penonton memaklumi Yudhis karena punya ibu seperti itu. Kami juga enggak ingin menghakimi ibunya dan semua [karakter] di sini. Rantai kekerasan itu berputar-putar dan sudah jadi sistem, susah cari sebab-musababnya. Kenapa ibu jadi begitu sudah enggak penting lagi. Yang penting adalah kita melihat ini sebagai sistem, sistem yang menular.
Untuk sistem ini, semua orang bertanggung jawab. Artinya, semua orang bersalah sebenarnya di sini. Termasuk orang-orang yang enggak ngomong, dan [atau] mempermasalahkan masalah ini. Jadi dengan cara seperti saya berharap, orang-orang itu juga enggak gampang nyalahin—tetap sih kita enggak toleransi kekerasan.
Pengalaman saya, ketika ada yang salah, dalam sebuah sistem, kita selalu cari siapa yang salah. Sudah, selesai di situ. Padahal kalau ada sesuatu yang sampai salah, misalnya terjadi pencurian dalam sebuah sistem perusahaan. Pasti kita mencari siapa pencurinya dan setelah ketemu melimpahkan semua kesalahan ke dia. Tapi bisa jadi, kenapa sistem ini bisa kecolongan, mungkin itu kesalahan semua pihak sebenarnya. Dengan ini sebenarnya saya ingin ngomong: yuk sama-sama kita beresin, jangan sibuk cuma nyari siapa yang salah. Jangan selesai dengan menyalahkan orang tertentu aja. Semua orang bertanggung jawab.
Kenapa loncat indah yang dipilih?
Kami butuh sesuatu yang bisa bikin karakter Lala punya kegiatan rutin yang menyita waktunya, sampai dia enggak punya waktu untuk kegiatan lain. Yang gampang ya atlet. Atlet itu, kan, hampir kayak tentara juga, ya. Sangat disiplin, dan patriarkis juga sebenarnya. Tapi, atlet apa nih? Loncat indah diputuskan karena, pertama kami ingin jenis olahraga yang punya ketegangan yang sama dengan apa yang dialami Lala.
Naik tangganya aja perjuangan, ketinggian ketika dia di atas 10 meter, sendirian, mungkin banyak yang nonton, tapi dia sebenarnya sendirian, fokus ke hubungannya dengan air, dengan melawan gravitasi. Artinya urusan dia sebenarnya hidup dan mati juga. Tapi dia harus melakukan hal terindah yang bisa dia lakukan, dengan risiko mati sebenarnya. Kalau kami analogikan ya sama dengan hubungan mereka. Jatuh, dan yang paling penting bangunnya gimana lagi nih? Lala berhasil naik lagi setelah hubungan yang destruktif itu.
Kenapa yang posesif jatuh ke karakter cowok? Karena mau menegaskan bahaya patriarki?
Korbannya paling banyak memang perempuan, dan itu karena sistem patriarki. Dimulai dari situ. Sebenarnya bukan masalah laki-laki atau perempuan. Sebenarnya ada sisi feminin yang mau dihancurkan sistem patriarki ini. Kita semua punya sisi feminin, laki-laki juga punya sisi feminin. Padahal, sebenarnya enggak bisa kita menghancurkan itu, karena itu bagian dari manusia. Laki-laki boleh berpikir sensitif, tapi di sistem patriarki enggak punya ruang untuk itu.
Film-film Edwin sebelumnya hadir di luar sinema komersil, lebih sering tayang di festival-festival dengan tema-tema bukan arus utama. Kenapa sekarang beralih ke pasar?
Pasar 'kan banyak, ya. Kami ngomong pasar ya dalam konteks ini. Di festival, film-film saya sebelumnya juga mencari pasar. Jadi bukan cuma diputar aja. Biasanya 'kan orang memasukkan filmnya ke festival berharap bisa dijual. Jadi sebenarnya komersial juga, cuma internasional.
Memang ini film pertama saya yang menyasar audiens dalam negeri dulu. Sebelumnya, saya cuek saja. Bikin dulu saja, nanti lihat bisa dipasarkan di mana. Kebetulan yang sekarang ini—Posesif—fokusnya memang ke pasar Indonesia. Tapi sebenarnya akan dipasarkan juga di internasional, tinggal cari festival. Alasannya lebih ke pemasaran, ya. Karena saya yakin film itu universal dan pasar film itu luas banget. Film yang saya buat sebelumnya mungkin enggak laku di Indonesia, tapi ternyata di luar lain sambutannya. Ya itu artinya banyak pasarnya. Cuma kantong-kantong pasar lain juga perlu dieksplor, kan?
Adakah perbedaan dalam proses produksi? Secara teknis mungkin, atau proses kreatifnya?
Enggak ada sebenarnya. Teknis—cara bikinnya sama. Kompleksitasnya, intensitasnya juga sama. Waktunya juga sama. Artinya, bukan berarti karena yang sekarang untuk pasar Indonesia, terus dibikinnya asal-asalan, ya enggak juga.
Proses produksi keseluruhan berapa lama?
Satu setengah tahun? Dua tahun sampai sekarang. Syuting cuma tiga minggu. Tapi development-nya yang lama. Editing-nya itu lama, lima bulan. Ketemu Adipati (Dolken) dan Putri (Marino) juga lama, ada sekitar tiga bulan untuk pengembangan karakter. Harus ketemu terus, intens, tiap hari.
Tapi apa ada penyesuaian khusus karena perbedaan pasar tadi, mungkin dari pemilihan tema?
Tema? Enggak. Seperti biasa, dari awal diskusi dengan semua pihak, produsernya, penulisnya, bahwa kami saat ini mau bikin film remaja, dipasarkan di Indonesia dulu. Itu yang beda. Kalau dulu, pemasarannya dipikir belakangan, yang penting bikin dulu. Nah, kalau yang ini udah dari awal dipikirin. Termasuk cara promosinya, apalagi distribusi.
Secara teknis enggak ada yang beda. Bentuknya ya bisa dibilang beda. Karena itu yang dikehendaki filmnya. Misalnya di editing. Kalau (film-film) sebelumnya enggak terlalu cepat temponya. Kalau (Posesif) ini film drama tapi ada sentuhan thriller-nya juga, jadi arahan atau teknis editing-nya juga jadi harus punya tempo yang lebih diatur. Kadang lebih cepat pacing-nya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Cerita filmnya membutuhkan itu.
Pemilihan lagu juga kuat di sini. Kenapa Sheila On 7? Apa karena mereka punya pendengar yang luas?
Saya bekerja dengan Mar (Galo) dan Ken (Jenie). Mereka banyak sekali kasih input yang bagus-bagus tentang musik, dan musik dalam film remaja, kan, penting sekali ya. Film ini pun begitu, bahasa musiknya punya sumbangan luar biasa untuk bentuk utuhnya.
Lagu "Dan" (oleh Sheila On 7) itu satu-satunya lagu yang ada dari awal. Bayangkan lagu itu dinyanyikan mereka (Lala dan Yudhis) seperti dalam skenario. Saya ingin punya satu film yang punya lagu klasik. "Dan" ini masih enak didengar sekarang. Sejak dia muncul sampai sekarang, masih terasa kontemporer terus. Itu artinya cukup abadi.
Ini semacam perayaan terhadap cinta pertama, dan kekerasan yang juga ada di film ini, ketika ditumpuk kemudian bisa berdialog dengan lagu ini. Lirik "Dan" sebenarnya tentang cinta, cuma ketika digabung dengan hubungan yang toxic, eh ternyata pas juga. Itulah enaknya kita ngomongin narasi yang multi-interpretasi. Cinta gitu juga, kapan kita tahu batasannya saja sebenarnya: ini cinta atau bukan? Ini kekhawatiran yang berlebihan atau cinta? Fungsi musik begitu sebenarnya (multitafsir).
Musik yang dipilih adalah yang bisa dekat dengan segala kalangan, baik secara usia, background sosial, dekat dengan siapa saja. Banyak yang akhirnya bilang juga, kalau sudah mendengarkan Sheila, dari kalangan mana pun, pasti enggak ada yang protes.
Kenapa pilihan aktor jatuh ke Adipati dan Putri Marino? Apa karena ingin menarik pasar Adipati Dolken?
Kami cari yang paling bisa menghidupkan karakter. Pertama cari anak SMA. Enggak gampang cari anak SMA ternyata, yang umurnya masih belasan, tapi bisa diajak intens berproses dengan film ini. Karena waktu yang diperlukan untuk membangun karakter Yudhis-Lala ini cukup panjang. Kami pernah casting anak-anak SMA, tapi kendalanya di waktu. Mereka kan sekolah. Belum bisa kami ajak mereka intens dan profesional tanpa ninggalin sekolah. Kami enggak mau mereka jadi enggak sekolah. Jadi mau enggak mau, kami cari yang profesional.
Banyak pilihan aktor, tapi untuk aktor laki-laki, selesainya memang di Adipati. Untuk karakter perempuan, lagi-lagi karena tuntutan waktu dan enggak banyak juga ternyata pemain kami yang di umur segitu, jadi mau enggak mau juga saya cari orang baru. Sebenarnya laki-laki juga cari orang baru, cuma pilihan ke Adipati itu memang yang terbaik sih, di luar dia punya popularitas. Ya baguslah. Tapi popularitas itu enggak bukan hal pertama yang kami pikirkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya memang ingin punya film yang karakternya memang kuat, kalau ngomongin toxic relationship ya langsung kepikiran Yudhis dan Lala. Saya sih senang banget dengan komposisi ini.
Ini di luar film Posesif. Sejumlah sutradara dan penulis, bahkan beberapa studio film sekarang ini sibuk bikin film-film yang punya semestanya sendiri—mungkin untuk kepentingan marketing. Joko Anwar, misalnya, dalam beberapa wawancara bilang kalau film-filmnya memang punya semesta sendiri. Itu kenapa dalam Pengabdi Setan ada Fachri Albar, ada ibu-ibu yang hamil. Anda sendiri punyakah?
Kalau saya sih enggak percaya kita harus membangun semesta sendiri ya. Kalau film, bisa aja orang menghubung-hubungkan. Artinya penontonnya bisa relate dan menghubung-hubungkan saja itu sudah bisa jadi universe sebenarnya. Beda sama Marvel yang didesain dari awal punya universe sendiri, karena karakternya sebanyak itu.
Untuk film-film saya, saya enggak merancang. Ya enggak bisa saya merancang Lala dan Yudhis beberapa tahun lalu. Joko mungkin punya strateginya sendiri. Dalam membuat film, pasti ada sisi-sisi alam bawah sadar yang selalu kebawa di film, terutama penulis ya biasanya. Sentuhan-sentuhan enggak sadar ini yang bisa menghubungkan tiap karya-karyanya sendiri.
Saya dapatnya dari para penonton juga sih. Tadinya saya juga enggak melihat hubungan apa-apa di antara film-film saya. Yang paling saya ingat, film-film saya selalu punya kritik pada masalah-masalah sosial kita. Semua bisa kita kritik di level keluarga. Hubungan yang paling terkecil itu mewakili masyarakat kita secara luas. Apa yang terjadi di keluarga, itu yang terpotret dari lingkungan kita.
Sikap politis yang ingin ditunjukan dari film ini sebenarnya apa?
Kalau secara verbal, sebenarnya secara politis film saya mengkritik sistem patriarki, yang makin kental, dan makin bisa dimanipulasi oleh kekuasaan. Hubungan Yudhis-Lala kan juga tentang relasi kekuasaan. Dimunculkan oleh Yudhis untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini, cara dia menguasai Lala. Tiba-tiba manusia merasa bisa mengontrol manusia lain, itu kan sedang terjadi sekarang.
Sebenarnya sikap politik saya adalah menawarkan medium untuk didiskusikan. Sampai sekarang, menurut saya, film harus memotret manusia, manusia hari ini, manusia yang direkam film pada zamannya.
Proyek berikutnya?
Saya lagi nyiapin [naskah] dari bukunya Eka Kurniawan (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas). Masih nulis [skenario]. Nulisnya bareng Eka. Idealnya, syutingnya tahun depan.
Rilisnya juga tahun depan?
Enggak, enggak, kayaknya tahun depannya lagi.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Windu Jusuf