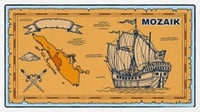tirto.id - Warsa 2011, Albert Rahman Putra, mahasiswa program studi Musik Tradisi di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, merasa berjarak dengan tanah kelahirannya sendiri, Solok. Albert tidak tahu banyak hal mengenai kampung halamannya itu, dan hal serupa ternyata dialami juga oleh sejumlah teman Albert.
Ketidaktahuan tersebut menggerakkan Albert dan teman-temannya untuk membuat kelompok belajar menulis blog. “Setelah 3 tahun kuliah, kami merasa ada kebutuhan untuk mendalami pengetahuan budaya di Solok,” ungkap Albert kepada Tirto.id, Senin (3/ 6/2024).
Dari kegiatan belajar menulis itu, Albert dan rekan-rekannya mulai mendokumentasikan banyak hal perihal Solok. Kerja-kerja pendokumentasian dan pengarsipan rutin digelar, sehingga Albert cs dapat memetakan sejumlah persoalan yang ada di wilayah Solok.
Lazimnya komunitas, yang keanggotaannya tidak mengikat, orang-orang datang dan pergi. Kegiatan jalan terus. Mereka yang bertahan kemudian sepakat mendirikan kolektif Gubuak Kopi Solok. Mula-mula, kolektif ini mengembangkan gagasan perihal literasi media.
“Kami melihat perlu ada yang mengambil peran mengkritisi kerja media dan mengembangkan kesadaran media dengan cara-cara yang bisa diakses warga,” ungkap Albert.
Kerja membangun kesadaran semacam itu ditempuh Gubuak Kopi Solok lewat berbagai cara, salah satunya dengan membuat workshop atau lokakarya literasi media. Seiring waktu, Gubuak Kopi Solok mulai mengembangkan jaringannya. Mereka belajar banyak dari kolektif lain yang lebih mapan, antara lain Jatiwangi Art Factory (Majalengka), Forum Lenteng, dan Ruangrupa (Jakarta).
Seiring waktu, anggota Gubuak Kopi Solok punya minat dan ketertarikan pada bidang yang lebih beragam. Ada yang menekuni musik, seni rupa, video, dan lainnya. Keragaman tersebut membuat Gubuak Kopi Solok mengembangkan praktik seni lintas disiplin dan lintas media.
“Gubuak Kopi Solok lebih banyak berkegiatan di bidang seni dan media. Sekarang, praktik seni dengan kesadaran media itu menjadi semacam tools bagi kami untuk merespon berbagai persoalan di Solok. Secara spesifik, kami berfokus pada studi mengenai kebudayaan yang berkembang di masyarakat pertanian Solok, yang kami sebut Daur Subur. Adapun workshop literasi media, penelitian tentang kebudayaan lokal dan pendokumentasian, masih berlanjut,’ terang Albert.
Disinggung soal ongkos operasional kolektifnya, Albert menyebut sumber pendanaannya beragam. Mulai dari penyewaan ruangan dan peralatan, membuat kedai kopi, hingga mengelola kebun bersama tetangga belakangan ini. “Secara ekonomi, hasil berkebun belum kelihatan, masih kami upayakan.”
Sejak 2017, sambung Albert, sebagian besar kegiatan Gubuak Kopi mendapat dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya lewat platform Dana Indonesiana dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Selain itu, Gubuak Kopi juga sempat mendapatkan dukungan dana hibah dari lembaga luar negeri, di samping sebagian anggotanya punya proyek seni atau usaha sendiri-sendiri.
Mengisi Kebutuhan akan Ruang
Di Palu, Sulawesi Tengah, kemunculan kolektif Forum Sudut Pandang circa 2016 juga bertolak dari hal yang sama. Sekelompok anak muda dengan berbagai minat dan profesi–perupa, pembuat film, musisi, dan jurnalis–tergerak membangun sebuah ruang untuk berbagi pengetahuan. Ruang yang sama, yang kelak menjelma menjadi Forum Sudut Pandang, diniatkan punya fungsi mendukung kebutuhan produksi dalam praktik-praktik seni yang digeluti masing-masing individu.
“Yang mengilhami kami membuat Forum Sudut Pandang adalah keinginan untuk berkumpul. Kami di Palu tidak punya institusi seni, dan generasi awal Forum Sudut Pandang bukanlah lulusan atau mahasiswa seni. Tapi, dari kecil kami punya hobi atau kegemaran pada seni, baik melukis maupun bermusik, sehingga kami merasa ada kebutuhan untuk belajar dan membuat sesuatu di Kota Palu,” ungkap Ama, sapaan akrab Rahmadiyah Tria Gayathri, salah seorang penggagas Forum Sudut Pandang, kepada Tirto.id, Senin (3/6./2024).
Saat tulisan ini dibuat, Forum Sudut Pandang baru selesai melangsungkan pameran bertajuk “Rasi Batu” di Aula Hotel Astoria, Palu. Pameran yang berlangsung sejak 15 Mei hingga 4 Juni 2024 itu menampilkan berbagai karya hasil seniman dari Palu dan wilayah lain di Indonesia. Sebelum berpameran, 16 seniman terpilih melakukan residensi. Mereka bermukim dan melakukan penelitian selama dua minggu di Lembah Pekurehua dan Besoa, Kabupaten Poso. Rangkaian kegiatan Rasi Batu mendapat dukungan Dana Indonesiana dari Kemendikbud Ristek.
Ama sendiri dikenal sebagai seniman lintas media, produser, aktivis, dan pegiat literasi kebencanaan. Karya-karya Ama kerap bertolak dari isu sosial dan lingkungan, yang berfokus pada pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pasca bencana. Pengalaman sebagai penyintas tsunami menumbuhkan komitmen dalam diri Ama untuk mengabdi dan menyuarakan isu-isu kemanusiaan dan pengetahuan baru pasca-rekonstruksi pasca-bencana melalui seni.
Kini, Ama didapuk sebagai salah seorang sarekat atau pengurus Lumbung Indonesia, sebuah wadah bersama bagi kolektif seni untuk saling berjejaring dan menguatkan anggota-anggotanya. Lumbung Indonesia diinisiasi oleh Ruangrupa. Sejauh ini, ada 12 kolektif–termasuk Forum Sudut Pandang dan Gubuak Kopi Solok–tergabung di dalamnya.
“Di Lumbung Indonesia, kami memetakan metode kerja bersama dan isu-isu krusial yang dihadapi kolektif-kolektif di setiap kota yang situasi politik dan medan seninya berbeda,” ungkap Ama.
Ama menambahkan, jejaring lumbung memudahkan kolektif anggotanya berinteraksi, bertukar sumber daya dan pengetahuan, sehingga saat sebuah kolektif membuat kegiatan mereka punya modal bersama yang lebih besar, yang sumbernya tidak hanya dari penyelenggara.
“Selain itu ada juga metode peningkatan kapasitas anggota setiap kolektif. Ketika dalam lumbung kami mengerjakan sebuah program, kami belajar mengadaptasi kerja-kerja di kolektif yang lain. Itu yang menurutku menarik, ada pertukaran pengetahuan seperti itu, yang berguna diterapkan di kolektif sendiri,” ungkap Ama.
Mengentaskan Ketimpangan
Ade Darmawan dari Ruangrupa menyebut kehadiran kolektif-kolektif seni di Indonesia, yang sebagian besar menerapkan konsep lumbung, pada dasarnya berperan mengisi kekosongan akan praktik edukasi, kreasi, dan apresiasi seni di banyak daerah.
Institusi pendidikan seni yang punya tugas memberikan edukasi jumlahnya masih sedikit, dan dari yang sedikit itu sebagian besar berada di Jawa. Perkara kreasi, yang lazimnya menjadi urusan seniman, boleh jadi melimpah. Seniman tidak selamanya perlu ruang edukasi untuk membuat karya, tapi dalam perkara apresiasi, seniman tentu butuh pihak lain juga. Setidaknya mereka butuh ruang untuk menunjukkan karyanya kepada publik.
“Kolektif itu tempat belajar,” ungkap Ade kepada Tirto.id, Senin (3/6/2024).
Ade menjelaskan, di daerah-daerah seperti Palu atau Majalengka, yang institusi seninya tidak ada, kebutuhan akan edukasi, kreasi, dan apresiasi seni bisa berlangsung berkat kolektif–dalam hal ini berkat Forum Sudut Pandang dan Jatiwangi Art Factory.
Sedangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung atau Yogyakarta yang institusi seninya terbilang mapan dan senimannya banyak, kolektif masih punya peran, paling tidak dalam hal apresiasi.
“Ketimpangan dalam praktik seni itu nyata. Di Yogya, kampus seninya ada, senimannya banyak dan hampir semuanya produktif bikin karya. Tapi, apakah ruang pamer atau gedung pertunjukan yang ada sanggup memfasilitasi semuanya? Kan nggak. Kalau bisa , dengan banyaknya seniman di Yogya mestinya setiap hari ada pameran,” beber Ade.
Terkait metode lumbung yang kini tengah ditawarkan oleh Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek untuk diterapkan khalayak, Ade Darmawan menyebut pendekatan tersebut dapat menggeser paradigma praktik seni yang biasanya kompetitif menjadi kolaboratif.
“Diakui atau tidak, kerja-kerja seni budaya selama ini sering kali membuat pelakunya bekerja sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain. Seni menjadi sangat kompetitif, sedangkan tolak ukurnya tidak jelas, berbeda dengan olahraga. Dengan metode lumbung, berbagai kompetisi yang selama ini berlangsung diarahkan untuk menjadi kolaborasi,” kata Ade.
Di level internasional, metode lumbung menjadi perbincangan, bahkan menuai kontroversi, kala diterapkan di ajang sekaliber Documenta Fifteen di Kassel, Jerman, tahun 2022 silam. Menurut Ade, dulu, seniman-seniman bersaing untuk bisa tampil di Documenta, dan mereka yang berhasil menembus event besar itu hanya berkomunikasi dengan kurator. Komunikasi antara seniman dan kurator pun lazimnya terbatas pada soal artistik.
Lewat metode lumbung, kolektif mencari sebanyak mungkin seniman untuk diajak berpartisipasi. Semua seniman yang tampil kemudian diminta berdiskusi satu sama lain, bukan hanya dengan kurator, untuk membicarakan karya dan hal-hal lain di luar karya, misalnya persoalan di negara asalnya.
Hasilnya mencengangkan. Karya-karya yang dipajang di Documenta Fifteen sebagian besar lahir dari proses diskusi, nongkrong, bukan keluar semata-mata dari ilham atau inspirasi senimannya seorang.
“Malah ada seniman yang memberikan materialnya buat seniman lain, sebab setelah diskusi dia pikir dia gak butuh material tersebut. Makanya diberikan kepada yang lain. Documenta Fifteen juga menerapkan prinsip Zero Waste. Sebelum membuat karya, para seniman sudah harus memikirkan akan disumbangkan ke mana atau akan jadi apa karya-karya mereka setelah pameran selesai. Tidak boleh berakhir sia-sia,” kata Ade.
Pendekatan semacam itu terbukti membuat produksi karya seni tidak lagi konvensional dan semata-mata berorientasi pada pasar. “Bahkan sekadar ngobrol, diskusi, bagi seniman-seniman Barat seolah merupakan hal yang canggih, aneh, baru. Padahal bagi bangsa kita, itu hal biasa,” kata Ade.
Lumbung sebagai sebuah metode memang menekankan aspek dialog dan berbagi sumberdaya, sebagaimana tampak pada keterangan Ama. Dari dialog dan berbagi itu, seni bisa relevan dan terhubung dengan persoalan sehari-hari, dan dengan cara itulah kerja-kerja kebudayaan bisa ditawarkan untuk menjadi haluan pembangunan.
“Di era sekarang, kolaborasi dan kekuatan komunitas itu dibutuhkan. Lumbung adalah kerja kolaborasi,” sambung Ade.
Ade menerangkan, dalam metode lumbung ada tiga tahapan kerja: rawat, panen, dan bagi. Rawat bisa diwujudkan dalam kerja-kerja seperti diskusi dan workshop, sedangkan panen adalah istilah untuk proses produksi.
“Terakhir, barulah seniman atau kolektif membagikan hasil panennya kepada publik. Perayaan besar seperti Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 masuk dalam kategori bagi.”
Ade bercerita, akhir-akhir ini ia dan sejumlah kurator lumbung giat menyambangi sejumlah pemerintah daerah dan komunitas-komunitas di banyak kota, mempresentasikan metode lumbung.
“Kami memfasilitasi pertemuan antara Pemda dan komunitas, kemudian bicara soal sumberdaya apa saja yang bisa dibagi. Jika sebuah Pemda tidak punya kemampuan membuat event, jangan bikin event. Serahkan saja pada komunitas yang kompeten. Bahwa Pemda cuma bisa memfasilitasi penyediaan ruangan, ya sudah, itu saja yang dibagikan,” papar Ade.
Ke depannya, Ade berharap gelaran sekelas PKN bisa disebar di banyak wilayah, tidak terpusat di Jakarta. Ia juga menginginkan hajat besar kebudayaan itu bisa dikelola oleh sebanyak-banyaknya orang, tidak lagi di-conduct oleh segelintir kepala.
Pertanyaannya, apakah praktik serupa itu memungkinkan?
“Di Documenta dan PKN, metode lumbung terbukti bisa dilaksanakan, dan berkelanjutan. Tantangannya ada pada rezim birokrasi. Birokrasi kita belum terbiasa dengan kerja-kerja gotong royong seperti ini, tapi sebetulnya bisa,” pungkas Ade. []
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis