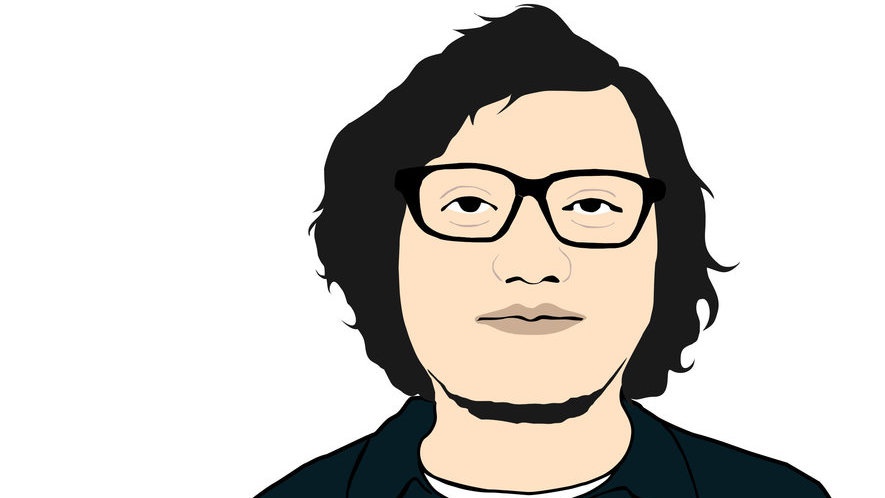tirto.id - Luna Maya dan Cut Tari tak seberuntung Rizieq Shihab.
Pada Juni lalu polisi mencabut status tersangka Rizieq dalam kasus dugaan chat mesum dan menghentikan penyidikan. Tapi, keputusan itu tak berlaku untuk Luna Maya dan Cut Tari. Padahal kasus yang menerpa dua artis ibukota dan satu aktivis ibukota itu sama belaka: dugaan pornografi.
Awal Agustus silam, proses hukum Luna Maya dan Cut Tari kembali ramai diberitakan. Sebuah LSM bernama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan praperadilan untuk kasus video asusila ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepolisian dituntut menghentikan penyidikan kasus video porno yang membelit Luna Maya dan Cut Tari.
PN Jaksel menolak praperadilan. Alasannya, kewenangan pengusutan kasus ada di tangan Bareskrim Polri. Pada saat bersamaan, Bareskrim menyatakan bakal melanjutkan proses hukum dan belum berniat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Kasus video asusila Luna Maya dan Cut Tari meledak pada 2010. Vokalis Peterpan, Nazriel Ilham alias Ariel, terseret dan didakwa tiga tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Tak hanya dibui, Ariel juga dikenai denda sebesar Rp250 juta. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Ariel dihukum 5 tahun penjara.
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso itu, Ariel dinyatakan melanggar Pasal 29 juncto Pasal 4 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ariel dinilai sengaja membuat atau menyediakan konten pornografi, serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyalin dan menyebarkan konten tersebut.
Upaya Ariel mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pun berakhir sia-sia. Ia mendekam di bui selama 3,5 tahun sebelum akhirnya bebas pada 2012.
Luna Maya dan Cut Tari sempat sedikit lebih mujur. Status mereka awalnya cuma saksi, tapi jadi tersangka tak lama usai Ariel diganjar status yang sama. Keduanya dijerat Pasal 282 ayat 1 KUHP.
Apabila status Ariel berakhir dengan keputusan tetap, tidak demikian dengan Luna Maya dan Cut Tari yang digantung tanpa kejelasan sejak 2010 hingga hari ini. Gilanya lagi, selama delapan tahun itu pula embel-embel tersangka dibiarkan terus melekat tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut.
Kepastian Hukum adalah Oksimoron
Hukum dibuat untuk memberi kepastian kepada warga negara. Tapi, hukum macam apa yang menjadikan subjeknya sendiri pesakitan tanpa kepastian?
Seorang tersangka bisa bebas dari tuntutan pidana jika tak ada bukti yang cukup kuat. Polisi semestinya paham itu—atau malah pura-pura tak tahu?
Masalahnya, memang tak ada undang-undang yang mengatur berapa lama seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Semua tergantung dari berapa lama proses penyidikan dilakukan. Selama proses penyidikan berlangsung, selama itu pula seseorang jadi tersangka—tak peduli jika proses penyidikan memakan waktu sampai bertahun-tahun seperti yang dialami Luna Maya dan Cut Tari.
Di sinilah SP3 punya peran penting untuk menghentikan segala ketidakpastian itu. Posisinya serupa pengingat sekaligus mantra sakti yang menentukan kelanjutan penyelidikan. Aturannya jelas: jika penyidik tak memperoleh bukti cukup untuk menuntut tersangka, kasus harus dihentikan, dengan SP3.
Namun, kita dibuat gagal paham dengan logika penegak hukum Indonesia. Bagaimana bisa polisi membiarkan kasus yang sudah diusut selama delapan tahun dan tidak memberikan hasil apa-apa kepada proses penyidikan?
Jika polisi saja bisa dengan cepat memutuskan kasus Rizieq dilanjutkan atau tidak, mengapa di kasus Cut Tari-Luna Maya mereka enggan melakukan langkah serupa? Sekompleks itukah kasus video syur Luna Maya dan Cut Tari sampai-sampai polisi butuh waktu delapan tahun untuk bekerja?
Pernyataan “Kami masih mencari bukti” oleh polisi adalah sinyal yang buruk: UU yang digunakan polisi memang sudah salah sehingga membuat mereka linglung dengan sendirinya.
Sudah Ringsek sejak dalam RUU
Luna Maya-Cut Tari adalah korban perdana UU Pornografi, undang-undang yang sejak penggodokannya sudah kacau.
UU ini semula diklaim mampu mengatasi dampak buruk dari maraknya pornografi dan industri yang menjual seks sebagai komoditas.
Pornografi, dalam bentuknya yang profesional maupun paling amatir, memang buruk, seksis, merugikan perempuan, dan membawa dampak buruk bagi anak-anak. Namun, alih-alih melindungi masyarakat dari segala pengaruh buruk, RUU Pornografi sekadar menciptakan ruang bagi konflik sektarian, konflik berdasarkan identitas primordial, konflik yang tak ada gunanya bagi kemajuan peradaban.
Gugatan terhadap pasal-pasal karet dalam UU Pornografi sebetulnya sudah pernah dilakukan pada 2010 oleh tiga pemohon: kelompok masyarakat Minahasa, Koalisi Bhinneka Tunggal Ika, serta Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan. Semuanya gagal.
Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin Mahfud MD, menilai bahwa pasal-pasal yang mereka ujikan, termasuk di dalamnya pasal mengenai definisi pornografi, masih tetap konstitusional—sekonstitusional UU Penodaan agama yang uji materinya ditolak MK di sebulan kemudian dan kini terbukti sebagai memporak-porandakan kebebasan beragama di Indonesia.
Sayangnya, UU Pornografi memang produk tribal ketimbang legal. Bagaimana tidak tribal jika sebelum disahkan namanya adalah RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi?
Silakan cari definisi “pornoaksi” dan Anda takkan menemukannya di kitab hukum belahan dunia mana pun kecuali di …. Draft RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi.
Menurut UU ini, pornografi ialah “... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
Penggalan “memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” jelas bermasalah karena bersifat relatif, lentur, dan multitafsir.
Lagi-lagi, definisi seperti ini bukan pernyataan hukum, tapi definisi tribal.
Tak heran jika salah satu prestasi penting UU Pornografi hari ini adalah normalisasi pemaksaan nilai yang diklaim agamis oleh satu kelompok terhadap golongan lain—sesuatu yang ditakutkan sepuluh tahun sebelumnya, ketika UU Pornografi disahkan dan disambut oleh para pendukungnya yang kerap mengatasnamakan kesucian “keluarga”, “moralitas”, dan “agama”.
Masalahnya bukan hanya definisi yang eksklusif, tapi juga privasi warga yang terganggu, terlihat dari pasal-pasal lainnya yang tak kalah ringsek. Pasal 5 dan 6, misalnya, menyebutkan setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, mengunduh atau menyimpan produk pornografi. Walhasil, jika seseorang mempermasalahkan video bokep yang Anda simpan di laptop atau ponsel, Anda bisa dipidanakan.
Pertanyaannya, sejauh mana negara berhak menjamah kehidupan privat, termasuk urusan seksual warganya? Tidakkah ini justru merepotkan bahkan buat kepolisian sendiri?
Tak usah heran jika kekacauan-kekacauan legal ini akhirnya bermuara pada cara aparat menangani apa yang kini enteng disebut “pornografi”. Segala hal yang dirasa memperlihatkan bentuk tubuh atau gerak-gerik yang dipandang sensual (lagi-lagi secara subjektif), bahkan di ruang-ruang yang jauh dari amatan publik, bisa langsung dicap pornografi.
Status tersangka Luna Maya dan Cut Tari selama delapan tahun tanpa pemeriksaan lebih lanjut dan cara polisi menangani kasus Rizieq dan Firza adalah dua bukti nyata dari linglungnya para penegak hukum akibat problem akut UU Pornografi.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.