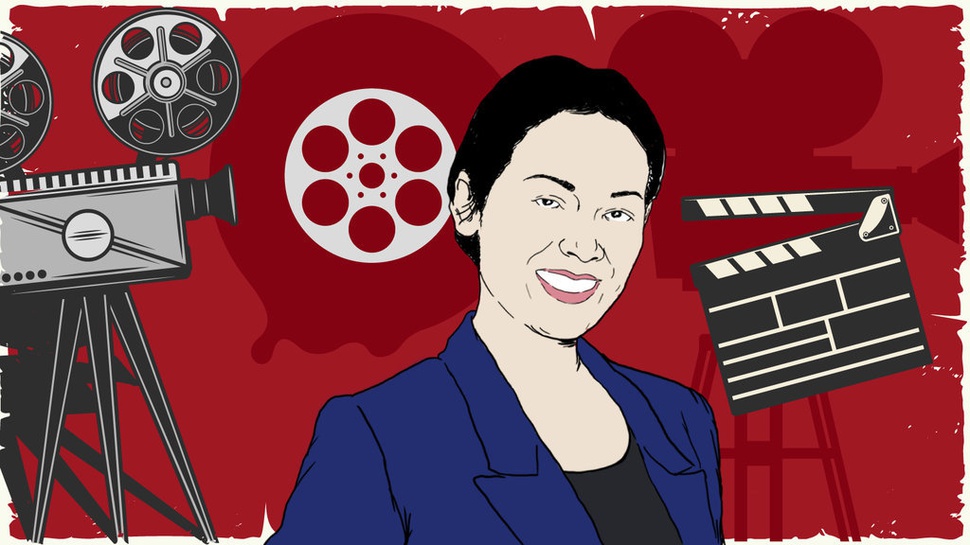tirto.id - “Kita sama-sama tahu, ya, suster di sekolah mendidik kita jadi perempuan seperti apa,” kata produser film Sheila Timothy kepada Tirto, ketika berbincang di ruang pertemuan rumah produksi Lifelike Pictures, Juni lalu.
Lala, panggilan akrab Sheila, sempat mengenyam pendidikan di salah satu sekolah katolik di Jakarta Selatan. Di sekolah itu, para guru dan pimpinan institusi terus mengingatkan setiap siswi agar mampu jadi pribadi independen, tangguh, dan tidak bergantung pada orang lain.
Wejangan itu masih diingatnya sampai hari ini dan mendorong Lala kembali berkarier setelah 10 tahun vakum bekerja karena mengurus anak dan rumah tangga.
“Situasi rumah sudah kondusif. Anak-anak sudah cukup besar, sudah bisa dilepas. Saya merasa itu waktu tepat untuk kembali bekerja karena saya selalu tahu kalau saya memang harus bekerja,” kata ibu empat anak ini.
Sebelum jadi ibu rumah tangga, Lala bekerja di salah satu biro periklanan internasional yang membuka cabang di Indonesia.
Proses pencarian karier dimulai dari hal sederhana dan dekat. Pada akhir 2000-an, adik Lala, selebritas Marsha Timothy, hendak membintangi film pertama, Ekspedisi Madewa. Marsha butuh manajer untuk membantu mengorganisir pekerjaan dan Lala bersedia menjalani pekerjaan tersebut. Dari sana terjadi perkenalan dengan insan-insan perfilman.
Sekitar 2007-2008, Marsha memperkenalkan salah satu kawannya, Joko Anwar, kepada Lala. Saat itu, Joko tengah mencari rumah produksi yang bersedia menggarap film Pintu Terlarang.
“Naskahnya breakthrough dan edgy. Saya belum pernah menemukan cerita serupa di film Indonesia,” katanya.
Lala berminat memproduseri film tersebut dan ingin terlibat dalam seluruh prosesnya. Ia mendiskusikan hal ini dengan sang suami, Luki Wanandi, yang kemudian sepakat membentuk rumah produksi film Lifelike Pictures dengan satu catatan: bila Pintu Terlarang gagal mendapat investasi, Lifelike tutup.
Pintu Terlarang dirilis pada 2009 dan tak laku di bioskop. Lala sangat kesulitan mencari investor. Publik tidak minat menonton film Pintu Terlarang yang terlihat membingungkan dan sadis. Film itu memang memuat adegan potong leher manusia dan mencelupkan kepala ke dalam wadah sup.
Maklum, 10 tahun silam, publik terlanjur akrab dengan film horor dan cinta-cintaan. Poster film dengan judul seperti Kuntilanak, Pocong, Rumah Pondok Indah, Hantu Tanah Kusir, hingga Setan Facebook, bergantian menghiasi dinding bioskop dalam negeri. Sementara kaum muda, disajikan dengan film seperti Mendadak Dangdut, Heart, Jomblo, dan I Love You, Om. Film-film ini menurut Lala bisa menarik 100 sampai 200 ribu penonton dan gampang balik modal.
“Saya pemain baru di industri film. Sebelumnya ibu rumah tangga pula. Jadi, sulit sekali meyakinkan orang kalau saya ini serius mau garap film. Apalagi filmnya kayak gitu. Tapi, saya persistent aja. Terus yakinkan mereka dan tetap berkomitmen bikin film dengan eksekusi yang mumpuni,” kata Lala, yang mendapatkan investor dari lingkar pertemanannya dan suami.
Meski tak laris, Pintu Terlarang mendapat respons positif dari sejumlah kritikus film dalam negeri, diputar di 20 film festival mancanegara, dan menang penghargaan sebagai film terbaik di sebuah festival film di Korea Selatan. Semua itu jadi bahan bakar Lala untuk tetap menghidupkan Lifelike Pictures dan mengeksplorasi berbagai jenis film di luar arus utama.
Dua tahun berselang, Lifelike memproduksi film kedua, Modus Anomali. Sejak awal Lala tahu film itu akan gagal di dalam negeri. Ia bersama tim sepakat memutar film di festival film South by South West, Texas, AS. Di sana film tersebut dilirik oleh perusahaan produksi film asal AS, XYZ. Kerjasama antara Lala dan XYZ membuat Modus Anomali bisa didistribusikan ke sejumlah negara. Film ini juga mendapatkan penghargaan di Bucheon International Fantastic Festival, Korea Selatan.
Jejaring dan penghargaan yang didapat di luar negeri membuat Lala terus berapi-api menjajakan filmnya di berbagai festival film di luar Indonesia.
Ia pun memutuskan untuk memperluas genre film-film yang diproduksi Lifelike. Setelah Modus Anomali, Lifelike memproduksi film kuliner Tabula Rasa yang berangkat dari keinginan Lala untuk menghibur ibunya setelah ditinggal wafat sang suami.
“Dia suka sekali memasak dan saya minta dia memasak untuk menghibur diri dan ternyata cara itu efektif,” katanya.
Lala, yang gemar menikmati masakan ibu dan juga penyuka film kuliner, lantas menghubungi penulis skenario Tumpal Tampubolon untuk menulis kisah tentang masakan. “Intinya makanan adalah pemersatu,” katanya.
Naskah dieksekusi Adriyanto Dewo, sutradara muda yang menarik perhatian Lala lewat film pendek Menunggu Warna, bagian dari omnibus Sanubari Jakarta.
“Saya tidak mengenal senior-junior dalam film. Saya pilih sutradara dan penulis naskah yang menurut saya cocok dengan cerita.”

Nasib Tabula Rasa serupa dengan 'saudara-saudaranya':berkelana ke festival film mancanegara. Di dalam negeri, film itu memenangkan empat Piala Citra untuk kategori Skenario Asli Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktris Utama Terbaik, dan Pemeran Pendukung Pria Terbaik.
Setelah Tabula Rasa, Lala mencoba hal baru dengan membuat film dokumenter Banda The Dark Forgotten Trail yang membahas komoditas pala di Pulau Banda.
Ia menghubungi Jay Subyakto—yang tidak pernah menyutradarai film—untuk menyutradari film tersebut. Hasilnya? Banda dipenuhi gambar-gambar memukau dan magis khas karya Jay.
Jay pernah menuturkan bahwa Banda ditujukan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak, bukan untuk kepentingan pasar semata. Ia pun sempat mengungkapkan harapan agar Banda bisa diputar di berbagai sekolah di Indonesia supaya siswa mengetahui kisah pulau tersebut.
Tahun lalu, Lala memproduseri Wiro Sableng yang cukup menghebohkan publik karena bekerjasama dengan Fox International Production, bagian dari perusahaan 20th Century Fox. Lala mengaku berkenalan dengan tim Fox saat ia berkunjung ke sebuah festival film di AS pada tahun-tahun awal berdirinya Lifelike.
Kerjasama antara Lifelike dan Fox terjalin dalam hal pembuatan efek Computer Graphic Image (CGI) di Wiro Sableng.
Bagi Lala, Wiro Sableng adalah salah satu karya fenomenal—buku cerita silat yang terdiri dari 185 judul dan terbit dalam kurun waktu 39 tahun. Ia juga melihat potensi pasar yang cukup besar dari film ini—tidak seperti empat film sebelumnya. Lala tak ingin mengecewakan investor yang cukup semangat mengucurkan dana untuk karya ikonik ini. Dari sanalah ide kerjasama dengan Fox muncul.
Perkiraan Lala tepat. Wiro Sableng meraih satu juta penonton dalam kurun waktu satu bulan dan masuk daftar film Indonesia terlaris.
“Wiro harus punya universe-nya sendiri layaknya film superhero lainnya,” kata Lala.
Wiro Sableng juga dikembangkan dalam produk video game, stiker pada aplikasi pengirim pesan Line, pameran di pusat perbelanjaan, mainan action figure, dan sekuel film.
Lala tak menceritakan seperti apa kira-kira Wiro Sableng dalam sebuah universe, sebuah proyek yang layak ditunggu kemunculannya.
Editor: Windu Jusuf