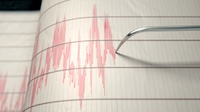tirto.id - Jumat menjelang magrib, 28 Oktober 2018, Palu diguncang gempa 7,4 SR. Saya yang saat itu sedang berada di kantor WALHI Sulteng, merasakan tanah bergetar mengayun dan kemudian naik-turun. Seluruh penghuni kantor langsung berusaha menyelamatkan diri. Namun, getaran kuat gempa membuat kami kesulitan berdiri. Kami keluar dengan susah payah, bahkan dengan merangkak.
Gempa adalah fenomena biasa bagi kami yang hidup di kota Palu. Tapi, gempa kali ini terlalu kencang dan berlangsung lama. Listrik mati dan sinyal ponsel hilang total. Saya mulai bertanya-tanya seberapa parah dampak gempa kali ini.
Pertanyaan saya terjawab kemudian. Gempa kali ini diikuti tsunami dan likuifaksi (pencairan tanah), istilah yang mendadak masuk dalam kosakata populer bagi orang Palu. Korbannya tidak sedikit.
Mayat bergelimpangan di sepanjang pantai dan tertimbun di lokasi-lokasi yang terkena likuifaksi. Tim penyelamat hanya mampu mengevakuasi 2.045 jenazah, padahal total korban tewas yang ditaksir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih dari 5.000 orang. Rumah-rumah ambruk, bahkan sebuah desa dan kelurahan menghilang dalam semalam.
Minggu pertama pasca-gempa adalah momen terkacau seumur hidup saya—terjebak di sebuah kota yang terisolir bersama penduduk yang gagap bencana. Listrik mati, sinyal ponsel menghilang, bahan bakar habis, bau busuk dari mayat yang terlambat dievakuasi dan persediaan makanan yang semakin menipis.
Bantuan yang tak kunjung datang membuat orang-orang terpaksa menjarah toko untuk mendapatkan air dan makanan. Penjarahan meningkat ke barang-barang berharga lain sehingga membuat aparat mengeluarkan perintah tembak di tempat para penjarah. Saya ingat saat membagikan bantuan empat hari setelah bencana, orang-orang berebut sambil membawa parang.
Bandara dipenuhi manusia yang berharap diangkut pesawat, sampai-sampai pesawat pengangkut tak jadi mendarat. Jumlah personel polisi dan tentara meningkat karena masyarakat sipil kalang kabut.
Setelah bantuan mulai banyak yang masuk, keadaan mulai normal. Orang mulai mencoba memahami apa yang terjadi. Gempa, tsunami dan likuifaksi dibicarakan di mana-mana. Ada anggapan bahwa perilaku syirik dan maksiat sebagai sumber bencana. Zikir dan doa digelar di pantai. Orang-orang mencari sandaran spiritual dalam iman dan taqwa seolah akan mati besok pagi. Bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah likuifaksi, gempa memang terasa seperti kiamat yang digambarkan dalam kitab suci.
Kabar baiknya, tak semua sekadar menyalahkan adzab. Belakangan kajian ilmiah kebencanaan juga menjadi populer. Semangat untuk memahaminya meningkat. Orang membahas masalah bencana dari mulai warkop-warkop, diskusi-diskusi ilmiah, radio hingga televisi. Informasi mengenai bencana juga beredar luas di media sosial, meski tak jarang masih bercampur hoaks.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang tergabung dalam Posko Sulteng Bergerak juga terlibat dalam edukasi kebencanaan. Pada 18 Oktober 2018, diskusi mengenai Sesar Palu-Koro digelar di posko yang menghadirkan Abdullah, peneliti yang telah lama berusaha mengingatkan bahaya sesar Palu-Koro.
Meskipun diskusi ini dibuat mendadak, tapi menarik minat lebih dari 50 orang. Warga yang kebetulan lewat juga mampir dan berdiri di depan gerbang posko. Pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah daerah mana saja yang aman dari gempa dan likuifaksi, ke mana warga harus menyelamatkan diri, dan lain sebagainya.
Sebulan kemudian, Posko Sulteng Bergerak mengundang Tim Ekspedisi Sesar Palu-Koro dalam diskusi bersama lebih dari 60 aktivis dan relawan. Pengetahuan mengenai karakteristik gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah menjadi semakin kaya. Di titik-titik pengungsian, para relawan membuka posko-posko yang tidak hanya membagikan logistik dan memberikan layanan trauma healing. Pengetahuan kebencanaan juga diserbaluaskan agar masyarakat tetap tenang dan tahu cara menghadapi bencana.
Gempa yang diikuti tsunami di Teluk Palu rata-rata berulang setiap 30 tahun sekali. Karena itu, tak ada jalan lain selain belajar agar siap menghadapinya.
Harus Masuk Kurikulum Pendidikan
Fenomena meningkatnya keingintahuan warga pasca gempa di Sulteng adalah potensi besar untuk melibatkan masyarakat dalam program pendidikan kebencanaan. Sudah sepantasnya pemerintah merespon dengan memasukkan pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan formal. Inisiatif-inisiatif masyarakat yang spontan, sporadis, dan terbatas tak lagi cukup.
Kesuksesan Chili dalam memberikan edukasi kebencanaan kepada warganya bisa menjadi contoh. Gempa 8,4 SR dan tsunami 4,5 meter yang terjadi pada 2015 menewaskan 13 orang. Jumlah korban ini sangat kecil dibandingkan dengan 500 korban tewas dalam gempa 8,8 SR lima tahun sebelumnya.
Kecilnya jumlah korban didukung oleh fakta bahwa masyarakat Chili sudah tahu cara menghadapi bencana berkat pengetahuan kebencanaan yang masuk dalam kurikulum pendidikan. Setiap tahun, Chili melaksanakan enam sampai tujuh kali simulasi menghadapi gempa dan tsunami dengan peserta kurang lebih satu juta orang. Standar bangunan tahan gempa yang ketat sudah diatur sejak 1972, ketika pemerintahan sosialis Salvador Allende berkuasa.
Jika Chili punya dokumen kebencanaan bernama Chile Prepares, Indonesia sebetulnya sudah memiliki Undang-Undang penanggulangan kebencanaan yang menekankan tahapan prabencana. Pasal 34 sampai Pasal 47 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur kegiatan pada tahap prabencana dan sudah memasukkan program pendidikan.
Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 setebal 131 halaman yang diterbitkan oleh BNPB juga sudah memasukkan pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana sebagai salah satu kegiatan prabencana.
Lagi-lagi, yang tak dilakukan adalah implementasi.
Sebenarnya Palu sudah pernah memulai pelaksanaan pendidikan simulasi tanggap bencana. Sebuah simulasi pernah dilakukan sekali di Pantai Talise pada 19 November 2012 sebagai rangkaian dari acara Gladi Nasional Penanggulangan Bencana yang dihelat oleh BNPB.
Kota ini juga sudah memiliki dokumen Rencana Kontegensi menghadapi gempa dan tsunami setebal 51 halaman yang ditandatangani oleh Walikota Rusdi Mastura pada November 2012.
Skenario dalam Rencana Kontinjensi disusun untuk menghadapi gempa bumi dengan episentrum di lempeng Palu-Koro, berkekuatan 7,4 SR, kedalaman 10 kilometer dengan durasi gempa 40 detik dan tsunami setinggi 4,3 meter yang akan menyerang Teluk Palu dalam 15 menit. Jadi, gempa dan tsunami yang terjadi tahun ini sebetulnya sudah diprediksi dengan akurat enam tahun lalu.
Hampir seluruh dampak gempa dan tsunami seperti bangunan dan jembatan rubuh, listrik padam, pasokan air bersih berkurang, sinyal telepon terputus, kelangkaan makanan, naiknya harga-harga barang, serta masalah pengungsi dimasukkan dalam skenario Rencana Kontinjensi.
Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dari tahap prabencana sampai dengan pasca bencana dirumuskan secara rinci beserta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Pada tahap prabencana, direncanakan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan SAR dan evakuasi serta latihan simulasi dan gladi posko secara berkala yang melibatkan 1000 warga.
Dalam bagian penutup, disebutkan rencana kontinjensi ini masih memerlukan penyempurnaan dan review berkala untuk memperbaharui data yang ada.
Sebulan kemudian, Desember 2012, Badan Geologi Kementerian ESDM merilis hasil penelitian Risna Widyaningrum yang berjudul “Laporan Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquifaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian ini seharusnya ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke dalam Rencana Kontinjensi beserta cara mengantisipasi likuifaksi.
Sayangnya, pelaksanaan Rencana Kontinjensi Kota Palu atau pembaruan data tidak dilanjutkan. Keselamatan warga dianggap sepele. Dokumen ini hanya menjadi arsip yang tersimpan di BNPB.
Seandainya Rencana Kontinjensi ini terus diperbarui dan dilaksanakan secara konsisten, kita bisa berharap korban yang jatuh lebih sedikit dan masyarakat lebih sigap menghadapi masalah-masalah yang muncul pasca-bencana.
Namun, angin segar bertiup dari daerah lain. Melalui akun Facebook-nya pada 23 November 2018, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan kurikulum sekolah tanggap bencana mulai diberlakukan di seluruh sekolah di Jawa Barat. Siswa-siswi diajarkan cara menyelamatkan diri dalam simulasi bencana gempa bumi, tsunami dan banjir. Sekarang tinggal memastikan agar program ini dijalankan secara berkelanjutan.
Di bawah desentralisasi dan otonomi daerah, kehendak politik kepala daerah ternyata menjadi penting. Tidak semua kepala daerah mau memajukan konsep pendidikan tanggap bencana sampai ke tingkat implementasi secara berkelanjutan.
Seringkali rencana hanya dibuat untuk keperluan kampanye, sekadar proyek temporer, atau tak ada sama sekali karena rencana menghadapi bencana dianggap bukan proyek yang menguntungkan bagi elite. Sistem politik kita yang sudah begitu korup membuat proyek fisik demi kepentingan investasi dengan fee yang besar dipandang lebih penting ketimbang pembangunan manusia melalui pendidikan.
Kita tidak kekurangan hasil-hasil riset untuk membuktikan gempa bumi dan tsunami adalah keberulangan yang niscaya. Pengalaman pahitnya, bencana juga telah mengajarkan kita pendidikan tanggap bencana sudah mendesak. Yang hampir tidak kita miliki adalah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan bisa menerima masukan ilmiah.
Tapi, kita sebagai rakyat, sebagai warga negara, bisa memiliki sikap yang jelas: menolak kekuasaan elite politik yang mengabaikan keselamatan kita. Apa yang dikatakan oleh aktor Harrison Ford dalam pidatonya di Global Climate Action Summit 2018 bisa menjadi sikap kita bersama:
“Berhentilah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak percaya pada sains, atau lebih buruk lagi, mereka yang berpura-pura tidak percaya sains demi kepentingan mereka sendiri.”
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.