tirto.id - Kasman Sirait tiba sekitar pukul dua siang di Bale Persantian, Medan Denai. Sambil menggeret sebuah koper, sesekali ia melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Hampir semua orang di kompleks perumahan itu menyapanya dalam bahasa Batak. Kasman tiba bersama putranya dari Jakarta, 4 Juli lalu.
Ia dan anaknya mengenakan batik dan celana panjang; sebuah tampilan unik jika melihat orang lain yang hadir di kompleks itu. Kebanyakan laki-laki memakai kaos atau kemeja, hanya satu-dua yang pakai batik rapi seperti Kasman. Tapi semua orang di sana—laki-laki maupun perempuan, tua dan muda—melilitkan kain sarung di pinggangnya. Tak berselang lama setiba di sana, Kasman hadir di pelataran Bale dengan sarung melilit di pinggangnya.
Siang itu, Bale Persantian di Jalan Air Bersih Ujung memang tengah sibuk. Ratusan orang mondar-mandir di pelataran luas. Ada yang membakar kambing guling, ada yang menyiapkan pentas penuh gendang-gendang, ada kaum ibu yang sibuk memasak, puluhan anak kecil yang lari sana-sini, dan banyak orang yang cuma duduk-duduk. Mereka tengah mempersiapkan tempat itu sebagai lokasi salah satu ibadah besar Malim, agama leluhur dari Tanah Batak.
Acara itu bernama Sipaha Lima, yang berarti bulan kelima dalam bahasa Batak. Dalam Malim, ia salah satu ibadah wajib Parmalim. Upacara ini biasa dilakukan tiga hari berturut-turut, yaitu tanggal 12, 13, dan 14 bulan kelima dalam kalender Batak—biasanya bertepatan pada bulan Juli dalam kalender Masehi.
Ibrahim Gultom dalam Agama Malim di Tanah Batak menyebut Sipaha Lima sebagai salah satu upacara agama paling besar dan meriah. Indikatornya adalah peserta yang hadir dan jumlah sesajian yang dikumpulkan. Dalam Malim, para penganutnya memang dianjurkan untuk pulang ke kampung halaman dan merayakan hari raya tersebut.
Kasman dan putranya datang ke Medan memang khusus merayakan Sipaha Lima. Istri dan satu anaknya yang lain akan menyusul keesokan hari, bersama sang Ibu yang tinggal di Jakarta. Tak hanya keluarga Kasman, penganut Malim lain, mayoritas tinggal di kawasan Toba Samosir, juga satu per satu mendatangi Bale Persantian.
Namun, ada yang berbeda dari perayaan Sipaha Lima kali ini. Yang dimaksud kampung halaman Parmalim bukanlah Medan, melainkan Huta Tinggi di Laguboti, sekitar 5-6 jam dari Medan, di kawasan Toba Samosir. Untuk kali pertama, Sipaha Lima diadakan di luar Huta Tinggi. Ini kabar mengejutkan bagi kalangan wartawan lokal yang sudah akrab dengan Parmalim. Syarat menyelenggarakan Sipaha Lima di Bale Pasogit Partonggoan di Huta Tinggi merupakan hukum wajib dalam keyakinan Malim.
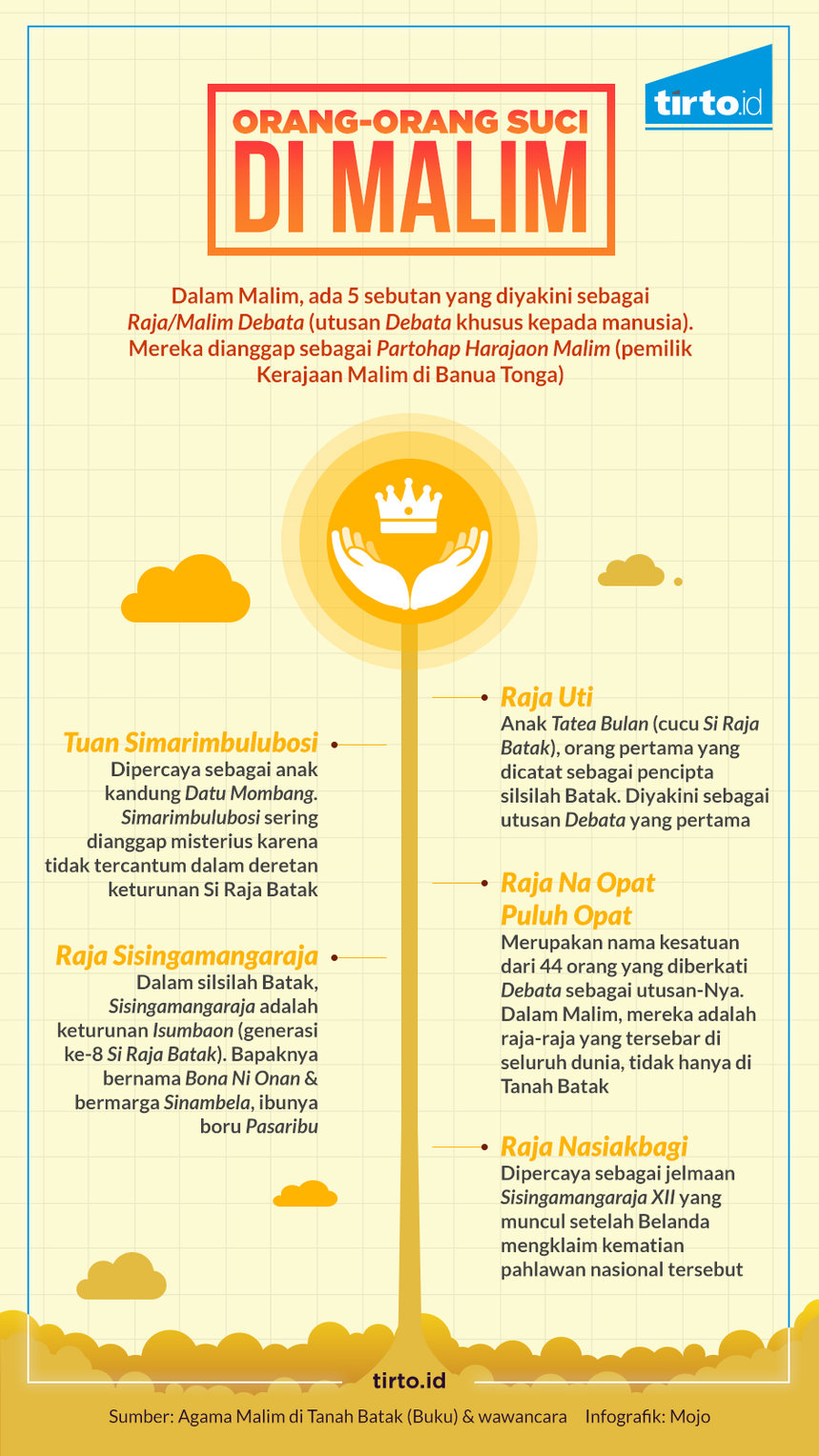
Dua Kubu Parmalim
Perubahan ini ditengarai ada perpecahan internal Parmalim selepas Raja Marnangkok Naipospos, pemimpin mereka, meninggal pada September 2016. Kini para penganutnya terbagi dua kelompok besar.
Ada dua orang yang mengklaim sebagai penerusnya. Kelompok pertama dipimpin Monang Naipospos, adik kandung almarhum Raja Marnangkok. Kelompok kedua dipimpin Poltak Naipospos, anak keempat almarhum Raja Marnangkok. Masing-masing memiliki pengikut setia yang meyakini mereka sebagai Ihutan—pemimpin tertinggi dalam komunitas Malim.
Sipaha Lima, yang diikuti Kasman dan sekitar 400 orang lain, adalah kelompok Parmalim yang meyakini Poltak Naipospos sebagai Ihutan mereka. Kelompok ini jauh lebih kecil ketimbang jumlah komunitas Malim—sekitar 5-6 ribu orang. Namun, perpecahan ini membuat kepolisian resor Toba Samosir menutup Bale Pasogit Partonggoan di Huta Tinggi.
Kubu Poltak Naipospos akhirnya membawa Sipaha Lima ke Medan. Bagi mereka, kewajiban untuk menggelar Sipaha Lima jauh lebih penting.
Poltak Simanjuntak, humas Parmalim dari kelompok Raja Poltak Naipospos, menyebut keputusan menyelenggarakan Sipaha Lima di luar Huta Tinggi untuk kali pertama dalam sejarah agama Malim hanya untuk tahun ini. Mereka tengah membangun Bale Pasogit baru di daerah dekat Laguboti.
“Menurut keyakinan Malim, acara ini harusnya diadakan di Tanah Batak. Medan ini bukan (Tanah) Batak. Ini Tanah Deli,” katanya.
Baca:
Sementara pihak Monang Naipospos tetap merayakan Sipaha Lima, tetapi tidak besar-besaran seperti biasanya. Ketika dihubungi via telepon, Monang menjelaskan Sipaha Lima dari kelompoknya hanya dihadiri 104 orang dan tetap dirayakan di sekitar rumahnya, yang terletak persis di belakang Bale Pasogit Partonggoan di Huta Tinggi.
“Yang lain merayakan di rumah. Ya, mau bagaimana, kan sempit,” katanya.
Perbedaan mendasar dari perpecahan kedua kubu terletak pada bagaimana cara Ihutan digantikan. Kelompok Poltak meyakini Ihutan dititiskan lewat garis keturunan. Sementara Monang mengklaim ayahnya, Raja Ungkap Naipospos—Ihutan sebelum Raja Marnangkok, sang kakak—sudah mewasiatkan yang berhak jadi Ihutan adalah semua anak lelaki yang berjumlah tiga orang.
“Kalau Abang saya yang kedua masih hidup, ya dialah yang jadi Ihutan, bukan saya,” kata Monang, putra ketiga Raja.
Namun, perpecahan ini justru dinilai oleh sebagian penganut Malim sebagai pertanda meneguhkan iman.
Sejumlah pengikut Poltak berkata "tidak takut" meski secara jumlah mereka lebih sedikit. Misalnya Poltak Simanjutak. Ia malah menganggap kejadian ini sebagai bukti kekuasaan Debata Mulajadi Na Bolon memang nyata.
“Dari kecil kita memang sudah dengar nubuat yang bilang kalau suatu hari Malim akan terbagi. Sedih memang di awalnya, tapi ya ini, kan, berarti bukti bahwa nubuat itu benar terjadi sekarang,” ungkapnya.
Sementara bagi Monang, perpecahan ini pertanda dan pelajaran agar Parmalim ke depan lebih meneguhkan spiritualitas. Perpecahan ini, menurutnya, menimbulkan kesan di mata orang-orang eksternal Parmalim bahwa ada perebutan kekuasaan. Ini bukan satu hal baik untuk nama Malim, kata Monang.
“Kesannya, kan, kayak organisasi jadinya, padahal ini agama, sesuatu yang spiritual,” ujar Monang.
Ferry Wira Padang, Direktur Aliansi Sumatera Bersatu, punya kajian serupa. Malim, yang biasanya jadi contoh baik bagi penghayat kepercayaan lain di Indonesia, bisa dianggap "mengalami kemunduran" karena konflik tersebut. Padahal, selama ini, konsep Malim yang lengkap sebagai agama dan kompak sebagai sebuah komunitas bisa menjadi modal besar untuk melawan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas agama di Indonesia.
“Tapi sebaiknya, kita yang orang luar tidak perlu mencampuri terlalu dalam. Biarkan ini jadi urusan mereka, dan kita tetap mendukung,” kata Wira. Baginya, lebih penting untuk mempromosikan keberagaman dan penerimaan pada keberagaman ketimbang harus sibuk menyatukan dua kubu tersebut.
Ketika ditanya bagaimana ujung konflik ini, Poltak Simanjuntak mengatakan kemungkinan besar kedua kubu tak akan bisa bersama lagi. Nada serupa diucapkan Monang.
“Saya sendiri cuma menunggu waktu. Keimanan itu, kan, urusan tiap individu dengan Tuhan, mana bisa saya campuri,” ujar Monang.
Meski penganutnya menyebut Malim sebagai sebuah agama, tetapi pemerintah Indonesia lewat Ketetapan Nomor IV/MPR/1978 mengakui Malim sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—digolongkan sebagai "penghayat kepercayaan."
Itu tentu jadi tantangan bagi Parmalim. Perkembangan terbaru lewat perpecahan ini akan sedikit-banyak memengaruhi nama Parmalim sebagai minoritas.
Menanggapi hal itu, Monang Naipospos tak ambil pusing. “Kalau mereka memang ingin tahu, mereka pasti akan langsung bertanya. Dan ujung analisisnya terserah kepada akalnya sendiri. Kita tidak bisa paksa dia mau bikin kesimpulan bagaimana, kan,” ujarnya, menanggapi diskriminasi terhadap Parmalim atas dasar ketidaktahuan.
Bagi Monang, masalah spiritualitas Malim biarlah jadi urusan internal masing-masing. “Cuma waktu yang bisa menjawab. Kalau orang-orang yang mengikut saya lari ke sana, ya tidak apa-apa juga. Berarti, kan, memang di sana yang terbaik.”
Seruan Wira menjadi relevan. "Yang perlu kita semua lakukan cuma menerima, menghormati, dan menghargai," ujarnya.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam
















