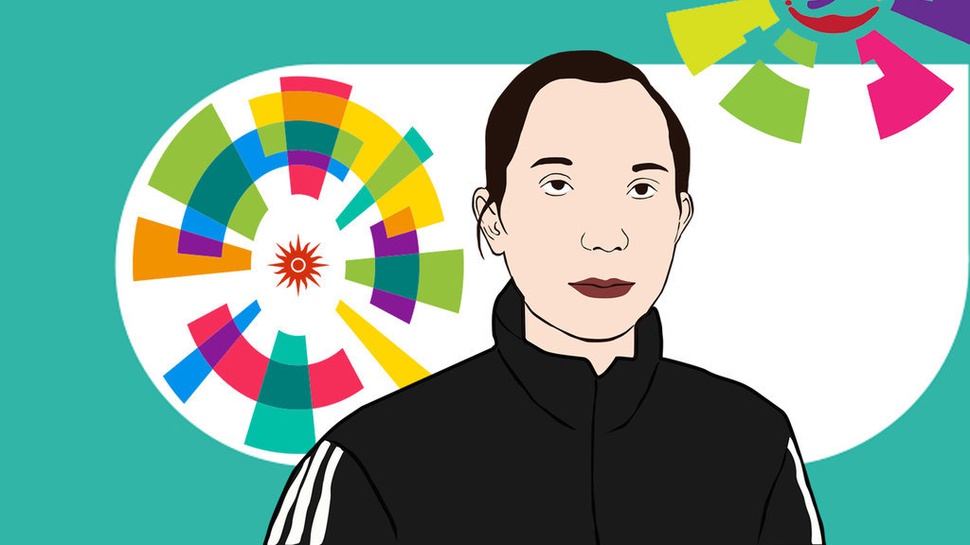tirto.id - Segala hal tentang hidupku serupa paradoks.
Aku seorang perempuan. Aku berdarah Tionghoa dan papaku warga negara Singapura. Aku bertarung untuk Indonesia.
Ada sebuah streotipe di negara ini bahwa orang-orang Tionghoa pasti mapan dan berada. Tentu saja itu omong kosong. Percayalah, jika situasi ekonomi setiap keluarga ibarat garis start bagi anak-anak yang terlahir darinya, aku mulai jauh, jauh, dari belakang.
Pada mulanya keluarga kami berkecukupan. Namun, suatu ketika Papa, yang berbisnis kayu, ditipu rekannya sendiri. Hidup seketika jadi bak abu di atas tanggul. Segalanya goyah, lalu ambruk. Bank menyita rumah, mobil, dan harta lainnya. Hidup di kota semakin menekan. Kemiskinan mendesak kami ke tepi.
Papa memboyong seluruh keluarganya ke kampung halaman Mama di Ciamis. Tinggal di kota kecil tak serta merta membuat hidup kami membaik. Papa enggan menumpang di rumah nenek karena ia enggan jadi beban. Ia ingin mandiri walau sulit.
Kami tinggal di rumah kontrakan yang sempit. Papa dan Mama mencoba bangkit berkali-kali, mulai dari berjualan bakso hingga barang-barang kelontong. Kami berdiri, jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi.
Utang membengkak. Kami bahkan tak sanggup menanggung biaya keperluan sehari-hari seperti beras, minyak, gula dan lain-lain. Suatu kali listrik rumah kami diputus karena pembayaran terlalu lama ditunggak. Bermalam-malam gelap gulita. Untuk mengecas ponsel Papa, satu-satunya alat komunikasi kami, aku terpaksa menumpang di rumah tetangga.
“Memang listrik punya nenek moyang lu?”
Bentakan itu akan selalu tergiang dalam kepalaku.
Papa bernama asli Yeo Meng Tong. Ketika ia masih berduit, orang-orang memanggilnya Mr. Tong dengan lagak manis. Begitu kami kere, orang enteng saja menyapanya Atong. Terkadang malah Otong. Itu membuatku jengkel. Kau tahulah, itu nama yang sering diberikan laki-laki buat alat kelaminnya sendiri.
Bagaimana pun, aku selalu merasa beruntung memiliki Papa yang tangguh dan penyabar. Dia tak pernah menyuruh istri atau anak-anaknya bekerja buat meringankan bebannya. Bahkan hal-hal sepele seperti menyapu, mengepel, atau mencuci piring, sering ia lakukan sendiri.
Aku pernah memergokinya berkata, dengan mesra, kepada Mama: “Biar Papa saja.” Papa adalah pemimpin keluarga kami, dan ia mengerti bahwa pemimpin sejatinya ialah pelayan.
Papa tak banyak bicara. Dia selalu memberi contoh dengan tindakan. Sifat konsekuen papa mulai kutiru sejak aku kecil. Sedari dulu aku sudah menyadari aku harus punya andil dalam keluarga ini.
Sejak kecil aku terbiasa bergaul dengan laki-laki. Aku jago bermain kartu dan gundu. Jika menang, gundu dan kartu mereka yang kumenangkan bisa kujual kembali. Uangnya kuserahkan ke Mama.
Itu bukan satu-satunya trik yang kupunya buat mencari uang. Bukan, bukan beternak tuyul. Dulu, ada snack berharga Rp500 yang kadang berisi hadiah uang Rp.5,000. Di warung langgananku, satu demi satu bungkus snack itu kukocok, kutimbang, kudengarkan bunyinya. Kalau cocok, aku ambil. Jika tidak, dengan polosnya aku akan berlalu meninggalkan penjaga warung yang cemberut karena barang dagangannya aku acak-acak. Konyol, jelas. Naif, mungkin. Tapi kisah itu benar belaka.
Saat aku lahir, Papa menamaiku Yeo Chuwey. Dalam bahasa Indonesia, artinya cukup keren: nomor satu yang paling bersinar. Sayang, kegaduhan politik di Indonesia waktu itu membuat Papa berpikir nama Tionghoa hanya akan membuat hidupku makin sulit. Maka, di akta kelahiranku tertera nama utama yang “lebih Indonesia”: Wewey Wita.
Sampai di sini, setelah mengetahui latar belakang keluargaku, kau mungkin mengira aku seorang atlet badminton, wushu, kungfu, basket, bridge, atau olahraga-olahraga yang telanjur lekat dengan etnis Tionghoa. Salah, aku adalah seorang pesilat.
Pencak silat cenderung lebih dekat dengan identitas keindonesiaan yang dibatasi pada satu entitas yakni etnis Melayu. Berkulit coklat, bukan kuning. Tentu pencak silat sendiri tak melahirkan sekat-sekat itu. Pembatasan, kukira, hanya ada dalam kepala kita. Pencak silat, seperti Indonesia, memeluk siapa saja yang mencintainya, termasuk aku.
Aku sendiri tak menyangka silat bisa jadi bagian dari hidupku. Memang semasa kecil aku biasa bermain dengan anak lelaki dan ikut beragam ekstrakurikuler olahraga, mulai dari voli dan basket hingga karate dan taekwondo. Mama selalu memaksaku menampakkan sisi feminin, sampai-sampai dia pernah memaksaku ikut lomba peragaan busana yang diadakan Radio Pitaloka, stasiun radio terkenal di Ciamis.
Aku terpilih sebagai juara 2.
Tetapi aku tak peduli. Buatku, berlenggak-lenggok itu tak nyaman. Kurasa bakatku memang olahraga. Semua guru olahraga mengenalku. Dalam berbagai kejuaraan olahraga antar sekolah, namaku selalu muncul dan mereka banggakan. Lalu, terjadilah sesuatu yang mengubah hidupku.
Dalam sebuah pesta perpisahan kakak kelas, seorang guru mendatangiku. Dengan enteng dia bilang: “Wewey, Bapak udah daftarin kamu, ya. Uang pendaftaran sudah masuk. Dua hari lagi pertandingan.”
Tentu aku terbelalak. “Tanding apa, Pak?” kataku.
“Silat.”
Aku bingung. Mau membantah takut durhaka. Tapi kalau harus mengembalikan uang pendaftaran, aku tak tahu harus mencari ke mana. Dengan terpaksa, aku menurut.
Hanya ada dua hari untuk belajar. Dan yang lebih ajaib, guru itu hanya mengajariku etiket masuk gelanggang, salam kepada wasit, dan hal-hal sepele lainnya. Sama sekali tak ada teknik pertarungan. Dan, oh, untuk kejuaraan pertamaku itu, meski masih kelas 4 SD, berat badanku melewati ambang batas yang ditentukan. Maka, aku diturunkan melawan anak-anak SMP.
Takut? Jelas. Musuhku adalah atlet-atlet pencak yang punya jam terbang, sedangkan aku cuma berlatih memberi salam selama dua hari. Aku menang dengan skor 3-2 dalam pertandingan pertamaku berkat teknik tendangan karate. Tendang, tendang, dan tendang. Aku gagal menjadi juara umum, namun saat juara terbaik diumumkan, namaku disebutkan di podium. Sejak saat itulah aku diminta guru-guru menggeluti pencak silat secara serius.
Popwilnas. Popda. Popnas. Satu demi satu kejuaraan berjenjang untuk pelajar itu kuikuti.
Seperti aku jelaskan di awal, hidupku penuh paradoks. Dan itu terjadi lagi di kejuaraan senior pertamaku, saat membela Kabupaten Ciamis di ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda).
Dalam sebuah kompetisi, lazimnya kasus pencurian umur terjadi saat si atlet mengurangi umur jagar tak melebihi batasan. Aku malah sebaliknya. Waktu itu, atlet Porda harus berusia 17-35 tahun, sedangkan aku baru 14 tahun. "Kalau kamu siap, gampang, semuanya bisa diurus," kata pelatih kepadaku.
Saat itu, aku tak begitu paham dan peduli apakah yang kulakukan benar. Yang kuinginkan hanya ikut kejuaraan dan berprestasi. Lagi pula, kita sama-sama tahu, sulap-menyulap bukan hal yang aneh di negara ini.
Aku memenangkan emas. Kabar soal pencurian umur yang kulakukan pun bocor dan jadi perbincangan. Namun, orang-orang sepertinya malah bangga sebab seorang atlet berusia dini mampu mengalahkan atlet-atlet yang lebih senior.
Emas Porda itu semestinya berarti bonus Rp10 juta untukku, tetapi yang kuterima hanya Rp7,5 juta—kukira aku tak perlu menjelaskan kepadamu bagaimana itu bisa terjadi. Aku tak mempermasalahkan hakku yang raib, lagi pula Rp7,5 juta bagi seorang anak SMP sepertiku saat itu sudah teramat besar.
Dari titik itulah karierku sebagai atlet pencak silat melejit. Aku bergabung dengan PPLP di Bandung.
Selain Papa dan Mama, aku beruntung memiliki kakek dan nenek yang amat berjasa ketika aku meniti karier di Bandung. Meski sulit, mereka selalu memaksaku menerima uang pemberian mereka, yang aku tahu didapat dengan susah payah.
Saat di Bandung, aku kadang tak bisa makan dengan lahap. Apakah keluarga di Ciamis sudah makan atau belum? Aku merasa telah meninggalkan keluargaku dalam situasi sulit.
Namun, pilihan pelik merantau ke Bandung harus kuambil. Hanya dari sanalah aku bisa berharap membantu Mama, Papa, dan lima adikku menyambung hidup dengan uang saku dan bonus kemenanganku di pelbagai kejuaraan.
Jika boleh jujur, aku sebenarnya sudah letih. 15 tahun aku bertarung, bertarung, bertarung. Aku sadar bahwa menjadi atlet bukan jaminan pasti untuk masa depan—ibarat bunga, segar dipakai layu dibuang. Namun, di sisi lain, kerja belum selesai, belum apa-apa. Aku akan berhenti hanya jika sudah memberikan prestasi terbaik bagi bangsaku, negaraku: Indonesia.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.