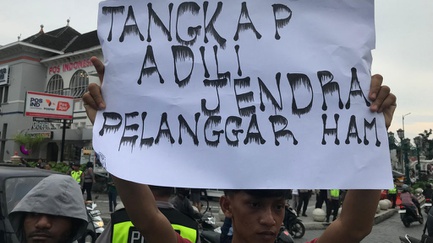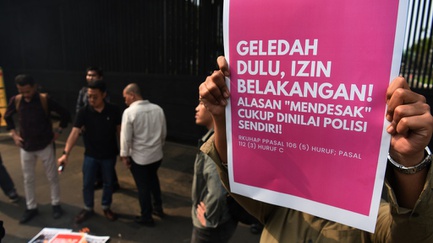tirto.id - Presiden Joko Widodo dalam akun Twitter miliknya mengatakan Indonesia memiliki 13 juta hektare kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Namun, Uni Eropa memunculkan isu minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan.
“Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka,” demikian twit Jokowi pada 11 Januari 2020.
Jokowi melanjutkan, “Jalan keluarnya ada: CPO kita pakai lebih banyak untuk domestik, jadi campuran biodiesel melalui program B20, dan kini B30. Komoditas lain seperti nikel, bauksit, timah, batu bara, dan kopra menyusul. Kita tidak akan ekspor mentah, tapi dalam bentuk jadi atau setengah jadi.”
Akan tetapi, twit Jokowi tersebut menuai kritik, salah satunya dari Ketua Tim Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas. Ia menyayangkan pernyataan “perang dagang” itu dilontarkan dari seorang presiden.
“Ini adalah pengabaian terhadap fakta-fakta dampak sawit yang merusak lingkungan. Sudah banyak dalam referensi ilmiah juga menjadi dasar kebijakan Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa yang mengeluarkan biofuel berasal dari penggunaan lahan, termasuk dari sawit," kata Arie ketika dihubungi reporter Tirto, Senin (13/1/2020).
Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan.
— Joko Widodo (@jokowi) January 11, 2020
Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. pic.twitter.com/YzzihBQggX
Fakta kerusakan lingkungan, kata Arie, akibat konversi hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit telah mengakibatkan dampak serius, terutama kebakaran hutan terjadi karena lahan gambut yang dikeringkan.
Hal itu mengakibatkan pelepasan emisi yang mendorong terjadinya krisis iklim dan mengancam kesehatan masyarakat akibat asap lahan gambut.
“Itu adalah bukti bahwa daya dukung lingkungan sudah tak bisa menampung lagi ekspansi baru, bahkan harus dipulihkan dengan merestorasi lahan gambut. Maka seharusnya tidak ada lagi ekspansi sawit baru," jelas Arie.
Biofuel yang berasal dari sawit seharusnya tidak dikategorikan sebagai energi terbarukan, kata Arie, lantaran sejarah penggunaan lahan dari deforestasi menghasilkan emisi.
"Rencana B20 dan B30 apalagi sampai B100, berpotensi menjadi penambahan ekspansi lahan sawit baru, karena orientasinya adalah pasar, bukan keberlanjutan energi dan perlindungan lingkungan," ujar dia.
Arie menambahkan, dari data Presiden Joko Widodo yang menyebutkan luas lahan sawit hanya 13 juta hektare tidak akurat, karena data Kementerian Kehutanan sendiri menyebutkan bahwa tutupan sawit sudah mencapai 16,381 juta hektare.
“Ini belum disesuaikan dengan luas izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Arie menambahkan.
Arie menegaskan yang terpenting, Presiden Joko Widodo seharusnya mendapatkan referensi yang tepat untuk membuat kebijakan, bukan menyampaikan isu perang dagang soal sawit.
Selain itu, kata Arie, Indonesia harusnya menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola di sektor sawit.
“Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dari perubahan iklim dan harus bertindak nyata untuk melawan krisis iklim, bukan menjadi climate denial," tegas Arie.
Jalan keluarnya ada: CPO kita pakai lebih banyak untuk domestik, jadi campuran biodiesel melalui program B20, dan kini B30.
— Joko Widodo (@jokowi) January 11, 2020
Komoditas lain seperti nikel, bauksit, timah, batu bara, dan kopra menyusul. Kita tidak akan ekspor mentah, tapi dalam bentuk jadi atau setengah jadi. pic.twitter.com/r3P2hI5uxn
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, kerusakan lingkungan hidup akibat ekspansi lahan sawit bukanlah isu. Penggunaan minyak sawit untuk program B20 atau B30 di Indonesia bisa saja dilakukan, akan tetapi tidak membuka kebun sawit baru.
"Biodiesel B20/30 ini dijadikan alasan oleh pengusaha untuk meminta lahan baru bagi ekspansi kebun sawit, padahal dengan luas yang sekarang saja sudah terlalu besar dan mendominasi penggunaan lahan di Indonesia," kata Nur Hidayati ketika dihubungi reporter Tirto, Senin (13/1/2020).
Nur Hidayati mengatakan, ketergantungan yang terlalu berlebihan pada satu jenis komoditi tidak sehat bagi ekonomi indonesia secara umum, karena semakin sedikit jenis produksi dari ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan semakin rentan. Apalagi ini komoditas ekspor yang sangat dipengaruhi dinamika pasar.
Sebenarnya ekspor CPO Indonesia masih bisa masuk Eropa, kata Nur Hidayati, tapi jika untuk memproduksi biodiesel di Eropa maka pengimpor di Eropa tidak mendapat subsidi dari pemerintahnya.
“Sebenarnya ekspor CPO ke Eropa tidak dilarang dan tidak ditutup sama sekali. Isu tentang perang dagang ini misleading karena seolah Eropa menutup seluruh pasokan CPO indonesia, padahal tidak," tutur dia.
Nur Hidayati melanjutkan, industri besar sengaja mengembuskan isu ini untuk menakuti pemerintah Indonesia, sehingga mereka bisa memaksa pemerintah Indonesia memberikan fasilitas yang menguntungkan industri dan pengusaha besar.
"Kalau pemerintah benar serius, sebaiknya membuat roadmap tentang peralihan dari bahan bakar fosil ke non-fosil, atau secara umum tentang penerapan energi terbarukan di Indonesia. Jangan impulsif seperti sekarang ini," imbuh dia.
Nur Hidayati menambahkan, dinamika isu biodiesel ini sejak lama dan pemerintah tidak serius untuk peralihan bahan bakar tersebut.
Isu biodiesel hanya dijadikan jaring penyelamat jika pasar sawit sedang tidak menguntungkan pengusaha, sehingga pemerintah mau tidak mau harus menyerap produksi CPO.
"Nanti kalau pasar sudah membaik, isu biodiesel ini akan hilang dengan sendirinya," ucap dia.
Beberapa dampak negatif dari perluasan lahan sawit seperti deforestasi, memengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah hutan, memicu konflik agraria dan menyebabkan kebakaran hutan.
Data Konsorsium Pembaruan Agraris (KPA), jumlah konflik agraria menurut sektor (2018): Perkebunan 144 (35%), Properti 137 (33%), Pertanian 53 (13%), Pertambangan 29 (7%), Kehutanan 19 (5%), Infrastruktur 16 (4%), dan Pesisir/kelautan 12 (3%).
Dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan, sebanyak 83 kasus atau 60 persen terjadi di perkebunan kelapa sawit.
Berdasar Studi Dinamika Hulu Hilir Industri Biodiesel Indonesia, November 2018, yang dikeluarkan oleh Koaksi Indonesia, kebutuhan biodiesel B100 meningkat, yakni: 0,82 juta kiloliter (2015), 2,80 juta kiloliter (2016), 2,70 juta kiloliter (2017), 4,10 juta kiloliter (2018), 6,19 juta kiloliter (2019), 9,66 juta kiloliter (2020), 10,05 juta kiloliter (2021), 10,45 juta kiloliter (2022), 10,87 juta kiloliter (2023), 11,30 juta kiloliter (2024), dan 11,75 juta kiloliter (2025).
Sementara CPO yang dihasilkan sejak tahun 2015-2025 juga meningkat, antara lain 0,74 juta ton; 2,61 juta ton; 2,22 juta ton; 3,69 juta ton; 5,57 juta ton; 8,69 juta ton; 9,04 juta ton; 9,40 juta ton; 9,78 juta ton; 10,17 juta ton dan; 10,58 juta ton.
Untuk luas lahan yang dibutuhkan selama tahun 2015-2025 sebagai berikut: 0,26 juta hektare (2015), 0,90 juta hektare (2016), 0,84 juta hektare (2017), 1,31 juta hektare (2018), 1,99 juta hektare (2019), 3,11 juta hektare (2020), 3,23 juta hektare (2021), 3,36 juta hektare (2022), 3,49 juta hektare (2023), 3,63 juta hektare (2024), dan 3,78 juta hektare (2025).
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id