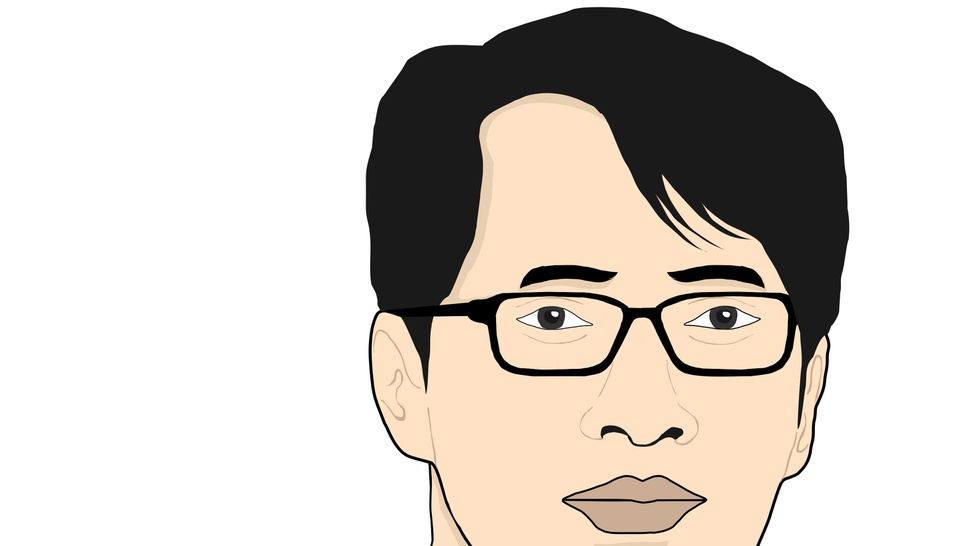tirto.id - Pada 1973, pemerintahan Orde Baru (melalui rancangan Ali Moertopo) mulai mempraktikkan kehidupan politik yang represif. Langkah paling mendasar adalah memaksa partai-partai bergabung satu sama lain. Seluruh partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, serta partai nasionalis dan Kristen digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia.
Nahdlatul Ulama (NU) bergabung dengan tiga partai muslim lain, menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berdirinya PPP diumumkan pada Januari 1973. Penggabungan menjadi PPP muncul sebagai kenyataan yang harus diterima bagi kebanyakan politikus NU.
Idham Chalid, tokoh terpenting NU di pentas nasional, dan kawan-kawan terdekatnya, langsung menerima campur tangan yang sangat jauh ini tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lain. Dapat dimengerti jika hal ini memunculkan ketidakpuasan di lingkungan NU. Namun, semua tampaknya setuju untuk berbuat yang terbaik dalam kondisi baru ini tinimbang menantang secara aktif (Bruinessen, 1994: 102).
Ada juga sebagian pemimpin NU yang berpikir bahwa perubahan ini akan terbukti menguntungkan NU. Wakil ketua PBNU Achmad Sjaichu mengutarakan pendapat yang menjadi lebih laku satu dasawarsa kemudian. Dalam pandangannya, keterlibatan NU dalam politik praktis telah mengorbankan tugas-tugas pendidikan dan dakwah. Dengan kehadiran PPP, politik dapat diserahkan kepada para politikus dan NU akan kembali menjadi sebagaimana aslinya: organisasi keagamaan (Mahfoedz, 1983: 246).
Namun, para kiai dan pendukung mereka di daerah sudah terlalu terbiasa dengan patronase politik sehingga saat itu sulit menerima pandangan realistis ini. Setelah volume kekuasaan mengalir melalui saluran NU berkurang secara drastis, barulah pandangan ini semakin banyak diterima.
Perlawanan NU Melalui PPP
NU bertahan sebagai komponen khusus, sekaligus utama, dalam PPP. NU dengan gencar mempertahankan kepentingan faksionalnya.
NU adalah partai yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lain yang bergabung dalam PPP. Dua di antaranya PSII dan Perti, partner lamanya dalam Liga Muslimin. Kedua partai ini sangat kecil. Perti bahkan hanya memiliki pendukung di lingkungan etnis (kaum tradisionalis Minangkabau dan Aceh).
Satu-satunya partner signifikan NU di PPP adalah Parmusi. Menurut hasil pemilu 1971, Parmusi mendapat 24 kursi di DPR, sementara NU 58, PSII 10, dan Perti 2 kursi. (Untuk perbandingan: Golkar mendapatkan 226 kursi dan partai-partai yang kelak bergabung dalam PDI mendapatkan 40 kursi)
Namun, fusi partai ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan identitas komponen-komponennya, dan sejarah PPP berikutnya ditandai oleh konflik-konflik antara keempat komponen ini dalam pembagian jatah kursi. Dalam konflik-konflik itu, NU terlalu sering menjadi faksi yang dirugikan.
Bagi NU, peleburan diri ke dalam PPP seperti kembali ke masa ia menjadi bagian dari Masyumi. Tidak sulit meramalkan sebagian problem dan konflik lama meledak kembali ke permukaan, kecuali jika ketimpangan antara kekuasaan massa pendukung yang besar dan jumlah politikus yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik.
Namun, posisi NU pada awalnya lebih baik, karena NU memulainya sebagai kelompok dominan di dalam PPP. Anggota NU mendapatkan jatah yang adil dalam jabatan pengurus. Ketua Umum PBNU Idham Chalid diberi kedudukan bergengsi tapi kurang berpengaruh karena ketua eksekutif diberikan kepada Mintaredja dari Parmusi (beberapa tahun kemudian Mintaredja harus digantikan Djaelani Naro, rekan Ali Moertopo).
Yang lebih penting lagi, Rois Aam NU Kiai Bisri Syansuri juga menjadi presiden Majelis Syuro PPP, dewan ulama yang menurut teorinya dapat mengeluarkan fatwa yang secara konstitusional harus diikuti partai. Berulangkali, saat-saat kritis selama 1970-an, Kiai Bisri mengeluarkan keputusan tegas tentang pendirian partai.
Kiai Bisri adalah pemimpin yang sangat berbeda dengan Kiai Wahab Chasbullah. Ia kurang memiliki naluri politik dan keluwesan yang dimiliki para pendahulunya. Ia lebih mendasarkan keputusan kepada penalaran fikih (ilmu tentang hukum Islam) ketimbang kebijaksanaan politik. Seperti kebanyakan ulama tradisionalis, ia lebih suka menghindari konflik dengan pemerintah tapi menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama.
Islam Politik Menentang Soeharto
Inilah yang justru membuat Kiai Bisri dan NU beberapa kali terlibat dalam perbenturan serius dengan pemerintah. Konfrontasi pertama terjadi ketika rencana undang-undang perkawinan dibawa ke sidang DPR pada 1973. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih, dan Kiai Bisri menolaknya dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan penolakan atas undang-undang tersebut.
Konfrontasi serius dengan pemerintah terjadi lagi pada pemilu 1977. Kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang timpang antara Islam dan rezim Orde Baru (Liddle, 1978). Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Lagi-lagi para politikus NU menjadi pengkritik paling vokal dan berani. Para juru kampanye PPP diancam dan bahkan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar.
Kiai Bisri bersikap tegas dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan setiap Muslim wajib hukumnya memilih PPP sekalipun ia khawatir akan kehilangan jabatan dan mata pencaharian. Beberapa kiai memihak ke Golkar, tapi NU terbukti mampu mempertahankan disiplin internal yang kuat; sementara para kiai yang “tergolkarkan” ini dikucilkan dan kehilangan banyak pengikut.
Dengan mempertimbangkan pelbagai situasi ini, PPP telah menampilkan diri dengan baik dalam pemilu 1977 dan berhasil mendapat tambahan 5 kursi lebih banyak dari pemilu 1971. PPP memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di ibukota. Di Jakarta mereka mendapatkan dukungan suara yang sangat besar, dan bahkan meraup suara mayoritas mutlak di Aceh (Bruinessen, 1994: 104-5).
Barangkali, konfrontasi paling serius terjadi selama Sidang Umum MPR 1978 ketika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diwicarakan. Kali ini GBHN mengandung dua item yang sulit diterima kebanyakan umat Muslim Indonesia. Satu item menyebutkan aliran kepercayaan berdampingan dengan agama-agama resmi dan karena itu secara implisit memberikan pengakuan formal kepada aliran kepercayaan sebagai agama tersendiri. Item yang lain adalah usulan program pemerintah untuk melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila (menurut penafsiran Orde Baru), secara massal, yang kelak memuncak menjadi keharusan asas tunggal Pancasila.
Kiai Bisri Syansuri memandangnya sebagai ancaman terhadap status Islam sebagai agama dan memprotesnya dengan keras. Ketika dilangsungkan voting atas pasal itu, para anggota NU yang diikuti kelompok PPP lain secara demostratif meninggalkan tempat sidang (walk out). Sikap ini bukanlah ketidaksenangan kalangan Muslim terhadap Pancasila itu sendiri, tetapi terhadap relativisme agama yang terkandung dalam program indoktrinasi ini. (Semua agama yang diakui sama benarnya serta memberikan tempat sejajar dengan Aliran Kepercayaan)
Kepekaan umat Muslim dapat dimengerti dengan lebih baik jika kita ingat bahwa umat Kristen terlalu banyak duduk di elite kekuasaan dan Soeharto sendiri serta para penasihat terdekatnya dipercaya sebagai penganut Aliran Kepercayaan dan tidak simpatik terhadap Islam skripturalis. Sudah ada kekhawatiran jika penguasa menginginkan Pancasila yang satu jenis ajaran Kepercayaan sebagai pengganti agama.
Dalam konteks Indonesia-nya Orde Baru, yang sangat menekankan konsensus, tindakan “walk out” ini adalah bentuk protes yang sangat radikal, sama artinya melakukan delegitimasi. Pemerintah memandang kejadian ini sebagai penghinaan terhadap penguasa dan ideologinya. Kejadian ini memperbesar kecurigaan Soeharto terhadap NU dan Islam pada umumnya. Ihwal ini semakin memperkuat tekadnya melakukan depolitisasi terhadap Islam Indonesia.
Reaksi pertama adalah penggantian Ketua Umum PPP Mintaredja dengan Djaelani (“John”) Naro, yang telah diatur rapi melalui manipulasi politik yang dikemudikan oleh Ali Murtopo. Bahkan, tanpa ada undangan rapat pengurus apalagi muktamar, Naro mengumumkan dirinya sebagai ketua yang baru.
Pada 1980, sekali lagi NU melancarkan protesnya dengan aksi “walk out” atas rancangan undang-undang baru yang mengatur proses pemilu. Ini setelah terjadi perdebatan nan panjang dan terbuka. Kali ini bukan masalah yang bersifat agama yang sedang dipertaruhkan, tapi soal prinsip kekuasaan yang demokratis. Partai-partai (PPP dan PDI) menginginkan agar undang-undang ini memuat jaminan-jaminan netralitas pemerintah dalam proses pemilu, tetapi pemerintah menolak memberikannya.
Nao, pimpinan PPP yang baru, mengalah dan memerintahkan anggotanya untuk menyetujui undang-undang itu. Namun, NU tetap tak mau menyerah: Semua anggota NU di PPP secara terang-terangan enggan masuk ke ruang sidang ketika undang-undang itu disahkan (Radi, 1984: 163-4).
Kiai Bisri, masyhur sebagai figur ulama yang membuat NU tak kenal kompromi pada 1970-an, pada saat itu sedang sakit-sakitan dan tampaknya tidak berperan sebagai penggerak utama di belakang konfrontasi ini. Pada April 1980 ia meninggal dunia sehingga organisasi ini tidak lagi mempunyai figur kepemimpinan moral yang kuat. Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) NU pada tahun berikutnya di Kaliurang, Yogyakarta, memilih seorang Rais Aam ad interim, Kiai Ali Ma’shum dari Krapyak, Yogyakarta.
Munas kali ini menarik perhatian banyak orang karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Sudah menjadi kebiasaan untuk semua jenis pertemuan menjelang pemilu untuk menyatakan “kebulatan tekad” yang mengharapkan agar Soeharto bersedia menjabat kembali sebagai presiden untuk masa bakti berikutnya. Sikap NU yang secara eksplisit menolak ikut dalam koor ini juga dipandang sebagai tanda dari sikap melawan.
Represi Pasca-Pemilu 1982
Setelah itu semua, represi politik dari Soeharto kepada umat Islam semakin kasar. Berturut-turut terjadi tragedi berdarah yang menimpa umat Islam: Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (1989), hingga Tragedi Haur Koneng (1993).
Represi lain adalah keharusan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, baik organisasi/partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Jika harus dirunut, represi melalui asas tunggal inilah yang justru memicu perlawanan dari umat Islam, baik perlawanan aktif seperti dalam Tragedi Priok maupun perlawanan pasif (dengan menyingkir dan membangun kampung sendiri) seperti yang dilakukan Warsidi di Talangsari.
Di tingkat lain, para ulama, ustaz, dan kiai kampung (yang menjadi pegawai negeri) sangat menderita karena harus memendam aspirasi politiknya. Tidak bisa tidak mereka harus mengakomodasi kehendak pemerintah untuk selalu memenangkan Golkar. Abah saya sendiri mengalami hal itu.
Abah saya, Jamhari Arsyad (1945-2003), sangat menghormati Tuan Guru Idham Chalid. Sebagai alumnus Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Kota Amuntai sekaligus warga Nahdlatul Ulama, wajar saja jika Abah saya punya rasa hormat kepada Tuan Guru Idham.
Tuan Guru Idham masyhur di kalangan muslim Banjar di Hulu Sungai sebagai ulama kharismatik-cum-politikus yang sukses di pentas nasional. Sepulang mondok di Ponpes Gontor (Ponorogo, Jawa Timur), Idham sempat kembali ke Amuntai dan mengabdi serta mereformasi sistem pendidikan di Rakha. Meski Abah tak sempat belajar secara langsung kepada Guru Idham, relasi antar-keduanya bak hubungan kultural antara guru dan murid (dalam tradisi santri).
Idham Chalid lahir di Setui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1921. Ia memulai karier politik sebagai ketua cabang Masyumi lokal di Kalimantan Selatan pada 1944. Pada 1947 ia menjadi anggota dewan regional yang disponsori Belanda. Titimangsa 1949-1950, ia menjadi anggota parlemen Republik Federal, dan pada 1955 ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai NU. Idham diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua (1956-1957), dan pada tahun yang sama menjadi ketua umum Tanfidziyah NU, posisi yang terus dipegangnya sampai ia dibujuk mengundurkan diri pada 1982.
Idham sempat menjadi wakil ketua DPA pada masa Demokrasi Terpimpin. Walaupun mempunyai hubungan dekat dengan Orde Lama, ia mampu melewati masa transisi dengan baik dan bahkan menjadi menteri era Orde Baru pertama (sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat 1967-1970, kemudian Menteri Sosial, 1970-1971), dan ketua DPR dan MPR pasca-Pemilu Orde Baru yang pertama (1971-1977). Jabatan-jabatan tinggi ini diikuti dengan jabatannya sebagai presiden PPP (sampai 1989).
Idham juga secara formal duduk dalam kepengurusan tarekat NU, tetapi baru memegang posisi ini secara serius sejak 1984. Abah tentu saja juga pengikut tarekat ini. Idham meninggal dunia dalam usia 88 tahun di Jakarta pada 11 Juli 2010. Ia ditahbiskan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia (berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011).
Posisi Abah saya tentu sangat dilematis. Sebagai abdi negara di Departemen Agama di era Orde Baru, Abah dipaksa untuk tidak partisan di luar partai resmi milik penguasa, yakni Golongan Karya. Sejak 1980, para anggota NU yang berstatus pegawai negeri sipil di Depag diharuskan secara formal melepaskan keanggotaannya di NU karena tuntutan “mono-loyalitas”. Seperti PNS lain, mereka diharuskan menjadi anggota “kelompok fungsional” KORPRI, salah satu soko guru Golkar, dan menghalangi mereka menjadi anggota partai lain.
Perlu diingat pula para anggota Muhammadiyah tidak menghadapi masalah yang sama, karena organisasi mereka bersifat non-politik.
Ada cerita lucu soal ini. Pada masa kampanye Pemilu 1982, Abah saya seringkali didatangi tim kampanye (tim sukses kalau bahasa sekarang) dari Golkar. Mereka bertamu ke rumah kami di Amuntai untuk membujuk, merayu, bahkan memaksa Abah untuk ikut terlibat menjadi juru kampanye seperti tokoh-tokoh masyarakat lain di kota itu. Karena Abah kadung cinta mati dengan NU dan sosok Idham Chalid, tentu saja Abah menolak, tetapi dengan cara halus: Tiap kali aparat pemerintah daerah ini datang bertamu, Mama yang disuruh menemui mereka.
“Bilang saja Abah tak ada di rumah,” ujar Abah. Abah biasa bersembunyi di dapur, di bawah ranjang, atau dalam lemari, atau kabur ke sawah. Karena bosan tak pernah ditemui kala bertamu, orang-orang Golkar itu akhirnya memberi ancaman serius: jika Abah tak mau menerima tawaran bergengsi ini, Abah bakal segera diminta menghadap Bupati.
Dan hal ini memang bukan pepesan kosong belaka. Tidak lama berselang, Abah termasuk dari kelompok ulama yang dipanggil untuk menghadap Bupati (yang notabene berlatar belakang militer). Singkat cerita, Abah diberikan dua pilihan: akomodatif dengan Golkar sehingga karier birokrat di daerah akan mulus; atau sebaliknya, jika membangkang akan dibuang atau bahkan bisa dipecat dari PNS.
Mungkin karena jiwa mudanya, Abah memilih opsi kedua: menolak kompromistis. Hasilnya, ketika hari pencoblosan, Abah tetap memilih lambang Ka’bah sebagai pilihan. Tentu saja ini menjadi alasan untuk menyingkirkan Abah dari Depag Amuntai.
Untunglah ia tidak sampai dipecat. Abah hanya dibuang ke daerah Alalak (kini masuk kabupaten Barito Kuala, Kalsel). Ia harus berpisah dari kami karena terpisah jarak yang jauh, sekitar 180-an km. Dengan sarana transportasi zaman dulu yang masih sangat terbatas, tidak mudah menempuh jarak sejauh itu untuk sekadar rutin bertemu dengan keluarga.
Pada 1985, Abah berhasil pindah dinas ke Kota Banjarmasin dan bisa memboyong kami semua ke sana. Belajar dari kepolosan di masa lalu, akhirnya Abah harus mau “dipaksa” menjadi simpatisan Golkar yang setia, seperti PNS seluruh Indonesia pada umumnya di bawah represi Orde Baru kala itu.
Cerita Abah saya bukanlah cerita unik. Ada banyak yang senasib Abah saya atau bahkan lebih malang. Akhirul kalam, kisah kecil ini melukiskan bagaimana mesin kekuasaan 32 tahun rezim Soeharto berjalan dan menindas Islam Politik secara hegemonik.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.