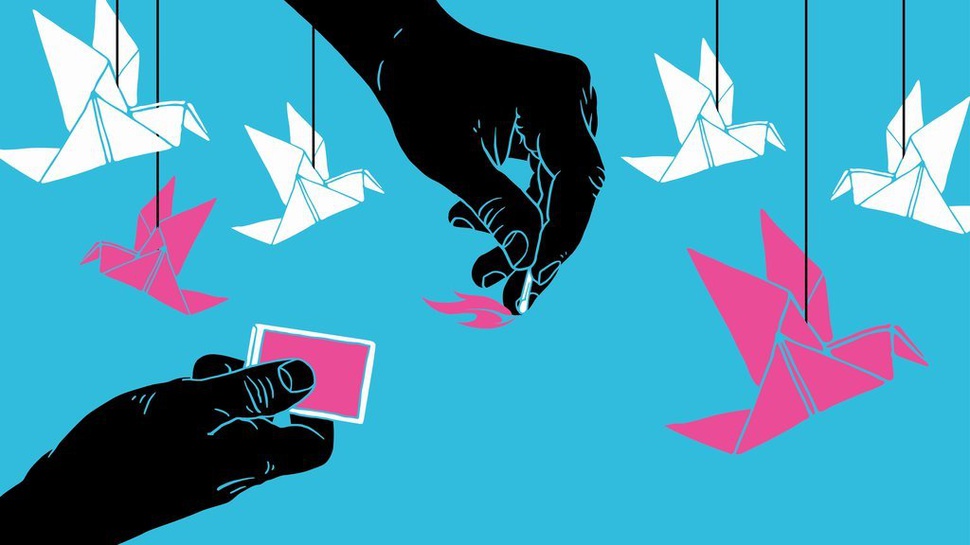tirto.id - Pak Rohmad turun ke liang lahat. Ia membuka tali pocong. Melepas plastik yang membungkus jenazah Mira. Meratakan tanah. Lalu merapal doa.
“Saya tahu dia waria. Pekerja seks. Tapi bagaimanapun dia manusia. Bukan binatang,” tuturnya.
Saya tercekat. Lalu ia menambahkan, “Saya tak bisa membantu materi. Cuma ini yang bisa saya lakukan.”
Sehari sebelumnya, 4 April 2020, sekelompok orang menyeret dan memukuli Mira dan membakarnya hidup-hidup.
Mira dituding mencuri dompet dan telepon genggam milik seorang sopir truk. Kontrakannya digeledah. Ia dibawa ke sebuah garasi truk tak jauh dari kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Di hadapan puluhan orang, tubuhnya dihajar habis-habisan. Mira melolong. Temannya sesama waria menyaksikan dari kejauhan, tak bisa berbuat apa-apa.
Tendangan mendarat ke tubuh Mira. Seorang lantas menuangkan bensin ke ujung kepalanya. Mira meraung. Berjongkok minta ampun. Sia-sia. Seorang lain sudah menyalakan korek api lalu menyulutkan ke dekat tubuhnya. Teman Mira berteriak-teriak mencegah. Mira meratap-ratap. Lalu api berkobar.
Dengan luka bakar hingga 70 persen, Mira dibawa ke rumah sakit. Ia meninggal esok paginya. Meninggalkan sepotong hati kita yang ikut terbakar karenanya.
Aksi persekusi kepada waria atau transpuan, bukanlah cerita baru. Dua tahun lalu di Bekasi, dua waria yang mejeng di jalanan dikejar-kejar sekelompok orang. Dipukuli, digunduli. Salah seorang ditelanjangi. Di Aceh, puluhan waria yang bekerja di salon dirazia dan digunduli dan foto-fotonya disebar. Di Lampung, tiga waria ditangkap lalu disemprot air comberan dari mobil pemadam kebakaran. Dipermalukan di depan umum.
Mira adalah potret waria pada umumnya. Yang terseok menegakkan hidup di jalanan. Lima belas tahun lalu, ia—bahkan tak ada yang tahu nama aslinya—kabur dari rumah di Makassar. Keluarga menolaknya lantaran ia dianggap tak normal. Mira mengadu nasib ke Jakarta, mejeng di jalanan Jatinegara. Puluhan kali kena razia, dikejar-kejar, kepalanya digunduli, ia akhirnya menyelip di antara deru truk-truk peti kemas pelabuhan di Cilincing. Usianya sudah di atas 40 tahun. Terlalu banyak persaingan di pinggiran aspal.
Menjadi waria adalah bersiap menelan stigma dan diskriminasi seumur hidup. Dimulai saat usia akil balig dan menyadari dirinya memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Saat itulah perundungan demi perundungan tiba. Dari teman sebaya, sekolah, dan orang-orang sekitar. Dihina-hina, dianggap menyimpang dari norma dan agama. Tak tahan dengan tekanan, mereka putus sekolah. Lantas, berujung diusir dari rumah. Pada usia sangat muda.
Tak ada ijazah dan kemampuan khususmelempar mereka ke nasib klise kaum jelata:menjadi pekerja seks. Jika sudah menua seumur Mira, mereka kalah bersaing dengan waria yang berumur lebih muda dan lebih segar, pasrah diganjar tarif paling melata. Menjadi pengamen, kompetisi pun tidak ringan. Suara mereka tak merdu. Tak bisa menggenjreng gitar. Jadilah berjoget erotis di lampu merah agar recehan diulurkan. Telanjur dihina. Telanjur dianggap badut. Bekerja di salon dan industri kreatif? Mungkin itu lebih baik, kendati tak luput dari persekusi seperti para waria di Aceh.
Tak ada kartu identitas berujung pada berjibun persoalan rumit. Tak bisa mengakses layanan sosial seperti asuransi kesehatan. Jika sakit, ia menanggung kerepotannya sendiri. Jika mati, persoalan pun belum berhenti: Tak ada keluarga yang mengakui dan sudi menguburkan.
Bagaimana negara?
Alih-alih memberi perlindungan dan menjamin hak hidup mereka, aparat negara kerap menjadi bagian dari pelaku kekerasan dan mendukung kebencian dengan dalih waria telah membuat masyarakat resah. Beragam bentuk propaganda kebencian terhadap mereka membuat kekerasan di akar rumput mudah terbakar. Ditambah banyak peraturan daerah diskriminatif yang menjadi legitimasi masyarakat melakukan persekusi.
“Ah waria, pantas saja!” seorang pembaca mengomentari berita kematian Mira.
“Ah, mereka juga menipu identitas, layak dibakar!”
“Tangkap semua pelakunya. Bakar hidup-hidup. Api bayar api!” celetuk lainnya.
Demikianlah. Kekerasan berujung bentuk kekerasan verbal lainnya.
Bengis. Biadab. Apalagi? Memukuli orang yang sudah meratap-ratap tanpa daya, menyiram bensin dan membakarnya selagi napasnya masih tersengal, lantas pergi meninggalkan tubuhnya yang gosong sekarat? Barangkali ini adalah laku paling biadab terhadap kaum minoritas seperti Mira.
Hukum di aspal jalan bekerja. Orang dipaksa bertarung dengan sesama jelata. Orang merasa berhak menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Berbagai instrumen hukum dibuat untuk melindungi warga tapi penegakan hanya ala kadarnya. Di lapangan, rakyat disuguhi parade kebencian, memandang rendah dan jijik kepada kelompok liyan. Dalam kasus Mira, polisi menangkap beberapa pelakunya.
Garasi truk di Cilincing menjadi saksi kebiadaban sekelompok orang. Sebaliknya, di seputar kontrakan Mira, solidaritas kemanusiaan bekerja.
Pak Rohmad menghampiri Mira yang terkapar sekarat. Mengurus pemakaman. Manyalatkan dan merapal doa. Ibu Ketua RT mengetuk pintu rumah warga mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya pengobatan Mira. Ia mencarikan ambulans dan mengantar Mira ke rumah sakit. Seorang warga tercekat ketika mengulurkan sarung untuk membungkus separuh tubuh Mira yang telanjang lantaran bajunya terbakar. Mereka mengurus pemakaman meski Mira tak punya kartu identitas. Teman-teman waria menggalang dana solidaritas untuk biaya pengobatan dan pemakaman.
“Kasihan. Ia sudah tua. Tidak ada saudara,” kata Pak Rohmad.
“Mira baik. Tak pernah bikin onar. Ia juga kerap royal, berbagi uang ke anak kecil,” ucap seorang warga.
“Mira itu ngemong. Kalau punya duit, suka belanja ikan. Masak makanan khas Makassar,” tutur teman dekatnya.
Mereka menerima Mira saat yang lain menatap dengan sebelah mata. Berkali-kali saya berucap terima kasih kepada Pak Rohmad. Saya menitip salam hormat kepada Ibu Ketua RT dan seluruh warga yang telah memperlakukan Mira dengan sehormat-hormatnya. Yang mengajarkan kita bagaimana cara menghargai manusia.
____
Lilik HS adalah penulis lepas.