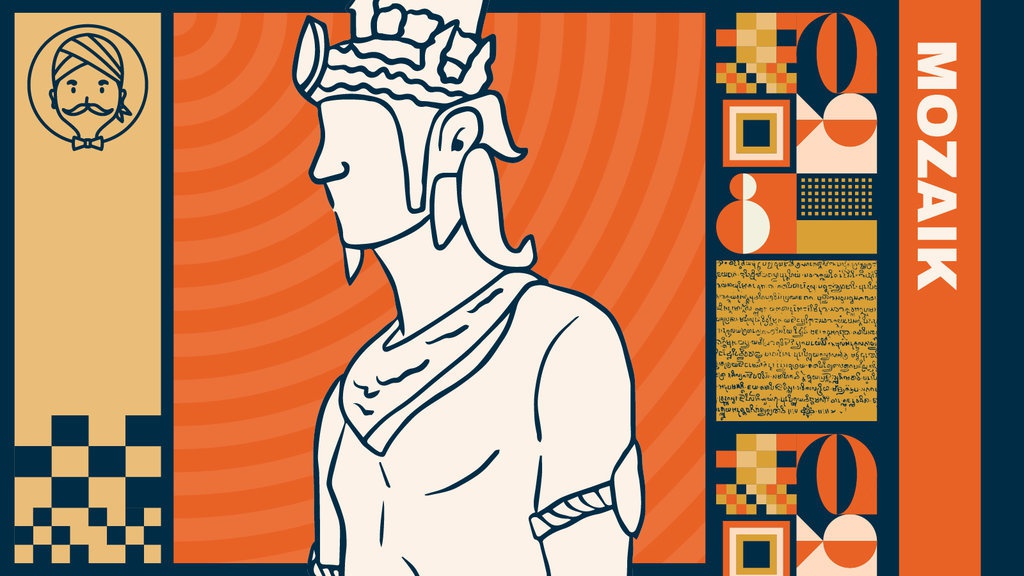tirto.id - Sebagai salah satu monarki paling awal yang berdiri dalam tonggak sejarah Nusantara, eksistensi Sriwijaya diteguhkan kali pertama dalam Prasasti Kedukan Bukit (682 M). Sampai saat ini, prasasti tersebut dianggap berangka tahun paling tua.
Dari sana kita tahu bahwa Sriwijaya yang lahir sebagai wanua (perkampungan), telah bertransformasi menjadi imperium transnasional dalam geopolitik Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Sebagaimana disampaikan Herman Kulke dalam “Śrīvijaya Revisited: Reflections on State Formation of a Southeast Asian Thalassocracy” (2016), Sriwijaya menjadi figur negara yang unik karena menganut sistem desentralisasi. Konsep mandala yang dijalankan dalam formasi negara Sriwijaya bagi Kulke dapat disederhanakan sebagai berikut:
“Pemerintahan pusat kuat dikelilingi oleh cincin pusat-pusat pemerintahan konsentris, di mana semakin panjang jarak dari pemerintahan sentral ke cincin di luarnya maka semakin berkuranglah otoritas sang penguasa pemerintah sentral."
Dapat dibayangkan bahwa legitimasi tentu menjadi aspek yang amat vital bagi berkuasanya seorang datuk atau pemimpin Sriwijaya di suatu negara federasi semacam itu. Wahana utama dalam memaksimalkan keabsahan sang datuk sebagai seorang penguasa terwujudkan dari bagaimana ia mencitrakan diri sebagai pemimpin ideal bagi rakyatnya.
Sejauh yang ditemukan dari berbagai sumber tertulis yang dikeluarkan oleh datuk-datuk Sriwijaya, bisa dijumpai beberapa framing khusus yang coba ditonjolkan dalam teks-teks itu.
Gahar Tapi Royal
Prasasti Kedukan Bukit misalnya, sebagaimana bisa diamati melalui hasil pembacaan dari tulisan G. Coedes dkk. berjudul Kedatuan Śrīwijaya (2014), menonjolkan sifat kekayaan sang datuk melalui penggambaran perjalanan Dapunta Hyang Sri Jayanasa--datuk Sriwijaya paling awal yang diketahui.
Bisa dibayangkan, betapa tajirnya sang datuk ketika harus membawa 20.000 orang untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan modal 200 peti harta. Jika cerita ini sebagai suatu fakta dan bukan metafora belaka, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa untuk logistik ribuan orang itu?
Narasi kekayaan datuk Sriwijaya tidak lepas dari sikap murah hati. Prasasti Talang Tuo yang juga dibaca oleh Coedes dkk., menyinggung soal bagaimana derma Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada semua makhluk melalui pembangunan Taman Sri Ksetra yang hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat wanua Sriwijaya secara cuma-cuma.
Sementara itu, prasasti-prasasti bercorak sapatha atau kutukan--genre paling dominan dari prasasti masa Sriwijaya--menunjukkan bahwa datuk juga orang bertangan besi sekaligus diplomatis.
Prasasti Telaga Batu yang dibaca oleh J.G. de Casparis pada Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D (1956), memperlihatkan sisi legalis seorang datuk Sriwijaya yang tiada pandang bulu menghukum siapa saja yang menjadi non-loyalis, mulai dari anak sang datuk sampai tukang cuci kerajaan.
Beda lagi dengan Prasasti Kota Kapur dari Bangka, sang datuk bahkan berani menghukum Bhumi Jawa (Pulau Jawa) karena tidak tunduk pada sang datuk. Ia kirimkan armada perangnya yang mungkin sekali dipersiapkan di Pulau Bangka.
Pengaruh Buddha Vajrayana
Beberapa aspek profan yang ditunjukkan dari ide kekuasaan Sriwijaya sebelumnya, bisa jadi muncul secara organik dari lokalitas masyarakat Sriwijaya. Gambaran soal pemimpin ideal disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis suatu pemerintahan federasi yang tingkat loyalitasnya dinilai dari ketundukan para bawahan. Di satu sisi metode yang digunakan bisa berupa “give and punish”.
Di sisi lain, Pemerintahan Sriwijaya juga secara konsisten mendekatkan unsur-unsur ajaran Vajrayana dalam kehidupan berpolitik para penguasanya. Implementasinya mulai dari aturan paling mendasar, sampai yang paling spesifik sekali pun.
Dua sumber data yang paling banyak menjelaskan perihal ini, antara lain Prasasti Talang Tuo yang sudah disebut sebelumnya dan Prasasti Ligor A yang ditemukan di Thailand Selatan.
Prasasti Ligor A menurut Coedes dkk. merupakan prasasti Sriwijaya termuda yang pernah ditemukan sampai saat ini, yakni berangka tahun 775 M atau sezaman dengan perintisan Dinasti Syailendra di Pulau Jawa.
Memang prasasti berbahasa Sansekerta ini tidak menyebut siapa nama datuk Sriwijaya yang diacu, namun jelas bahwa isi inskripsi ini tiga perempatnya puji-pujian pada sang penguasa Sriwijaya. Kutipan akan pujian dalam Prasasti Ligor itu berbunyi kira-kira sebagai berikut:
“Lagi pula, [raja] yang merupakan wadah segala kebajikan itu, di dunia ini menjadi [dukungan] orang-orang yang penuh kebajikan secemerlang puncak-puncak Himalaya dan yang sangat termahsyur; sebagaimana pula samudra besar pembasmi keburukan, [yang menjadi wadah] sejuta permata, merupakan [wadah] kaum Naga yang tudung kepalanya dikelilingi kalangan cahaya permata."
Selanjutnya:
"Setelah mereka yang hatinya tadinya dimakan jilatan api kepapaan, datang menemuinya, mereka menyerahkan diri pada kekuasaannya yang luar biasa; sebagaimana pula gajah-gajah, bila matahari sedang terik, mempunyai kebiasaan mencari keteduhan dalam kolam dengan air heningnya yang telah surut... dan yang disepuh serbuk sari bunga seroja. Orang-orang baik budi yang dari segala sudut mendekati raja yang penuh kebajikan dari Manu.”

Pujian puitis di atas seyogyanya kental sekali dengan bumbu doktrin Vajrayana. Pasalnya ungkapan “wadah sejuta intan” itu sebenarnya merujuk pada konsep vajrakaya atau “tubuh intan”, yang dikenal sebagai metafor seseorang dengan pencapaian spiritual esoteris Buddha Vajrayana.
Oleh karena statusnya yang sudah menyerupai boddhisatwa dalam buddhisme itu, perilaku semacam memohon berkahdari para bawahan datuk pada sang datuk sebagaimana disebut pada kutipan di atas adalah hal yang tidak mustahil.
Ia dianggap sebagai jalan keselamatan dari seseorang untuk menuju pembebasan dalam konsep Vajrayana, yaitu konsep kemanunggalan.
Prasasti Talang Tuo di sisi yang lain justru banyak melampirkan doa-doa atau mungkin pengharapan yang dipanjatkan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa kepada rakyatnya. Sekilas beberapa doa ini bisa ditafsir sebagai bentuk aktualisasi dari konsep-konsep manusia paripurna yang sebenarnya melekat pada diri sang datuk.
Salah satu hal yang dapat dijadikan bahan perhatian lebih lanjut adalah penyebutan doa agar semua orang terlahir sebagai laki-laki. Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha (2017) mengasosiasikan doa yang eksentrik ini dengan tradisi Boddhicaryyaavatara dalam aliran esoterisme Buddhis.
Dalam tradisi berpikir ini, seseorang baru bisa masuk ke jenjang boddhisatwa hanya apabila ia terlahir sebagai laki-laki--perempuan secara ekstrem dianggap terlahir dengan karma tidak baik di masa lalu.
Hal ini bisa memunculkan suatu jawaban atau pertanyaan, apakah ini aspek yang membuat datuk-datuk di Sriwijaya semuanya laki-laki?
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id