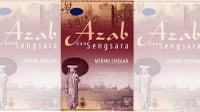tirto.id - Memilih kata atau frasa dalam berita bukan hanya tentang ketepatan makna yang mewakili informasi, melainkan juga soal mendidik masyarakat. Bagi Masmimar Mangiang, memilih kata yang mengandung rasa rendah diri merupakan hal yang tidak sehat untuk pendidikan publik dan merugikan cara berpikir khalayak luas.
Pada esainya, “Dinamika Bahasa Media Massa” dalam Bahasa Media yang Mencerdaskan (2015), Masmimar mencontohkan gejala rendah diri dalam berbahasa pada berita kampanye produk buatan Indonesia. Ia melihat wartawan sering menulis bahwa mutu produk buatan Indonesia tidak kalah dengan produk negeri lain. Menurutnya, frasa tidak kalah tersebut mengingatkan khalayak bahwa mutu itu tidak sama.
Dalam esai yang sama, Masmimar mencontohkan kasus lain yang mengandung rasa rendah diri dalam berbahasa, yaitu penggunaan kata berhasil dalam judul “PSSI Berhasil Menahan Muangthai Seri 1-1”. Baginya, judul berita itu menunjukkan rasa tidak percaya diri kepada Indonesia, perasaan tidak akan dapat mengimbangi Thailand, apalagi menang. Maka, ketika Indonesia seri melawan Thailand, wartawan itu menulis kata berhasil hanya untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak kalah.
Di dunia pers Indonesia, Masmimar memang dikenal sebagai pakar bahasa jurnalistik yang jeli. Ia hampir selalu menemukan kesalahan berbahasa dalam tiap berita yang ia baca. Ia kemudian menulis catatan tentang kesalahan berbahasa yang ia temukan tersebut. Sebagian besar tulisan itu ia terbitkan di akun Facebook-nya, sebagian lagi terbit di blog Patahtumbuh.com, selebihnya terbit sebagai makalah dalam seminar atau diskusi bahasa jurnalistik, dan bahan ajar di kampus serta berbagai pelatihan bahasa jurnalistik.
Dari banyak kesalahan berbahasa yang disorot Masmimar, saya memilih beberapa kasus yang memperlihatkan kejelian Masmimar dalam melihat kesalahan itu. Jika bukan diamati oleh orang yang jeli, kesalahan tersebut barangkali tidak tampak.
Hal itu misalnya terdapat dalam kalimat Pemudik di stasiun nampak riuh melihat kehadiran Anies (“Tiup Peluit, Anies Lepas Pemudik di Stasiun Senen”, Kompas.com, 23 Juni 2017). Menurutnya dalam tulisan “Memoles Berita” (Patahtumbuh.com, 24 Juni 2017), tidak dapat disebut pemudik di stasiun nampak riuh karena yang riuh bukan manusia, melainkan suasana. Riuh adalah kata yang menunjukkan keadaan (tentang suara/bunyi). Maka, riuh tidak tampak, tetapi terdengar. Karena itu, Ia membuang kata nampak yang terdapat pada kalimat sebelumnya dan memperbaiki kalimat itu menjadi Suasana di stasiun jadi riuh ketika para pemudik melihat kehadiran Anies.
Bagi wartawan yang berprinsip “asalkan orang paham” dalam berbahasa, kalimat pemudik di stasiun nampak riuh bukanlah masalah karena merasa pesannya sudah sampai kepada publik. Namun, bagi pengamat bahasa jurnalistik seperti Masmimar, hal itu mengandung masalah sebab kata riuh digunakan sebagai kata sifat untuk menjelaskan kata pemudik. Padahal, yang dijelaskan oleh riuh bukanlah orang, melainkan suasana atau suara dari banyak orang.
Contoh lain kejelian Masmimar dalam melihat penggunaan bahasa di media dapat dilihat ketika ia menyorot penggunaan frasa batal digunakan dalam judul berita “13 Kilometer Jalur Tol Trans-Sumatera di Lampung Batal Digunakan” (Kompas.com, 16 Juni 2017). Dalam berita itu, Kapolda Lampung, Irjen Sudjarno, menegaskan bahwa jalan tol trans-Sumatera sepanjang 13 kilometer yang berada di Provinsi Lampung belum bisa difungsikan. Kompas.com menafsirkan belum bisa difungsikan sebagai ‘batal digunakan’ sebagaimana yang terdapat dalam judul berita.
Dalam tulisan “Belum Bisa Difungsikan dan Batal Digunakan” (Facebook, 16 Juni 2017), Masmimar mengatakan bahwa belum bisa difungsikan tidak sama artinya dengan batal digunakan. Menurutnya, belum mengandung pengertian ‘sedang menunggu waktu untuk mulai/sudah’, sedangkan batal membawa pengertian ‘tak akan ada atau tak akan terjadi dalam waktu yang tak terhingga’. Lain halnya kalau di belakang kata batal disebutkan batas waktunya.
Masmimar juga menyoroti pemakaian kata yang tidak perlu ditulis dalam berita, seperti pemakaian kata tampak, misalnya dalam kalimat SBY tampak mengenakan kemeja koko putih dan peci hitam. Dalam tulisan “Tampak yang Tampaknya Tak Perlu” (Patahtumbuh.com, 15 Januari 2015), ia mengatakan bahwa kata tampak pada kalimat itu tidak berfungsi sehingga terjadilah pemborosan kata. Menurutnya, dengan menulis kata tampak, wartawan seakan-akan khawatir bahwa pembaca menganggap ia tak punya mata.
Dalam tulisannya, “Apanya yang Jadi Resmi?” (Facebook, 13 Maret 2017), Masmimar menegaskan kepada wartawan untuk memahami diksi, baik makna maupun pemakaiannya, sebab bahasa merupakan alat untuk menyampaikan fakta dan gagasan. Ia mewanti-wanti bahwa jika wartawan tidak memahami diksi, hasil transformasi fakta maupun gagasan menjadi bahasa bisa keliru. Dampak lainnya ialah melahirkan bahasa yang tidak logis.
Masmimar mencontohkan kasus seperti itu pada pemakaian kata resmi dalam judul berita “17 Duta Besar Resmi Dilantik Presiden Jokowi” (Kompas.com, 13 Maret 2017) dan paragraf pertama berita itu, Presiden Joko Widodo resmi melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara-negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang.
Menurutnya, pemakaian kata resmi di sana keliru sebab yang resmi bukan dilantik atau melantik. Ia menjelaskan bahwa melantik/dilantik adalah proses atau upacara peresmian, yang membuat orang-orang itu sah menjadi duta besar. Jadi, orang-orang itu resmi/sah menjadi duta besar setelah dilantik presiden.
Itulah pentingnya bagi wartawan untuk melihat kamus. Kamus berisi kelas kata, arti kata, dan contoh penggunaan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, resmi merupakan kata sifat. Dalam konteks berita itu, resmi berarti ‘sah (dari pemerintah atau dari yang berwajib); ditetapkan (diumumkan, disahkan) oleh pemerintah atau instansi yang bersangkutan’. Jika ditulis 17duta besar resmi dilantik, kalimat itu menjadi rancu sebab artinya ’17 duta besar sah dilantik’. Padahal, yang sah bukan dilantik, melainkan 17 duta besar. Bisa juga ditulis 17 orang resmi menjadi duta besar atau 17 duta besar dilantik secara resmi.
Masmimar juga memperhatikan logika bahasa dalam kalimat. Dalam tulisan “Memoles Berita”, ia menyoroti kalimat yang tidak logis, yaitu Saat turun dari kereta, Anies kemudian menuju lokomotif dan terlihat berbincang dengan masinis yang akan membawa pemudik ke Jawa Timur. Ia menilai kalimat itu aneh sebab bagaimana mungkin “kemudian menuju ...” pada “saat turun dari kereta”. Masmimar benar. Menurut KBBI, saat berarti ‘waktu (yang pendek sekali)’. Anies tidak mungkin melakukan dua kegiatan, yaitu turun dari kereta dan menuju lokomotif, dalam saat bersamaan. Anies harus turun dulu dari kereta, barulah dapat menuju lokomotif.
Karena itu, Masmimar menyarankan agar kalimat itu berbunyi Setelah turun dari kereta, Anies menuju lokomotif dan berbincang dengan masinis yang akan membawa pemudik ke Jawa Timur. Pilihan lainnya, kata Masmimar, ialah memperbaiki kalimat itu menjadi Anies turun dari kereta, kemudian menuju lokomotif dan berbincang dengan masinis yang akan membawa pemudik ke Jawa Timur.

Mungkin karena kepekaan nalarnya akan bahasa, Masmimar dipercayai menjadi ahli bahasa dalam persidangan perkara gugatan Tomy Winata terhadap Goenawan Mohamad dan Koran Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 26 Februari 2004. Sebagai informasi, Tomy menganggap pemuatan pernyataan Goenawan di Koran Tempo (12 dan 13 Maret 2003) sebagai penghinaan dan pencemaran nama baiknya.
Dalam berita “Goenawan Mohamad Tidak Cemarkan Nama Tomy Winata” (Tempo.co, 26 Februari 2004) disebutkan bahwa Tomy mempersoalkan kalimat Goenawan: Jangan sampai Republik Indonesia jatuh ke tangan preman, juga ke tangan Tomy Winata. Goenawan mengatakan itu sehubungan dengan aksi penyerangan di kantor majalah Tempo. Tomy membantah keterlibatannya dalam penyerangan itu.
Menurut Masmimar, pernyataan Goenawan itu sama sekali tak bermakna bahwa Tomy adalah preman. Ia berpendapat bahwa sesuai dengan strukturnya, kalimat itu tidak menyamakan Tomy dengan preman. Menurutnya, kata juga dalam pernyataan Goenawan adalah konjungsi yang memberikan fungsi alternatif. Ia mencontohkannya dengan kalimat Saya jualan parfum, juga jualan bensin. Ia mengatakan bawa parfum dan bensin merupakan kata yang sama sekali berbeda.
“Kedudukan mereka setara, sebagai unsur kata, namun, maknanya jelas berbeda,” katanya.
Oleh karenanya, kata Masmimar, pernyataan Goenawan juga tidak memberikan makna buruk terhadap Tomy karena antara preman dan Tomy adalah unsur yang terpisah. Ia menafsirkan pernyataan Goenawan itu sebagai penolakan agar Indonesia tidak dikuasai preman maupun Tomy. Namun, penolakan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan yang bermaksud mencela Tomy.
Kepiawaian Masmimar akan bahasa jurnalistik tentu ia peroleh dari pengalaman panjangnya bekerja di media massa sebagai wartawan, juga dari pendidikan jurnalistik yang ia ikuti. Dikutip dari 121 Wartawan Hebat dari Ranah Minang dan Sejumlah Jubir Rumah Bagonjong (2018) suntingan Hasril Chaniago, Masmimar bekerja di media massa sejak kuliah.
Ia menjadi wartawan harian KAMI (1971—1972), harian Pedoman (hingga koran itu dibredel pada 1974), dan anggota staf redaksi “Siaran Pemuda” (kerja sama Radio ARH dengan LP3ES dan Friederich Naumann Stiftung, Jerman). Pada 1976 Masmimar mengikuti pendidikan jurnalistik di International Institute for Journalism di Berlin, Jerman.
Sepulang dari Jerman, ia menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Prisma (1977—1982), Redaktur Pelaksana majalah berita mingguan Fokus (1982—1983), anggota Sidang Redaksi majalah Tempo (1984), Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Prisma (1985—1989), Senior Staff for Public Relations PT Indocement (1989—1990), Redaktur Pelaksana (1991—1993) dan Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Neraca (1993—2005). Selain itu, ia menjadi pengajar di Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia sejak 1980 dan Lembaga Pers Dr. Soetomo sejak 1989.
Masmimar lahir di Nagari Limbanang, Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, pada 10 September 1949 dan meninggal di Jakarta pada 29 Juni 2020. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia jurnalistik Indonesia. Sulit mencari pengamat bahasa jurnalistik yang sepeka dan sejeli ia. Karena itu, gagasan-gagasannya tentang bahasa jurnalistik perlu disebarkan kepada pubik, khususnya kalangan media massa.
Sayangnya, Masmimar tidak meninggalkan satu buku pun tentang bahasa jurnalistik. Jauh sebelum meninggal, ia memang menyusun sebuah buku tentang bahasa jurnalistik, sebagaimana yang ia ceritakan kepada saya melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga ia wafat, tidak ada kabar tentang buku itu.
Editor: Nuran Wibisono