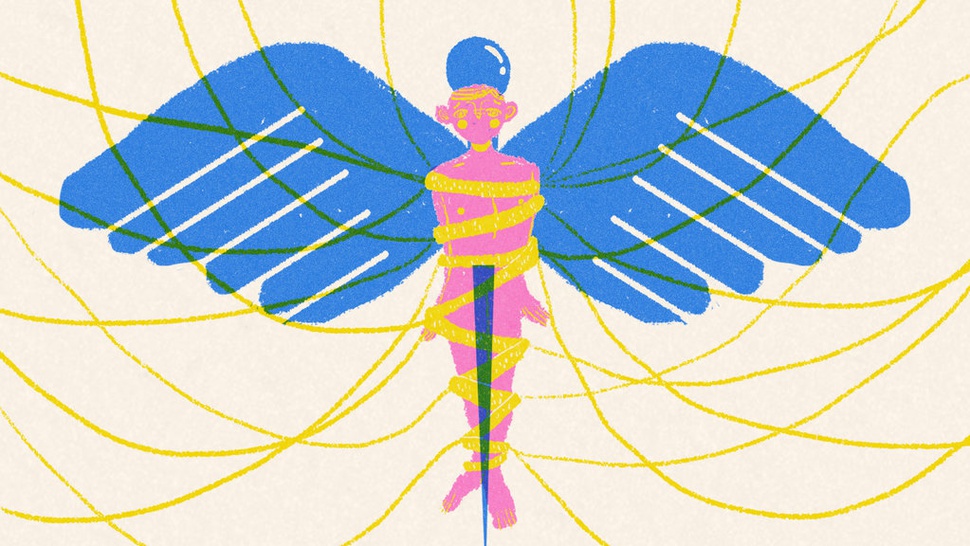tirto.id - Tony Briffa—bukan nama sebenarnya—tampak sehat dan bugar saat kami bertemu di Plaza Atrium, Jakarta Pusat, Ahad pertama Februari kemarin. Ia sama sekali tak tampak seperti orang yang baru dua hari keluar dari rumah sakit karena operasi besar.
“Udah mendingan?”
“Udah aman, paling masih nyeri-nyeri dikit,” jawabnya.
Empat hari sebelum pertemuan kami, Tony melakukan mastektomi—operasi pengangkatan payudara. Selain karena masalah obesitas yang membuat pernapasannya terganggu, operasi itu memang dilakukan Tony sebagai bagian proses transisi—ia diidentifikasi sebagai perempuan saat lahir tapi merasa diri sebenarnya laki-laki.
Namun, Tony bukan transgender. Ia lahir sebagai interseks—sebutan untuk mereka yang lahir dengan ciri fisik dan kondisi kesehatan yang lebih bervariasi dari apa yang biasa disebut perempuan atau laki-laki. Media di Indonesia sering menyebutnya "kelamin ganda," tapi istilah ini ofensif dan salah kaprah.
“Kalau emang kelamin ganda, berarti punya dua-dua kelamin binary yang utuh. Sementara interseks itu sangat variatif bentuknya,” ungkap Tony.
Ia benar. Bentuk interseks memang tak selalu sama.
Sampai sekarang dunia medis mengenal ada 30 hingga 40 variasi dari interseks. Kondisi Tony disebut PAIS alias "Partial Androgen Insensitivity Syndrome." Sebagian selnya tidak merespons androgen yang diproduksi tubuh, yang akhirnya mengganggu perkembangan maskulinisasi genital pria. Dan ia bukan keadaan langka. PAIS terjadi pada 1 dari 130 ribu kelahiran.
Populasi interseks sebanyak 1,7 persen populasi manusia atau setara populasi orang-orang yang lahir dengan rambut merah. Prevalensinya 1 per 2.000 bayi. Jika penduduk dunia digenapkan 7 miliar jiwa, artinya ada 140 juta orang dengan interseks. Jumlah ini lebih besar dari 25 kali jumlah penduduk Singapura. Karena itu, interseks bukanlah kondisi yang langka.
Namun, dunia gender biner—yang meyakini hanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan—menciptakan situasi yang sulit bagi mereka.
“Saya lahir dengan vagina, tapi tidak memiliki rahim dan ovarium. Secara utuh punya sperma, dan bisa menghamili karena tubuh saya memproduksi testosteron,” kata Tony.
Namun, karena waktu lahir vaginanya yang lebih terlihat, dokter mengidentifikasi Tony sebagai perempuan. Atas informasi itu, orangtua Tony membesarkannya sebagai perempuan. Mereka juga memutuskan untuk memutilasi penis Tony berdasarkan saran dokter.
“Kalau sunat itu cuma dirobek. Kalau ini dimutilasi—dipotong,” ujar Tony.
Hal demikian biasa dilakukan dokter dan orangtua yang punya anak seperti Tony karena terbatasnya pengetahuan.
Menurut Kyle Knight, peneliti dari Human Rights Watch, praktik menyarankan anak-anak interseks menjadi salah satu gender biner biasa dilakukan oleh para dokter kepada orangtua, dengan alasan-alasan yang “tak pernah disokong dalam literatur medis mana pun,” tambah Kyle. Misalnya, menakuti-nakuti orangtua bahwa anak mereka akan di-bully jika tidak melakukan operasi.
“Mereka adalah anak-anak yang sehat (sebelum operasi). Mereka berbeda, dan itu mungkin menakutkan bagi orangtua. Namun, solusinya adalah memberikan dukungan dan informasi yang akurat, bukan justru menyebarkan rasa takut atas perbedaan dan mengusulkan operasi kosmetik sebagai sesuatu yang disebut solusi,” tambahnya.
Selain itu, operasi-operasi sepihak bisa berdampak bahaya bagi perkembangan fungsi seksual seorang interseks.
Tony belum merasakan dampak yang aneh hingga usianya sekarang, 26 tahun. Namun, tetap saja ia menyayangkan dan sekaligus marah atas keputusan orangtuanya.
Menurutnya, mereka harusnya bisa lebih sabar dan menunggu ia dewasa. Tony juga paham pengetahuan tentang Interseks memang sangat terbatas.
Ia merasa beda sejak kecil. Lebih senang bermain dengan teman laki-laki, misalnya. Tapi ia dibesarkan sebagai perempuan yang otomatis didikte batasan-batasan. Perbedaan itu makin terasa ketika memasuki masa pubertas.
Tony remaja tak mengalami menstruasi seperti anak perempuan lain. Orangtuanya mulai teringat riwayat medis Tony tapi “mereka enggak terima,” katanya.
Ia diberi jamu dan obat alternatif lain yang dianggap bisa "menyembuhkan" masalah menstruasinya—yang tentu saja tak mempan.
Tony tetap merasa berbeda tapi tak bisa membantah orangtua. Keluarganya religius dan tak punya budaya diskusi.
“Tipikal orangtua Indonesia-lah. Anak harus nurut aja dengan orangtua. Enggak ada ruang untuk tanya-jawab,” tambahnya.
Tekanan ini membuat Tony yang semula bersikap terbuka dan periang jadi lebih tertutup. “Di situ saya beneran ngerasa sendirian. Bener-bener ngerasa gue tuh kayak Alien,” tutur Tony.
Ia merasa tak ada yang mengerti apa yang ia rasakan, dan tak ada gunanya berdiskusi. Tekanan itu makin parah ketika ia mulai dilabeli oleh orang-orang terdekat sebagai lesbian karena perilakunya dianggap lebih maskulin dari "karakter perempuan semestinya."
Namun, Tony tak merasa sebagai lesbian sebab di dalam dirinya ia sadar ia laki-laki.
Baru ketika SMA, Tony pertama kali tahu istilah interseks. Sejak itu ia mengisi diri dan mempelajari istilah tersebut. Saat kuliah, ketika mendapatkan informasi lebih mudah dan teman-temannya punya pikiran lebih terbuka, Tony bersemangat lagi.
Ia bergabung dengan forum diskusi LGBT di internet. “Di sana ada section khusus untuk interseks,” katanya.
Ia mendapatkan banyak informasi dari terapi hormon sampai ilmu gender lain. Ia juga mulai paham hak-haknya dan ikut berorganisasi. Sejak itu ia lebih bisa menerima dirinya dan tidak stres lagi.

Perjalanan Panjang Transisi
Sejak kecil Tony memang ingin melakukan transisi. Ia selalu merasa lebih laki-laki dibanding perempuan—jenis kelamin yang dipilihkan orangtuanya. Dalam dunia medis hal ini dimungkinkan. Namun, prosesnya sulit dan harganya mahal.
Sebelum akhirnya menjalani operasi mastektomi di Jakarta, Tony lebih dulu menjalani sejumlah proses yang melelahkan. Ia sempat pindah tiga kali rumah sakit sebelum akhirnya menemukan yang cocok.
Prosesnya kurang lebih sama: sebelum bertemu dokter bedah, ia harus mengantongi surat keterangan medis yang menyebut dirinya interseks. Ia juga harus melakukan pengecekan kesehatan lengkap lain--tentu saja memakan biaya.
Sebelum akhirnya menemukan rumah sakit yang cocok, Tony semula mengincar klinik kecantikan lebih dulu. “Kalau untuk payudara laki-laki yang membesar itu, kan, ginekomastia. Jadi ketika saya datang, saya tanya bisa enggak untuk handle case ginekomastia. Ketika udah proses, baru saya dikasih informasi, saya interseks dan saya perlu operasi."
Namun, rupanya, kasus Tony tak sesederhana itu. Payudara yang membesar memang perlu diamputasi, dan ada beberapa jaringan otot yang mesti diangkat karena masalah obesitas. Sementara ginekomastia hanya untuk menyedot lemak.
“Ketika saya datangi klinik kecantikan, mereka enggak bisa karena cuma bisa sedot lemak doang,” tambahnya.
Tony juga sempat ke sana-kemari mencari tempat operasi yang bagus. Ia bolak-balik bertanya ke dokter di beberapa kota. Ia bahkan sempat mempertimbangkan ke Thailand. Namun, untuk menghemat waktu, tenaga dan uang, pilihannya jatuh ke rumah sakit di Jakarta.
“Kalau misalnya dibilang recommended, ya recommended, sih. Tapi dari harga, jauh banget. Jauh banget. Kalau ambil di Thailand, sudah bisa untuk pergi-pulang. Kalau di sini cuma untuk mastektomi doang. Kemarin saya syok juga lihat bill-nya,” kata Tony.
Toh, perjalanan Tony belum selesai. Ia masih bermimpi untuk melakukan operasi phalloplasty—perombakan kelamin perempuan menjadi laki-laki—yang harganya lebih mahal dan prosesnya lebih sulit.
Tak cuma itu, Tony masih harus melewati tahap legal; artinya harus merogoh kocek, tenaga, dan waktu untuk mengganti identitas gender. Hukum Indonesia memang memfasilitasi hal ini tapi prosesnya tidak semudah kedengarannya.
Tony harus menghadapi petugas yang homofobik, sebagaimana dialami para interseks atau transgender yang pernah mengalami proses ini. “Hakim kasih dalil-dalil dan nasihat ini-itulah,” katanya sambil tertawa.
Ia bahkan sempat dimintai uang lebih “bila urusannya di pengadilan mau cepat diselesaikan.”
Semua tantangan ini dihadapi Tony dengan tenang dan sabar. Ia sadar ada yang salah dari cara dunia gender biner memperlakukan interseks. Dari perlakukan medis yang semena-mena sejak lahir, diskriminasi sosial, hingga perlakuan negara yang masih belum memprioritaskan minoritas seksual.
Namun, Tony tak ambil pusing. Pada saat yang sama, ia sadar ia manusia yang bebas dan mandiri terutama untuk mewujudkan mimpinya.
Salah satu mimpi itu adalah berbagi kisahnya kepada orang dengan interseks lain di Indonesia—yang nyata tapi terpaksa dibikin tak kasatmata karena tekanan sosial, agama, dan politik.
======
Redaksi:
Nyaris setahun setelah naskah ini terbit, Tony kembali menghubungi redaksi Tirto, meminta untuk menyamarkan namanya karena menerima perundungan. Pertengahan tahun lalu, ia sampai dipecat dari pekerjaannya di kantor yang semula menerimanya dengan baik. Tony paham risiko yang dihadapinya ketika wawancara ini dibuat, tapi karena pertimbangan dari keluarga dan kemungkinan perundungan yang ia terima, Tony memutuskan untuk merahasiakan identitasnya.
Menghormati itu, redaksi mengganti namanya sebagai Tony Briffa, wali kota interseks pertama yang terbuka tentang identitasnya di Australia.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam