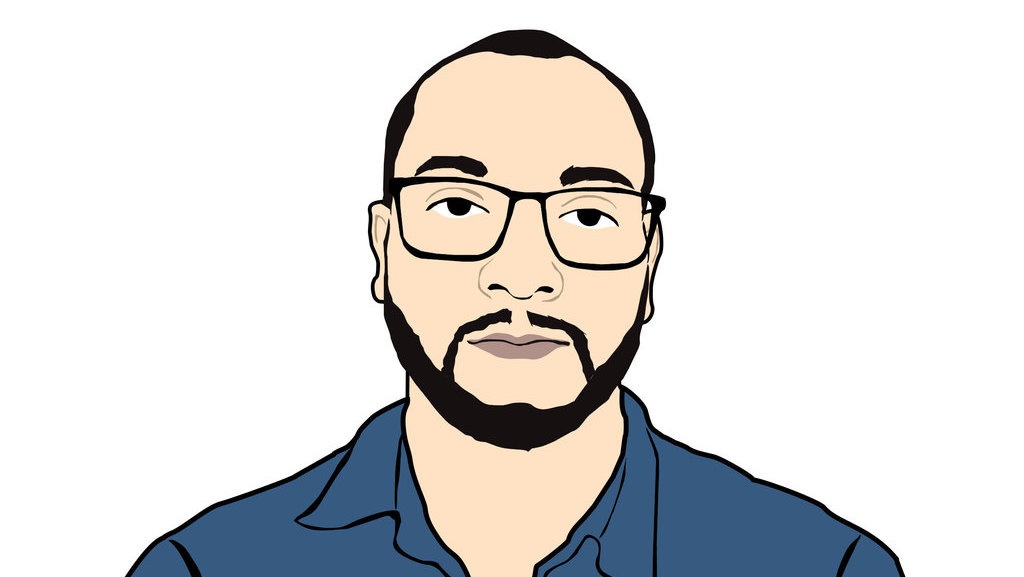tirto.id - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Kate Laurell Ardern (38) memberikan pidato penghormatan terhadap para korban penembakan massal Masjid Al Noor Masjid Al Noor Christchurch. Dalam pidato itu dia mengenakan hijab dan mengucapkan salam.
Jacinda dan solidaritas Selandia Baru berhasil mengambil simpati dunia, termasuk rakyat Indonesia.
Namun, beberapa kelompok Muslim di Indonesia malah memaknai solidaritas pasca-tragedi dengan cara yang tidak elok. Saya mendapat pesan via Whatsapp judul “50 orang Mujahid melahirkan 5000 Mualaf”. Ada juga judul “Fajar Baru Islam di Selandia Baru”. Pesan-pesan singkat itu memiliki muatan yang sama, yaitu bagaimana Islam berjaya di Selandia Baru dengan cara sederhana yaitu menjadikan penduduknya mualaf.
Menerjemahkan solidaritas di Selandia Baru dengan cara seperti itu sangatlah murahan dan mengkhianati korban dengan memanipulasi tragedi Christchurch demi syahwat “Islamisasi”.
Di sisi lain, seorang teman membagikan cuitan yang menyebut Selandia Baru sebagai contoh solidaritas negara berpenduduk mayoritas Kristen terhadap saudara Muslim. Pernyataan itu agak bermasalah. Berdasarkan survei terakhir 41% warga Selandia Baru menyebut diri mereka tidak beragama atau ateis. Jacinda Arden, yang besar dari keluarga Mormon, mengklaim dirinya sebagai Agnostik. Selandia Baru mengikuti pola beberapa negara yang tak lagi menjadikan agama faktor penting dari kehidupan sosial.
Potret usaha untuk memasukkan toleransi dan solidaritas di Selandia Baru dalam kacamata agama menggambarkan masalah yang lebih besar dari percakapan toleransi di Indonesia, Indonesia tidak mengenal toleransi beragama yang dilakukan oleh orang tidak beragama. Ateisme dalam kacamata Islam konservatif di Indonesia lebih buruk ketimbang kafir, dan tidak juga mendapat tempat yang baik di dalam Kristen dan Katolik.
Tidak populernya toleransi tanpa agama di Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, dominasi percakapan mengenai toleransi di Indonesia dipegang oleh tokoh dari tiga agama: Islam, Kristen dan Katolik. Mereka mendominasi percakapan mengenai toleransi, dominasi ini memungkinkan mereka untuk mendesain platform toleransi dari moralitas dan tradisi keagamaan masing-masing. Dengan kata lain, toleransi di Indonesia berakar dari klaim teologis Islam, Kristen dan Katolik. Kita menemukan toleransi dibicarakan di ruang publik dalam kaidah Al-Quran, Hadist, adab Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, Alkitab dan ajaran moralitas kasih Kristus—seakan-akan segala hal yang baik dan toleran adalah hak prerogatif agama monoteis.
Dominasi ini kemudian mengakar kuat di dalam ideologi nasional Indonesia yaitu Pancasila. Dari sini kita masuk ke masalah kedua, yaitu bagaimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya memuat agenda agama-agama monoteis yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan politik agama dan moralitas di Indonesia. Ini terlihat jelas dari perdebatan panjang apakah aliran kebatinan dianggap agama atau tidak, ini karena aliran kebatinan tidak memiliki konsep Tuhan yang tunggal, kerasulan dan kitab suci—kriteria yang disepakati oleh agama-agama monoteis.
Kebijakan negara kemudian mendukung dan mempromosikan masuknya agama sebagai faktor tunggal dari toleransi. Situasi ini didukung dengan konflik berdarah di mana Islam, Kristen dan katolik bahu-membahu bersama Orde Baru menghajar komunisme pada tahun 1965. Sejak itu, komunisme selalu dicitrakan ateis, anti-agama, dan tidak bermoral.
Sepuluh hari setelah tragedi, media arus utama di Indonesia memberitakan solidaritas Selandia Baru tanpa menyinggung pandangan atau pilihan Selandia Baru terhadap agama. Pilihan etis ini tepat. Namun, media di Indonesia juga punya rekam jejak panjang menceritakan seorang Muslim taat yang bertoleransi terhadap tetangganya yang berbeda agama, budaya Pela Gandong antara Islam dan Kristen di Maluku, atau toleransi umat Katolik di NTT, dan seterusnya yang menempatkan aktor toleran sebagai aktor religius. Mungkin ada faktor lain, yaitu percakapan publik di Indonesia memang tidak terbiasa dengan toleransi dari orang yang tidak beragama.
Toleransi dari tradisi agama bukanlah masalah. Dalam banyak situasi ia menyelamatkan Indonesia dari potensi konflik atau bahkan menyelesaikan konflik. Tetapi agama bukan satu-satunya sumber toleransi, sebagaimana agama juga bukan sumber tunggal intoleransi. Membicarakan toleransi hanya dari tradisi agama membuat kita lupa dengan alternatif toleransi yang lain, baik dari tradisi sekuler maupun kultural. Pertanyaan berikutnya yang perlu diuji adalah, apakah citra mulia warga Selandia Baru akan berkurang di mata rakyat Indonesia jika kita tahu mereka ateis?
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id