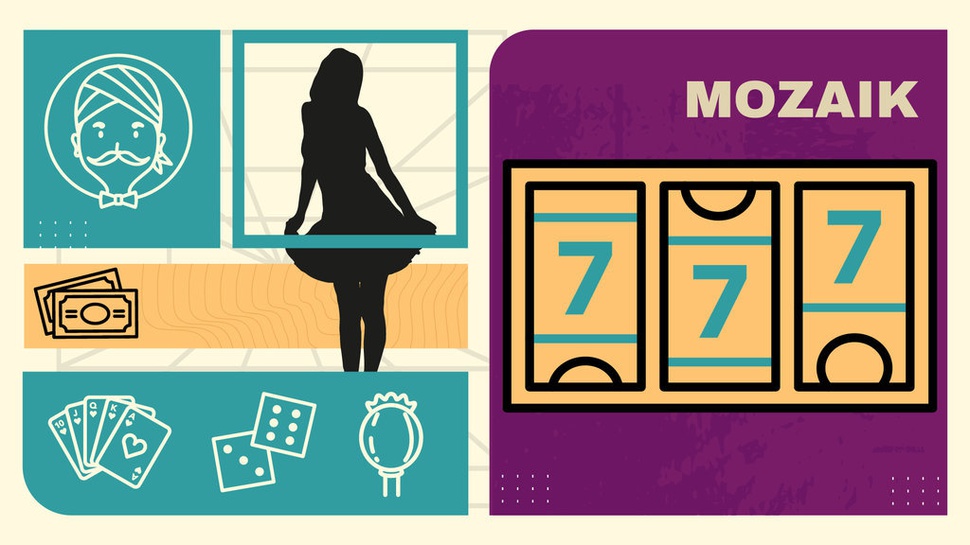tirto.id - Setelah Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker, menerbitkan novel spektakulernya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860, terjadi perubahan tata pengelolaan koloni di Hindia Belanda.
Kritik sang novelis terhadap kurangnya pengawasan kolonial yang akhirnya memungkinkan kesewenang-wenangan eksekutor pemerintahan lokal, terutama bupati, telah—dalam kata-kata politisi Wolter Robert van Hoëvell di parlemen rendah Belanda— “mengirimkan udara yang menggigil ke seluruh negeri." Kritik Multatuli menyebabkan monopoli negara dalam pengelolaan koloni berakhir.
Pada tahun 1870, kebijakan baru liberalisasi ekonomi Hindia dijalankan. Pemodal dan perusahaan swasta, baik Belanda maupun asing, memiliki kesempatan yang luas untuk turut “mengelola” Hindia. Pada periode ini, yang dianggap sebagai masalah cukup jelas: kejatuhan taraf hidup penduduk Jawa karena cultuurstelsel (dijuluki tanam paksa).
Keterlibatan swasta diharap mampu menumbuhkan inspirasi baru untuk mengembangkan hidup penduduk bumiputra ke arah yang lebih baik. Tentu saja, studi-studi sejarah membuktikan sebaliknya.
Konsekuensi pertama yang timbul dari liberalisasi ekonomi 1870 adalah meluasnya penjelajahan dan eksploitasi dari pihak swasta ke luar Jawa. Untuk kasus Sumatra, penjelajahan ini memang sudah terjadi agak lebih awal.
Dari tulisan D.G. Stibbe dalam Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1927:22), tampak bahwa penanaman tembakau pertama di Sumatra Timur dilakukan pada 1864. Jika mengacu pada tahun ini, artinya pengembangan tanaman tembakau secara profesional untuk kepentingan perkebunan pertama kali dilakukan oleh Jacob Nienhuys.
Namun, Yasmis dalam “Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli” (2007:3) menjelaskan bahwa penanaman lebih awal sempat dilakukan oleh seorang Arab, Syaid Abdullah Ibn Umar Bilsagih, pada tahun 1863 di atas tanah milik Sultan Deli.
Percobaan awal Bilsagih itulah yang akhirnya mengundang perhatian dari beberapa pengusaha Belanda, termasuk Firma J.F. van Leeuwen yang mengirim Nienhuys ke Deli.
Tanah-Tanah Kosong
Dari berbagai literatur tentang perkebunan tembakau di Sumatera Timur, Ann Laura Stoler dalam “Plantation Politics and Protest on Sumatra’s East Coast” (1986:124–125) menguak dengan cermat bahwa perkebunan-perkebunan itu didirikan di atas banyak tanah kosong tak berpenghuni.
Simpulan ini muncul karena status tanah tersebut memang dinyatakan demikian oleh Sultan Deli. Namun demikian, wilayah operasi perkebunan tembakau rupanya mencakup tanah dengan dua jenis kepemilikan yang berbeda.
Di dataran rendah yang lebih selatan, tanah-tanahnya ada di bawah kekuasaan Sultan Deli. Namun, dataran yang lebih tinggi di utara banyak dimiliki oleh masyarakat Batak yang memegang hak adat secara pribadi atas tanah-tanahnya.
Penduduk Batak yang tidak berada di bawah naungan Sultan Deli tidak mengenal konsep tanah negara milik sultan atau penguasa. Bagi orang Batak yang agraris, tanah adalah properti pribadi. Dan, seperti diungkap Sita van Bemmelen dalam kasus orang Batak Toba lewat Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra (2018), tanah adalah instrumen penting yang dipertimbangkan dalam berbagai tindakan sosial masyarakat.
Oleh sebab itu, penggunaan tanah-tanah Batak perlu melibatkan masyarakat Batak. Sebagai hasilnya, pekerja-pekerja pertama di perkebunan-perkebunan tembakau Sumatra Timur diambil dari orang-orang Batak dan orang Melayu dari Penang.
Sayangnya, jumlah mereka tidak mencukupi. Merekrut orang Melayu lokal dari Deli bukanlah pilihan. Stibbe (1927) mengungkap bahwa orang-orang ini tidak mau terlibat dalam pekerjaan kasar perkebunan.

Tipu Daya Lowongan Pekerjaan
Jalan keluar yang tersedia adalah mendatangkan pekerja dari luar daerah itu. Selain mengambil dari Jawa, perusahaan-perusahaan Hindia Belanda ini merekrut tenaga kerja dari Tiongkok Selatan. Kebanyakan berasal dari daerah Fujian, berangkat dari kota-kota besar di selatan seperti Guangzhou dan Xiamen.
Rekrutmen pada periode awal dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja swasta di Tiongkok yang menjanjikan kehidupan lebih baik di wilayah selatan (nányáng)—yaitu wilayah Asia Tenggara yang saat itu menjadi negeri-negeri koloni. Maklum, kondisi Tiongkok setelah kekalahan mereka dalam Perang Candu Pertama (1839–42) dan Kedua (1856–60), sangat kacau balau.
Prospek pembangunan masa depan digantungi awan mendung. Kekuasaan Dinasti Qing mengalami degradasi di berbagai sudut. Pergi ke selatan yang dilingkupi mitos kesuksesan terlihat lebih menggiurkan daripada tetap tinggal. Tidak jarang, orang-orang rekrutan ini ditipu.
Awalnya, beberapa dari mereka dijanjikan pekerjaan seperti juru tulis atau pegawai kantor rendahan di Singapura. Namun, mereka berakhir juga di perumahan kuli perkebunan di Deli atau tambang timah di Bangka.
Seiring berjalannya waktu, cara rekrutmen pekerja juga berkembang. Administrator tenaga kerja di pertambangan timah Bangka, C. Lankamp, mengungkap dalam laporannya (Algemene Secretarie Grote Bundel No. 8436, 1930) bahwa selain melalui agen swasta, rekrutmen di Tiongkok sekarang juga melalui laukeh dan sistem klan.
Gregor Benton dalam Chinese Indentured Labour in the Dutch East Indies, 1880-1942: Tin, Tobacco, Timber, and the Penal Sanction (2022) menjelaskan bahwa laukeh adalah sebutan bagi orang Tionghoa yang sudah berada di Sumatra dan diutus kembali ke Tiongkok untuk mencari pekerja baru.
Praktik ini tidak melulu dipakai Hindia Belanda. Inggris juga melakukan cara serupa di Malaya dengan mengirim orang India yang sudah bekerja di Malaya untuk mencari pekerja baru lagi dari India.
Sistem lain yang berkembang dari sini adalah sistem klan. Sederhananya, ada suatu desa atau kampung tertentu di Tiongkok yang menjadi kolam rekrutmen bagi suatu perusahaan. Benton (2022) mengutip pendapat A.F. van Blommestein bahwa hubungan terus-menerus seperti ini pada akhirnya menciptakan ikatan yang lebih kuat dan ketergantungan ekonomi antara desa atau klan pemasok dan perusahaan di Hindia.
Lankamp (1930) berpendapat bahwa ikatan pada pekerja yang direkrut dengan sistem ini lebih kuat. Jelas sekali, pekerja itu tidak lagi memiliki tempat untuk lari dari kontrak yang mengikatnya dan pulang ke kampung halaman.
Kontrak dan Lingkaran Setan
Aspek yang mengikuti praktik pemanggilan tenaga kerja ini adalah adanya kontrak. Peraturan atau ordonansi pertama tentang kontrak antara pekerja atau kuli dan perusahaan dibuat pada tahun 1880. Dari sudut pandang hukum, Ordonansi Kuli 1880 sebenarnya berangkat dari ketidakpastian hukum dan prinsip ketenagakerjaan dalam masyarakat lokal Nusantara.
Wertheim dalam Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change (1959) mengungkapkan bahwa Nusantara “[…] tidak memiliki tradisi kuat tentang pembayaran upah bagi tenaga kerja."
Di satu sisi, pendapat ini mengandung kebenaran. Dalam tradisi kekuasaan agraris Nusantara, tenaga manusia dipandang sebagai pajak kepada penguasa. Oleh sebab itu, Ordinansi Kuli 1880 berusaha memberikan ikatan hukum antara kuli dan perusahaan, serta membuat kuli memahami aturan-aturan apa yang mengikat mereka.
Namun, praktiknya yang melibatkan pembayaran upah di muka menghadirkan masalah yang pelik.
Perusahaan tidak mau pergantian pekerja terjadi dalam waktu singkat. Mereka menghindari rektrutmen baru karena biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendatangkan pekerja sangat mahal. Oleh sebab itu, pekerja yang sudah ada di tempat harus “ditahan” selama mungkin dan dengan berbagai cara.
Untuk melakukan ini, ada dua “tembok” yang dibangun. Pertama, pekerja harus menandatangani kontrak di muka dan menerima pembayaran atas pekerjaan mereka di depan. Dengan demikian, mereka terikat secara hukum untuk menyelesaikan masa kerja.
Hukuman untuk kegagalan menyelesaikan kontrak atau melarikan diri mulai dari hukuman fisik seperti cambuk, hingga kurungan. Sayangnya, kuli sering kali tidak mengerti aturan yang ada di dalam kontrak karena mereka buta huruf.
Pemerintah kolonial sebenarnya mewajibkan perekrut untuk menjelaskan rincian kontrak kepada kuli yang tak dapat membaca, tapi kenyataannya tidak selalu sesuai aturan. Selain itu, pengawasan pemerintah kolonial terhadap praktik ini sangat lemah karena mereka adalah “orang-orang tanpa nama”.
Tidak ada catatan jelas tentang nama mereka. Saat melakukan penelitian bersama Prof. Gregor Benton di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2019 hingga 2020, saya mengalami kesulitan besar untuk menemukan data para pekerja.
Prof. Benton kemudian menerangkan bahwa nama-nama yang kita cari bukanlah nama Tionghoa umum, melainkan kode-kode semacam “A-1” atau “743” sebagai sekadar penanda siapa adalah siapa.
Tembok kedua yang dibangun perusahaan adalah menciptakan sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan ini terdiri dari judi, opium, dan pelacuran.
Setiap musim panen, perusahaan memanggil opera Tionghoa dari Semenanjung Malaya. Secara terus menerus, seperti ditulis Benton (2022), perusahaan dan staf-stafnya memiliki cara untuk memaksa kuli-kuli itu terus bermain judi dan menghisap madat supaya ia berutang atau supaya uangnya habis.
Dengan cara ini, mereka akan terus memiliki kewajiban finansial dan ketergantungan pada perusahaan. Akhirnya, kontrak yang secara aturan maksimal hanya mencakup tiga puluh bulan, dapat diperpanjang lagi dan lagi. []
Penulis: Christopher Reinhart
Editor: Nuran Wibisono