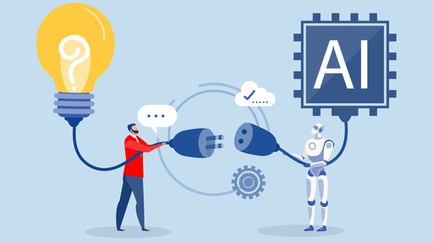tirto.id - Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, punya memori kolektif yang kuat perihal tahun 1997.
Kala itu, rencana pembangunan turbin listrik menyebabkan berlangsungnya kerja bakti paling besar dalam sejarah masyarakat Ciptagelar. Ribuan orang berjalan kaki dari Cicadas ke Cipulus, menempuh jarak sejauh 17 kilometer.
“Para perempuan mengangkut semen, sedangkan laki-lakinya membawa gulungan kabel dan material pembuatan turbin lainnya. Panjang iring-iringan mencapai dua kilometer,” tulis Muhammad Fasha dalam skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia, Model Komunikasi Masyarakat Adat dalam Resolusi Konflik: Studi Etnografi Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar.

Pada 1988, Abah Anom alias Encup Sucipta, pemimpin masyarakat adat Ciptagelar, sebelumnya sudah berusaha menerangi wilayahnya dengan teknologi ala kadarnya.
Memanfaatkan aliran deras yang bersumber dari Gunung Halimun, ia membangun sebuah kincir air. Kincir tersebut dilengkapi bilah-bilah kayu rasamala yang difungsikan sebagai pipa. Di malam hari, upaya itu berhasil menerangi 55 rumah.
Keinginan Abah Anom membuat kampung halamannya terang benderang 1x24 jam membuahkan hasil sembilan tahun kemudian. Lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), bantuan datang dari Pemerintah Jepang.
Pendiri IBEKA Iskandar Budisaroso Kuntoadji ingat betul suasana pada hari bersejarah di Ciptagelar itu.
“Sejak pukul dua dini hari, warga sudah berkumpul di Cipulus, kemudian turun ke Cicadas. Berbilah-bilah bambu disiapkan sebagai tandu buat mengangkut generator. Tiap ujung tandu dipegang oleh enam orang,” ungkap Iskandar kepada Tirto, Selasa (16/4).
Tenaga Mikrohidro Jadi Solusi
IBEKA eksis sejak 1992. Tepat pada usianya yang ke-30, lembaga yang kini dipimpin “wanita listrik” Tri Mumpuni Wiyatno itu tercatat sudah membangun 89 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di antero Indonesia. Sebagian besarnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
“Teknologi mikrohidro cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Operasionalnya juga lebih mudah dipelajari oleh masyarakat,” terang Iskandar.
Iskandar menambahkan, pemanfaatan air sebagai sumber energi sudah dikenal leluhur orang Indonesia. Di Sumatra, misalnya, orang-orang pada abad ke-14 sudah menjadikan air sebagai sumber tenaga kinetik dengan menciptakan alat penumbuk padi.
Akhir tahun 1970-an, Iskandar menyaksikan orang-orang di Cianjur Selatan memanfaatkan air sungai untuk menyalakan lampu, dan itu membuatnya terkagum-kagum.
“Teknologinya benar-benar sederhana. Komponen generatornya dibuat dari dinamo sepeda motor rusak.”
Pada 2002, kiprah IBEKA menarik perhatian banyak orang setelah membangun PLTMH Cinta Mekar di Serang Panjang, Subang. Dalam sejumlah publikasi, PLTMH Cinta Mekar diapresiasi bukan semata karena kemampuannya menghasilkan energi bersih, tapi karena dampaknya bagi masyarakat. Inilah model bisnis dan ekonomi kerakyatan yang ingin terus dikembangkan IBEKA.
“PLTMH Cinta Mekar dikelola oleh Koperasi Mekar Sari. Kepemilikannya dibagi dua dengan investor swasta, masing-masing 50 persen. Listrik yang dihasilkan PLTMH Cinta Mekar sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagian lainnya dijual ke PLN,” papar Iskandar.
Iskandar menambahkan, pendapatan yang diperoleh dari penjualan listrik dikembalikan ke masyarakat, yakni berupa beasiswa dan subsidi kesehatan.
Lebih lanjut, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Badan Riset Nasional, BRIN) Purwanto (2017) menyebut pengelolaan mikrohidro oleh masyarakat melalui koperasi patut dicontoh.
“Persoalan kekurangan dana, kesulitan memperoleh investor, dan peningkatan kapasitas SDM yang selama ini menjadi persoalan klasik berhasil dipecahkan melalui kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta secara saling menguntungkan,” tulis Purwanto dalam studinya.

Sayangnya, ketika Tirto menyambangi kediaman Iskandar dan Tri Mumpuni di bilangan Sagalaherang, Subang, pasangan yang gemar mendatangi desa-desa pelosok itu menyebut saat ini PLTMH Cinta Mekar tidak lagi beroperasi. “PLN menjual listrik lebih murah kepada masyarakat. Jadi, ya sudahlah…”
Biar begitu, Iskandar dan Tri Mumpuni tak patah arang. Kini mereka sedang menggarap proyek di wilayah timur. Bersama anak-anak muda yang tergabung dalam Patriot Energi, IBEKA tengah berencana membangun sebuah PLTMH di Dusun Ausem, Kepulauan Yapen, Papua.
“Di IBEKA, skemanya selalu begitu. Pembangunan PLTMH dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, karena mereka yang punya sumber daya, dan untuk pendanaannya kami yang mencarikan sponsor. Nanti kepemilikannya dibagi dua, milik warga dan milik sponsor atau investor,” pungkas Iskandar.
Tri Mumpuni menambahkan, baginya ini bukan hanya soal ketersediaan listrik. “Tapi demokratisasi energi. Memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal, serta membantu PLN mengurangi konsumsi BBM.”
Tantangan Energi Terbarukan
Pendapat Tri Mumpuni senada dengan temuan Yayasan CERAH Indonesia. Peneliti CERAH, Sartika Nur Shalati, menyebut riset yang dilakukan CERAH di Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada akhir Desember 2023 menunjukkan semacam ironi.
“PLTS atap yang digunakan masyarakat sejak tahun 2000 mampu memberikan penerangan berkelanjutan kepada warga dibandingkan PLTS terpusat yang dibangun oleh Kementerian ESDM, yang usia produksinya hanya bertahan kurang dari setahun,” ungkap Sartika kepada Tirto, awal April 2024.
Berdasarkan temuan itu, Sartika menyebut program Listrik Desa dengan energi terbarukan di bawah komando Kementerian ESDM, justru terasa masih jauh api dari panggangan.
“Jenis pembangkit yang paling banyak dibangun adalah PLTS terpusat yang merupakan proyek Kementerian ESDM melalui program Listrik Desa,” ungkap Sartika. “Sayangnya, beberapa wilayah yang telah dibangun pembangkit justru mengalami kerusakan dan berakhir mangkrak.”
Sartika menilai, ada tujuh alasan mengapa program di atas tidak berjalan sesuai rencana. Pertama, masyarakat hanya dibekali pengetahuan dasar sehingga tidak piawai mengelola sistem pembangkit terpusat. Padahal, sistem pembangkit terpusat seperti PLTS cenderung rumit dan membutuhkan tenaga ahli.
Kedua, pilihan jenis pembangkit dan sumber energi terbarukan diputuskan secara top-down, alih-alih menyesuaikan dengan potensi kawasan. Ketiga, masyarakat tidak dilibatkan secara partisipatif. Mulai dari perumusan rencana, strategi, skema pengelolaan, hingga penyelesaian masalah jika terjadi kendala dan kerusakan sistem pembangkit.
Keempat, minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga tidak ada sinergi dalam pengelolaan pembangkit. Kelima, dalam memilih jenis pembangkit, faktor ketersediaan infrastruktur kurang dipertimbangkan.
Seperti menentukan akses jalan, transportasi dan jaringan telekomunikasi. Padahal hal ini patut dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk memudahkan koordinasi dan perbaikan jika terjadi kerusakan.
Keenam, pemerintah daerah, yang saat ini belum mendapat akses listrik dari PLN, tidak memiliki pengetahuan memadai, baik secara teknis, biaya, maupun sumber daya manusia. Akibatnya, pemerintah daerah belum siap mengelola dan mengoperasikan pembangkit.
Terakhir, PLTS atap belum dijadikan sebagai pilihan untuk penerangan dan mendorong produktivitas masyarakat di desa terpencil. Padahal, ini merupakan potensi yang bisa diandalkan.
Atas persoalan tersebut, Sartika menilai skema pengelolaan pembangkit listrik perlu dilakukan berbasis komunitas, terutama di wilayah terpencil. Untuk mencapai itu, Sartika berpendapat perlu tahapan dan nilai-nilai yang mestinya dipegang pemerintah.
“Mulai dari diversifikasi energi, pelibatan partisipasi masyarakat, terbentuknya kelembagaan yang memiliki pola kerja sistematis untuk mengelola pembangkit terpusat,” terang Sartika.
Selain it diperlukan jalur koordinasi yang jelas, hingga monitoring dan evaluasi berkala dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga desa. Ini guna memastikan operasi pembangkit berjalan sesuai tujuan.
Sartika menyebut riset yang dilakukan CERAH di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Berau, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya tidak mendapat akses listrik dari PLN, sangat terbantu dengan kehadiran PLTS terpusat.
Ia menjelaskan bahwa dengan mengumpulkan iuran Rp 10.000 per bulan, PLTS Teluk Sumbang mampu melistriki 177 Kepala Keluarga dan 10 fasilitas umum.
“Ekonomi warga mulai meningkat seperti aktivitas pasar dan usaha masyarakat juga semakin hidup. Tak hanya itu, kegiatan sosial juga sangat terbantu, seperti mempermudah proses belajar mengajar di sekolah dan menerangi tempat ibadah,” ungkap Sartika.
Jika penerapan energi terbarukan berbasis komunitas terbukti membawa perubahan positif, sebagaimana yang dilakukan IBEKA dan hasil riset Yayasan CERAH, kedepannya apakah pemerintah bersedia menempatkan kepentingan oligarki jauh di bawah kepentingan masyarakat Indonesia?
Editor: Dwi Ayuningtyas
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id