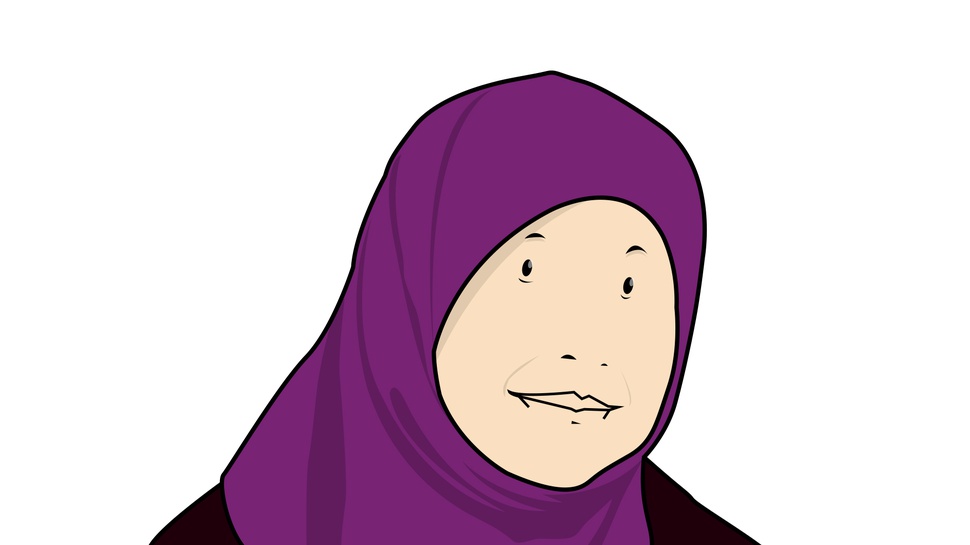tirto.id - Pagi ini, saya menemukan sebuah video yang diposting di akun Twitter yang membuat saya terhenyak. Dalam video itu ada rekaman Bapak Jokowi yang sedang menceritakan pengalaman masa kecilnya yang pernah mengalami penggusuran. “...bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali... sangat sakit sekali.”
Saya percaya bahwa saat itu Bapak Jokowi berkata dengan jujur. Namun adalah fenomena yang jamak di berbagai penjuru dunia bahwa pemerintah populis akan berhadapan dengan kekuatan korporasi yang terlalu besar untuk dilawan.
Seorang narasumber penelitian saya, seorang aktivis dari kalangan masyarakat sipil di bidang pangan yang berperan besar dalam mengorganisasi para petani agar mendukung Bapak Jokowi--yang berjanji akan mewujudkan kedaulatan pangan, janji yang kian hari terlihat kian jauh panggang dari api--menjelaskan situasi yang saat ini terjadi. Kurang lebih begini, “Sangat wajar terjadi pertarungan narasi di seputar presiden, ada pihak-pihak yang lebih punya bargaining position, mereka lebih intensif berada di sekitarnya, sementara kita dari masyarakat sipil tidak terlalu mendapatkan akses menyampaikan alternatif.”
Jadi, ini memang perjalanan ekonomi-politik yang “biasanya”, kelanjutan dari rezim-rezim sebelumnya. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, selama dua tahun masa pemerintahan Bapak Jokowi, terjadi 285 kasus konflik agraria atau rata-rata 142 kasus. Selisih ‘hanya’ 10 kasus dengan rata-rata konflik agraria per tahun selama 1 dekade masa SBY, yaitu 152 kasus. Konflik agraria adalah konflik perebutan tanah antara warga dan pemerintah. Biasanya, wargalah yang dikalahkan, tanah mereka direbut paksa, dengan berbagai jenis justifikasi.
Yang membuat saya terhenyak adalah komentar di postingan video itu: “Memimpin dg hati, betul, tapi anda lupa mendisiplin. Menuruti semua keinginan karena kasihan tanpa Disiplin ??” Si komentator menilai warga yang digusur adalah mereka yang tidak disiplin. Komentar sejenis sangat banyak ditemukan di media sosial: menyalahkan korban penggusuran.
Kebanyakan komentar seperti ini berasal dari kalangan kelas menengah, asumsi yang didasarkan pada data bahwa 64,7% pengguna internet di Indonesia adalah lulusan SMA, mayoritasnya pekerja dan wiraswasta (APJII, 2015). Sementara itu, Boston Consulting Group menyebutkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia tahun 2012 adalah 64,8 juta. Mereka terbagi dua kategori, yang pengeluaran bulanannya 3-5 juta rupiah (upper middle), dan 2-3 juta rupiah (middle). Dengan kata lain, mereka bukanlah kelompok yang dengan ongkang-ongkang kaki saja mampu membeli segala kemewahan di kawasan pantai atau bantaran sungai –hasil menggusur, eh merelokasi, warga –yang kelak akan dibangun oleh korporasi kaya raya.
Kelas menengah zaman ini hidup dalam budaya kompetisi yang menganggap wajar bila sang pemenang mendapat jauh lebih banyak daripada orang-orang kalah. Mereka pun mudah terkagum-kagum pada hasil “pembangunan”, tanpa peduli betapa banyaknya korban berjatuhan di balik pembangunan itu. Merekalah yang dengan gagah berkata, “Para tergusur itu beruntung karena diberi ganti rugi berupa rumah susun!”, sambil memajang foto rumah susun yang dikontraskan dengan rumah kumuh di dinding media sosial. Wajar, karena dalam perspektif mereka, kebahagiaan identik dengan rumah mewah, bukan permukiman kumuh.
Kelas menengah ini, yang heboh membela penggusuran, biasanya akan berargumen dengan menyodorkan link-link berita online tentang ‘betapa senangnya warga yang mendapatkan rusun’ sambil menyebut mereka yang menyebar link tentang fakta di balik rumah susun dan kisah pahit korban tergusur sebagai haters. Mereka tidak peduli bahwa ada solusi selain penggusuran, alternatif yang bahkan ditawarkan sendiri oleh Bapak Jokowi pada September 2012.
Prof. Wendy Brown menyebut sebuah fenomena yang diistilahkannya neoliberalism’s stealth revolution. Secara diam-diam, ideologi neoliberalisme telah merasuk ke pikiran kelas menengah dan menghancurkan solidaritas di antara sesama mereka. Mereka mengagungkan pencapaian kemakmuran sebagai hasil kerja individu, kemenangan dalam kompetisi, dan peningkatan karir. Dogmanya, setiap individu harus bekerja keras dan menang dalam kompetisi bila ingin sukses. Kesetaraan yang esensial, demokrasi yang substansial dan partisipatif, kebaikan untuk orang banyak, adalah nilai-nilai yang semakin diabaikan oleh kelas menengah. Padahal, ibarat lomba lari, bagaimana mungkin kompetisi berjalan adil ketika garis start masing-masing pelari tidak sama?
Kata Prof Brown, kelas menengah memandang bahwa penyelesaian masalah secara fundamental adalah terlalu rumit, membuang-buang waktu, tidak produktif, dan karena itu tidak ada gunanya dibahas. Fakta bahwa dalam lomba lari, beberapa pelari terjatuh kalah karena perutnya sangat lapar, tak mereka hiraukan. Fakta bahwa di balik sekian banyak penggusuran, ada korporasi-korporasi amat-sangat kaya yang meraup mega-profit, tak mereka pedulikan. Mungkin karena mereka sendiri bermimpi kelak akan menjadi bagian dari kelas kaya itu.
Dalam kamus mereka, kata-kata keadilan, nilai, tujuan, kekuatan kelas, telah semakin memudar. Dan kelas menengah pun berpolitik seolah tanpa ideologi: fokus mereka adalah apa yang bisa dilakukan saat ini, secara cepat dan efisien. Meski sebenarnya, tanpa sadar mereka sedang disetir oleh sebuah ideologi yang sangat merusak kemanusiaan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.