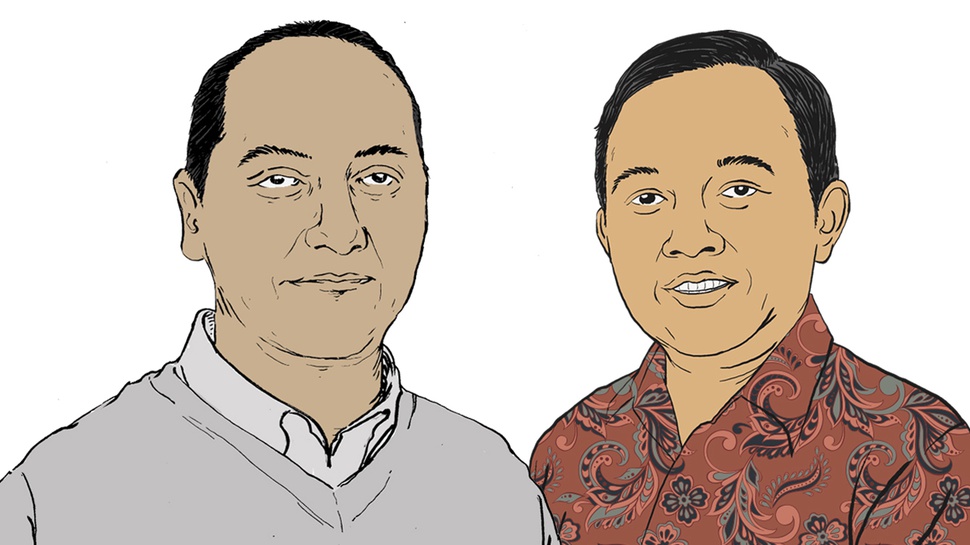tirto.id - Indonesia tidak pernah sepi dari isu-isu agama. Beberapa minggu lalu, ramai kabar soal penyerangan dan perusakan masjid jemaat Ahmadiyah di Sintang. Sebelumnya, dan belum selesai hingga kini, marak isu “penodaan agama” oleh Muhammad Kace dan Yahya Waloni. Ada pula kontroversi yang dipicu pernyataan Menteri Agama terkait agama Baha’i.
Masih di tahun ini, beberapa persoalan terkait rumah ibadah juga mengemuka lagi. Mulai dari soal penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, pemboman terhadap gereja (Makassar), juga relokasi GKI Yasmin yang mengundang pro-kontra. Di luar itu semua, persoalan pasal-pasal tentang agama dalam wacana perubahan KUHP juga masih jadi pembicaraan hingga hari ini.
Masing-masing kasus itu memiliki kekhasan dan selalu ada konteks-konteks lokal yang melatarinya. Namun, kita perlu melihat konteks yang lebih luasuntuk memahami masalah-masalah itu. Konteks itu adalah tata kelola keagamaan.
Tulisan ini melihat unsur-unsur utama tata kelola agama di Indonesia, khususnya ide moderasi beragama sebagai unsur yang baru dirumuskan sekira tiga tahun terakhir.
Konsep Tata Kelola Keagamaan
Istilah tata kelola (keragaman) agama makin kerap digunakan belakanganini. Di negara-negara yang menyebut dirinya sekular sekali pun—seperti India, Bangladesh, Turki, Perancis, dan banyak negara Eropa lain, pemerintahnya kerap membuat kebijakan yang mengatur agama dan manifestasinya.
Istilah tata kelola agama dapat merujuk pada sekularisme, multikulturalisme, interkulturalisme, atau sistem lain yang dipahami sebagai ideologi atau tipe ideal. Namun, ia dapat juga merujuk pada tingkatan lebih praktis, yang lebih dekat atau mendasari regulasi terkait agama. Tulisan ini menggunakan pemaknaan yang kedua.
Dalam pemaknaan yang lebih spesifik ini, negara-negara yang menyebut dirinya sekular atau multikultural itu pun bisa memiliki perbedaan-perbedaan signifikan. Perbedaan itu lebih merupakan cerminan partikularitas sejarah masing-masing negara ketimbang pilihan ideologinya.
Lantas, bagaimana dengan sistem tata kelola agama di Indonesia? Ketimbang mencirikannya dengan suatu tipe ideal, akan lebih produktif jika kita memahaminya dalam artian tata kelola agama yang kedua. Melalui tinjauan sejarah, setidaknya ada tiga konsep utama yang jadi komponen tata kelola agama di Indonesia, yaitu kerukunan, kebebasan, dan moderasi beragama. Ketiganya tidak selalu diungkapkan secara eksplisit, namun diisyaratkan dalam hukum dan politik agama.
Kerukunan Beragama
Momen penting yang memunculkan ide tentang kerukunan adalah ketegangan umat Islam-Kristen pada 1967 yang dibawa hingga ke parlemen. Pada akhir tahun itu, diadakan Musyawarah Antar Agama yang dibuka Presiden Soeharto. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama K.H.M. Dachlan menyebut, “Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi …” (Lihat tulisan M. Adlin Sila).
Mukti Ali, menteri agama berikutnya, mendefinisikan kerukunan hidup beragama sebagai, “Suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-samatanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.”
Perkembangan berikutnya yang cukup signifikan terjadi di masa setelah Reformasi 1998. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkanPeraturan Bersama No. 8 dan 9 Tahun 2006yang memuat definisi atas sejumlah kata kunci penting dalam konteks kerukunan beragama. Kata kunci itu di antaranyatoleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.
Peraturan Bersama itu sekaligus menjadi dasar berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama di lebih dari 500 provinsi dan kota/kabupaten.
Namun, konsep kerukunan itu juga diiikuti kritik. Menurut Trisno Sutanto dalam Pluralisme Kewargaan (2011), khususnya dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, kerukunan lebih terasa seperti“perukunan”. Ia merupakan konsep yang dipaksakan dari atas. Dalam praktiknya pun, ia cenderung menguntungkan kelompok-kelompok arus utama dan merugikan minoritas keagamaan.
Namun, sesungguhnya beberapa kata kunci lain, seperti “tanpa mengurangi hak dasar masing-masing” dan “kesetaraan”, menunjukkan bahwa konsep ini masih terbuka untuk ditafsirkan secara lebih demokratis dan sesuai dengan konstitusi.
Kebebasan Beragama
Ide tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sebetulnya telah ada sejak Indonesia merdeka. UUD 1945 menjanjikan, “Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Setelah 1998, konsep ini muncul lebih kuat sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia dalam UU HAM (1999) maupun Amandemen UUD 1945 (Pasal 28E Ayat 1 dan 2).Salah satu asas terpenting kebebasan beragama—yaitu nondiskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan—pun muncul dalam banyak UU atau peraturan.
Kritik atas konsep ini berkitar pada semantik “kebebasan” yang dianggap berasal dari konsep Barat dan dikhawatirkan menjadi “kebablasan”. Dalam kenyataannya, kebebasan beragama dapat dikatakan merupakan konsep yang paling Indonesia, dalam artian memiliki landasan legal dan konstitusional paling kuat dibandingkan komponen tata kelola agama yang lain. Ia juga konsep yang paling tua dan terus mengalami peremajaan pemahaman.
Namun, salah satu konsekuensi kebebasan pasca-1998 adalah terbukanya ruang lebar untuk kemunculan beragam kelompok keagamaan dengan orientasi yang juga amat beragam. Kelompok-kelompok yang tidak dapat hidup di masa Soeharto—misalnya mereka yang mengusung aspirasi khilafah atau syariat Islam secara eksplisit—kini bisa eksis. Dalam sepuluh tahun masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono(2004-2014), kelompok-kelompok itucukup leluasa bergerak dan berhasil melakukan mobilisasi, meskipun jumlah pengikutnya relatif kecil dibanding organisasi-organisasi keislaman yang jauh lebih tua.
Puncaknya adalah pada periode2016-2017, di sekitar pilkada DKI, ketika kelompok-kelompok tersebut berhasil memobilisasi massa dalam rangkaian demonstrasi. Di antara respon pemerintah adalah pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (2017) dan kemudian Front Pembela Islam (2020). Konteks politik ini penting untuk memahami konsep moderasi beragama, yang setidaknya mengemuka sejak 2018.
Moderasi Beragama
BukuModerasi Beragama (2019)yang diterbitkan Kementerian Agama menyebut moderasi beragama dikembangkan sebagai “amunisi dan alternatif kebijakan pemerintah dalam menanggulangi paham keagamaan yang ekstrem”, ideologi radikalisme, mengurangi kekerasan, dan agar tidak terjebak pada intoleransi dan tindak kekerasan.
Sikap moderat sendiri dipahami sebagai kecenderungan untuk berada di tengah, tidak terjebak pada ekstrem konservatif maupun ekstrem liberal. Legitimasi kuat atas moderasi beragama ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dokumen itu memahami moderasi beragama sebagai jalan mencapai kerukunan, sementara konsep kebebasan beragama sama sekali tidak muncul.
Sikap moderat dalam banyak hal memang baik dan diinginkan, sementara ekstremisme dianggap menjadi sumber banyak masalah. Meskipun demikian, setidaknya ada empat tantangan yang muncul dari pendekatan ini. Pertama, benarkah untuk mencegah konflik kekerasan kita memerlukan orang-orang moderat?
Jika ditilik dari perspektif resolusi konflik (interest-based approach), yang diperlukan untuk mengatasi konflik sebenarnya adalah pembangunan relasi dan kerja sama. Sementara itu, moderasi beragama justru bisa berpotensi mempertajam pembelahan karena label “moderat” dan “tidak moderat”. Lagi pula, orang tidak harus menjadi moderat untuk bisa bekerja sama dan orang moderat belum tentu bisa bekerja sama.
Kedua, yang terutama menjadi target moderasi beragama adalah sikap individu. Dalam kebijakan-kebijakan terkait terorisme dan ekstremisme beberapa tahun terakhir ini, kerap muncul asumsi bahwa sumber utama permasalahan adalah pemikiran seseorang yang dianggap tidak moderat. Padahal, penyebab persoalan-persoalan itu bersifat multidimensi. Karenanya, penekanan pada satu dimensi moderasi jelas tidak akan efektif.
Ketiga, pendekatan moderasi beragama untuk mengubah sikap atau pandangan individu berpotensi menarik negara terlalu jauh dalam urusan pikiran warga. Jika diterjemahkan menjadi instrumen legal, ia dapat berujung pada pembatasan dan pengekangan. Pada akhirnya, jika negarapascareformasi yang mendefinisikan moderat, ia jadi tak ada bedanya dengan Orde Baru yang merukunkan rakyatnya dengan kebijakan top-down.
Akankah ada pandangan-pandangan progresif tertentu yang mungkin dianggap “liberal” atau ekstrem yang akan terbatasi juga?
Keempat, fokus pada pengubahan sikap individu juga bisa melupakan dimensi lain dari persoalan-persoalan terkait agama, yaitu peran negara. Moderasi beragama dianggap sebagai bukti kehadiran negara dalam mengelola keragaman agama. Namun, yang kemudian jadi soal adalah bentuk dan cara kehadirannya—apakah untuk menentukan apa yang baik bagi warga (“moderat” atau “rukun”) atau menjaga arena dan lalu lintas bagi ungkapan-ungkapan keragaman itu?
Dalam kenyataannya, kerap ada kelemahan penegakan hukum jika kelompok rentan yang dirugikan—bahkan ada hukum-hukum tertentu yang justru memberi insentif pada intoleransi.
Buku Moderasi Beragama(hlm. 110) sebetulnya sudah menyinggung hal ini dengan menyatakan,“Munculnya berbagai kebijakan keagamaan tersebut[seperti terkait penyiaran agama, penodaan agama dan rumah ibadat] harus diakui, tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan menghindarkan konflik. Namun, jika regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan akan lebih banyak terjadi.”
Namun, tentu ada pilihan lain yang perlu diupayakan sungguh-sungguh, misalnya dengan melakukan perbaikan regulasi. Contoh terbaik untuk yang terakhir itu adalah hukum penodaan agama yang kerap menjadi andalan kelompok-kelompok intoleran untuk mendapatkan justifikasi legal atas intoleransi dan pelintiran kebencian (seperti dalam kasus Meliana dari Tanjung Balai). Sementara itu, kelompok-kelompok moderat di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU, justru tak pernah menggunakannya.
Benar bahwa, seperti didalihkan lebih jauh di buku itu, pendekatan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk pengelolaan kemajemukan agama. Namun, akan selalu ada pertanyaan jika pemerintah yang mengembangkan moderasi itu juga mempertahankan regulasi yang justru bertentangan dengan tujuan moderasi.
Jika demikian, bisa jadi justru pemerintah dan aparaturnya yang perlu “dimoderasi”. Moderasi beragama dapat lebih diterima jika targetnya terutama adalah aparatur negara.
Kesimpulan
Masing-masing komponen tata kelola agama yang ada dan efektif di Indonesia saat ini memiliki genealoginya sendiri. Masing-masing juga menunjukkan adanya prioritas atau hierarki norma yang berbeda. Perbedaan itu tak selalu berarti bertentangan, tapi mesti ada upaya penyelarasan.
Dalam pembahasan di atas, moderasi beragama dibahas relatif lebih panjang karena ia adalah konsep terbaru yang konseptualisasi dan implementasinya masih berkembang.
Moderasi jamak dipahami sebagai jalan menuju kerukunan, tapi perhatian juga perlu diarahkan pada norma-norma kebebasan beragama atau kebebasan-kebebasan lain (seperti ekspresi, berorganisasi, dan sebagainya). Moderasi beragama perlu diselaraskan dengan pendekatan HAM yang menuntut negara bertanggung jawab sebagai pengemban kewajiban untuk menjamin hak warga.
Ini bukan semata-mata tuntutan untuk perhatian pada hukum dan regulasi. Pasalnya, tata kelola agama bukan sekadar berarti hukum. Pendekatan HAM pun juga bukan semata-mata persoalan hukum.
Dalam hierarki norma-norma yang dikandung ketiga komponen tata kelola agama itu, norma-norma KBB—khususnya kesetaraan, nondiskriminasi, dan nonkoersi—mesti menjadi pertimbangan utama. Pasalnya, ia memiliki dasar konstitusional dan legal paling kuat dan permanen, dan karenanya merupakan watak utama Indonesia.
Perspektif yang disampaikan di sini tidak hanya bersifat teoretis. Implikasinya pada kebijakan sangat jelas. Sebagai satu contoh, kita bisa melihat pasal-pasal terkait pengaturan agama dalam Draf RKUHP, termasuk penodaan agama, yang sedang diperdebatkan.
Apakah draf tersebut akan membantu terciptanya kerukunan? Apakah ia sejalan dengan niat moderasi atau justru sebaliknya? Apakah pasal-pasal itu selaras juga dengan komitmen negara untuk menghargai martabat warganya secara setara sebagaimana diamanatkan Konstitusi?
Kiranya debat ini perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan kehidupan keagamaan Indonesia.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.