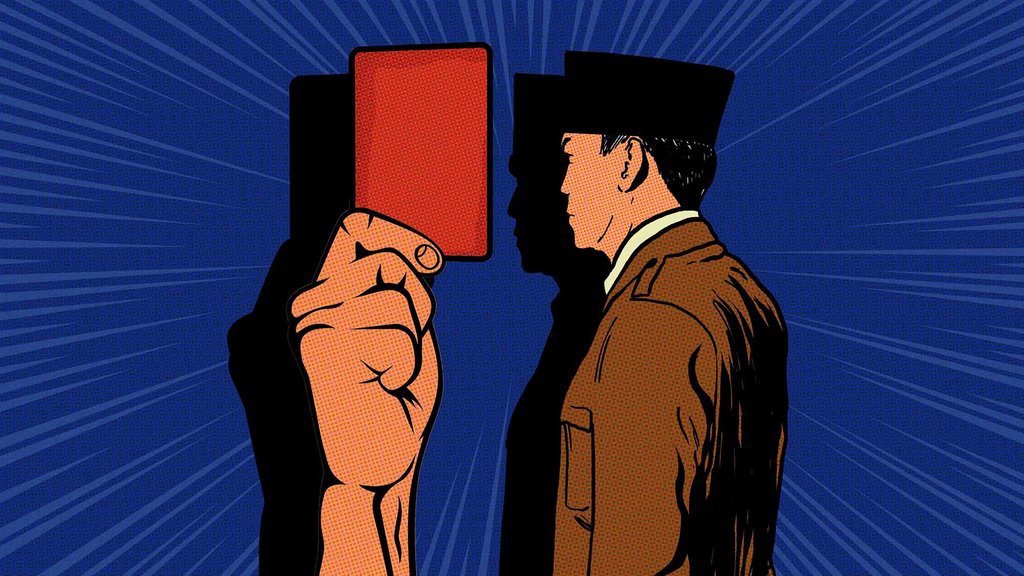tirto.id - Setelah PKI dan semua onderbouw-nya dibabat habis pada akhir 1965, Sukarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak awal 1960-an runtuh dan manuver Angkatan Darat kian tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Sukarno.
Kekuatan politik Sukarno surut dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Terlepas dari perdebatan bahwa Sukarno dipaksa menerbitkan surat itu, yang terang Supersemar memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden.
“Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa,” tulis sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2008: 568).
Soeharto langsung tancap gas. Pada 12 Maret Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Sukarno. Lalu pada 27 Maret Sukarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Pembersihan loyalis Sukarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi.
Dominasi Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS yang anti-Sukarno. Sepanjang Juni hingga Juli sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto, seperti ratifikasi Supersemar dan pelarangan marxisme. MPRS juga tak ragu lagi menuntut penjelasan resmi Sukarno terkait mismanajemen rezim Demokrasi Terpimpin dan termasuk peran Sukarno dalam G30S.
“Gelar ‘presiden seumur hidup’ yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 ditanggalkan. Sukarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Sukarno menolak tuntutan MPRS untuk memberi penjelasan, tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Sukarno sudah berakhir,” tulis Ricklefs (hlm. 571-572).
Beberapa pengamat menyebut adanya dualisme kepemimpinan nasional setelah Supersemar terbit. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Soeharto mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif presiden. Sukarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Soeharto mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Sukarno.
Nawaksara Tak Memuaskan MPRS
Sukarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuduli Nawaksara. Sesuai namanya, pidoto itu mengurai masalah nasional selama Demokrasi Terpimpin dalam sembilan bab.
Substansi Nawaksara di antaranya mengurai tentang retrospeksi Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi sekaligus Mandataris MPR, landasan pembangunan, wewenang MPRS dan DPR, ketetapannya pada Demokrasi Terpimpin, hingga pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Sebuah pidato yang sangat jauh dari ekspektasi para anggota MPRS yang mulai meragukan Sukarno.
“Hal yang menecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. ... Masalah G-30-S/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden tidak disinggung dalam Nawaksara,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Natosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia IV (2008: 558).
Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam Kronik ’65 (2017) menyebut tak hanya MPRS yang tidak puas dengan pidato Sukarno. Sehari setelah Sukarno menyampaikan Nawaksara, Istana Olahraga Senayan—tempat MPRS bersidang—diserbu demonstrasi mahasiswa. Para demonstran itu jengkel dengan pidato Sukarno yang tak menjelaskan apa-apa.
Perwakilan demonstran yang menemui Ketua MPRS Jenderal Nasution bahkan berani meminta agar Sukarno segera dilengserkan. Tapi Nasution bergeming.
“Bung Karno masih presiden kita yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar ’45. Kita mesti menghormatinya,” kata Nasution kepada demonstran sebagaimana dikutip Kuncoro Hadi dan kawan-kawan (hlm. 646).
MPRS lalu mengirim nota kepada Sukarno pada 22 Oktober 1966 yang pada intinya meminta Sukarno melengkapi pertanggungjawabannya. Meski jelas terdesak, Sukarno bukannya tanpa pendukung. Ricklefs menyebut setidaknya perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat padanya.
Pada November mereka disebut-sebut membuat skenario pura-pura menculik Sukarno ketika berkunjung ke Jawa Timur. Mereka siap mendesak Sukarno untuk melawan balik Soeharto. Sukarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan tentu dengan tegas menolaknya. Sukarno tak ingin pecah perang saudara.
Soeharto yang tahu rencana itu lantas melarang kunjungan itu dan kemudian melancarkan usaha lebih gencar untuk membungkam loyalis Sukarno. Para perwira yang dianggap masih setia pada Sukarno diberi beberapa pos jabatan yang menguntungkan. Dia juga menunjuk anggota baru DPR Gotong Royong yang sejalan dengannya untuk memuluskan pelengseran Sukarno melalui mekanisme Sidang MPRS.

Babak Akhir Sukarno
Sang Penyambung Lidah Rakyat akhirnya mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS pada 10 Januari 1967. Dalam nota berkepala Pelengkap Nawaksara itu Sukarno menyebut tiga alasan G30S 1965 bisa terjadi, yakni keblingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihaian subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar.
Lagi-lagi MPRS menilai penjelasan itu tidak memuaskan dan menolaknya. Itu adalah usaha terakhir Sukarno mempertahankan diri dan ia kalah.
“Setelah membaca isinya, hari ini juga, Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, menyelenggarakan konferensi press dan menyebutkan bahwa ‘Pelengkap Nawaksara’ menunjukkan keengganan Presiden Sukarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS,” tulis Kuncoro (hlm. 704-705).
Agaknya Soeharto menyadari betul Sukarno sudah tak mampu menopang kekuasaanya lagi. Apalagi MPRS lalu mengelurkan sikap resmi pada 21 Januari yang intinya menyatakan bahwa Sukarno “alpa memenuhi ketentuan konstitusional”. Dua hari kemudian Soeharto memberi Sukarno pukulan telak: ABRI menyatakan telah sampai pada batas kesabaran terkait penyelesaian kasus G30S 1965.
“Di saat itulah kita akan menarik garis yang jelas antara kita dan mereka yang berdiri di luar garis yang telah ditentukan oleh MPRS. Barulah di waktu itu kita akan mengambil langkah-langkah yang tegas dan tindakan yang keras terhadap siapapun,” kata Soeharto sebagaimana dikutip Kuncoro (hlm. 708).
Opsi yang tersisa bagi Sukarno kini adalah mundur dari jabatan persiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Tapi di saat terakhir pun Sukarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada 7 Februari ia mengirim surat kepada Soeharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asal ia tetap dipertahankan sebagai kepala negara.
Tentu Soeharto menolak usulan itu. Karena masih alotnya hati Sukarno, beberapa hari kemudian empat panglima angkatan turun tangan membujuknya untuk bersedia lengser keprabon. Nasution, yang sebelumnya masih bersikap lunak, kini juga terus terang bahwa seharusnya Sukarno diturunkan dan diseret ke pengadilan.
Akhirnya Sukarno bertekuk lutut. Pada 22 Februari, di Istana Negara, dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Sukarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto.
Sidang Istimewa MPRS yang mulai digelar pada 7 Maret 1967, tepat hari ini 53 tahun lalu, lantas mengukuhkan kejatuhan Sukarno. Dalam sidang itu MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai UUD 1945—bukan lagi pembantu presiden.
“Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia,” tulis Kuncoro (hlm. 722).
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id