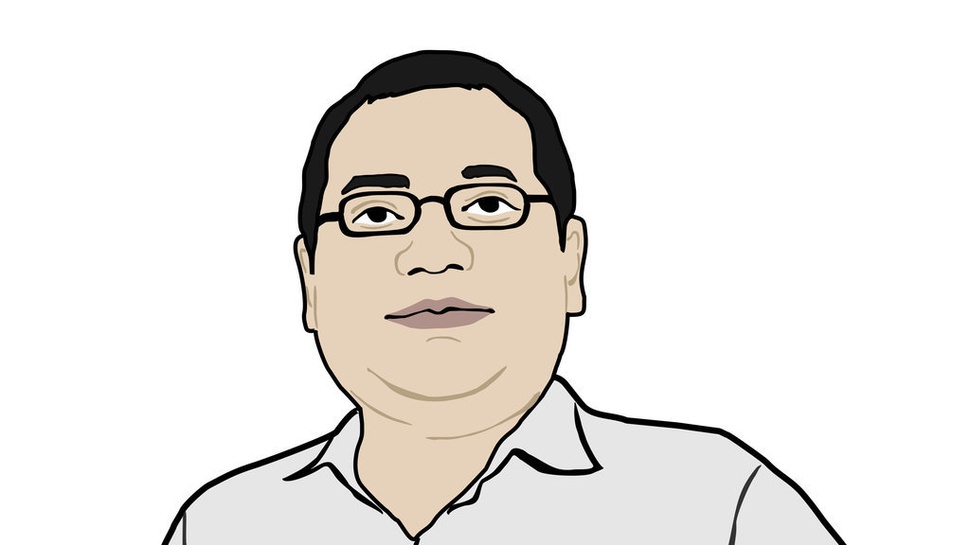tirto.id - Pemerintahan Joko Widodo sedang gencar melakukan pembangunan di sektor infrastruktur, termasuk ratusan jenis proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tak dapat dipungkiri, negara kita tertinggal dalam pelbagai sektor infrastruktur bila dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Namun, pembangunan infrastruktur memerlukan tanah, dan banyak dari tanah tersebut dikuasai penduduk.
Tanah untuk pembangunan infrastruktur diperoleh melalui proses pengadaan tanah yang dua aturan utamanya—Undang-Undang 2/2012 dan PP 71/2012—dibuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua aturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintahan Jokowi untuk menggenjot beragam proyek infrastruktur.
Sayangnya, posisi rakyat dalam kedua aturan itu sangat lemah.
Mekanisme Tenggat Mengajukan Keberatan Gampang Diakali
Kelemahan pertama adalah ketatnya jadwal pengadaan tanah. Undang-undang yang berlaku menetapkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian berlangsung hanya dalam tempo 30 hari sejak appraisal menyampaikan hasil penilaian kepada lembaga pertanahan. Sementara penduduk yang terkena proyek hanya punya waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan atas bentuk dan besarnya ganti rugi ke pengadilan. Jika telat dari batas waktu itu, hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan otomatis usang; penduduk akan dianggap setuju serta menerima berapa pun kompensasi yang diajukan pemerintah.
Praktiknya, jarang sekali orang awam yang tahu tenggat 14 hari tersebut. Kalaupun tahu, seringkali tak jelas kapan batasan 14 hari tersebut dimulai. Kadang panitia mengundang penduduk untuk "tatap muka", tetapi prosedur ini dijalankan saat tempo 30+14 hari. Kemungkinan lain, panitia menentukan sudah terjadi deadlock (dan mulai menghitung masa 14 hari) ketika penduduk masih menganggap kurun waktu itu sebagai masa musyawarah.
Saat penduduk mengajukan keberatan ke pengadilan, kontraktor yang menjalan proyek tersebut bisa saja membela diri di depan hakim dengan mengatakan bahwa tenggat 14 hari telah usai, sehingga berapa pun ganti ruginya harus diterima.
Bagi yang berkepentingan dengan proyek infrastruktur, "menyamarkan" rentang 30+14 hari ini dapat dijadikan strategi untuk mengadakan tanah secara cepat. Karena jika mekanisme musyawarah pun tak jelas kapan dimulai dan kapan berakhir buntu, penduduk (dibuat) tak menyadari bahwa penghitungan 30+14 hari sebenarnya telah berlangsung dan akhirnya warga tidak bisa membela diri di pengadilan.
Mekanisme Musyawarah Hanya Akal-Akalan
Kelemahan kedua soal bentuk dan besaran ganti rugi. Pasal 37 dalam UU 2/2012 menyebutkan bahwa musyawarah dilakukan untuk “menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian” berdasarkan penilaian appraisal. Kompensasi ini bisa uang, tanah pengganti, saham, dan sebagainya.
Sementara pasal 68 (3) dalam Perpres 71/2012 menyebutkan musyawarah hanya menetapkan bentuk ganti kerugiannya. Artinya, menurut Perpres, besaran kompensasi melalui penilaian oleh appraisal sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi—yang masih mungkin didiskusikan hanya bentuk ganti ruginya. Tapi, Pasal 75 (1) dalam regulasi yang sama menyebutkan: “Pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.”
Alhasil, dengan logika kritis yang sederhana, kita bisa melontarkan pertanyaan: kalau bentuk dan besarnya hasil kerugian sudah final, lantas apa fungsinya "musyawarah"?
Kelemahan ketiga soal insentif pajak. Menurut Perpres 71/2012, insentif hanya diberikan kepada mereka yang mendukung tanahnya diambil untuk proyek "kepentingan umum'; tidak mengajukan gugatan terhadap lokasi proyek maupun bentuk dan besaran kompensasi. Artinya, bila ada yang menggugat ke pengadilan, mereka tidak mendapatkan insentif pajak.
Masalahnya, UU 2/2012 tak mencantumkan mekanisme macam itu. Pasal 44 dalam undang-undang itu cuma menyebutkan pihak yang berhak menerima ganti rugi "dapat" diberikan insentif perpajakan. Tak ada persyaratan bahwa mereka dilarang menggugat ke pengadilan.
Perkara lain: insentif pajak bisa dijadikan strategi mempercepat proyek. Negara, lewat BUMN atau kontraktor yang ditunjuknya, bisa memakai alasan bahwa jika warga menggugat ke pengadilan, maka secara hukum tidak dapat insentif pajak. Padahal, menggugat ke pengadilan adalah hak asasi manusia.
Praktiknya, penafsiran berdasarkan Perpres inilah yang dijadikan patokan badan-badan pemerintahan di seluruh Indonesia. Walau demikian, ada juga pengadilan yang mengesampingkan Perpres tersebut. Misalnya, penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 84/PDT.P/2013/PN.KAG mengesampingkan Perpres “karena perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah”. Ia juga menentukan bahwa musyawarah penetapan ganti rugi meliputi musyawarah untuk mencapai kesepakatan besarnya kompensasi.
Saat ini pemerintah dikejar dua masalah dalam pembangunan infrastruktur: kurang waktu dan kurang uang. Presiden Jokowi berkeliling Indonesia untuk menggeber dan memberikan tekanan kepada pelbagai jajaran birokrasi agar proyek-proyek infrastruktur segera selesai. Saya khawatir tekanan ini bakal direspons oleh birokrasi dengan memberikan tekanan pula pada proses pengadaan tanah.
Masalah kurang waktu bisa saja dijawab dengan "menyamarkan" proses musyawarah, sehingga tenggat 14 hari pengajuan keberatan terlampaui. Masalah kurang uang bisa saja direspons dengan membayar ganti rugi dengan harga murah, padahal UU Pengadaan Tanah menganut “asas keadilan” yang didefinisikan “memberikan jaminan penggantian yang layak … sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.”
Sudah seharusnya presiden mencabut dan mengganti Perpres 71/2012 karena beberapa ketentuannya bertentangan dengan UU 2/2012. Ia juga mencederai sila ke-4 dan ke-5 dalam Pancasila. Pembangunan infrastruktur harus jalan terus, tapi harus dilakukan dengan cara yang adil, yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.