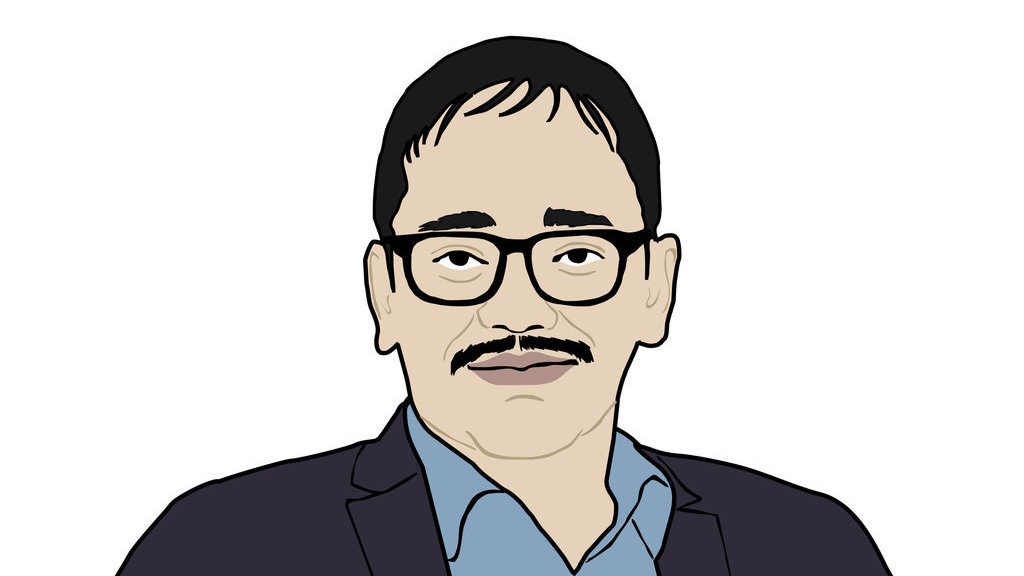tirto.id - Solo 1970-an. Aparat keamanan dibuat gusar dengan kiprah seorang pemain wayang wong bernama Surono. Seniman itu mementaskan lakon Petruk Dadi Ratu yang mengangkat kisah seorang bawahan tak tahu diri yang berpolah menjadi penguasa dengan akhir tragis tertimpa pohon beringin yang menjadi tempatnya berlindung.
Dalam suasana menjelang Pemilu 1971, lakon tersebut menjadi sindiran telak terhadap rezim, dan khususnya terhadap sosok Jenderal Soeharto sebagai penguasa baru Indonesia saat itu. Aparat keamanan akhirnya menangkap Surono.
Membungkam lawan politik melalui penjara, intimidasi dan kekerasan adalah bagian tak terpisah sistem kekuasaan rezim Orde Baru yang lahir dari rahim kekerasan terbesar sejarah Indonesia. Cara penguasa menyikapi guyonan politik sebagai ancaman ketertiban dan keamanan juga bukan hal asing dalam riwayat rezim tersebut. Perkara pentingnya justru terletak pada bagaimana guyonan dalam kehidupan politik di Indonesia.
Kisah Surono telah menjadi perhatian antropolog Paul Stange dalam uraiannya tentang 'rasa' dalam kebudayan Jawa (2007). Satu uraian menarik adalah tentang sosok punakawan yang diwakili Semar dan anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk dan Bagong. Mereka berbicara ngoko, menampilkan dagelan kasar, sifat urakan, dengan segala sesuatu di luar moralitas arus utama. Semar sendiri digambarkan sebagai sosok setengah dewa setengah manusia, setengah perempuan dan setengah pria, dan memiliki satu payudara. Menurut Stange, secara subtil keberadaan, sifat urakan dan guyonan mereka “memperlihatkan makna bagaimana massa rakyat menyatakan politik” (Stange: 80).
Kekecewaan Kaum Muda
Tidak jelas sejak kapan sosok Semar dan para penukawan mengisi pakem Mahabarata. Yang jelas adalah guyonan dan humor terkait sosok para punakawan yang merupakan bagian tak terpisah dalam sejarah lama masyarakat Jawa.
Bagaimanapun, fakta bahwa guyonan politik menjadi bagian tak terpisah dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya bukan ciri unik masyarakat Jawa. Setiap masyarakat memiliki modelnya sendiri. Kita bisa mengingat popularitas buku Mati Ketawa Ala Rusia di Indonesia pada akhir dekade 1980-an. Kesejajaran pengalaman keseharian masyarakat di bawah kekuasaan otoriter Orde Baru dengan pengalaman Rusia di bawah komunisme nampaknya menjadikan buku yang terbit dalam bahasa Indonesia dengan pengantar Abdurrahman Wahid dalam waktu cepat meraih popularitasnya.
Kemunculan Dildo—singkatan dari Nurhadi-Aldo—yang membangun “koalisi tronjal-tronjol” menjelang kampanye pilpres 2019 menjadi petunjuk menarik dari kelanjutan psikologi populer tersebut dalam kehidupan kontemporer masyarakat Indonesia pada era digital. Dari pembicaraan-pembicaraan usil dalam shitposting yang berkembang menjadi akun dengan pengelolaan terorganisir di sosial media menjadikannya goro-goro menarik di kalangan generasi milenial dan generasi Z era digital.
Terkait fenomena Dildo, ada fakta penting yang muncul dalam popularitas cepat kampanye tersebut. Ekspresi ini tidak muncul pada 2014 ketika pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla muncul sebagai kandidat presiden saat itu. Kemungkinannya banyak orang—terutama kalangan muda—menaruh harapan dan kepercayaan terhadap pasangan tersebut dan menumpahkan kreativitas untuk mendukung keduanya. Model komik bergaya Tintin mewakili gambar kampanye Jokowi-JK dan tampilan wajah dengan gaya pop-art ala Andy Warhol memberikan kesan dukungan kalangan muda dalam kampanye politik mereka.
Setelah lima tahun, kita mendapatkan suasana berbeda. Jokowi-JK sekarang ini adalah pemerintahan, dan setiap pemerintahan menjadi buku terbuka untuk dinilai, dihujat, dan dikritik. Wawancara Voxpop(4 Januari 2019) dengan salah satu pengelola akun Nurhadi-Aldo menangkap pokok kekecewaan dan kritik tersebut. Ia mengungkapkan perasaan miris terhadap minimnya politik kerakyatan dalam dalam kehidupan politik dan harapan agar rakyat “jangan mau diadu domba oleh kelas penguasa, parpol, elite politik, dan lain-lain”.
Dari segi tema, langgam Kampanye Dildo adalah bahasa kalangan muda terdidik perkotaan. Ada kecemasan terhadap kapitalisme global yang mengunyah kehidupan jelata, kegetiran terhadap masa depan kalangan muda, dan kejenuhan hipokrisi kosmetik elite yang menyatakan diri mewakili rakyat. Bagian akhir ini juga menunjukkan bahwa mereka bukan pendukung oposisi yang diwakili Prabowo-Sandiaga Uno. Pendukung Dildo menunjukkan kesadaran bahwa kedua tokoh oposisi sejak lahir sampai dewasa jauh dari persentuhan dengan masalah kaum jelata dalam kehidupan pribadi mereka, dan “rakyat” hanya sekedar rujukan dalam bahasa politiknya.
Sifat urakan, kekonyolan tema kampanye, bahasa lugas, dan konotasi seksual kampanye Dildo sekali lagi mengungkap kesinambungan tradisi lama dalam kehidupan politik kontemporer. Khasanah sastra Jawa klasik memiliki ragam istilah dan bahasa simbolik yang mengungkap aspek seksual dalam ungkapannya, dan kekonyolan tema yang muncul. Perhatikan saja ungkapan dan tema dalam serat Gatholoco dan Darmogandul yang mengandung pernyataan pahit kekalahan budaya tradisional (kalangan rakyat) oleh kekuasaan elitis dan menguatnya praktek keagamaan legalistik dalam kehidupan publik pada masa kelahiran teks-teks tersebut. Ungkapan-ungkapannya pun tak berbeda jauh dari bahasa yang muncul di dalam era digital melalui Dildo.
Impotensi Politik
Mengapa kesinambungan seperti itu terus berjalan dalam kehidupan politik Indonesia? Ada dua jawaban sementara yang bisa diberikan.
Pertama, persoalan klasik jarak lebar antara elite dan massa yang sulit ditembus dalam praktek politik kontemporer. Ini, sekali lagi, bukan persoalan unik Indonesia. Kelompok sejarawan subalternis di India telah menyadari keberadaan domain berbeda antara elite dan massa yang sulit dijembatani dalam pembentukan India modern. Seperti disampaikan Ranajit Guha, elite berbicara dalam bahasa abstrak tentang bangsa, sementara rakyat kebanyakan bicara persoalan kongkrit kehidupan sehari-hari dalam bentuk simbol. Kegagalan kaum borjuis dan kelas menengah India membawa modernisasi menjadi pokok dasar keterbelahan domain politik rakyat yang tidak terintegrasi dalam unit politik baru sejak kemerdekaan India.
Di Indonesia, kita mendapatkan gambaran senada seperti disampaikan Guha. Elite gemar bicara persoalan abstrak, sementara rakyat berada dalam tuntutan persoalan kongkrit terkait tanah, upah, sekolah, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Kita bisa melihat harapan ini dalam tema-tema penuh humor dan konyol yang diusung kampanye Dildo. Dildo mengungkapkan upaya menembus elitisme yang menghalangi harapan banyak orang dalam praktek politik Indonesia.
Kedua adalah kebutuhan atas Dildo itu sendiri. Impotensi panjang politik kerakyatan telah menjadi bagian tak terpisah dalam perkembangan politik Indonesia modern sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Sejak peralihan awal abad ke-20, praktek politik radikalisme kerakyatan dalam semangat—meminjam istilah Takashi Shiraishi (1990)—'zaman bergerak’ telah menjadi landasan kemajuan politik di Indonesia yang menerjemahkan dunia modern dalam budaya politik Indonesia pada awal abad sampai dekade 1960-an.
Kemunculan Orde Baru, penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kemunculan politik massa mengambang (floating masses) menjadi pijakan dasar impotensi politik gerakan rakyat.
Reformasi yang mengubah tatanan politik Orde Baru pun akhirnya gagal membawa rakyat dalam politik. Pemerintahan dan politik adalah urusan golongan ksatria dan kaum jelata hanya diundang dalam pembicaraan itu setiap lima tahun sekali. Para kandidat yang bertarung sekarang akhirnya hanya memberikan rangsangan tetapi tidak mampu memberikan ejakulasi energi politik kerakyatan.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id