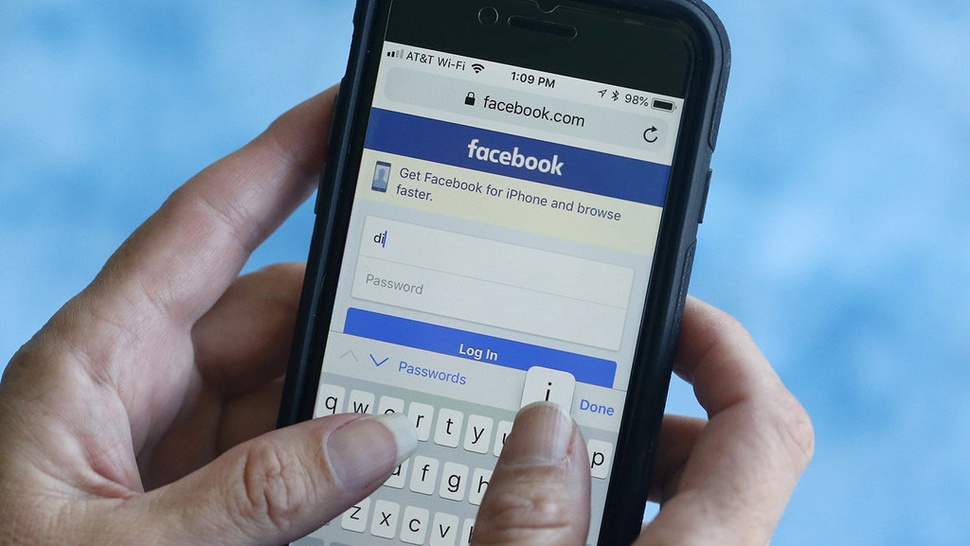tirto.id - Sejak diluncurkan pada 2004 silam, Facebook telah berkembang pesat menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia. Hingga kuartal kedua 2018, jumlah penggunanya sudah mencapai lebih dari 2,2 miliar di seluruh dunia, menurut data Statista.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan Facebook selain sekadar menghubungkan banyak orang di jagat maya. Melancarkan kampanye politik dan perebutan pengaruh adalah salah duanya.
Pada 21 Agustus 2018, sebuah perusahaan keamanan siber FireEye yang bermarkas di California Amerika mengungkap aktivitas ganjil di media sosial Facebook. Ada indikasi kuat bahwa ratusan akun penyebar tulisan bertema politik Iran yang ditujukan ke publik AS, Inggris, Amerika Latin dan Timur Tengah diciptakan oleh pemerintahan Iran sendiri.
Narasi politik yang dipromosikan akun-akun ini meliputi tema anti-Saudi, anti-Israel dan pro-Palestina, serta dukungan kepada kebijakan AS selama menguntungkan Iran—misalnya dalam hal kesepakatan nuklir AS-Iran.
FireEye mendasari temuannya berdasarkan penelusuran beberapa situs web seperti Liberty Front Press, Instituto Manquehue yang memakai jasa iklan desain web Gahvare asal Iran. Konten-konten di dalam situsweb inilah yang kerap dipromosikan ke akun-akun media sosial, termasuk Twitter.
Beberapa akun Twitter juga terdaftar dengan kode sambungan telepon Iran, yakni +98. Beberapa akun media sosial pun ketahuan menyamar sebagai warga AS yang sedang mendukung kebijakan yang sejalan dengan Iran.
Menanggapi temuan FireEye, Facebook langsung bereaksi. Perusahaan milik Mark Zuckeberg itu segera bergerak menghapus lebih dari 650 halaman, grup dan akun yang selama ini menyebarkan konten seperti yang dipaparkan oleh FireEye.
Duterte Cyber Army
Unggahan-unggahan seperti yang ditemukan pada akun-akun pro-Iran kian lazim dijumpai pada akun-akun buzzer pemerintah yang memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye dan pertahanan siber. Di beberapa tempat, kasusnya berbeda karena yang dipromosikan bukan negara beserta politik luar negerinya. Di Filipina, misalnya, Duterte memanfaatkan media sosial untuk membungkam kritik terhadap kebijakan perang anti-narkoba yang ia luncurkan dua tahun silam.
Sejak Juni 2016 (ketika Duterte mulai berkuasa) hingga Januari 2018, ada lebih dari 12.000 warga Filipina yang tewas di tangan aparat keamanan karena diduga sebagai pengedar atau pengguna narkoba. Pembunuhan ini dilakukan tanpa penangkapan, penyidikan, dan proses peradilan.
Salah satu yang vokal mengkritik kebijakan Duterte adalah senator Leila de Lima. Sejak terpilih pada 2016, de Lima adalah salah satu politisi yang paling vokal menentang perang narkoba Duterte yang brutal.
Akun-akun pro-Duterte tidak tinggal diam menyaksikan kampanye de Lima. Pada Agustus 2016 lalu, sebuah foto beredar di jagat Facebook Filipina menunjukkan laki-laki dan wanita paruh baya tengah berhubungan seks di atas seprei bermotif bunga. Wajah sang pria disamarkan, sedangkan sosok wanitanya secara terang-terangan memperlihatkan wajah Leila de Lima.
Tentu saja postingan itu tak lebih dari propaganda. Dalam laporan panjang Davey Alba untuk Buzz Feed News, propaganda pemerintahan Duterte yang isinya lebih banyak memuat penyesatan informasi ini sebagian besar beredar di Facebook dalam bentuk tulisan, meme, gambar, hingga video.
Facebook adalah media sosial populer di Filipina. Pada 2012, 29 juta orang Filipina memakai Facebook. Kini, penggunanya naik menjadi 69 juta orang. Dengan kata lain, hampir setiap warga Filipina punya akun Facebook.
Laporan Laurent Etter untuk Bloomberg pada Desember 2017 juga menunjukkan bagaimana pemerintah membayar buzzer untuk menyebarkan disinformasi di media sosial dengan narasi yang menyudutkan lawan-lawan politik Duterte.
Akun-akut bot pun dilibatkan. Mengacu penelusuran tim data Rappler yang dikutip Bloomberg, 26 akun robot yang secara masif menyebarkan pesan-pesan pro-Duterte tiap kali sang presiden dikritik. Akun-akun tersebut mengunggah tulisan yang sama dan kerap membagikan berita palsu dari situs macam Global Friends of Rody Duterte dan Pinoy Viral News. Jika ditotal, lebih dari 12 juta akun menyebarkan pesan-pesan plus berita palsu pro-Duterte.
Dipakai untuk Transaksi Senjata
Sejak 2014, Libya dilanda perang sipil yang melibatkan sejumlah kubu, mulai dari tentara pemerintah hingga jejaring ISIS. Ketika perang di dunia nyata terus berlangsung, beberapa kombatan memilih untuk bertempur di jagat maya.
Sama halnya dengan di Filipina, Facebook adalah media sosial terpopuler di Libya. Sambil berlindung dari bom dan desingan peluru, masyarakat Libya menghabiskan waktu berjam-jam di rumah untuk berselancar di Facebook untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kepercayaan terhadap media TV dan surat kabar menurun karena masing-masing media dikuasi oleh pihak yang bertikai.
Sayangnya, penduduk sipil Libya masih harus berbagi ruang dengan para kombatan di Facebook. Bahkan, menurut laporan panjang Declan Walsh dan Suliman Ali Zway untuk The New York Times pada Selasa (4/9), transaksi senjata dilakukan lewat Facebook dan hampir semua kelompok kombatan punya akun Facebook.
Dalam sebuah laman diskusi di Facebook, seorang pengguna mengunggah peta dan koordinat guna membantu serangan bom udara ke target sasaran.
"Dari lampu lalu lintas di Wadi al Rabi, persis 18 kilometer arah landasan pacu, berarti dapat ditargetkan dengan artileri 130 mm," tulis pengguna Facebook bernama Narjis Ly. "Koordinat terlampir di foto bawah," lanjutnya.
Apa yang terjadi di Libya serupa dengan Rakhine, negara bagian Myanmar yang terus bergolak akibat pembantaian etnis Rohingya.
Peneliti dan analisis digital Raymond Serrato memeriksa sekitar 15.000 postingan Facebook dari pendukung kelompok nasionalis garis keras Ma Ba Tha. Postingan kebencian paling awal diunggah pada Juni 2016 dan secara kuantitas meningkat pada 24 dan 25 Agustus 2017. Saat itu, militan ARSA Rohingya menyerang tentara Myanmar. Serangan tersebut direspons militer dengan meluncurkan operasi pembasmian.
"Facebook mempermudah elemen-elemen tertentu dalam masyarakat untuk menentukan narasi konflik di Myanmar," kata Serrato kepada The Guardian.
Cerita-cerita palsu yang tersebar di Facebook terdengar provokatif. Misalnya kabar bahwa ada sebuah masjid di Yangon yang menyimpan senjata untuk meledakkan pagoda-pagoda Buddha. Tak sedikit pula tulisan yang menyebut etnis Rohingya sebagai gerombolan "teroris Bengali".

Tantangan untuk Facebook
Langkah penghapusan akun-akun gelap pro-Iran jadi adalah satu langkah nyata yang diambil Facebook.
Dilansir dari New York Times, pada Juli 2018, Facebook mulai menghapus beberapa informasi yang keliru dari laman-laman mereka yang tersebar di Sri Lanka, Myanmar, dan India yang berpotensi menyebabkan kekerasan di dunia nyata.
Pada Rabu (5/9), chief operating officer Facebook, Sheryl Sandberg berbicara di hadapan Komite Intelijen Senat AS mengenai pembatasan konten disinformasi terkait kasus di Libya. Facebook menegaskan pihaknya terus mengawasi Libya dengan memperkerjakan peninjau konten berbahasa Arab, mengembangkan kecerdasan buatan untuk menghapus konten terlarang, hingga bekerjasama dengan organisasi lokal dan kelompok pegiat HAM.
Tak hanya kali ini saja Facebook disorot akibat konten-konten pengguna yang memengaruhi situasi politik suatu kawasan. Pada 2017, Facebook mengungkap peranan agen-agen Rusia yang mengunggah 80 ribu postingan di Facebook untuk memengaruhi arah politik AS dalam Pilpres 2016.
Maret lalu, The New York Times dan The Observer membongkar operasi Cambridge Analytica, sebuah firma yang ditunjuk Trump untuk mengurusi kampanyenya pada Pilpres 2016 lalu. Cambridge Analytica secara ilegal telah menyedot data pribadi 50 juta lebih akun Facebook.
Akibat skandal ini, Mark Zuckenberg dipanggil Kongres AS untuk dimintai kesaksian tentang bagaimana selama ini Facebook melindungi data penggunanya.
Dalam standar komunitas Facebook, tercantum peraturan yang tegas melarang pengguna menggugah konten ujaran kebencian, kekerasan, dan sejenisnya. Disebutkan juga bahwa Facebook tak segan-segan menghapusnya.
Masalahnya, sistem pengawasan konten di Facebook relatif kompleks. Para pengawas konten kerap tak konsisten menegakkan aturan yang mereka buat sendiri. Tak jarang, mereka baru bergerak sigap setelah diberitahu oleh pihak ketiga mengenai beberapa konten yang dianggap bermasalah.
Seiring situasi geopolitik dunia terus memanas, bisakah Facebook menjalankan misi maha berat itu?
Editor: Windu Jusuf