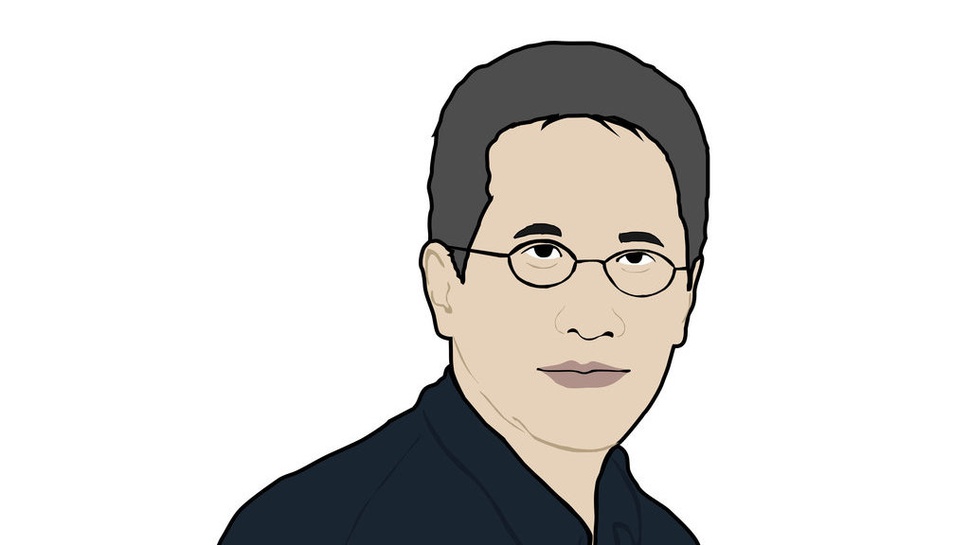tirto.id - Indonesia adalah keajaiban besar dalam sejarah dunia. Mengingat skala kemajemukan yang luar biasa, wartawan senior Amerika Elizabeth Pisani menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang “tak masuk akal” (improbable) bisa hadir secara utuh seperti selama ini.
Dilahirkan di zaman pemerintahan Sukarno, saya sendiri bersyukur, sebelum mati masih bisa menyaksikan Indonesia hari ini yang secara umum lebih baik dari masa-masa sebelumnya.
Bukan berarti indonesia hari ini tak punya masalah. Namun, apa dan bagaimana masalah yang ada itu dipahami secara berbeda-beda oleh bangsa yang semajemuk Indonesia. Pokok inilah yang ingin saya bahas, dengan fokus situasi politik pasca-Pilpres 2019.
Usai keputusan MK, wacana publik dikuasai oleh kubu yang berjaya dalam Pilpres 2019 dengan tema utama perdamaian, rekonsiliasi, kebersamaan dan persatuan nasional. Dalam bahasa rakyat sehari-hari: “Lupakan permusuhan cebong versus kampret”.
Kedengarannya indah dan merdu. Tapi, setidaknya ada dua masalah raksasa yang masih dan bisa terus mengganjal jika disangkal atau tidak dipahami dengan seksama.
Pertama, selama kegaduhan masa kampanye Pilpres 2019, terjadi kegagalan umum dalam memahami pertikaian “cebong versus kampret”. Pertikaian itu terlalu dibesar-besarkan kedua belah pihak. Akibatnya, seusai pilpres, persatuan dua kubu itu dianggap sangat penting untuk kebaikan Indonesia pada tahun-tahun mendatang.
Kedua, kemenangan dalam Pilpres 2019 hanya menjelaskan besaran jumlah pemberi suara pada kubu 01. Ia tidak dengan sendirinya memberikan pembenaran pada berbagai pandangan, asumsi, praduga dan tuduhan dari kubu tersebut tentang berbagai hal.
Kedua masalah itu akan saya bahas satu demi satu. Tentu saja, layak diakui dalam masing-masing kubu hadir kemajemukan internal. Sehingga sulit membuat generalisasi tanpa perkecualian.
Cebong Vs Kampret
Tentu kita masih ingat betapa sengit pertikaian dualisme “cebong” versus “kampret”. Banyak orang dituding sebagai cebong oleh yang anti-cebong, dan sekaligus dituding kampret oleh yang anti-kampret. Seakan-akan tidak ada ruang lain di luar dua kubu itu.
Kerugian besar dari perdebatan semacam itu adalah terabaikannya kemajemukan masing-masing kubu. Di antara Joko Widodo sebagai capres dan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya terdapat jarak tidak kecil. Di antara Paslon 01 ini dengan berbagai kelompok yang mendukung terbentang berbagai posisi dan kepentingan yang sangat majemuk. Hal yang sama dapat diamati pada Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan para pendukung mereka. Semua kemajemukan itu habis terinjak-injak oleh ganasnya wacana dualisme “cebong” versus “kampret”.
Lebih parah lagi, ketika yang ditonjolkan bukan dua versi paslon atau kubu, melainkan dua sosok perorangan: Jokowi versus Prabowo. Seorang Jokowi/Prabowo menjadi pusat pujian pendukungnya sekaligus pusat kecaman penentangnya. Yang diuntungkan dari debat sedangkal itu adalah mereka yang berbagi kuasa di sekitar kedua tokoh. Mereka terbebas dari pantauan publik. Padahal, mereka akan tetap berpeluang besar ikut menikmati jatah kuasa, terlepas siapa pun yang memenangkan Pilpres 2019.
Ada kerugian lain yang lebih besar dari perdebatan dangkal berpusat pada cebong lawan kampret. Yakni terabaikannya berbagai kelompok majemuk yang tidak (atau tidak sepenuhnya) tertampung dalam salah satu dari dua kubu tersebut.
Sebagian dari mereka bersuara kritis, misalnya para pendukung golput. Tapi, karena mereka berjumlah kecil dan tak punya mesin propaganda seperti kedua paslon. Maka suara mereka mudah terabaikan, atau dijadikan obyek kecaman. Di luar golput ada berbagai kelompok lain yang tidak terwakili oleh kedua kubu paslon, dan tidak bersuara seperti pendukung golput.
Misalnya di lapisan menengah dan bawah, termasuk kaum minoritas (agama, etnisitas, orientasi seksual, geografis, penyandang cacat fisik, dan sebagainya). Juga mereka yang hak-hak sipil dan hak-asasinya diabaikan dan ditindas (misalnya dalam kasus perampasan tanah, orang-orang yang tak mendapat akses pendidikan, miskin secara ekonomi, korban pelecehan seksual). Bahkan nasib kelas menengah profesional yang mengalami kekerasan tidak lagi dipedulikan kedua kubu: aktivis anti-korupsi, jurnalis, aktivis lingkungan-hidup, penerbit dan toko korban razia buku, kelompok sosial yang diserang semata-mata karena berdiskusi atau menonton film bersama.
Karena terlalu sibuk saling menyerang, kedua kubu utama dalam pilpres tak sempat memperhatikan nasib berbagai kelompok sosial di luar kedua kubu. Sebagai warga yang terpisah dari perebutan kuasa negara, berbagai kelompok sosial ini juga tak punya alasan kuat untuk mendukung atau menyerang salah satu dari dua kubu Pilpres 2019. Perdamaian, rekonsiliasi atau terhapusnya label “cebong/kampret” tidak banyak artinya untuk mereka.
Para pendukung golput telah berkali-kali memaparkan banyak kemiripan di antara kedua kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019. Namun kedua kubu lebih suka membesar-besarkan ancaman lawannya, dalam rangka membesar-besarkan kehebatan kubu mereka sendiri.
Masing-masing kubu menciptakan momok tentang kubu lawannya. Yang satu mengandalkan momok “Arabisasi/intoleransi” sambil mendaku paling “Nusantara/Pancasila”. Yang lain menjual momok “Komunis/Cina” sambil mendaku paling “Islami”. Kampanye pemilu bukan adu visi dan kebijakan tentang Indonesia di masa depan yang bisa dibina lebih baik, alih-alih adu program tentang bencana yang menimpa Indonesia bila pilpres dimenangkan kubu lawan.
Seusai pilpres, publik diberi tontonan kemesraan Jokowi dan Prabowo. Tontonan ini tidak berkisah tentang pertemuan dua visi atau kebijakan kenegaraan. Tapi hanya basa-basi dua individu. Tontonan itu menelanjangi semua omong-kosong kampanye tentang ancaman dari kubu lawan. Tontonan itu juga menunjukkan betapa konyol berbagai kecaman dari pendukung kubu 01 terhadap pandangan pendukung golput.
Kemenangan, Bukan Kebenaran
Saya yakin para pendukung Paslon 01 jujur dan tulus meyakini wawasan, visi dan pokok pikiran dalam kampanye paslon mereka tentang Indonesia. Juga tentang Pancasila, toleransi pada kemajemukan, dan jatidiri Nusantara. Tidak ada muslihat, pura-pura, atau niat menipu. Tetapi, keyakinan berbeda dari kebenaran.
Karena Paslon 01 sudah memenangkan pilpres, tidak berarti wawasan, visi, dan pokok pikiran mereka sudah tidak terbantahkan lagi. Tidak juga berarti pandangan mereka sudah atau akan segera diterima oleh yang kalah dalam pilpres. Apalagi oleh mereka yang berada di luar kedua kubu paslon. Indonesia sangat majemuk, dan tidak dapat direduksi menjadi dua kubu. Tapi kemajemukan itu sering diabaikan, bahkan oleh mereka yang gemar berkampanye tentang kemajemukan dan toleransi.
Pengabaian begitu tampil mencolok dalam sebuah diskusi untuk publik di Melbourne awal Juli lalu. Di situ tampil tiga pembicara super-cerdas: Ganjar Pranowo, Yenny Wahid dan Yunarto Wijaya. Diskusi dikemas dengan niat untuk meninggalkan pertikaian cebong lawan kampret, dan membina perdamaian, rekonsiliasi, kebersamaan dan persatuan nasional. Diskusi juga disajikan dengan berbagai canda santai.
Sayangnya, canda itu beberapa kali tergelincir menjadi ejekan dan olok-olok sepihak terhadap mereka yang kalah dalam pilpres kemarin. Istilah cebong dan kampret dihindari, bahkan ditolak. Namun diskusi itu tetap mirip dengan acara perayaan kemenangan satu pihak.
Beberapa penanya dari hadirin mempertanyakan timpangnya diskusi ini yang berpihak ke kubu Jokowi. Tanggapan-balik dari yang dikritik sungguh menarik. Pertama, mereka menolak dilanjutkannya pemakaian label kubu 01 dan kubu 02, karena pilpres sudah usai.
Seakan-akan hanya ada dua kubu dalam dinamika politik di Indonesia.
Kedua, tanpa label cebong dan kampret, selama dua jam para pembicara terjerat oleh dualisme label “kita” (para pembicara: yang mendaku sudah Nusantara, toleran, Pancasila) lawan “mereka” (yang tidak tampil di panggung: yang dituduh radikal, intoleran, berkiblat Timur Tengah).
Tema perdamaian dan persatuan diangkat berkali-kali. Tapi di balik istilah merdu itu ada kenyataan yang tidak diakui: dalam perdamaian itu ada pihak yang statusnya naik sebagai pemenang, dan ada yang merosot sebagai pihak yang kalah. Persatuan nasional dimuliakan berkali-kali. Tapi, yang implisit di balik wacana tersebut adalah persatuan yang dipimpin oleh “kita” yang sudah menang pilpres (yang Nusantara, toleran, Pancasila). Berbagai substansi pertikaian sebelumnya, apalagi sumber bangkitnya pertikaian itu, dianggap kadaluwarsa, dan bisa diabaikan begitu saja.
Yang eksplisit dinyatakan pembicara dalam diskusi itu: masalah ideologi dan kenegaraan Indonesia “sudah selesai”. Artinya, tidak ada ruang untuk diskusi bagi “mereka” yang punya wawasan, visi dan pokok pikiran berbeda. Mungkin yang dimaksud “sudah selesai” itu proklamasi kemerdekaan dan perumusan Pancasila (1945).
Padahal kita tahu, Indonesia merupakan proyek untuk masa depan bersama milik seluruh bangsa yang luar biasa majemuknya. Bukan warisan masa lampau yang sudah jadi atau selesai.
Proklamasi kemerdekaan disusun terburu-buru secara darurat. Perumusan Pancasila merupakan hasil kompromi berbagai unsur majemuk Indonesia untuk bersepakat menahan diri dan menunda (bukan mengakhiri) perbedaan dan pertentangan visi dan ideologi. Tujuannya agar kemerdekaan bisa segera terwujud. Perdebatan tentang ke-Indonesia-an yang dicita-citakan bersama itu belum pernah selesai. Ia menjadi proses yang terus hidup dan menampung kemajemukan Indonesia.
Sekelumit diskusi di Melbourne itu hanya ilustrasi kecil dari arus utama dalam wacana “rekonsiliasi” atau perdamaian dan persatuan pasca-pilpres secara umum. Yang paling mengkhawatirkan dari perayaan kemenangan kubu 01 yang dikemas dengan tema “rekonsiliasi” dan perdamaian adalah asumsi bahwa pemenang Pilpres 2019 adalah perwakilan atau perwujudan tunggal dari sosok sejati Indonesia yang ‘‘sudah jadi” dan “sudah selesai”.
Seakan-akan semua yang di luar mereka bukan atau kurang Indonesia, sehingga layak ditolak.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.