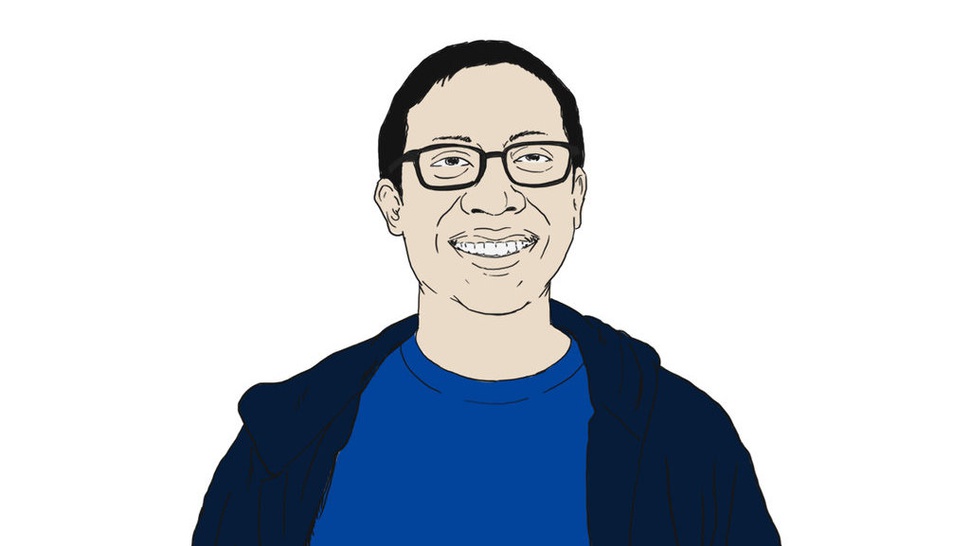tirto.id - Ada kekeliruan berpikir yang menyelinap dalam alam nalar semua orang saat ini: buatlah aplikasi maka hidupmu akan tenang. Membuat sebuah aplikasi seolah menjawab berbagai persoalan sebuah sektor. Ini sebuah sesat pikir yang harus diluruskan dari sekarang. Terlebih bagi pejabat publik yang tugas sejatinya adalah membuat kebijakan, bukan aplikasi.
Seorang birokrat, terlebih menteri, baiknya diingatkan bahwa ia menaungi sebuah lembaga dengan kekuatan besar yang apabila dikelola dengan cermat, memiliki daya perubahan yang lebih besar ketimbang aplikasi. Namun dalam era kerja,kerja, kerja, pejabat pun lupa bahwa dia memiliki superpower yang melampaui teknologi. Disertai sedikit refleksi, kuasa itu bisa berdampak baik secara jangka panjang, sejalan dengan konstitusi dan kebutuhan warga alias rakyat.
Tanpa harus menyebut nama, pembaca paham bahwa tulisan ini secara khusus dialamatkan kepada menteri termuda yang berkantor di Senayan. Namun, kritik ini relevan bagi pejabat publik mana pun yang berimajinasi bahwa membuat aplikasi akan meyakinkan masyarakat akan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan. Belum tentu.
Ada dua kritik yang dicoba digarisbawahi oleh tulisan ini, yakni kritik kelembagaan dan kritik dependensi teknologi. Kritik kelembagaan menyangkut upaya mendorong kementeriaan untuk membenahi paradigma bekerja dan pembuatan kebijakan. Sementara kritik dependensi teknologi mengingatkan kita semua untuk melihat teknologi sebagai alat, bukan sebagai obat.
Kritik Kelembagaan
Tiap menteri yang pertama kali menjabat akan dihadapkan pada sebuah fakta: menghadapi birokrasi itu rumit. Namun, saya memberanikan diri untuk bersikap optimis dan meyakini bahwa mereka juga melihat manfaat birokrasi. Data dan informasi yang terdapat di dalam lembaganya bagai harta karun. Ini hanya bisa terungkap jika ia mampu menerabas rimba informasi yang umumnya terdapat di semua kementerian.
Untuk itu, ada baiknya semua menteri taat pada terobosan yang dihasilkan pemerintahan periode sebelumnya: Open Data, One Data, dan bila relevan: one map. Semua terobosan ini sia-sia jika para menteri baru mengabaikan ketersediaan perangkat tersebut, apalagi memilih untuk tidak menggunakannya. Dari pengalaman pribadi penulis, data yang menggunung di kementerian sia-sia sesederhana karena data tidak terkonsolidasi dan tidak dipublikasikan. Akhirnya kebijakan sering dibuat berdasarkan asumsi dan intuisi, bukan data. Padahal, ketiga terobosan di atas sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
Kembali pada persoalan membuat aplikasi: Membangun aplikasi biasanya membutuhkan pengumpulan data dan informasi baru. Ketimbang memulai proses tersebut dari awal, lebih baik kementerian merapihkan dan memanfaatkan data yang sudah ada. Jika disambungkan dengan potensi yang terdapat dalam pemanfaatan teknologi, maka kesimpulannya adalah warisan terbaik yang bisa diberikan pucuk pimpinan adalah membentuk, menjalankan, lembaga yang ramping dan tanggap dengan memanfaatkan repositori data yang apik.
Kritik Dependensi Teknologi
Anggapan bahwa terobosan harus datang dalam bentuk sebuah aplikasi juga menyiratkan masalah dependensi teknologi. Aplikasi dianggap solusi atas semua masalah. Padahal, di balik ketepatan teknologi terdapat isu yang lebih krusial, yakni kecermatan membaca masalah. Meminjam istilah yang lazim dalam pembuatan aplikasi, yang harus dikerjakan seorang menteri adalah menggali dan memahami User experience (UX).
Dalam bukunya Tools for Conviviality (1973)sosiolog Ivan Illich sudah mewanti-wanti bagaimana proses modernisasi menciptakan ketergantungan apabila individu kehilangan kendali atas alat-alat yang ia ciptakan. Ringkasnya, teknologi adalah alat yang harusnya memungkinkan pembebasan individu, bukan dijadikan obat. Di tengah gebyar wacana revolusi industri 4.0., negara seperti Indonesia yang proses modernisasinya berjalan secara pincang dan tidak menyeluruh, teknologi harus didudukkan secara cermat. Ia bisa saja mendorong akselerasi pembangunan, namun belum tentu disertai dengan perubahan kultural dan mental. Seandainya aplikasi dibuat secara instan demi target kinerja namun birokrasi di baliknya tidak turut berbenah (sesederhana mempublikasikan data ke publik), maka perubahan yang terjadi hanya superficial alias di permukaan belaka.
Dalam rangkaian riset di bawah program Making All Voices Count, beragam lembaga riset di Indonesia meneliti ketepatgunaan teknologi untuk mendorong kapasitas pemerintahan. Kesimpulannya cukup lugas: teknologi tepat guna mensyaratkan ketepatan membaca konteks dan peluang. Beberapa penelitian dalam konteks e-government menunjukkan bahwa pelibatan pengguna dan kejelian dalam membaca teknologi tepat guna akan lebih mudah mendorong penyelesaian masalah. Contohnya, pengaduan masyarakat yang bisa disampaikan melalui aplikasi Lapor!, oleh warga Bojonegoro tidak banyak digunakan karena mereka lebih gemar menyampaikan aduan via siaran radio atau melalui dialog terbuka di pendopo bupati.
Dalam kiprahya terdahulu, mendikbud memang berhasil mendorong optimasi ojek sehingga menjadi sebuah disrupsi. Namun, jangan lupa: disrupsi itu berhasil karena sistem transportasi kita yang sama sekali tidak mumpuni. Publik juga lupa bahwa di balik disrupsi yang dihasilkan oleh transportasi daring, persoalan utamanya masih belum diatasi: ketiadaan sistem transportasi publik. Namun berhubung transportasi daring kemudian sudah sedemikan menancap dalam keseharian kita, kehadirannya telah menjadi kenormalan. Sebaliknya, ketiadaan transportasi publik pun hingga kini dianggap normal. Jika cara berpikir demikian yang digunakan seorang menteri, maka kita semakin berhak untuk berprasangka buruk kepada inisiatif-inisiatif yang ditawarkan.
Teknologi Tetap Dibutuhkan
Tulisan ini tidak berpandangan anti-teknologi. Justru sebaliknya, saya berpendapat bahwa teknologi sangat dibutuhkan. Hanya saja, kapasitas kelembagaan dan relevansi teknologi harus sejalan. Contohnya adalah bagaimana teknologi dapat berperan penting dalam memastikan kemutakhiran data yang diperlukan seorang menteri untuk mengambil keputusan. Sangat penting bagi seorang pimpinan lembaga untuk memiliki ruang kendali (bahasa kerennya: war room) yang bisa memperbaharui informasi dengan cepat. Penulis sangat berharap semua pimpinan lembaga memiliki dashboard terbaik dengan angka dan indikator terakurat yang ia butuhkan. Hal yang tidak bisa ditawar adalah data yang akurat, berkualitas dan dapat diakses dengan cepat. Ketersediaan perangkat seperti ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam mengambil keputusan, terutama yang bersifat lintas sektor. Jika data yang terdapat antar kementerian saja tidak sama, maka klaim akan terobosan dalam bentuk perangkat lunak sangatlah muskil.
Dengan demikian, pekerjaan rumah yang nyaris abadi bagi semua kementerian adalah merapikan dan mengkonsolidasikan data demi menguatkan kapasitas kelembagaan. Sebab, jika masalah persoalan kelembagaan tidak dituntaskan, maka teknologi yang paling efektif bagi seorang pejabat publik—sebagaimana kita pelajari dari Bu Risma—hanyalah marah-marah.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.