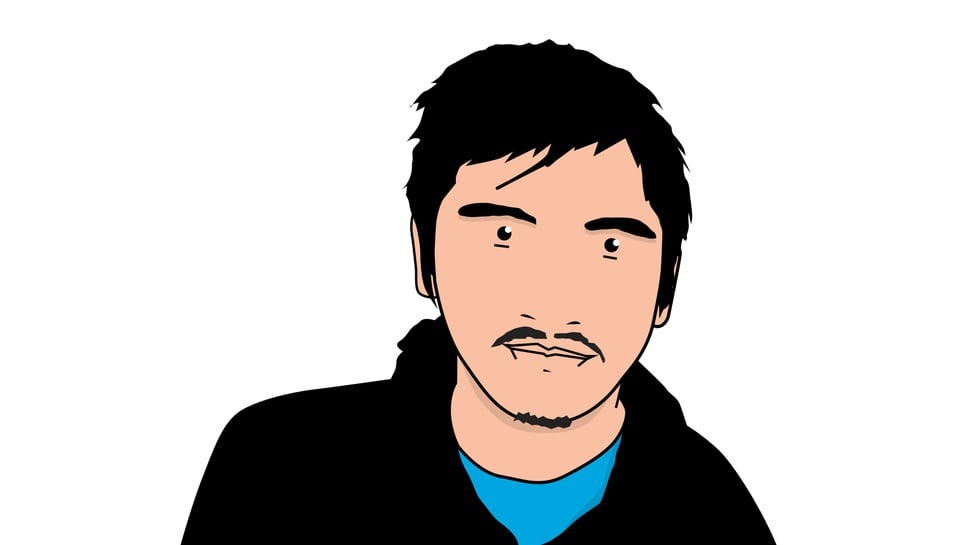tirto.id - Kecurigaan Ahok terhadap "Romo" Sandyawan menggemakan kembali politik massa mengambang.
Seperti diberitakan Viva (14/9), Ahok menuding Sandyawan Sumardi menghambat upaya penggusuran warga Bukit Diri yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Advokasi yang dilakukan Sandyawan terhadap warga yang akan digusur, dengan mengajukan class action terhadap Pemerintah Provinsi DKI dan menawarkan konsep alternatif penataan bantaran kali, dicurigai Ahok sebagai "mau main klaim". Selain menyeret asal-usul Sandyawan sebagai "bekas Romo", Ahok juga membawa-bawa domisili Sandyawan sebagai warga Kampung Pulo, bukan warga Bukit Duri.
Pernyataan Ahok ini segendang-sepenarian dengan pendukung Ahok yang, salah satunya, menuduh orang-orang yang menolak penggusuran sebagai orang yang "hidup dari proyek kemiskinan". Tuduhan "menghambat pembangunan" atau "menjual kemiskinan", bersama istilah "provokator", bukan kosa kata yang baru dalam sejarah politik Indonesia. Cap macam itu sangat lazim dipakai di era Orde Baru dan amat biasa ditempelkan ke jidat siapa saja yang dianggap berseberangan dengan agenda-agenda negara.
Entah apa pula maksudnya Ahok membawa-bawa latar belakang Sandyawan sebagai bekas Romo dan bukan warga Bukit Duri. Namun rasa-rasanya, upaya Ahok menyeret-nyeret latar belakang Sandyawan ini segendang-sepenarian dengan polah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang beberapa kali bertanya asal-usul ("Anda orang mana? Anda dari mana?") kepada orang-orang yang mempersoalkan keberpihakan Ganjar kepada proyek pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng.
Mudah menebak ke mana pertanyaan itu hendak dibawa: delegitimasi para penentang karena bukan korban langsung sebuah kebijakan. Kira-kira begini nalarnya: karena Anda bukan warga Bukit Duri, tidak usah sok-sokan membela korban penggusuran, karena Anda bukan warga Kendeng tidak perlu sok heroik berpihak kepada para petani.
Nalar macam itu bukan hanya dipakai oleh Ahok atau Ganjar melainkan lazim dipakai oleh, terutama, aparat negara saat berhadapan dengan "orang-orang luar" yang masuk ke arena konflik. Saya pernah diusir aparat desa saat menemani warga yang memprotes galian pasir di sebuah kecamatan di Cirebon. Kawan-kawan yang sering terjun ke wilayah konflik saya kira sudah kenyang dengan nalar macam itu.
Ini sudah menjadi semacam modus operandi untuk memutus jejaring solidaritas lintas wilayah, lintas golongan, bahkan lintas kelas. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengisolir warga yang sedang menentang kebijakan pemerintah dari dunia luar. Warga dikondisikan untuk menjadi "cupet", agar membayangkan bahwa persoalan yang sedang mereka hadapi adalah persoalan yang terpisah dari dunia, tak berkait dengan agenda-agenda besar yang melampaui geografi kampungnya sendiri.
Secara bersamaan, warga dirancang agar tidak berpikir bahwa persoalan yang mereka hadapi juga dihadapi oleh warga-warga yang lain di tempat yang berbeda. Nalar macam itu menghendaki warga berada dalam posisi sendirian, memikul beban dan persoalan secara mandiri, untuk memastikan warga tidak mendapatkan dukungan dari "orang luar". Dengan sendirinya, jika siasat macam ini berhasil, warga akan benar-benar merasa sunyi, merasa sepi, untuk kemudian frustrasi dan akhirnya menyerah.
Bayangkanlah efek moral yang dirasakan warga kala didatangi warga dari tempat yang jauh, yang sama-sama menghadapi persoalan dengan negara. Menyaksikan bagaimana seorang warga mengisahkan cerita sukses tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan olehnya dan tetangga-tetangganya kepada warga di tempat berbeda yang sedang terjepit oleh penetrasi negara/korporasi selalu menjadi momen yang berharga. Solidaritas muncul dengan organik, perasaan senasib menyeruak dengan meyakinkan, dan keberanian serta semangat pun mencuat kembali.
Nalar bahwa "orang luar tidak boleh ikut campur" ini juga mengandaikan bahwa warga pada dasarnya tidak pernah bermasalah dengan agenda-agenda negara. Warga dibayangkan sebagai makhluk-makhluk naif yang secara alami selalu menerima niat baik negara dengan tulus. Sehingga jika ada warga yang berserikat untuk menolak agenda-agenda negara, hal itu sudah pasti bukan tindakan yang alamiah.
Gema "negara organik", atau "negara integralistik" ala Soepomo, pun tercium keras. Secara singkat bisa dikatakan bahwa negara organik membayangkan bahwa tidak ada ketegangan antara negara dan rakyat. Keduanya adalah manunggal. Rakyat dan pemimpin itu tidak terpisah-pisahkan. Negara-bangsa dibayangkan sebagai sebuah keluarga besar, dengan pemimpin sebagai bapak dan rakyat sebagai anak-anaknya. Tidak pada tempatnya mencurigai sang bapak hendak mencederai anak-anaknya. Segala yang dilakukan sang bapak, jika pun dirasa merugikan, semuanya untuk kebaikan anak-anaknya.
Dalam jawabannya untuk Hatta yang mengusulkan hak-hak warga negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar di sidang PPKI, Soepomo mengatakan: "Tuan Hatta bertanya bagaimana haknya orang seorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh pemerintah. Pertanyaan ini berdasar atas kecurigaan kepada pemerintah yang dalam menyelenggarakan kepentingan negara dianggap selalu menentang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pernyataan Tuan Hatta timbul dari sikap individualisme, yang kami tolak."
Konsep negara organik macam itu diterjemahkan Ali Moertopo pada 1972, melalui tulisan berjudul 'Dasar-Dasar Pemahaman tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun', ke dalam siasat "politik massa mengambang". Siasat ini pada dasarnya adalah sebentuk depolitisasi warga, menjauhkan warga dari diskursus politik. Dalam bentuk yang konkrit, politik hanya boleh sampai di tingkat Kabupaten/Kotamadya, tidak boleh masuk hingga level kecamatan apalagi tingkat desa. Jika pun hendak berpolitik, hanya boleh melalui saluran resmi yaitu lewat dua partai (PPP-PDI) dan Golkar.
Mudah ditebak siasat ini hanya menguntungkan Golkar. Dibandingkan PPP dan PDI, hanya Golkar yang infrastruktur politiknya dapat menjangkau hingga pelosok-pelosok desa. Melalui aparat birokrasi dan organisasi-organisasi turunannya (dari PGRI, Korpri, Dharma Wanita, PKK, hingga pemerintah desa yang diawasi oleh Koramil, Polsek dan Babinsa), Golkar akan dengan mudah menancapkan kepentingan politiknya dengan demikian intens.
Moertopo mendasarkan argumentasinya kepada mendesaknya agenda-agenda pembangunan yang tidak boleh diganggu oleh kancah perjuangan politik partai dan golongan. Dalam kalimatnya Moertopo: "...sudah selayaknya bila rakyat, yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan, dialihkan perhatiannya dari masalah sempit dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing."
Dari situlah genealogi istilah "provokator" masuk ke dalam kosa kata politik Indonesia. Dibayangkan bahwa orang-orang luar, semacam Sandyawan Sumardi atau siapa pun itu, sebagai biang kerok munculnya inisiatif perlawanan warga. Tanpa orang luar, warga yang dianggap masih bodoh, kurang berpendidikan, tidak rasional, mustahil punya keberanian atau punya inisiatif menentang agenda-agenda negara. Orang-orang luar, entah atas nama advokasi atau pendampingan atau solidaritas atau apa pun, dianggap sebagai intervensi nurture terhadap nature, yang merongrong kedamaian dan ketenteraman, sebab pandangan bahwa desa manut kepada negara adalah hal yang alami, sudah dari sononye, sudah dengan sendirinya.
Jika orang seperti Sandyawan Sumardi, yang rekam jejak keberpihakannya merentang dari peristiwa Waduk Kedung Ombo dan kasus Mei 1998 hingga penggusuran di Bukit Duri, pernah dituduh “komunis” oleh Orde Baru, hal itu adalah konsekuensi logis dari usaha masif melakukan depolitisasi rakyat di akar rumput, di desa-desa, maupun di wilayah urban. Tuduhan “komunis” kepada orang seperti Sandyawan Sumardi di masa Orde Baru dulu menjelaskan satu hal penting: pengakuan negara Orde Baru bahwa (hanya) PKI yang memang paling getol melakukan praktik-praktik politik hingga ke pelosok-pelosok desa.
Padahal ya tidak begitu juga. Sebelum Orde Baru, sangat biasa partai-partai melakukan penggalangan massa, memberikan pendidikan politik, hingga level terkecil masyarakat. Kendati PKI yang memang paling menonjol melakukan “politik turba”, namun partai-partai lain juga sangat bergairah mendatangi massa rakyat. Tidak heran jika di masa itu, rakyat yang buta huruf sekali pun, kendati hanya seorang petani atau tukang becak, bisa memiliki sense of politic yang kuat.
Para politisi, kepala daerah, para jenderal atau menteri dan presiden yang masih berpikir bahwa penolakan warga terhadap agenda-agenda negara sebagai tindakan yang tidak alamiah, menyimpang, dan mengganggu ketertiban bukan hanya ketinggalan zaman atau gagap membaca perubahan mas(s)a tapi juga masih merasa dirinya sebagai “bapak” yang serba-berhak menilai dan memutuskan apa yang terbaik bagi rakyat yang terus dianggap sebagai (kek)anak-anak(an).
Orde Baru, apa boleh bikin, memang sudah telanjur menyelinap hingga ke urat-urat.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.