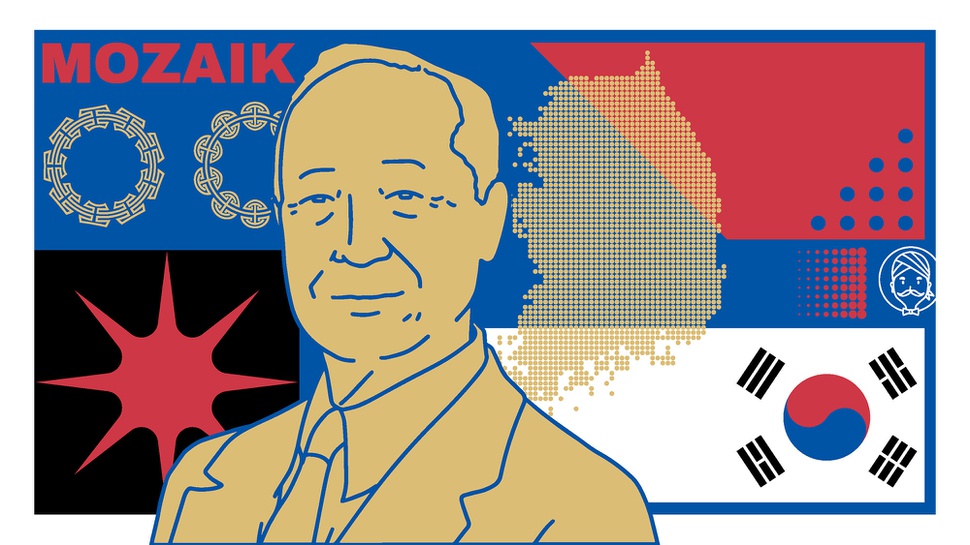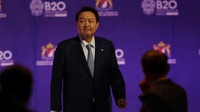tirto.id - Di penghujung tahun 1943, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina mengadakan pertemuan tinggi di Kairo untuk menentukan masa depan Asia jika Jepang menyerah dan Perang Dunia II berakhir. Salah satu kesepakatan dari pertemuan itu ialah membiarkan Korea menjadi negara berdaulat yang didirikan oleh kaum nasionalisnya, tentu dengan “bimbingan” Sekutu khususnya AS. Kabar ini jelas dimaknai bahwa Korea yang saat itu dijajah Jepang akan mendapat kemerdekaan di masa depan.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada 6 dan 9 Agustus 1945, AS menghajar Jepang lewat bom atom yang membuat kekuatan Jepang semakin melemah. Dari sini, tanda-tanda kekalahan Kaisar Hirohito (1926-1989) sudah terlihat, yang artinya panggung PD II akan segera berakhir. Berita ini menjadi angin segar bagi penduduk di seluruh wilayah yang diduduki Dai Nippon. Di Indonesia, berita ini berdampak besar karena berujung pada percepatan proklamasi kemerdekaan. Begitu juga yang terjadi di Korea.
Penduduk Korea menanggapinya dengan suka cita. Mimpi mereka untuk hidup dalam satu negara berdaulat seperti yang terjadi 35 tahun sebelumnya ketika Kekaisaran Korea (1897-1910) masih utuh sudah didepan mata.
Namun, semua tidak semulus yang dibayangkan.
Pada 11 Agustus 1945, Uni Soviet merangsek ke Semenanjung Korea dari utara untuk melucuti militer Jepang. Tindakan ini membuat AS ketakutan karena khawatir Soviet akan terus bergerak ke selatan dan menguasai seluruh wilayah Kores. Untuk membatasi ruang gerak Soviet, militer AS secara sepihak membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian berdasarkan garis 38 derajat Lintang Utara, suatu garis sembarang pada peta yang tidak sesuai dengan kondisi geografi dan budaya.
Seiring memanasnya persaingan antarkubu, kedua bagian itu menjelma menjadi negara dengan ideologinya masing-masing: Republik Rakyat Demokratis Korea (Utara) dan Republik Korea (Selatan)—yang keduanya dipimpin oleh tokoh lokal pilihan Soviet dan AS: Kim Il-Sung dan Syngman Rhee.
Kepercayaan dan Sokongan AS
Dalam pergerakan nasional di Korea, Syngman Rhee (ejaan lain: Ri Seung Man) bukan nama yang asing. Lahir pada 26 Maret 1875, tepat hari ini 147 tahun lalu, Rhee telah terjun ke dunia pergerakan sejak usia 20 tahun dengan ikut dalam gerakan kritik terhadap monarki Korea—meskipun ia sendiri masih keturunan bangsawan.
Langkah ini membuatnya menjadi incaran aparat hingga dipenjara pada tahun 1897 dan baru dibebaskan pada tahun 1904. Selepas menjalani masa hukuman, ia terbang ke AS untuk bersekolah. Kepiawaiannya dalam berbahasa Inggris dan dana yang memadai, membuat dirinya dapat lancar menempuh pendidikan dari sarjana hingga doktoral. Keberhasilan ini juga menjadikan Rhee sebagai orang Korea pertama yang mendapat gelar doktor.
Hampir setengah abad hidup Rhee dihabiskan di Negeri Paman Sam. Mengutip Britannica, di sana ia banyak melakukan lobi-lobi politik untuk mencapai kemerdekaan karena posisinya sebagai juru bicara kemerdekaan Korea.
Pada tahun 1925, ia diangkat menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Korea atau Korean Provisional Government (KPG). KPG adalah pemerintahan pengasingan yang dibentuk pada tahun 1919 oleh nasionalis Korea di Shanghai. Tujuannya untuk menjaga api perjuangan kemerdekaan Korea dalam melawan kolonialis Jepang.
Rhee menjabat selama dua periode, tahun 1919-1925 dan 1947-1948. Selama itu, ia banyak menjalankan roda pemerintahan dari AS, baik di Hawai atau di Washington D.C. Keberadaanya di sana tidak lepas dari keinginannya untuk meraih simpati AS agar mendukung gerak langkahnya.
Baginya, sebagaimana disampaikan Lee Sang-Hoon dalam “Syngman Rhee’s Vision and Reality” (2011), AS adalah negara yang telah mengaktualisasikan semangat kemerdekaan yang membuat manusia menikmati kebebasan sejak lahir. Inilah yang ingin ia terapkan ketika Korea merdeka. Pandangan ini pula yang kelak menjadi sebab Rhee bersikap anti-komunis.
Ketika Semenanjung Korea terbagi dua, Rhee dibawa oleh AS pada Oktober 1945 untuk diperkenalkan kepada penduduk di selatan. Menurut peneliti Universitas Incheon Kim Hakjoon di CNN, pemulangan Rhee tidak terlepas dari keinginan AS untuk memiliki figur anti-komunis yang dapat menggalang persatuan masyarakat guna menangkal perluasan pengaruh Soviet di daratan Korea.
Saat itu, pria lulusan Harvard ini tidak terlalu dikenal karena terlalu lama tinggal di AS. Ia kalah pamor dengan tokoh gerakan lain seperti Song Jin Woo dan Chang Duk Soo. Namun, menurut Max Hasting dalam The Korean War (1988: 41), urusan pamor bukan persoalan bagi Rhee. Pemahaman intelektual tentang demokrasi yang tinggi dan kedekatan dengan AS menjadi modal utama untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Dan ini terbukti ketika lambat laun sokongan AS semakin kuat dan tokoh politik lain namanya meredup. Ia akhirnya memenangkan Pemilu 1948 dan resmi menjadi presiden pertama Republik Korea atau Korea Selatan.
Bara Anti-Komunis
Sejak Syngman Rhee menjadi presiden pada 26 Juli 1948, dunia politik Korsel langsung berubah. Sebagaimana diungkap Michael J. Seth dalam A History of Korea (2011), politik Korsel didominasi oleh ketakutan terhadap komunis. Sikap ini semakin menjadi-jadi ketika Soviet melebarkan sayap komunisme di Korea dan beberapa wilayah dunia lainnya yang menandai persaingan ideologi yang kelak dikenal sebagai Perang Dingin.
Selama lebih dari satu dekade kepemimpinan Rhee (1948-1960), terjadi rangkaian peristiwa yang menjadi catatan kelam dalam sejarah Korsel. Pandangan anti-komunis menjadikan Rhee sebagai sosok yang otoriter dan bertangan besi, jauh dari cita-cita demokrasi yang diutarakannya. Ia tidak segan menghabisi dan memusnahkan segala sesuatu yang berbau komunis di Korsel.
Rhee membangun pemerintahan yang berisi para pengikut setianya agar dapat leluasa membuat berbagai kebijakan. Hampir seluruh anggota Majelis Nasional, birokrat, dan pihak keamanan adalah pendukung setia Rhee. Untuk menangkap orang yang tidak sejalan, lahir UU Pengkhianatan Nasional dan UU Keamanan Nasional. Aturan ini tulis Michael J. Seth, mendorong terjadinya pembersihan besar-besaran untuk menjaring simpatisan komunis. Enam puluh ribu orang dari berbagai elemen masyarakat dan institusi terpaksa masuk penjara. Bagi Rhee, mendukung komunis adalah mengkhianati negara dan mengganggu keamanan nasional.

Rhee berulang kali memerintahkan pembunuhan terhadap pendukung gerakan kiri. Salah satu yang terkenal adalah Pemberontakan Jeju. Dalam peristiwa yang terjadi dari bulan April 1948 sampai Mei 1949 itu, pasukan anti-komunis Rhee membunuh puluhan ribu--versi lain menyebut ratusan ribu--penduduk Pulau Jeju yang menyatakan dukungan terhadap komunisme dan penolakan terhadap pemerintahan Korsel.
Kebencian Rhee terhadap komunis semakin besar ketika Perang Korea (1950-53) pecah, apalagi setelah ibu kota Seoul diinjak-injak militer Korut. Rhee yang menjadi penyulut utama pertempuran kerap memberikan pidato, mengorganisasi rapat umum, dan menggunakan setiap kesempatan untuk menyerukan perang sampai Korea bersatu kembali. Namun, ambisi ini tidak terwujud karena PBB berhasil mendorong resolusi gencatan senjata pada 1953, meskipun tanpa persetujuan Rhee.
Setelah perang berakhir, infrastruktur Korsel luluh lantak dan angka kemiskinan meningkat. Dalam kurun 1953-1960, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Korsel mandek. Korupsi di kalangan elite dan intimidasi terhadap rakyat menjadi hal lazim. Oposisi dihabisi dan pers dibungkam. Proses pemilu dimanipulasi. Rhee juga dapat mempertahankan kursi kepresidenannya lebih lama, apalagi usai Majelis Nasional menghapus pembatasan jabatan presiden pada tahun 1952.
Di sisi lain, dampak dari tindakan otoriternya ini membuat AS dan masyarakat tidak lagi simpati. AS terus mengurangi bantuan dana setiap tahunnya sebagai bentuk protes. Masyarakat perkotaan Korsel, khususnya mahasiswa, yang semakin terbuka berhasil melakukan mobilisasi untuk melakukan demonstrasi penurunan Rhee. Pada 26 April 1960, Rhee akhirnya mengundurkan diri dan pergi ke Hawai hingga akhir hayatnya.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Irfan Teguh Pribadi