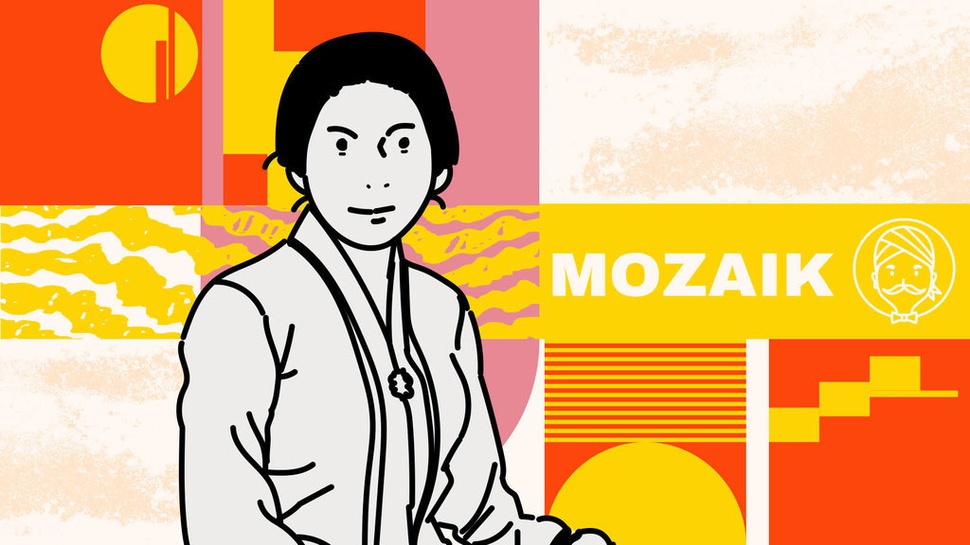tirto.id - Suatu hari di bulan Juni 1912, seorang lelaki bernama Ibrahim mendapat gelar adat Datuk Tan Malaka dalam sebuah upacara adat masyarakat Minangkabau yang berlangsung di Pandan Gadang, Sumatra Barat.
Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, ia mengenakan nama Tan Malaka sebagai identitasnya. Namun, perayaan upacara adat pada hari itu terasa kurang meriah. Sebab, sejatinya setelah pemberian gelar, acara dilanjutkan dengan prosesi mengikat diri dalam pertunangan. Untuk hal ini, Tan Malaka menolaknya.
"Menurut perkiraan kawan-kawannya, Tan Malaka tidak mau bertunangan karena ia [hanya] mau kawin dengan satu-satunya murid perempuan di sekolah guru, yakni Syarifah Nawawi," tulis Harry A. Poeze dalam Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 (2000).
Nahas, cintanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan, saat merantau ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di sekolah guru Haarlem, ia rutin menyurati surat cinta untuk pujaan hatinya. Namun, tak satupun pernah terbalaskan. Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan utama cintanya ditolak.
Mengutip Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan (2010), pada tahun 1980 Harry A. Poeze--sejarawan yang banyak menulis buku tentang Tan Malaka--pernah menemui Syarifah untuk mencari tahu alasan dirinya menolak cinta dari laki-laki revolusioner yang pernah menaksirnya.
Namun, dalam pertemuan itu, tidak banyak informasi yang didapat. Ia hanya berkata, "Tan Malaka? Hmm, dia seorang pemuda yang aneh."
Raden Ayu Bandung
Syarifah Nawawi lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 1896. Ia anak keempat dari pasangan Chatimah dan Engku Nawawi Sutan Makmur, seorang guru di Kweekschool atau lebih dikenal Sekolah Raja di Bukittinggi.
Mengutip Drs. Isma Tantawi, M. A. dalam Terampil Berbahasa Indonesia (2019, hlm. 26), bersama dengan Muhammad Taib Sutan Ibrahim, Engku Nawawi Sutan Makmur terlibat dalam penyusunan ejaan van Ophuijsen yang mulai diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1901.
Sadar akan pentingnya pendidikan modern, Engku Nawawi mendorong anak-anaknya, termasuk Syarifah, untuk mengenyam pendidikan formal di Europeesche Lagere School (ELS), yang berhasil dituntaskannya pada tahun 1907.
Tidak lama setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Kweekschool tempat ayahnya mengajar. Dari total 75 murid seangkatannya, ia satu-satunya murid perempuan dan dikenal sebagai murid yang cerdas.
Sekitar tahun 1914, setamatnya dari Kweekschool, ia bersama adiknya, Syamsiar, dikirim ayahnya ke Batavia untuk mengenyam pendidikan di sekolah Kristen, Salemba Kostschool. Sejak saat itu, Syarifah dikenal sebagai "perempuan Minang pertama yang menempuh sistem pendidikan sekolah Eropa," tulis Selfi Mahat Putri dalam Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20 (2018).
Di Batavia, ia dan adiknya menjalin hubungan pertemanan dengan seorang putri Cianjur bernama Tjoetjoe. Saking dekatnya pertemanan mereka, saat libur Natal tahun 1914, kakak-adik tersebut diundang oleh Tjoetjoe untuk berlibur ke kampung halamannya.
Setibanya di Cianjur, keduanya bertemu dengan Bupati Cianjur saat itu, R. A. A. Wiranatakusumah V, yang merupakan suami Tjoetjoe. Dalam pertemuan itu, tak disangka-sangka sang Bupati jatuh cinta kepada Syarifah. Bahkan, di hari-hari berikutnya, ia kerap dikirimi surat.
"Pikirannya terganggu dan terkacau oleh perhatian pria ini, ia jauh lebih tua, anggota ningrat Sunda [...] Anaknya telah lima orang, seorang putra dari perkawinannya yang pertama dan seorang putra serta tiga putri dari perkawinannya yang kedua," tulis Syarifah dalam buku hariannya dikutip dari otobiografi putri bungsunya, Mien Soedarpo, yang berjudul Kenangan Masa Lampau (1994).
Selain itu, gaya hidup sang Bupati dirasa sangat asing baginya. Terlebih, sebagai perempuan yang mengenyam pendidikan modern, ia masih menyimpan pengharapan untuk dapat mengembangkan dirinya.
Namun pada Mei 1916, keduanya menikah dan dikaruniai dua anak laki-laki--yang kedua meninggal saat masih berusia 2 tahun--dan dua anak perempuan. Empat tahun kemudian, suaminya diangkat sebagai Bupati Bandung dan Syarifah memangku gelar Raden Ayu Bandung.
Mengutip kembali Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan (2010), keputusannya menerima pinangan Wiranatakusumah V, memunculkan sebuah anekdot yang menyebutkan bahwa Tan Malaka memantapkan dirinya menjadi seorang komunis untuk melawan kaum feodal yang telah merebut pujaan hatinya.
Pada tahun 1923, keduanya berencana untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Namun, rencana tersebut batal. Tanpa alasan yang jelas, Wiranatakusumah V memutuskan untuk pergi haji seorang diri. Syarifah diperintahkan untuk menunggu kepulangannya di Bukittinggi, bersama anak-anaknya.
Tidak banyak mendebat, ia memenuhi titah sang suami dan tiba di rumah orang tuanya pada 28 Maret 1924. Kesempatan itu ia gunakan untuk beristirahat panjang setelah melahirkan putri bungsu sambil menunggu kepulangan suaminya.
Namun, di tengah masa menunggu, suaminya tiba-tiba mengajukan perceraian melalui telegram yang diterima oleh Engku Nawawi Sutan Makmur pada 17 April 1924. Alasannya, Syarifah dirasa "kurang luwes dan kurang bisa menyesuaikan diri dengan tradisi dan tata hidup Sunda," terang Mien Soedarpo (1994).
Berita perceraian menyebar dengan cepat melalui surat kabar yang diwarnai reaksi keras dan kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Haji Agus Salim. Menurutnya, alasan gugatan cerai itu terlalu dibuat-buat.
Lebih lanjut, Agus Salim menilainya sebagai bentuk penghinaan kepada kaum ibu dan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Sebab, dilakukan pada waktu yang kurang pantas, terutama saat melaksanakan ibadah haji.
Mengutip kembali Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan (2010), berita perceraian tersebut terdengar oleh Tan Malaka. Ia mencoba kembali untuk meminang cinta pertamanya, Syarifah. Nahas, untuk kedua kalinya ia kembali ditolak.
Setelah Perceraian
Mengutip kembali buku Mien Soedarpo (1994), setelah diceraikan, ia tidak pernah menikah lagi. Syarifah kemudian bekerja sebagai epala sekolah de Meisjes Vervolg School (sekolah lanjutan perempuan) yang didirikan pemerintah kolonial di Bukittinggi. Pekerjaan itu diembannya dalam kurun waktu sepuluh tahun (1927-1937).
Kesedihan kembali menghampiri. Ayah dan sang ibu, meninggalkannya untuk selama-lamanya, masing-masing pada tahun 1928 dan 1937. Setelah itu, ia bersama putri bungsunya memutuskan untuk tinggal di Batavia.
Setelah satu tahun tinggal di Kwitang No. 8, ia pindah ke Laan Bafadel, Meester Cornelis (Jatinegara), dan mulai bekerja sebagai Kepala Sekolah Kemajuan Istri milik Yayasan Kartini yang saat itu diketuai Siti Katidjah, kakak perempuan Achmad Soebardjo.
Dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat (1982) disebutkan, selain aktif dalam pendidikan, ia juga aktif dalam organisasi Serikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS) yang didirikan Rasuna Said pada 1912.
Mengutip surat kabar De Sumatra Post (10/3/1941), pada akhir 1940, Syarifah termasuk dalam sebuah Komisi Inspeksi Film di Hindia Belanda yang diketuai oleh pensiunan serdadu artileri, Letnan Kolonel R. F. C. Smith.

Pada masa pendudukan Jepang, setelah mengundurkan diri sebagai kepala sekolah, Syarifah melibatkan diri dalam organisasi wanita, Fujinkai. Atas tawaran dari teman-teman Belandanya, ia bersedia untuk pindah tempat tinggal ke Jalan Pegangsaan Barat No. 16. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengelabui militer Jepang yang kapan saja dapat merampas rumah dan aset-aset mereka.
Pada Desember 1945, ia mendirikan organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).
"Di samping keterpautan organisasi, ia meneruskan kegiatan pendidikannya dan memberi pengajaran kepada anak perempuan serta wanita muda yang tidak mempunyai biaya pendidikan. Mula-mula, ibu memakai sebuah kamar di rumah Ny. Abdoerachman untuk kegiatan pendidikan ini, kemudian ia memakai rumahnya sendiri," terang Mien Soedarpo (1994).
Sebagai pengakuan atas sumbangsihnya dalam memajukan pendidikan perempuan, ia menerima beberapa piagam penghargaan. Potret dirinya masih tetap tergantung di gedung Panti Trisula Perwari.
Dalam buku Biografi Selasih dan Karyanya (1995), sebagai salah satu simbol emansipasi di tanah Minang, Sariamin Ismail alias Selasih--novelis wanita angkatan Pujangga Baru--pernah membuat sebuah puisi untuk Syarifah berjudul "Beringin Sakti".
Memasuki tahun 1984, kesehatannya mulai terganggu. Namun, kepada anak-anaknya ia berpesan, jangan sekali-kali dirinya dibawa ke rumah sakit, sekalipun jika kesehatannya semakin terganggu. Sebab, ia ingin meninggal dunia tempat tidurnya sendiri.
"Akhirnya tengah hari pada Ahad tanggal 17 April 1988, persis pada tanggal ketika 64 tahun sebelumnya dia menerima telegram mengenai perceraiannya, ibuku berpulang ke Rahmatullah. [...] Dia dimakamkan di Tanah Kusir," pungkas Mien Soedarpo dalam Kenangan Masa Lampau II (1997).
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi