tirto.id - Lima puluh menit pertama Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (selanjutnya disebut Sultan Agung) dibalut kisah cinta ala-ala Crazy Rich Asian, film garapan Jon Chu yang diadaptasi dari novel laris Kevin Kwan.
Sultan Agung remaja, yang masih bernama Raden Mas Rangsang (Marthino Lio), dikirim ke sebuah padepokan untuk belajar ilmu tarung dan agama. Di sana, identitasnya dirahasiakan. Sehingga ketika Lembayung (Putri Marino) jatuh cinta pada Rangsang, ia tak menyangka bahwa pemuda itu adalah pangeran Kerajaan Mataram.
Namun, Lembayung tak akan sempat dibawa ke istana oleh kekasihnya, seperti Rachel Chu diboyong Nick Young ke Singapura untuk bertemu keluarga taipannya. Hubungan Lembayung-Rangsang kandas, saat sang ayahanda Panembahan Hanyokrowati wafat. Lembayung yang hanya anak lurah tak akan punya peluang dipersunting sang pangeran.
Keadaan Mataram yang “tengah tak aman karena pengkhianat dan perampok sedang bekerjasama untuk meruntuhkan keraton” membuat penasbihan Rangsang sebagai Panembahan Hanyakrakusuma dipercepat. Dalam prosesnya, ia juga dituntut untuk segera menikahi Putri Adipati Batang (Anindya Kusuma Putri) agar Mataram lebih kuat.
Sutradara Hanung Bramantyo, dalam babak ini, tampak fokus membangun motivasi karakter Sultan Agung yang ia gambarkan ambisius, pantang takut, tegas, dan pemarah. Proses Rangsang menjadi raja memang tak mudah belaka. Ia sebenarnya lebih ingin jadi ulama, sebab sebagai anak dari istri kedua, rangsang memang tak digariskan jadi raja. Lagipula ia ingin bisa mempersunting Lembayung, cinta pertamanya. Menjadi raja hanya akan menghalangi hasrat pribadi itu.
Lima puluh menit pertama ini adalah bagian yang paling bisa dinikmati. Lakon para aktor begitu cair, latar kampung padepokan di atas gunung cukup rapi dibangun, bahasa Jawa yang dipakai jadi bahasa utama juga berhasil membangun suasana. Cuma koreografi tarungnya masih cupu: terlalu patah-patah dan tak ada jurus-jurus menarik perhatian.
Sayang, ketika Sultan Agung dewasa dan sudah berganti rupa—diperankan Ario Bayu—cerita makin keteteran. Fokus Hanung mulai pecah. Naskah kelihatan masih ingin menonjolkan intrik keraton yang penuh tikam-menikam dari belakang, seperti yang berhasil ditonjolkan sinetron kolosal Game of Thrones. Tapi, di saat bersamaan, Hanung memasukkan fokus lain: Belanda sebagai musuh baru Kerajaan Mataram.
Yang terakhir tak terbangun dengan baik. Para kompeni cuma tampil jadi tempelan. Membuat perjuangan Kerajaan Mataram akhirnya terasa melempem. Lagi pula, tak ada koreografi tarung yang istimewa. Pembahasan taktik perang juga biasa saja. Tak ada twist, tak ada sinematografi yang cantik. Padahal Hanung punya potensi mengolah bagian ini.
Selain itu, sejumlah karakter yang sepertinya penting tiba-tiba muncul bersamaan. Beberapa di antaranya para pangeran dan panglima yang dikirim Sultan Agung untuk menyerbu Batavia. Sayangnya, ini dilakukan Hanung tanpa motivasi dan perkenalan yang jelas. Nama mereka memang disebut beberapa kali, tapi desain karakternya biasa saja. Semua karakter itu justru terlihat mirip, sehingga tak heran penonton susah bersimpati dan terikat dalam ceritanya. Apalagi mereka tidak diperankan aktor terkenal.
Anomali Lembayung
Hanung terang-terangan soal kesulitan mengumpulkan literasi yang mengupas karakter Sultan Agung secara dalam. Kebanyakan cerita yang ia temukan cuma mengupas peristiwa-peristiwa saja, tak ada yang menggambarkan perasaan dan karakter Sultan Agung dengan jelas, misalnya pada sang istri, anak-anaknya, atau ketika mengambil keputusan penting melakukan penyerangan ke Batavia.
“Saya harus gali lagi dari berbagai macam literatur. Saya temukan literatur dari kelompok Islam. Kerajaan Turki Osmani membuka literatur tentang kerajaan Islam. Ada alasan mengapa Sultan Agung harus menyerang Batavia,” katanya pada 13 Agustus lalu.
Sang Sultan akhirnya memilih perang karena VOC dianggap tidak memenuhi perjanjian dagang yang telah dibuat dengan Mataram. Sebab, maskapai dagang Belanda itu membangun kantor di Batavia. Hanung memasukkan unsur nasionalisme sebagai motivasi sang Sultan. Namun, meski menceritakan soal pahlawan nasional, Hanung sadar filmnya tak bisa jadi rujukan sejarah.
Soalnya, ia memang melakukan improvisasi di sana-sini. Salah satu yang paling besar adalah menambahkan karakter Lembayung sejak awal sekali. Tokoh perempuan yang jadi love interest sang tokoh utama ini benar-benar diberi porsi besar. Karakternya didesain berani, jago tarung, mandiri, pintar, dan bertekad besar.
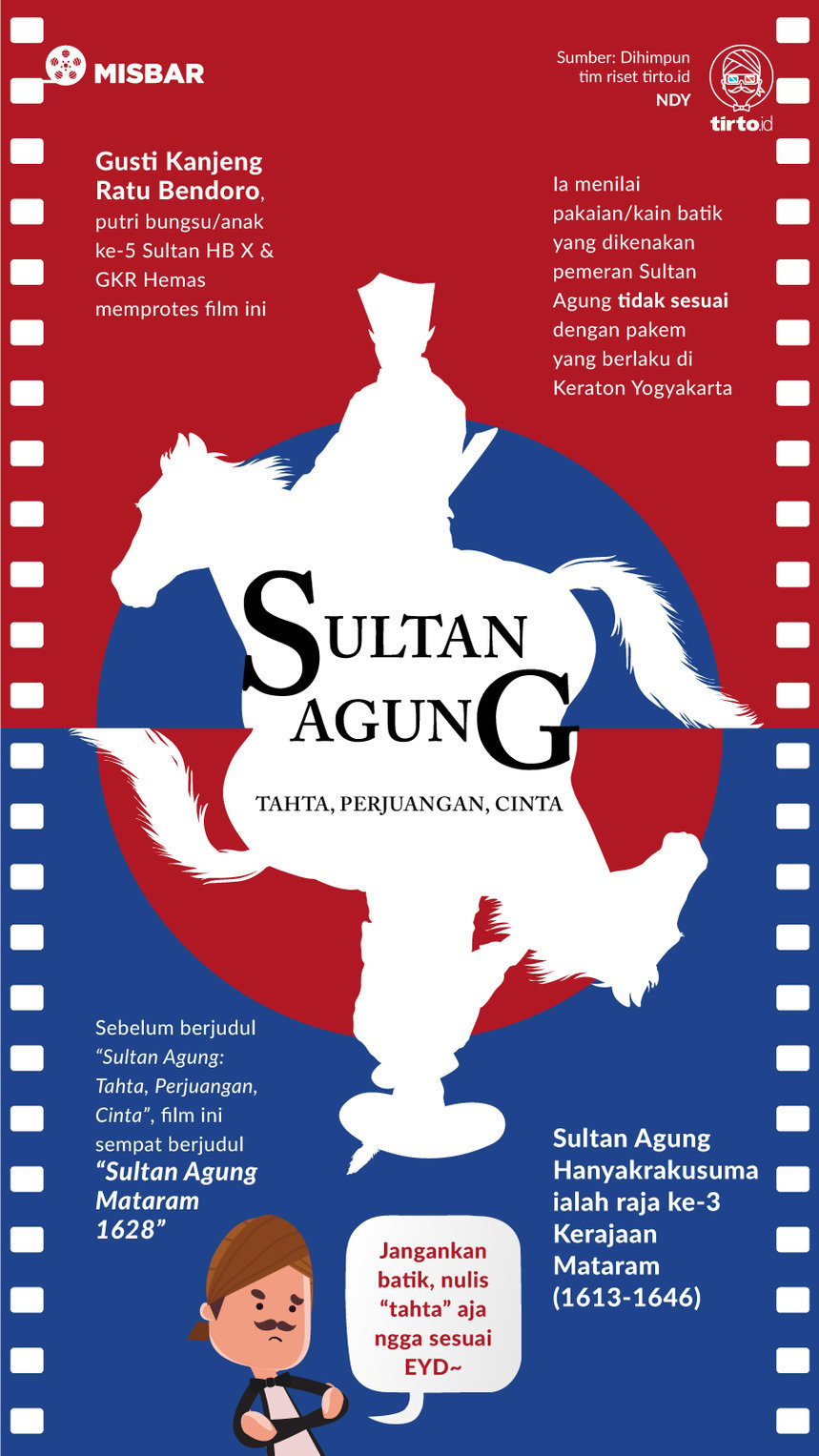
Lembayung benar-benar sempurna menjadi perempuan. Ia sama sekali tak digambarkan punya konflik apa pun, kecuali hatinya yang terkunci pada Rangsang. Tak ada yang protes ketika Lembayung mondar-mandir di dalam barisan prajurit Mataram—yang sedang bersiap menyerang benteng VOC. Ia juga tak dimarahi Ki Jejer (almarhum Deddy Sutomo) karena menyela latihan tarung murid-muridnya.
Kita juga tak akan melihat adegan orang tua atau orang kampungnya menceramahi Lembayung yang tak kunjung nikah, saat mantan kekasihnya, Sultan Agung, sudah punya anak satu yang kira-kira berumur 10 tahun. Karier Lembayung memang tak jelas. Kegiatan sehari-harinya cenderung seperti perempuan lain di film ini: belanja, memasak, membawa bakul ke sungai, menyuci, dan bergosip. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa eksistensinya benar-benar jadi anomali dari perempuan lain di sana.
Sayang, porsi besar yang disediakan Hanung buat Lembayung tak benar-benar dipakai dengan baik. Masih sulit rasanya membayangkan seorang perempuan benar-benar bisa bergerak sebebas Lembayung pada masa itu. Sosok permaisuri Sultan Agung saja nyaris hadir tanpa dialog. Di takhta paling tinggi bagi seorang perempuan pada masa itu saja, Anindya Kusuma Putri cuma berakting mendengarkan, duduk manis, menguping. Suaranya benar-benar tenggelam ditelan budaya patriarki sang suami.
Ini yang membuat Lembayung jadi susah terasa nyata. Akan lebih baik, jika ia sekalian jadi pendekar saja, sehingga tingkahnya yang suka kelayapan dan sikap "emang gue pikirin" prajurit Mataram saat melihat Lembayung ikut perang, lebih terasa masuk akal.
Hanung punya waktu yang leluasa sebenarnya. Film ini baru berakhir setelah menit ke-148—waktu yang sangat cukup untuk menjelaskan informasi tentang para pahlawan yang ada di Perang Batavia, menyusun intrik yang lebih tajam dalam politik busuk kerajaan, mempertebal karakter Lembayung, dan menjelaskan penobatan gelar Sultan Agung dengan lebih baik.
Dari 148 menit itu, Hanung cuma menyelipkan cerita tentang mengapa Panembahan Hanyakrakusuma diberi gelar kehormatan dari Arab pada menit-menit terakhir. Itu pun hanya lewat sepenggal narasi dari narator. Ujung film ini benar-benar hampa. Rasanya seperti melihat seorang pendongeng kehabisan waktu tampil di atas panggung, padahal kisahnya belum tamat.
Sayangnya, terlalu banyak babak yang bertele-tele dan tak tegas ingin bercerita apa. Terlalu banyak konflik yang tak disusun apik. Serta adegan-adegan yang perlu dijelaskan dengan lebih masuk akal. Waktu 148 menit terlalu panjang untuk sebuah kisah yang cuma bikin ngantuk.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id





























