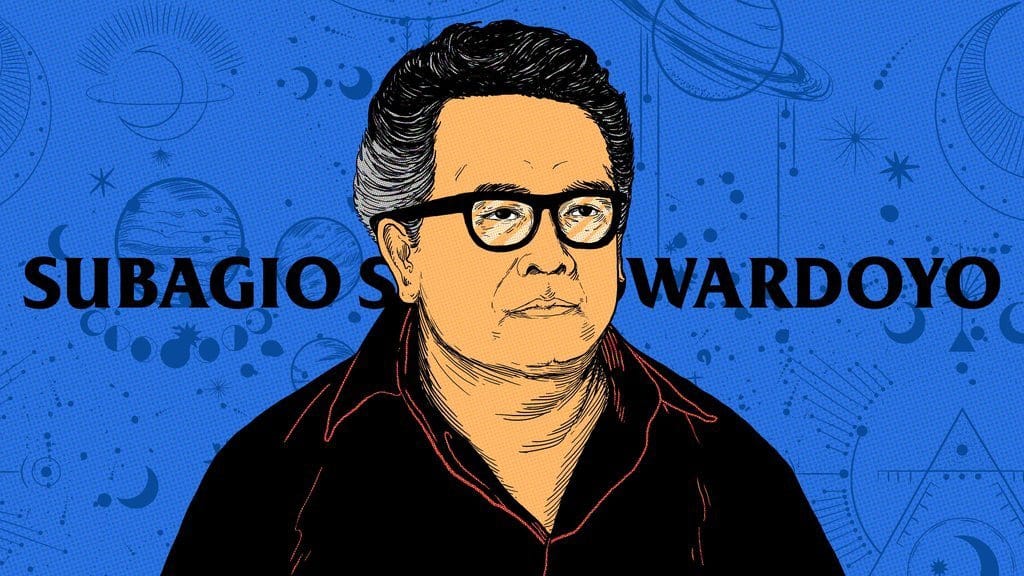tirto.id - Pada sekitar 1971 kritikus sastra Mangasa Sotarduga Hutagalung menyatakan Goenawan Mohamad adalah penyair utama di Indonesia kontemporer. Jika menilik kiprah GM hingga saat itu, pendapat Hutagalung tidak berlebihan. Sedari awal 1960-an GM sudah dikenal sebagai penulis cemerlang. Ia didapuk pula sebagai salah satu redaktur majalah sastra Horison sejak 1969. Beberapa puisinya dipublikasikan dalam antologi Manifestasi pada akhir 1960-an.Antologi puisinya yang bertajuk Parikesit (1971) pun makin mengukuhkan pendapat tersebut.
Tapi pendapat itu hanya bertahan dua tahun. Hutagalung meralat penilaiannya dalam sebuah diskusi sastra yang digelar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Menurut timbangan mutakhirnya, penyair kontemporer yang pantas menyandang predikat terunggul adalah Subagio Sastrowardoyo.
Hutagalung menilai selalu ada progres setiap Subagio menerbitkan antologi baru. Antologi Subagio yang pertama terbit pada 1957 berjudul Simphoni. Pada 1970 terbit lagi antologi Daerah Perbatasan. Sajak-sajak Subagio mengasyikkan karena lontaran gagasan yang mengejutkan dan diungkapkan secara unik.
“Rumit, tetapi selalu merangsang kita untuk dapat lebih memahaminya,” tutur Hutagalung sebagaimana dikutip harian Kompas (14/12/1973).
Di antara sekian puisi Subagio, salah satu puisi yang menurut Hutagalung cukup menunjukkan kapasitas kepenyairannya adalah "Manusia Pertama di Angkasa Luar" dari bunga rampai Daerah Perbatasan.
Dalam puisi tersebut Subagio dengan jitu memotret kegalauan manusia kontemporer di tengah kemajuan teknologi. Di masa itu nuklir, roket, dan pesawat ulang-alik sudah jadi kenyataan. Obsesi menggapai langit bukan lagi isapan jempol berkat kemajuan sains.
Subagio menulis, “Aku kini melayang di tengah ruang/Di mana tak berpisah malam dan siang./Hanya lautan yang hampa dilingkung cemerlang bintang.” Di zaman teknologi itu, angkasa luar ia citrakan sebagai puncak cita-cita kemanusiaan. Tiada lagi batas dan cita-cita lain lagi. “Sebab semua telah terbang bersama kereta ruang ke jagat tak berhuni,” katanya.
Tapi di titik tertinggi cita-cita manusia modern itu si Aku mendapati sesuatu yang agaknya di luar ekspektasinya. Di angkasa luar rupanya tak ada hal-hal spektakuler, apalagi saintifik. Ia justru terlempar pada kenangan tentang “bunga mawar dari Elisa/Yang terselip dalam surat yang membisikkan cintanya/kepadaku.” Di antara bintang-bintang si Aku mendapati dirinya rindu pada apa-apa yang ia tinggalkan di bumi: istri, anak, sanak keluarga, hingga pergantian cuaca—segala hal yang melengkapinya sebagai manusia.
Di langit yang tenang tak bertepi itu si Aku menyadari kesepiannya. Ironis, memang, tapi sayangnya, “aku telah sampai pada tepi/Darimana aku tak mungkin lagi kembali.” Pada akhirnya si Aku yang menyadari kesepian dan keterasingannya itu hanya bisa mengirimkan “Ciumku kepada istriku, kepada anak dan ibuku/Dan salam kepada mereka yang kepadaku mengenang” dan sebuah permintaan “Bunda,/Jangan membiarkan aku sendiri.”
Menurut Hutagalung, itulah cara penyair yang meninggal pada 18 Juli 1995, tepat hari ini 25 tahun silam, melukiskan manusia modern yang telah mencapai puncak kemajuan saintifik justru terasingkan dari bagian esensial kehidupan seperti emosi, kemesraan, dan perasaan rindu. Hingga kini Subagio diingat karena ketekunannya mengeksplorasi tema eksistensialisme macam ini.
Ingin Jadi Seniman
Subagio lahir di Madiun pada 1 Februari 1924. Bagio—sapaan akrabnya—bercita-cita jadi seniman sejak kecil. Maka itu sejak remaja ia memulai sendiri proses kreatifnya. Minat seninya cukup luas, tapi,selazimnya remaja, prosesnya dilalui dengan cara yang agak ugal-ugalan.
“Sedjak di sekolah menengah sudah gemar akan filsafat dan seni, sering bertengkar dan melawan gurunja, dan tidak djarang minggat dari sekolah. Dizaman Djepang Subagio beladjar melukis pada Sudjojono, dizaman revolusi menjanji di Radio Militer Jogja,” tulis majalah Horison (Februari 1967).
Usai menamatkan SMA di Yogyakarta, Subagio meneruskan studi di Jurusan Sastra Timur Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Di titik ini Subagio kian mantap menapaki jalan seni.Ia makin rajin mengikuti seminar-seminar sastra dan melibatkan diri dalam pementasan sandiwara. Lain itu ia juga mulai menulis puisi, cerpen, esai, dan kritik drama untuk diterbitkan di beberapa majalah kebudayaan. Pada 1955 cerpennya, "Kedjantanan di Sumbing", memenangkan penghargaan dari majalah Kisah.
Setamat dari UGM pada 1958, Subagio sempat mengajar di almamaternya dan beberapa lembaga. Setahun sebelum lulus sarjana, kumpulan sajak pertamanya yang berjudul Simphoni terbit. Sejak itu puisinya makin sering terbit di media massa dan menyabet penghargaan. Salah satunya adalah puisi "Dan Kematian Makin Akrab" yang memenangi kusala sastra dari majalah Horison untuk periode 1966/1967.
Pada 1961 hingga 1966 ia memperdalam lagi ilmunya pada Department of Comparative Literature di Universitas Yale, Amerika Serikat. Di tengah masa studinya, penerbit Pembangunan mengumpulkan dan menerbitkan cerpen-cerpennya dalam sebuah antologiKejantanan di Sumbing pada 1965.
Itu adalah satu-satunya kumpulan cerpen Subagio karena kemudian ia lebih banyak mencurahkan daya pada puisi dan kritik sastra. Sebagaimana diakuinya sendiri dalam esainya pada antologi puisi Keroncong Motinggo (1975), ia tidak begitu sabar kalau harus berkisah.
“Tetapi sajak lebih sanggup memenuhi kebutuhan saya menyatakan pengalaman estetik secara langsung tanpa berpaling pada rencana-rencana yang disengaja mengenai pembentukan watak tokoh-tokoh, kejadian-kejadian dan plot-plot,” tulis Subagio.
Terbukti kemudian ia amat produktif dalam menulis puisi dan kritik esai. Beberapa karyanya bahkan beroleh kusala.
“Sepanjang 71 tahun usia hidupnya, ia menelurkan tujuh buku puisi, dua di antaranya memperoleh penghargaan: Anugerah Seni dari Pemerintah RI tahun 1970 untuk kumpulan Daerah Perbatasan (1970) dan SEA Write Award 1991 untuk kumpulan Simphoni Dua (1990),” catat Arif Bagus Prasetyo dalam “Metakritik untuk Subagio Sastrowardoyo” yang terbit di jurnal Poetika (2013).
Antologi puisi Subagio lainnya adalahBuku Harian (1979), Hari dan Hara (1982), serta Dan Kematian Makin Akrab (1995).
Dalam sejarah perpuisian Indonesia modern yang nisbi muda, Subagio punya posisi istimewa. Hutagalung punya beberapa ukuran: lingkup tema yang kaya, gaya ucap yang unik, dan diksi yang dinamis dengan memanfaatkan kosa kata keseharian.
Hal yang sama juga diungkapkan Andries Teeuw. Dalam amatan Teeuw, sebagaimana diterakan dalam pengantar antologi Daerah Perbatasan, sajak-sajak Subagio kaya makna meski diksinya sederhana. Di tangan Subagio, kata-kata sederhana itu bisa “menjadi sangat berganda dan melimpah artinya dengan belokan yang mendadak dan tak diharapkan, sering kali dengan kandungan ironi”. Tak heran jika penekun sastra Jawa Kuno itu memberi simpulan, “Dari semua penyair modern Indonesia, dialah sebenarnya yang paling mengasyikkan saya.”
Tak hanya dikenal sebagai penyair, Subagio dikenal pula sebagai kritikus sastra jempolan. Seperti puisi-puisinya, beberapa buku kritik sastra anggitan Subagio juga diganjar kusala. Sastra Hindia Belanda dan Kita (1983), misalnya, berhasil menyabet Hadiah Sastra Dewan Kesenian Jakarta di tahun penerbitannya.
Karya kritiknya yang lain terkumpul dalam beberapa bunga rampai, di antaranyaBakat Alam dan Intelektualisme (1972), Manusia Terasing di Balik Simbolisme Sitor (1976), Sosok Pribadi dalam Sajak (1980), Pengarang Modern sebagai Manusia Perbatasan (1989), dan Sekilas Soal Sastra dan Budaya (1992).

Puisi-Puisi Renungan
Dalam majalah Horison (Februari 1967) Goenawan Mohamad mengulas beberapa sajak Subagio Sastrowardoyo. GM menangkap kesan bahwa puisi-puisi Subagio adalah gumaman yang dicatat. Puisi-puisi itu lahir dari seorang yang sedang diam merenung di tengah keramaian sekelilingnya. “Satu penghajatan jang intens, jang tak diburu ketjemasan apapun,” kata GM.
Subagio pun mengakui bahwa puisi-puisinya memang hadir dari proses perenungan. Baginya, sajak yang murni akan terungkap setelah ia bertafakur. Intensinya adalah mengendapkan segala pengalaman inderawi maupun emosional untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang nilai-nilai dasar hidup. Maka tak heran jika pembaca mendapati sajak-sajak Subagio sebagai puisi yang religius.
"Memang ada kedekatan antara puisi-puisi saya dengan religi. Sebenarnya puisi sangat dekat dengan religi, keduanya bicara tentang nilai-nilai dasar hidup," kata Subagio sebagaimana dikutip Kompas (13/1/1993).
Sekalangan pembaca lain menilai puisi-puisi Subagio bermuatan filsafat. Subagio pun tak menampik pandangan ini karena baginya sastra sejatinya adalah filsafat yang cair. Maka itu sudah semestinya sastra menyampaikan filsafat dalam bentuknya sebagai inti pengalaman hidup. Sajak-sajak penyair lama seperti Chairil Anwar dan Amir Hamzah, menurut Subagio, semuanya mengandung filsafat.
Tentang ini, kritikus sastra Zen Hae dalam “Pembicaraan Ringkas Puisi-puisi Subagio Sastrowardoyo” yang terbit di jurnal Poetika (2013) menulis, “Bagi saya dialah penyair Indonesia modern yang secara sadar menjadikan puisinya sebagai medan perenungan filosofis.”
Menilik kecenderungan ini, tak heran bahwa tema-tema yang dieksplorasi Subagio umumnya berkitar pada eksistensialisme seperti kesepian, cinta, nasib yang tak menentu, hingga soal kematian.Tema yang disebut terakhir adalah yang paling menonjol dan dianggap paling lekat dengan dia.
Karya Subagio yang dianggap kritikus paling berhasil dalam membicarakan kematian adalah puisi "Dan Kematian Makin Akrab". Dalam puisi ini beberapa kali ia memberi tengara betapa hidup dan mati sebenarnya hanya terpisah oleh selaput amat tipis. Katanya kematian itu “seakan kawan berkelakar/yang mengajak tertawa” atau “hanya selaput/gagasan yang gampang diseberangi”.
Dalam soal kematian, Subagio kerap dibandingkan dengan Chairil Anwar yang juga pernah mengeksplorasi tema ini. Namun, menurut Goenawan Mohamad, pandangan mereka berdua sebenarnya berbeda. Subagio menganggap kematian adalah siklus biasa dalam perjalanan hidup manusia. Maka itu dalam puisinya Subagio justru membahas kematian dengan kegairahan yang sama seperti membahas kehidupan.
“Ketjemasan akan Maut jang terdapat pada Chairil tidak ada pada Subagio Sastrowardojo, walaupun keduanja memiliki kegelisahan jang sama dengan tendens2 fatalisme jang sama pula,” tulis pendiri Tempo itu di majalah Horison.
Bukannya gelisah atau takut, bagi Subagio maut semestinya dihadapi dengan berani. Dalam sajak "Daerah Perbatasan", misalnya, ia menulis, “Ada baiknya/mati muda dan mengikut/mereka yang gugur sebelum waktunya./Di ujung musim yang mati dulu/bukan yang dirongrong penyakit/tua, melainkan dia/yang berdiri menentang angin.”
Rasa takut semestinya tak perlu ada jika kita menyadari bahwa terkadang “Mati lebih mulia/dan kekal daripada seribu tahun/terbelenggu dalam penyesalan.” Lagi pula manusia sebenarnya tak punya kendali atas nyawanya sendiri. Sebagaimana Subagio dalam sajak "Juga Waktu" menandaskan bahwa “nyawa ini sendiri/terancam setiap saat/Tak ada yang kita punya.”
Lantas apa yang bisa diperbuat di sisa hidup yang tak pasti kapan akhirnya ini?
“Yang kita bisa hanya/membekaskan telapak kaki,/dalam, sangat dalam,/ke pasir/Lalu cepat lari sebelum/semua berakhir.” Walaupun pada akhirnya “Semuanya luput/Juga waktu.”
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id