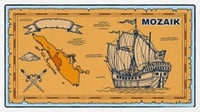tirto.id - Suhu politik daerah mulai menghangat. Sejumlah lembaga survei lokal dan nasional mulai merilis tingkat popularitas dan elektabilitas para tokoh berdasar penilaian masyarakat. Partai politik sibuk membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon walikota beserta wakil-wakilnya.
Wajah-wajah calon pemimpin daerah tampil dalam baliho/pamflet besar, berita media, serta pencitraan di media sosial. Tampang mereka berseliweran mengekspresikan “hasrat atas kekuasaan“. Replikasi pemilu lagi-lagi menampilkan langgam seremonial para tokoh dengan paras muka tertentu, gagasan dan pemikiran revolusioner, berbicara tentang perubahan bagi kehidupan dan kemaslahatan masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pilkada serentak dilaksanakan akhir November 2024, berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Tentunya, 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi bagian dari gelaran pesta demokrasi besar tersebut.
Pemilu merupakan pintu penting dalam pergantian struktur dan kepemimpinan di daerah yang diharapkan berpihak pada kepentingan rakyat. Bahkan, konstitusi menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amanat tersebut jelas-jelas menunjukkan pentingnya kepemimpinan daerah yang dibentuk dengan sistem politik demokratis demi mewujudkan cita-cita bangsa. Pertanyaan saya, akankah Pilkada serentak mereplikasi Pemilu nasional yang memungkinkan munculnya anomali demokrasi?
Anomali Demokrasi
Meskipun Pilkada telah mendongkrak demokrasi hingga kian melesat, tapi kemaslahatan demokrasi masih terjerembap. Anomali demokrasi terjadi karena praktik-praktik politik dan proses demokrasi tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diharapkan banyak pihak.
DI DIY, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus meningkat. Tahun 2009, IDI wilayah DIY adalah 65.55, kemudian naik menjadi 72.96 pada tahun 2012. Bahkan kelahiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menguatkan sistem pemerintahan monarki demokratis justru terbukti melesatkan demokrasi. Pada 2014, IDI berada di angka 82.71, lalu naik menjadi 83.61 (2017) dan naik lagi menjadi 85.62 (2022).
Pilkada telah lima kali diselenggarakan dan mampu membuat pergantian kepemimpinan daerah berlangsung aman dan damai. Namun, realitas kehidupan masyarakat masih jauh dari harapan demokratis dalam kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Semua variabel itu dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut.
Dalam hal lingkungan, keseimbangan ekologis perlu perhatian. Perubahan iklim sedang berlangsung ditandai peningkatan suhu permukaan bumi, membuat cuaca panas dan gerah, serta berimplikasi luas. Kebutuhan energi fosil meningkat, kegagalan panen yang berulang mendera petani di desa-desa, masalah lingkungan dan kepatuhan tata-ruang masih perlu perhatian, kualitas air dan udara menurun, dan akhir-akhir ini pengelolaan sampah tak kunjung tertangani.
Secara sosial, masalah keadilan sosial masih dirasakan. Ketimpangan kian menganga, kemiskinan masih tertinggi di Jawa, kebahagian masyarakat menurun, penduduk lansia butuh perhatian khusus, dan angka bunuh diri meningkat. Selain itu, pembangunan inklusi sosial masih menyisakan pertanyaan sekitar Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI).
Meski Undang-Undang Partai Politik dan UU Pemilihan Umum mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam badan eksekutif dan legislatif minimal 30%, faktanya kesenjangan masih signifikan. Keterwakilan perempuan masih jauh dari ideal.
Di DIY, kuota perempuan 30% di parlemen pada pemilu 2019 belum tercapai. Data Rencana Induk Keistimewaan DIY tahun 2024 menunjukkan, porsi perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Bantul hanya 9%, Kota Yogyakarta 13%, Gunungkidul 20%, Kulonprogo 20% dan paling tinggi di Sleman, 24%.
Dalam kontestasi Pemilu legislatif tahun 2024, kecuali Kabupaten Sleman, angka partisipasi perempuan masih jauh dari ideal. Belum lagi bicara soal keterwakilan disabilitas atau ketahanan sosial dan budaya di masyarakat yang cenderung menurun, semuanya masih menjadi tantangan, wujud kompleksitas persoalan di komunitas.
Secara ekonomi, standar upah minimum belum terpenuhi. Upah minimum kabupaten meningkat, tapi masyarakat pelaku usaha tidak banyak yang mampu mengupah sesuai standar. Hal demikian bukan disebabkan oleh kebijakan pengecualian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, tetapi disebabkan oleh jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di DIY dan kabupaten/kota memang lebih banyak yang belum mampu memenuhi standar pengupahan.
Tawaran Transformasi Lingkungan atau Sosiologi Hijau
Sosiologi hijau mengarahkan sistem sosial dan politik menuju prinsip-prinsip Keistimewaan DIY. Sosiologi hijau melibatkan pemahaman tentang hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari tindakan manusia terhadap lingkungan.
Sosiologi hijau juga mempertimbangkan etika tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan generasi masa depan. Sosiologi hijau perlu dikemukakan untuk memberikan pandangan dengan menggunakan perspektif sosiologi dalam memaknai konstelasi dinamika politik di DIY. Meminjam disertasi Harsono (2018) di salah satu universitas ternama di Australia, komitmen sistem pemerintahan monarki demokratis memang membedakan DIY dengan daerah lain, tapi sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan prinsip kebaikan publik?
Misalnya, satu prinsip dari Panca Mulia Keistimewaan adalah prinsip hamemayu hayuning bawana, baik dalam laku, tindakan, dan hasil (outcome). Dalam pernyataannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa semestinya Panca Mulia (termasuk hamemayu hayuning bawana) tidak lagi dipahami dalam konteks tradisional, tetapi harus tumbuh dewasa dan dipahami sejalan dengan pertumbuhan pengetahuan dan teknologi terkini untuk memajukan tradisi itu sendiri.
Prinsip di atas sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), politik dan kelembagaan kebijakan hijau, juga strategi pembangunan rendah karbon. Pada saat bersamaan, masyarakat terus bergerak mengupayakan perbaikan lingkungan melalui mitigasi emisi gas rumah kaca pada semua sektor dan subsektor yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Pemimpin daerah perlu menggunakan perspektif sosiologi hijau untuk mewujudkan perilaku pemimpin yang nyawiji, greget, saguh ora mingkuh. Setidaknya, pemimpin mampu membangun komitmen dan semangat bersama rakyat untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, berjuang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta mengupayakan keseimbangan ekologis.
Strategi pembangunan rendah karbon telah dilakukan oleh masyarakat melalui kampung iklim, bank sampah, rumah kompos, komunitas pertanian organik, ragam aktivitas mitigasi dan adaptasi. Semua itu memerlukan dukungan kelembagaan yang sesuai, demi kesejahteraan bagi para pelaku, pembiayaan, dan pendanaan yang tidak konvensional.
Seiring dengan peta jalan pembangunan hijau menuju Indonesia Emas Tahun 2045, instrumentasi pembangunan hijau kian masuk dalam arena pengetahuan dan teknologi terkini, sehingga berbagai usaha kebaikan yang dilakukan rakyat harus mendapat tempat dan terus berdaya. Transformasi lingkungan yang humanis melalui perspektif sosiologi hijau berusaha memahami dan merumuskan solusi terhadap masalah lingkungan melalui pendekatan sosial dan perilaku manusia.
Pertanyaannya sekarang, beranikah para calon bupati atau calon walikota beserta wakil-wakil mereka beradu gagasan demi membangun sistem sosial-ekonomi kemasyarakatan dengan transformasi lingkungan yang humanis (sosiologi hijau) dan tangguh di kabupaten/kota?
*Penulis adalah Dosen Program Studi Sosiologi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.